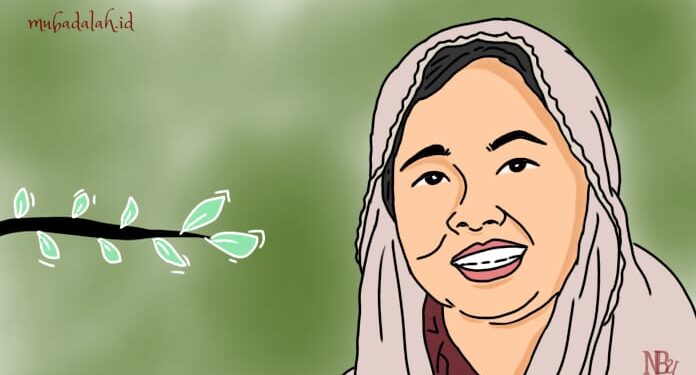Mubadalah.id – Gara-gara mengomentari tes wawasan kebangsaan KPK, ratusan kritik dan cacian serta dukungan mampir ke kolom ”sebutan” (mention) akun Twitter saya. Fenomena ini sudah tak lagi mengherankan bagi saya setelah bertahun-tahun kerap menerima banjir balasan dan sebutan, semisal saat membandingkan FPI dengan Ma Ba Tha dari Myanmar, demikian juga saat mengkritik Abu Janda. Pasukan pendukungnya secara militan menyatroni kolom sebutan selama berhari-hari.
Demikianlah konsekuensi upaya untuk konsisten pada basis prinsip dalam menanggapi kasus, dengan risiko menyenggol kelompok mana pun. Misalnya, kubu penentang ataupun pendukung Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) sama-sama pernah menghujani saya dengan komen-komen penghakiman atas kritik yang saya lontarkan.
Para veteran pegiat media sosial Indonesia pasti amat paham watak warganet Indonesia yang terkenal di seantero jagat maya. Peristiwa demi peristiwa menunjukkan kekuatan pasukan maya yang kemudian digambarkan dalam istilah netizen mahabenar.
Apalagi dalam hal peristiwa yang dianggap terkait harkat dan martabat bangsa, para warganet bisa berbondong-bondong bahu-membahu menerjang lawan. Para pejuang papan ketik (keyboard warrior) Indonesia sepertinya pantang mundur sampai ada hal lain yang menarik perhatian mereka.
Jangankan akun media sosial personal, seperti GothamChess, atau akun resmi lembaga All England atau Badminton World Federation (BWF), kapitalis sekuat Microsoft pun bertekuk lutut. Sumber daya teknologi informasi, finansial, dan jejaring kepemimpinan globalnya tak cukup ampuh menghadapi terjangan netizen mahabenar Indonesia setelah mengumumkan hasil Digital Civility Index 2020 yang melibatkan 16.000 pengguna media sosial di 32 negara.
Indeks disusun dengan berbagai kriteria, seperti penyebaran berita bohong atau hoaks, ujaran kebencian, dan perisakan daring. Menurut Microsoft, dalam hal keberadaban digital tahun 2020, Indonesia menempati posisi terendah di Asia Tenggara dan posisi ketiga terbawah dari seluruh negara yang disurvei. Merasa martabat negaranya diganggu, pejuang papan ketik Indonesia menyerbu akun Microsoft, yang sejatinya justru memberi bukti konkret hasil riset tentang netizen Indonesia.
Keaktifan dan intensitas warganet Indonesia memang sangat tinggi, terutama di platform Facebook, Twitter, Youtube, dan Instagram. Ini tidak bisa dilepaskan dari watak masyarakat Indonesia yang sosio-sentris, menempatkan kehidupan sosial sebagai hal utama. Orang Indonesia suka berinteraksi, membangun sistem dengan infrastruktur sosial yang kuat untuk menopang kehidupannya. Ronda, arisan, dana sehat, paguyuban, dan berbagai inisiatif berbasis interaksi warga adalah hal yang tidak asing.
Media sosial memberikan ruang tanpa batas untuk memperluas interaksi sosial. Orang Indonesia bisa memiliki banyak akun Facebook karena batas 5.000 teman per akun ternyata tidak cukup. Berbagai hal dan informasi pribadi dibagikan di media sosial tanpa sungkan dan ekspektasi privasi. Bahkan, kebiasaan tersebut dapat menjadi sumber penghasilan, sebagaimana dialami para influencer (pemengaruh) media sosial.
Pakar psikologi budaya, Richard Shweder, menyatakan, banyak kelompok masyarakat yang berwatak sosio-sentris, di mana kepentingan sosial menjadi prioritas yang lebih tinggi daripada kebutuhan individu. Watak ini membuat warga suka menggunakan norma sosial sebagai tolok ukur menilai warganya, apa yang disebut sebagai collective mind. Watak ini juga memberi izin kelompok masyarakat melakukan intervensi atas perilaku anggotanya, didasari kebutuhan untuk menjaga harmoni dan solidaritas.
Akibatnya, kecenderungan untuk menilai dan menghakimi orang lain menjadi besar. Konflik antarwarga atas nama kepentingan bersama kerap terjadi, dipicu sikap mau tahu dan mencampuri urusan orang lain. Dalam jagat maya, kecenderungan ini menghebat karena anonimitas media sosial. Anonimitas memperbesar kenyamanan berinteraksi karena jarak fisik yang besar, alter ego yang bisa dibentuk sesuka hati, dan ketiadaan akuntabilitas sehingga tidak ada beban moral yang menjadi rem.
Dengan literasi yang relatif rendah, masih banyak warganet yang tidak bisa membedakan antara berpikir kritis dan perundungan. Alhasil, netizen Indonesia mudah sekali terperangkap oleh penghakiman massal hari demi hari. Setiap kasus yang muncul dengan cepat memicu doxing, yaitu pengumpulan data pribadi seseorang untuk diekspos melalui media sosial. Contohnya tiga kasus perempuan bertingkah kasar, yang dengan segera dicari dan diekspos data pribadinya.
Malangnya, watak netizen Indonesia ini terpetakan dengan baik oleh para konsultan sosial-politik. Kecenderungan ini dimanfaatkan untuk memainkan sentimen, terutama sentimen kebencian untuk kepentingan politik kekuasaan, sebagaimana ditemukan Cherian George dalam penelitiannya circa pada 2015.
Para profesional media sosial membangun strategi untuk memengaruhi diskursus publik. Hashtag dalam trending topics tidak lagi menjadi refleksi percakapan organik, tetapi menjadi tren yang absurd. Buzzers (pendengung) dan pemengaruh menjadi pasukan untuk membangun gimmick politik, bahkan mengintimidasi dan melakukan pelintiran kebencian. Polarisasi pun tak terhindarkan di media sosial, dengan contoh epik perseteruan antara para cebong dan kampret.
Yang awalnya hanya sekadar tren percakapan sosial sekarang menjadi pertempuran politik kekuasaan. Untuk kepentingan kekuasaan, doxing dilakukan bertubi-tubi untuk mempermalukan oposan. Ini menjadi pekerjaan rumah yang sangat penting untuk direspons, sayangnya sampai saat ini belum juga terformulasikan strategi tersebut.
Sekali lagi, Gus Dur menggambarkannya secara utuh: kehidupan (berbangsa) kita hanya dipenuhi oleh kegiatan untuk mempertahankan kekuasaan, tidak lagi mengindahkan aspek moril kehidupan kita sebagai bangsa. Sayangnya. []
Sumber : kompas.id