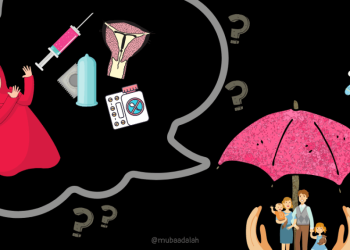Katanya santri harus melek literasi. Kadang-kadang saya suka menautkan kedua alis jika mendengar kalimat tersebut karena terkesan jauh dari peradaban menulis dan membaca. Padahal justru menjadi santri membuat seseorang mau tidak mau membuka sebuah kitab (buku) kemudian mengabsahinya dengan tulisan huruf pegon dan membacanya.
Minimal kitab Safinatun Najah terjamah oleh para santri. Bahkan kini mulai bermunculan penulis-penulis yang berasal dari kalangan santri maupun pesantren yang bukunya ramai dipinang oleh banyak pembaca. Seperti Hati Suhita karya Khilma Anis, Hilda karya Muyassaroh Hafidzoh, dan yang masih hangat sehangat gosip Yu Sari yakni Dua Barista milik Najhaty Sharma.
Berlatar pendidikan menjadi santri di Pondok Pesantren An-Nur Maron dan Pondok Pesantren Sunan Pandanaran Yogyakarta tidak membuat Najhaty merasa terkungkung untuk menyuarakan pemikirannya dan menyalurkan hobi menulisnya. Bagi Ibu tiga anak ini, menulis merupakan sebuah media yang sempurna untuk menyampaikan gagasannya secara detail. Akan sangat sulit jika gagasan tersebut tidak dituangkan dalam sebuah tulisan.
Karena dengan menulis maka gagasan maupun pemikiran tersebut dapat dibaca berulang kali tanpa perlu ia jabarkan berkali-kali. Najhaty memilih menulis fiksi untuk menyampaikan gagasan-gagasannya. Lantaran menurutnya fiksi lebih mudah diterima oleh banyak kalangan dengan kata-kata yang sederhana dan alur cerita yang menarik tentunya.
Komunitas
Meski begitu, dunia literasi tanpa komunitas adalah bagaikan nasi kucing tanpa karet alias ambyar. Najhaty memutuskan untuk bergabung bersama Halaqoh 1001 Aksara dan karya pertamanya yang berjudul Radio Usang menjadi salah satu cerita yang dibukukan dalam antologi Perempuan Tali Jagat.
Hingga kini karya dan pemikirannya dapat dinikmati dalam Perempuan Tali Jagat (antologi kumpulan cerita pendek), Moral Code KPFI (antologi kumpulan cerita pendek), Kupu-Kupu Marrakesh (kumpulan cerita bersambung), Dua Barista dan yang terbaru yaitu Lipstik (kumpulan cerita pendek) kolaborasi bersama Arie Singawidjaya.
Support
Dengan karya fiksi sebanyak ini, perempuan kelahiran 30 Juli ini tetap mampu mengatur jadwal kesehariannya sebagai seorang ibu, istri, pengajar, dan juga berwirausaha. Baginya aktivitas tersebut merupakan aktivitas yang memang harus ia jalani dan ia sukai meski ia mengaku tidak bisa membaginya dengan rata dan hanya melakukannya sesuai kebutuhan saja. Namun tentu mengurus rumah tangga dan mengajar di pondok merupakan prioritas utama baginya. Jika prioritas utama ini sudah selesai ia kerjakan, maka ia lanjutkan dengan berwirausaha dan mengasah inspirasi untuk kembali menulis.
Tentu aktivitas sepadat ini tidak akan mampu dikerjakan dalam satu waktu atau pun satu hari tanpa adanya dukungan dari lingkungannya seperti anak, suami, keluarga dan juga rekan kerja serta sahabat. Saya jadi teringat pengalaman emosional yang ia dapatkan ketika buku Dua Barista sudah tercetak 3300 eksemplar yang ia bagikan kisahnya di sosial medianya.
Jauh sebelum ia menulis sebuah cerita, dalam lingkungannya, ia beranggapan bahwa menulis sebuah cerita yang dibukukan bukanlah sesuatu yang prestisius dan dianggap cita-cita yang mulia. Najhaty remaja justru kerap dilerai agar tak menghabiskan waktu untuk menulis karena dirasa mengganggu waktu mengajinya. Namun kali ini berbeda, sepulangnya dari mengambil 3300 cetakan pertama Dua Barista, ia masuk ke sebuah minimarket, lalu terpaku lama disana dan termenung.
Saat itu ia merenung karena merasa belum bisa memberikan sebuah hadiah untuk orang tuanya terutama sang ayah yang sedang sakit dan hanya mampu berbaring di atas kasur. Tentu saja yang beliau butuhkan bukan lagi hadiah berupa materi namun ia tetap membelikan sang ayah hadiah berupa susu khusus untuk penderita diabetes meski air mata tiba-tiba membasahi pipinya karena pikirannya dilanda bisikan “Meski berkardus-kardus susu telah kau beli, kau tak dapat mengembalikan kesehatan bapak mu, Hati!”
Sembari membawa susu yang ia beli, Najhaty pulang dengan lesu menuju ke ranjang sang ayah untuk mencium tangannya dan bercerita bahwa ia baru saja mengambil cetakan pertama Dua Barista sebanyak 3300 eksemplar. Saat itu ia mengira sang ayah akan diam saja dan sedikit gusar karena tahu bahwa anak perempuannya mengerjakan sesuatu yang dianggap kurang berfaedah.
Ternyata ia salah! Dengan sorot mata bahagia dan berbinar-binar, sang ayah menepuk-nepuk bahunya dan menggenggam Dua Barista yang ia letakkan di depan dadanya. Bahkan ketika sang ibu hendak mengambil dari tangan sang ayah, beliau tidak mau melepas buku tersebut dan tetap menahan dalam genggamannya.
Sang ayah tidak banyak bicara karena sakit yang mengganggu tenggorokannya. Tetapi dari pancaran mata itu Najhaty dapat melihat dengan jelas bahwa beliau merestui passion-nya yang sempat membuatnya putus asa dan merasa belum mampu menjadi anak yang membahagiakan orang tua, karena mengerjakan hal yang dianggap lahwun (kurang bermanfaat atau tak berguna) dilingkungannya. Namun di sisi lain ia tengah tenggelam dalam euforia mengurus preorder Novel Dua Barista yang begitu gegap gempita.
Saat itu akhirnya ia sadar bahwa ia telah menemukan penawar dari rasa keputusasaannya. Cara sang ayah memandang novel itu menyadarkannya bahwa detik itu mereka sedang saling memberikan hadiah. Sang ayah menghadiahi anaknya dukungan dan restu untuk merealisasikan cita-cita kecilnya. Serta seorang putri yang memberikan hadiah untuk sang ayah sebuah tulisan berisi pesan-pesan spiritual yang dulu pernah diajarkan olehnya.
Berlatih, practice makes perfect
Pada dasarnya sosok pengagum Andrea Hirata ini memanglah sosok yang sangat tekun dan senang belajar. Kisah Najhaty menjadi pengingat bagi siapun yang menyukai dunia literasi untuk gemar membaca dan teruslah berlatih menulis meski dianggap sebelah mata.
Karena baginya, tajamnya pena akan berbanding lurus dengan seberapa banyak berlatih, sedangkan isi tulisan akan berbanding lurus dengan kualitas bacaan. Ada kesalahan tidak mengapa, karena baginya mengutip kalimat indah milik Pramudya Ananta Tour “kamu boleh pintar setinggi langit. Tetapi kalau kamu tidak menulis, kamu akan dilupakan sejarah.”
Ya, kesalahan tentu ada bagi siapapun yang sedang berlatih menulis, cara memperbaikinya adalah dengan terus berlatih. Kalimat di penghujung tulisan ini mengingatkan saya pada Jodi Picoult yang pernah berkata, “You can always edit a bad page, but you can’t edit a blank page”. []