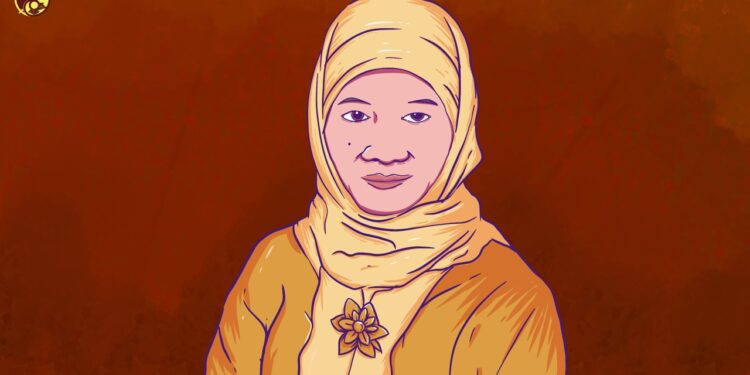Mubadalah.id – Feminisme pada dirinya memiliki ruh kritik, oleh karena itu kritik atas dirinya sendiri tak terelakkan. Pengantar ini disampaikan oleh mba Lies Marcoes mengawali diskusi daring dalam Seri Diskusi Dekolonisasi Ilmu-ilmu Sosial yang secara khusus mengangkat tema tentang “Dekolonisasi Feminisme: Kritik Intelektual dan Aktivis Musim”, yang dikelola mas Dr Moch Nur Ichwan pada 14 Desember 2021 malam.
Tulisan ini tentu saja tidak seutuhnya rekaman diskusi tersebut, namun terurai melalui pembacaan ulang atas pemahaman yang diperoleh dari diskusi tersebut yang telah mengendap, yang juga bercampur dengan beragam informasi yang telah lebih dahulu ada dalam pikiran saya.
Semoga tidak terlalu jauh dari fokus yang dimaksud dalam diskusi tersebut.
Diksi ‘dekolonisasi feminisme’ sungguh menarik sebagaimana semua perbincangan tentang dekolonisasi ilmu-ilmu sosial lain, terutama terkait praksis.
Sangat mungkin banyak kalangan terpelajar termasuk para feminis yang lupa –atau mengabaikan sejarah konstruksi ilmu pengetahuan– yang membentuk kerangka berfikir mereka dan menghasilkan sebuah cara baca, atau ‘frame’, bahkan teori. Ketika ilmu pengetahuan akan digunakan untuk membaca sebuah situasi, –apalagi untuk mencari solusi dari masalah–, maka penting diingat dan dihadirkan kembali bagaimana dan dalam konteks apa pengetahuan tersebut dibangun.
Dalam hal ini Mba Lies mengingatkan bahwa feminisme lahir dalam konteks masyarakat Barat, yang telah mengalami revolusi industri, yang memunculkan perubahan tatanan sosial khususnya memunculkan kelompok-kelompok yang termarginaslisi. Sebagai sebuah faham yang menghasilkan cara berfikir, tentu ia memiliki akar dalam bangunan ilmu-ilmu sosial saat itu.
Keragaman situasi dan keunikan manusia terlalu kaya untuk diseragamkan dan dibaca dengan suatu ‘frame’ yang dibentuk dalam suatu konteks sosial-poitik-budaya tertentu. Dalam sebuah frame juga terkandung kepentingan-kepentingan yang tidak tunggal. Bayangkan ketika kita menggunakan kaca mata dengan lensa merah, maka semua yang kita lihat akan kemerah-merahan. Sebuah frame akan menentukan data mana yang diperhatikan dan data mana yang dianggap tidak penting, yang kemudian akan dianalisa untuk menghasilkan suatu pemahaman atau kesimpulan.
Dari ilustrasi tadi, semangat yang diambil dalam terma dekolonisasi ilmu ini dapat diungkapkan dalam narasi ini; peneliti atau perumus pengetahuan hendaklah menjelaskan posisinya –bagaimana latarbelakang budaya, posisi sosial-akademisnnya dan seterusnya— sebagai sebuah pernyataan yang adil bahwa bias dalam merumuskan pengetahuan si peneliti atau si perumus dapat saja terjadi.
Dengan adanya penjelasan tentang posisi ini, pembaca dapat mengambil jarak dari kontstruksi pengetahuan yang dibentuk dan turut terlibat menilai dan menganalisa data tanpa merasa didikte, dan tidak terjadi memaksakan cara pikir atau dalam diksi yang lebih lugas; penjajahan pikiran.
Kiranya cukup jelas, penjajahan pikiran pun dapat dilakukan oleh siapa saja termasuk oleh masyarakat yang pernah terjajah sendiri ketika tidak krisis, tidak mengambil jarak dengan ‘frame’ yang menyeragamkan perbedaan konteks sosial- politik -budaya peneliti atau per0umus pengetahuan.
Terkait dekolonisasi feminisme, Mba Lies mengingatkan ada beberapa faktor pembeda. Perbedaan tersebut terkait konteks kelahiran feminisme yang adalah budaya Eropa atau kulit putih, dalam masyarakat yang mengalami industrialisasi, bangsa yang menjajah dan sekuler.
Ketika feminisme akan digunakan untuk membaca –atau diandaikan dapat memberi solusi masalah untuk masyarakat Indonesia katakanlah–, perlu diingat masyarakat ini belum mengalami industrialisasi, korban penjajahan dan lebih dari itu menganut alam pikir keagamaan. Tentu konteks yang tidak sama ini harus mendapat perhatian.
Memaksakan sebuah frame untuk sebuah konteks yang berbeda bukan hanya pasti terjadi bias, karena memaksakan cara berfikir, tidak lain adalah penundukkan pada yang berbeda. Penjajahan pikiran, adalah sesuatu yang bertentangan dengan nilai kesetaraan yang diperjuangkan oleh feminisme sendiri.
Pada diskusi ini Mba Lies menggariskan beberapa kesadaran yang penting sebagai kerangka kritiknya, yang intinya adalah menyadari keragaman yang tidak mungkin dinafikan.
- Kesadaran Keragaman Epistemologi
Hampir setiap budaya memiliki alam pikir yang unik. Dalam masyarakat modern yang mengunakan alam pikir filsafat positivistik, (memisahan urusan ‘dunia dan agama” karena yang metafisika dianggap nonsense, menjauhkan dari nilai-nilai, spiritualitas maupun semua hal yang tidak dapat dicerna pancaindera). Cara pikir positivistik ini, satu sisi menyukseskan industrialisasi dan di sisi lain menjauhkan manusia dari kesadaran relasional dengan sesama maupun alam semesta secara umum.
Sementara banyak masyarakat Asia, diantaranya Indonesia, Tuhan, nilai-nilai dan spiritualitas adalah hal yang dianggap penting dalam kehidupan. Ini terhubung dengan bagaimana memandang manusia yang dalam masyarakat Eropa modern, manusia lebih dipandang pada aspek ketubuhannya dan diposisikan sebagai pusat kehidupan. Sementara dalam alam pikir budaya di Asia, manusia tidak sekedar aspek ketubuhan, melainkan seimbang jasmani dan ruhani, yang terhubung langsung dengan alam semesta, bukan pusat.
Ketika ‘frame’ dari masyarakat Eropa ini digunakan dalam masyarakat Asia atau dunia selatan atau dunia yang belum mengalami industrialisasi (namun justru menjadi korban penjajahan negara-negara indutri Eropa) tentu tidak dapat digunakan seutuhnya dan tidak dapat untuk membaca berbagai realitas yang tidak dikenali dalam frame tersebut.
Tidak sambungnya kerangka berfikir dan realitas yang dipikirkan, menunjukkan perlunya keterbukaan dan pengakuan pada keragaman. Oleh karena itu kemudian muncul beberapa aliran feminisme baru yang berkembang dari tuntutan konteks wilayah dan budaya yang berbeda.
Perbedaan budaya sangat terasa dalam komunikasi, misalnya dalam proses edukasi, adakalanya muncul kesalahpahaman, atau anggapan bahwa feminisme adalah paham yang cocok hanya untuk dunia Eropa-Amerika saja. Sangat mungkin di sini terjadi ketidaksinkronan antara referensi makna dengan bahasa, simbol, imajinasi yang digunakan oleh publik setempat.
Sesungguhnya simbol, bahasa, dapat saja dipertukaran sepanjang dapat menyampaikan makna yang menjadi substansi dari suatu proses edukasi, sesuai kebutuhan lokal. Masalahnya suatu makna belum tentu ditemukan dalam budaya yang berbeda. Dialog Kartini, seorang bangsawan Jawa muslim dengan Abendanon, feminis berlatar partai buru di Belanda memperlihatkan ada makna-makna yang penting dalam suatu budaya yang tidak ditemukan dalam budaya lain. (bersambung)