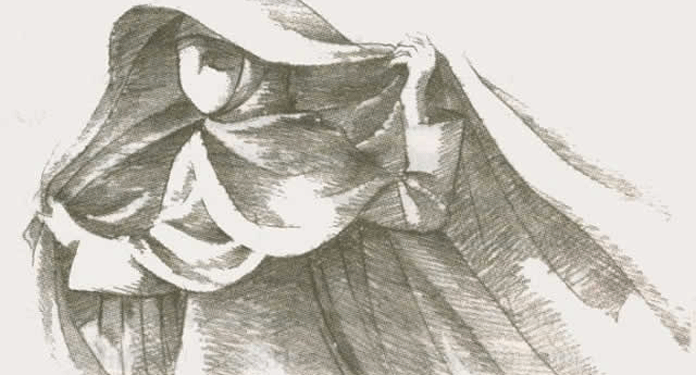Mubadalah.id – Berikut ini adalah cerpen berjudul Cinta Sepanjang Jalan. Semoga para pembaca menikmatinya.
Tak biasanya, udara pagi ini terasa sangat panas. Tak seekor pun binatang yang terlihat sepanjang perjalanan pulang, tidak yang melata, yang terbang, maupun yang loncat-loncat. Semua binatang memilih bersembunyi dan berteduh di sarangnya masing-masing di tengah cuaca kemarau yang memanggang. Namun manusia, yang bisa menyiasati segala cuaca tak memedulikan terik matahari yang menyengat. Tak peduli di tengah guyuran hujan atau pun di bawah terik matahari, mereka terus melakukan aktivitas, bekerja, dan tidur. Berbeda dari hewan lain, hewan berakal ini tidak mengenal musim kawin.
Cinta tak mengenal jarak, rupa, atau harta. Seperti kisah Laila Majnun, cinta itu rahasia, membutakan pandangan, dan membuat gila
Memang di beberapa daerah, orang-orang memilih waktu, bulan, hari, bahkan jam tertentu untuk melaksanakan upacara akad nikah. Di perkampungan, mungkin juga di sebagian kawasan perkotaan, pasangan yang hendak menikah akan mendatangi orang yang dianggap pintar, tahu, dan dituakan, lalu menanyakan hari dan waktu yang tepat untuk menikah. Ada banyak sebutan untuk orang yang menjadi penanyaan, seperti kyai, jerepun, punduh, dan lain-lain. Punduh yang ditemui calon pengantin atau orangtuanya itu, biasanya akan menanyakan nama lengkap dan hari lahir (weton) calon pengantin yang akan menikah. Lalu, dengan menggunakan rumus-rumus tertentu, Sang Punduh menghitung hari lahir keduanya dan mengaitkannya dengan karakter hari dan tanggal yang ada di kalender. Maka, muncullah satu hari atau tanggal yang dianggap paling tepat dan baik untuk menikah. Bahkan, lebih jauh, Sang Punduh dapat menentukan pukul berapa tepatnya calon pengantin pria harus keluar rumah menuju rumah pengantin wanita.
Saya sendiri pernah mengalami, satu pasangan pengantin mendaftarkan pernikahan mereka, lalu meminta dengan sangat agar akad nikah dilaksanakan bakda magrib dan jangan sampai masuk waktu Isya (bakda magrib tong kaisaan). Bagi mereka, itu penting, dan mesti dijalankan. Mereka mengaitkan kebahagiaan dan keutuhan rumah tangga dengan hari, tanggal, dan jam pernikahan. Bisa jadi, jika akad nikah dilaksanakan di luar ketentuan waktu itu, karena saya terlambat datang, dan di kemudian hari pernikahan mereka berantakan, sayalah yang akan dianggap sebagai penyebab keretakan rumah tangga mereka. Pernah pula, seorang tetangga meminta saya untuk mewakili keluarganya, menjemput calon pengantin laki-laki. Memang, selama menetap di kampung, saya sering diminta, baik oleh saudara maupun tetangga untuk mewakili keluarga mereka, baik untuk menjemput calon pengantin pria, menerima lamaran, menerima calon pengantin, dan lain-lain. Hanya saja, kali ini permintaan tetangga saya itu cukup aneh, dan lumayan mengesalkan. Tetangga saya itu minta agar saya menjemput calon pengantin pria pada pukul setengah empat pagi. Mantap!!! Yang lebih menjengkelkan, jarak antara rumah calon pengantin pria dan rumah calon pengantin wanita kurang dari 500 meter! Dia bersikukuh menjalankan amanat atau perintah Sang Punduh sehingga tepat pada pukul 3 dinihari, seseorang mengetuk pintu rumah saya: “Mari Pak, yang lain sudah siap,” ujar tamu dinihari itu sambil menatap saya yang sedang ngucek-ngucek mata.
Masih tentang waktu ideal untuk menikah, ada sebagian kalangan yang menganggap bulan safar bukanlah waktu yang baik untuk akad nikah sehingga kami yang sudah santai semakin sering bersantai pada bulan itu. Bulan Syawal menjadi bulan favorit sehingga bahkan tepat pada tanggal 2 Syawal, hari kedua Idul Fitri, saya sudah harus ngantor karena banyak pasangan yang memilih tanggal itu untuk menikah. Lepas dari soal pilihan waktu itu, tak ada batasan waktu bagi manusia untuk menikah. Kapan pun, di tengah cuaca seperti apa pun, manusia bisa kawin, dan beranak pinak, termasuk hari ini. Saya baru saja pulang menghadiri sebuah acara pernikahan melalui perjalanan yang panjang, melelahkan, dan menegangkan.
Tidak seperti hari-hari biasa, hari ini saya harus berangkat lebih pagi, nyaris subuh. Jadwal harus ditepati. Harga diri harus dilunasi. Tanpa mampir lebih dahulu ke kantor, saya langsung bergerak menuju medan perjuangan. Semua perbekalan dan senjata telah lengkap, termasuk peci, jas yang sudah belel, juga pulpen. Lima belas kilometer perjalanan dari rumah ke kantor harus ditempuh setiap hari, termasuk hari sabtu dan minggu, pernah juga di hari raya—dasar manusia! Hari ini, jarak yang harus saya tempuh lebih jauh lagi. Dari kantor saya harus bersepedamotor delapan kilometer ke arah desa Sukadana. Setibanya di alun-alun desa, tim penjemput sudah menunggu. Dua orang: seorang tukang ojek dan Ketib, atau di tempat lain disebut amil. Masing-masing membawa satu sepeda motor.
“Mengapa enggak boncengan saja?” saya bertanya, demi efektifitas.
“Jalannya sulit Pak, repot kalau boncengan,” jawab Ketib, sambil membetulkan pecinya yang miring ke kanan.
“Lalu, kenapa bawa ojek segala?” tanya saya kepada Ketib.
“Saya tidak hapal jalan pintasnya Pak. Dan medannya sulit kalau boncengan,” ujar Ketib.
Maka, ada tiga prajurit kavaleri yang siap berangkat tempur.
Kami segera menghidupkan mesin motor masing-masing. Dari alun-alun desa Sukadana (nama desa ini berasal dari bahasa Arab sûq yang berarti pasar dan danâ yang berarti bawah, atau pasar sekunder, bukan berasal dari bahasa Indonesia yang cenderung berkonotasi matre suka-dana) kami bergerak menuju desa tetangga, Padarama, yang berjarak sekitar empat kilo melewati hutan jati yang tak pantas disebut hutan karena pohon-pohon jatinya masih sangat kecil hanya sebesar betis orang dewasa, dengan daun-daun yang rontok semua. Pemandangannya lebih mirip medan perang Paschandaele di Kanada pada PD II. Tiba di Padarama, pasukan kavaleri bergerak menuju pinggiran desa, memasuki jalan sawah dengan lebar kurang dari setengah meter. Kami harus ekstra hati-hati, karena jalan setapak itu tak dilapisi beton atau hamparan batu. Hanya tanah merah dengan rerumputan mengering di kedua sisinya. Pada beberapa bagian kami harus turun dari kendaraan karena melewati selokan kecil dengan sepotong batu pipih untuk menyeberang.
Setelah sepuluh menit perjalanan, saya tersentak! Pemandu yang sekaligus komandan kavaleri berhenti lalu memberi isyarat: tangan kirinya digerakkan naik turun bergelombang, sedang tangan kanannya mengacungkan jari telunjuk lurus ke langit, persis seperti seorang komandan peleton memberi isyarat untuk bergerak perlahan menuju sarang musuh. Saya baru paham isyaratnya ketika tiba di belakangnya dan melihat jalan di hadapan saya. Sebuah bukit kecil. Jalan setapak yang dibuat (entah kapan) oleh pasukan pendahulu, zipur, hanya dilapisi bebatuan sebesar alpukat, dan ada juga yang sebesar semangka. Yang bikin saya miris, jalan setapak itu menanjak curam, nyaris tegak lurus. Meskipun puncak bukit terlihat jelas, karena tidak terlalu tinggi, jalan curam itu cukup membuat saya gentar dan berkeringat lebih deras. Komandan kavaleri langsung mengoper gigi ke gigi satu, lalu bergerak lincah menyusuri tanjakan menghindari batu-batu besar. Sebentar kemudian ia telah tiba di puncak dan melambaikan tangan. Disusul kemudian Ketib yang tak kalah gesit dari si komandan. Mereka tiba di puncak dan melambaikan tangan. Saya dapat melihat seringai mereka. Tahu rasa dia! Sekolah boleh saja lebih tinggi, tetapi di jalanan ini, kami lebih jago. Kami lebih berkuasa. Mungkin itu tafsir seringai mereka.
Andrenalin saya terlonjak seketika. Harga diri harus ditegakkan. Penghulu juga bisa jadi offroader. Saya oper gigi REVO ke gigi satu dan dengan gerakan terbata-bata saya susuri tanjakan curam itu hingga akhirnya tiba di puncak bukit. Saya tersenyum puas, seperti bintang iklan petualangan Djarum Super. Sepertinya, daerah ini tak pernah tersentuh para meneer dan mevrow Belanda. Jika mereka pernah ke sini, tentu mereka akan bikin jalan yang melingkar-lingkar memutari bukit, bukan setapak curam seperti ini. Ada alasan tersendiri mengapa Belanda bikin jalan yang berputar-putar, bukan bikin jembatan atau menerobos bukit, yaitu agar mereka lebih lama menjajah dan menyiksa. Seneng banget mereka melihat orang-orang pendek berkulit tembaga, tanpa kain menutupi punggung, mencangkul, melinggis, meratakan jalan sambil dipecuti para mandor yang sama pendeknya namun berkulit lebih terang. Persis seperti Columbus yang mendarat di kepulauan Amerika dan menjajah bangsa Indian. Mencambuki, memukul, dan membunuhi orang Indian Amerika menjadi hiburan tersendiri bagi si petualang gila itu.
Petualangan belum berakhir. Kami harus menuruni bukit, lalu kembali memasuki jalan sawah, dan tiba di pinggir sebuah sungai yang cukup lebar. Saya kembali melihat seringai komandan kavaleri di depan saya. Ia matikan mesin motornya, menanggalkan sepatu dan memasukkannya ke dalam kantong keresek, lalu melipat celananya sampai di atas lutut. Dengan santai, ia dorong motornya melewati bebatuan dan arus sungai hingga tiba di seberang. Mau tak mau saya harus mengikutinya. Sial! Komandan kavaleri curang. Dia telah menyiapkan kantong keresek, sementara saya harus memasukkan sepatu, kaos kaki, dan berkas pernikahan ke bagasi motor, lalu melipat celana hingga lutut. Untunglah saat itu musim kemarau, air sungai tak terlalu dalam. Di musim hujan, kami harus tinggalkan motor di sana, kemudian melewati sebuah jembatan gantung dari anyaman bambu selebar setengah meter. Setelah berbasah ria, sekali lagi kami masuki jalan sawah, berputar, dan kembali menyeberangi sungai yang sama namun lebih ke hilir.
Lima menit kemudian kami tiba di masjid tempat pelaksanaan akad nikah dengan baju kuyup oleh keringat, sepatu yang terlipat karena sesak dalam bagasi, dan berkas pernikahan yang kusut tak karuan. Nama kampung itu Patapan. Mungkin berasal dari kata Pertapaan. Entah siapa yang dulu bertapa di sana. Kalo memang dulu ada orang yang bertapa di sini, dia pasti orang yang sangat iseng atau sangat serius. Kampung itu masih termasuk wilayah desa Sukadana, pos keberangkatan kami. Namun, untuk mencapainya kami harus menyusuri jalan yang berputar dan sulit. Ada jalan yang lebih besar, tapi membutuhkan waktu yang lebih lama karena harus melewati wilayah Kabupaten Cirebon.
Tuntas menghadiri dan mencatat pernikahan itu, kami kembali bersiap-siap menempuh perjalanan yang cukup berat. Sepanjang perjalanan pulang tak henti-hentinya saya berpikir, bagaimana seandainya istri saya, Teni Saptariah Martini binti Djajuli Winata Putra berasal dari Patapan Sukadana. Poin pentingnya, bagaimana saya apel ke sana, sementara tidak ada angkutan umum, tidak ada telpon kabel, dan sinyal GSM pun musnah tak berbekas. Tetapi, itulah misteri cinta. Rahasia perjodohan manusia. Pengantin laki-laki yang menikah di Patapan hari itu juga berasal dari daerah yang cukup jauh, Bekasi. Saya tak melihat mobil pengantar atau kendaraan lain. Mungkin pengantin itu ditendang dari helikopter, atau menjelajah sendiri ke sana sebagai backpacker, atau naked traveller.
Cinta tak mengenal jarak, rupa, atau harta. Seperti kisah Laila Majnun, cinta itu rahasia, membutakan pandangan, dan membuat gila. Mungkin karena itu orang-orang mengatakan “jatuh cinta” atau “fall in love”. Mereka jatuh begitu saja ke dalam kubangan cinta, tanpa pernah menyadari siapa yang mendorong atau membetotnya. Mereka seperti dijebak dan diperangkap sehingga tak bisa menghindar atau melarikan diri. Jebakan dan perangkap itu menjadi semakin kuat dan ketat ketika mereka menikah dan memasuki kehidupan rumah tangga. Kau tak bisa lagi berlari sekehendak hati, menjadi offroader atau naked traveller. Itulah arti akad—ikatan, belenggu, penjara, jebakan yang penuh kenikmatan… bagi sebagian orang.