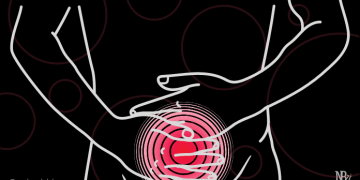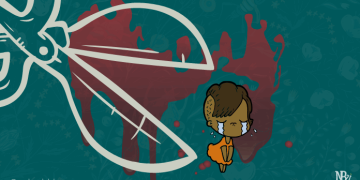Mubadalah.id – Sebagai Sarjana Teknik Sipil di sebuah Institut Teknologi ternama di Kota Bandung, Mbak Ning menikmati pekerjaannya yang sesuai dengan minat dan latar belakang pendidikannya.
Membangun sanitasi umum dan jaringan air bersih untuk warga penyandang disabilitas, perempuan dan warga miskin di perkampungan padat atau di desa-desa tandus dan kering sungguh menantang. Produktivitas kerjanya juga ditunjang oleh suasana kerja di kantornya yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan prinsip integritas.
Tim kerja Mbak Ning tidak bekerja untuk proyek pemerintah atau menjadi sub ordinat kontraktor proyek pemerintah. Mereka menjalankan program bantuan negara-negara donor untuk penyediaan air bersih dan sanitasi.
Mbak Ning sudah terbiasa bekerja dengan standar nilai Negara Donor. Mulai dari sistem pengelolaan keuangan yang menjunjung tinggi kejujuran, hingga sistem pengawasan kinerja yang dilakukan secara berjenjang. Proses dan hasil pekerjaan mereka akan dipertanggungjawabkan melalui proses audit oleh auditor independen.
Budaya kerja seperti itu cukup berpengaruh pada pola hidup kesehariannya di dalam rumah tangga. Suatu ketika, usai sarapan bersama ke dua (bukan) anak kandungnya: Andi Fatina Lubis dan Andi Nauval Lubis, Mbak Ning membuka pembicaraan agak serius.
“Mama hendak membicarakan masalah harta peninggalan almarhum Ayah kalian ya. Dulu, Ayah belum sempat berwasiat apa-apa. Sekarang, Mama sudah selesai mengurus uang jaminan hari tua, santunan dari kantor, serta uang tabungan dari rekening almarhum. Jumlahnya ratusan juta. Uang itu menjadi hak kalian berdua. Mama tidak akan mengambil sedikitpun. Usul Mama uang itu bisa kalian gunakan untuk sekolah dan kuliah hingga selesai. In Sya ALLAH cukup”. Terangnya.
Kedua anak itu menunduk bungkam, lalu meneruskan ucapannya; “Uang itu bisa dikelola oleh kakak Fatina. Kamu sudah dewasa, bisa bertanggung jawab mengatur uang sendiri dan keperluan sekolah adik Nauval. Soal kebutuhan kalian sehari-hari, Mama akan penuhi semuanya. Kita tinggal bersama di rumah ini, mengurusnya secara bersama-sama dengan prinsip kesalingan”. Ujarnya lembut penuh keibuan.
Anugerah Anak-anak Baik
Fatina yang tadinya menunduk tiba-tiba bersuara; “Tidak Ma…semua uang peninggalan Ayah diurus Mama saja. Aku sudah selesai kuliah dan sudah mulai kerja untuk membiayai hidupku sendiri. Mama bisa mengelolanya untuk Adik”. Suaranya tegas.
“Ya sudah, bagaimana dengan adik?” tanya Mbak Ning.
“Aku ikut Kakak dan Mama saja…”. Tatapan mata anak umur 9 tahun ini begitu tajam penuh kepasrahan ke arah mata Mbak Ning.
Tidak terasa, air mata Mbak Ning tumpah membasahi pipinya. Berlembar-lembar kertas tisu diambilnya dari meja makan. Dalam hatinya ia berucap, “Alhamdulillah ya ALLAH, Engkau memang Maha Pemurah, menghadiahiku dua anak yang begitu baik”.
Sebelum kedua anak itu mencuci piring masing-masing, tiba-tiba Fatina membuka pembicaraan baru; “Ma….sebenarnya Ayah dulu punya rumah dan kebun kopi dan cengkeh di kampung halaman. Apa perlu kita urus kepemilikannya?” Tanyannya.
“Iya, Ayahmu juga pernah cerita dulu. Tapi maaf lho ya, Mama merasa tidak punya hak apapun atas rumah dan kebun itu. Bahkan untuk bertanya sekalipun tidak berani. Sekarang kalian maunya bagaimana? Mama bisa bantu mencarikan pengacara yang bisa mengurus itu”. Jelasnya.
“Katanya sih rumah dan kebun itu sudah dijual sama saudara-saudara Ayah lalu dibagi-bagi. Sudahlah Ma, kita fokus ke depan saja, toh aku dan adik senang banget tinggal di rumah ini, kami punya Mama kok” Jawabnya singkat. Dalam hitungan detik, kepala Mbak Ning serasa disiram air es ketika matahari sedang terik-teriknya. Tidak ada kata lain selain “Alhamdulillah ya Allah….”
Tantangan Baru
Selang beberapa tahun kemudian, Andi Fatina Lubis menyandang gelar Sarjana Hukum sekaligus lisensi pengacara. Ia aktif berpraktik di kantor Lembaga Bantuan Hukum yang bekerja secara probono. Atas kegigihannya ia berhasil menyabet gelar LLM (Legal Lawyer Master) dari sebuah perguruan tinggi ilmu hukum di Belanda.
Meski punya gelar cukup mentereng, ia memilih menggunakan keterampilan beracaranya untuk lebih mengurusi masalah struktural yang menimpa warga miskin yang rentan menjadi korban kekerasan dan kriminalisasi.
Kemampuanya terasah sejak bergabung di LBH. Ia selalu ada di garis depan dalam mendampingi para korban penggusuran, anak jalanan yang dikriminalisasi, hingga mahasiswa yang tertangkap saat aksi demonstrasi.
Fatina mampu berdebat dan bernegosiasi dengan Satpol PP, Polisi dengan argumentasi hukum yang sulit dibantah. Ia pun rela menginap di kantor polisi hanya untuk memastikan bahwa semua tahanan karena aksi demonstrasi bisa keluar tanpa syarat.
Ketika belajar di Belanda, Fatina berhubungan dekat dengan seorang peneliti di kampusnya. Pria lajang itu jauh lebih tua, namun matang, penyayang dan gentle. Aura kebapakannya terpancar jelas dari kepribadiannya. Ia merasa sangat cocok dan yakin bisa hidup bersama dengan pria bersahaja itu. Ia tidak hanya menemukan kekasih, tetapi juga bapak yang selalu ia dambakan selama ini.
Meski sudah merasa cocok, namun tersisa satu pertanyaan kecil yang belum bisa terjawab, yaitu tentang agama yang dipeluk oleh pria bersahaja itu. Selama hampir 1,5 tahun membina hubungan, mereka tidak pernah sekalipun mendiskusikan perkara agama masing-masing.
Fatina tidak pernah melihat kekasihnya melakukan ritual keagamaan (apapun). Bahkan, ketika tiba perayaaan hari-hari besar keagamaan, pria ini tidak pernah terlihat merayakan. Anehnya, saat Iedul Fitri dia cukup fasih mengucapkan “Minal Aidin Wal Faizin”. Namun agamannya tetap menjadi misteri. Mulut Fatina tiba-tiba tertutup rapat saat hatinya ingin menanyakan hal itu.
Proses Beragama
Fatina mengajak Mama sambungnya berdiskusi karena ada pertanyaan yang menghantuinnya. Mungkinkah ia akan menjalin hubungan dengan pasangan yang berbeda agama, atau bahkan pasangan yang tidak percaya agama?
Sambil menyeruput kopi Arabica Gayo Mbak Ning bercerita tentang masa lalunya. Bercerita, menjadi pilihan terbaik karena ia tidak ingin terlalu menuntut Fatina dalam menentukan masa depan hidupnya. Ia khawatir anak (tiri) perempuannya merasa tidak nyaman, akhirnya tidak mau lagi bisa berkomunikasi intim dengan dirinya.
Mbak Ning bercerita bahwa dia lahir dari kedua orang tua yang tidak mengenal agama sama sekali hingga menjelang pensiun. Sebagai petinggi di sebuah BUMN, bapak menyekolahkan anak-anaknya di SD Katholik di Kota Semarang.
Sekolah swasta terbaik di kota saat itu. Di rumahnya tidak ada praktik ritual keagamaan apapun. Lonceng gereja dan suara azan hanya terdengar sayup-sayup dari kejauhan. Anak-anak mereka bebaskan untuk memilih agama apa saja yang mereka kehendaki.
Jika ayah dan ibu dulu menuliskan identitas agama di kolom KTP, itu lebih karena untuk menjaga kepentingan pekerjaan di kantor BUMN. Mereka terancam dicap sebagai antek PKI, jika tidak memilih salah satu agama yang ada di Indonesia.
Pilihan pragmatis itu jauh dari niat serius untuk beragama. Konon, ketika ayah dan ibu dulu hendak menikah, mereka melakukan penjajakan sederhana tentang syarat dan ritual keagamaan dalam pernikahan yang paling mudah, murah serta praktis. Maka agama itulah yang akan mereka pilih.
Anak-anak Yatim
Keajaiban tiba ketika Mbak Ning sedang kuliah di semester akhir jurusan Teknk Sipil. Ia harus mengikuti program praktik lapangan di perkampungan padat. Setiap hari ia bergumul dengan warga miskin. Mereka tidak memiliki sanitasi umum dan air bersih.
Mereka membuang kotoran di saluran air atau sungai. Sementara air sungai itu juga digunakan untuk mandi dan mencuci. Terkadang, setelah dijernihkan dengan tawas, air itu juga digunakan untuk masak dan minum. Warga sangat menantikan pembangunan sanitasi dan saluran air bersih.
Mbak Ning bertugas mendampingi anak-anak muda yang sedang mengasuh panti asuhan milik Ranting Muhammadiyah. Ada musala kecil dan beberapa kamar untuk tempat tinggal. Fasilitas kamar mandi tanpa WC di panti itu selalu kering karena krisis air. Setiap jam 5.00 sore, telinga Mbak Ning selalu mendengar anak-anak mengapal surat “Al Asr” sebagai penutup pelajaran. Saking seringnya mendengar ayat pendek itu, lama-lama ia mampu menghapalnya.
Pandangan mata batin Mbak Ning selalu tertuju pada anak-anak yatim piatu yang tinggal di asrama itu. Setiap waktu salat tiba, hatinya tersayat saat melihat puluhan anak-anak yatim berjejer di depan musala mengantri air bersih untuk berwudhu.
Ketika itu, ia belum mengenal agama, tetapi percaya bahwa ada Tuhan sebagai pencipta yang menguasai jagat raya. Hatinya berbisik; “Ya Tuhan, berilah aku kemampuan untuk bisa merawat dan membesarkan anak-anak yatim untuk meraih harapan baik.”
Memuliakan Anak Yatim
Suatu ketika diam-diam ia masuk ke dalam musala lalu mengambil satu buku lusuh setengah robek yang berserakan. Ternyata itu adalah lembaran kitab Juz Amma. Ia membaca salah satu tulisan berbahasa Indonesia secara random. Itu adalah Surat Al Ma’un.
Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?
Itulah orang yang menghardik anak yatim
dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin.
Ia tidak meneruskan bacaannya hingga akhir. Baginya bacaan itu sudah cukup. Surat Al Ma’un adalah satu-satunnya surat yang pertama kali ia baca seumur hidupnya.
Selesai kegiatan praktik kerja lapangan, ia terus teringat surat Al Asr yang dihapalnya. Lalu muncul beberapa pertanyaan lain;
Mengapa orang Islam itu selalu membersihkan diri 5 kali sehari saat menjelang salat? Sependek yang ia ketahui, jika seseorang hendak memeluk agama Islam, ia juga harus mandi dengan bersih.
Tidak hanya itu, mereka wajib mandi bersih ketika keluar air mani, baik secara sengaja maupun tidak, atau setelah berhubungan seksual, serta setelah darah haid berhenti (bagi perempuan). Sebegitu penting ketersediaan air bersih bagi umat Islam. Sebegitu pentingkah prinsip kebersihan itu bagi mereka. Mengapa agama ini sangat mengajarkan kebersihan?
Mbak Ning juga berusaha memahami isi surat Al Ma’un secara otodidak. Ia menyimpulkan bahwa agama Islam ternyata sangat menjunjung tinggi derajat anak yatim. Bahkan memerintahkan penganutnya untuk memuliakan dan mengharamkan siapapun untuk memakan harta anak yatim. Begitu bernilainya anak-anak yatim.
Mbak Ning menyudahi ceritannya sambil memberikan pesan;
“Fatina, jika kamu melihat Mama sekarang sudah mengenakan jilbab, salat lima kali sehari, berpuasa penuh di bulan Ramadan, berzakat untuk orang-orang yang tidak mampu, berusaha memuliakan anak-anak yatim, itu bukan karena Mama saat itu dilahirkan dari rahim seorang muslim. Setelah Mama memilih Islam, barulah kakek dan nenekmu mengikuti. Dulu, kakekmu selalu meletakkan bacaan salat dalam bahasa Indonesia di atas sajadahnya saat salat. Mengapa? karena kakekmu tidak hafal bacaan salat yang berbahasa Arab, namun ia terus berusaha taat”. Mbak Ning mengusap air matannya dengan jilbab.
“Mama memeluk Islam bukan karena pengaruh ajakan mengasah pedang untuk berperang. Mama trenyuh melihat anak-anak muda perempuan seusiamu yang rela berkorban menemani anak-anak yatim di panti asuhan untuk meraih harapan. Yakin, ilmu dan ketrampilan Mama akan berarti buat kehidupan mereka kelak”. Air matannya terus tumpah
“Sekarang, jika kamu berharap calon pasangan hidupmu bisa seiman denganmu, maka buktikan bahwa hatimu bersih, perilaku hidupmu selalu berusaha untuk baik, selaras dengan ajaran inti agama yang sarat kebaikan. Biarlah waktu dan takdir alam itu bekerja. Kamu hanya perlu berdo’a, meminta dengan sungguh-sungguh agar pasanganmu mendapat hidayah, hingga bisa mengarungi hidup bersamamu dalam satu tarikan nafas yang seirama denganmu”.
“Cukuplah peristiwa masa lalu itu menjadi pelajaran, ketika kakek-nenekmu dulu memilih agama hanya sekedar memenuhi syarat untuk mengisi kolom di dalam KTP.”
Seruputan kopi terakhir mengakhiri perbincangan sore menjelang malam. (Bersambung)