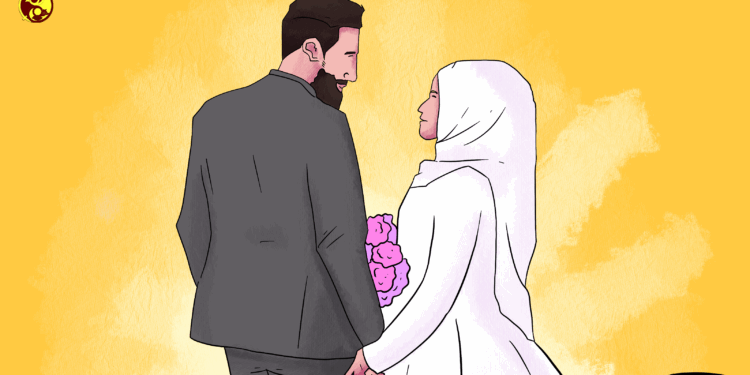Mubadalah.id – Sudah delapan belas tahun saya mengajar di beberapa perguruan tinggi di Jakarta. Di sela-sela bahasan kuliah, saya cukup sering berbincang dengan mahasiswa dengan topik lain. Termasuk rencana mereka menikah.
Saya ingat betul, terutama sejak 10 tahun ke belakang, mahasiswa cenderung memiliki dua orientasi utama dalam kehidupan romantis. Ingin memiliki pacar sebagai langkah awal menuju hubungan serius atau ingin menikah setelah lulus. Narasi pernikahan mereka pandang sebagai tujuan hidup yang logis dan penting, serta menjadi bagian dari peta kehidupan.
Keinginan menikah tidak hanya dimonopoli kelompok heteroseksual (pria maupun wanita), tetapi juga beberapa gay (saya belum pernah berbincang tentang ini ke mahasiswi lesbian—meskipun saya mengetahui ada mahasiswi yang seperti itu). Namun kini, berdasarkan pengamatan di kelas dan berbagai diskusi, terlihat jelas bahwa narasi dan harapan terhadap pernikahan mulai bergeser.
Bagi beberapa mahasiswa, terutama perempuan, pernikahan tak lagi mereka anggap sebagai keharusan sosial atau akhir ideal dari kedewasaan atau capaian kesuksesan. Sebaliknya, mahasiswi masa kini semakin terbuka bersuara dan mengambil keputusan terhadap lembaga pernikahan. Pergeseran ini bukan hanya tentang gagasan terhadap kesetaraan dalam pernikahan. Tetapi tentang munculnya keputusan untuk tidak menikah atau menikah tapi tanpa anak.
Keputusan untuk tidak menikah
Tidak hanya sebagian kecil mahasiswi, yang memutuskan tidak berminat dengan pernikahan adalah mahasiswa gay (dekade sebelumnya, ada beberapa gay yang berencana menikah karena sekadar ingin punya anak). Berbeda dari itu, semua pria mengaku berencana menikah. Keputusan untuk tetap melajang berdasarkan beberapa faktor, tetapi yang paling menonjol adalah tidak ingin merasakan kerumitan hubungan.
Salah seorang mahasiswi, misalnya, mengatakan bahwa dia tidak berencana menikah karena dia yakin pernikahan justru akan membuat dirinya rentan dan terbebani, karena dia mengidap bipolar.
Ada pula yang mengatakan bahwa dia lebih baik memprioritaskan pencapaian pribadi. Menurutnya dia bisa hidup bahagia di luar institusi pernikahan. Yang lain mengatakan bahwa dia menjadi saksi pernikahan yang sulit dan dia pikir tidak perlu mengalaminya.
Menikah Tanpa Anak
Perempuan dengan pilihan ini merasa bahwa memiliki pasangan hidup tidak selalu harus ia ikuti dengan keharusan melahirkan dan membesarkan anak. Mereka tetap ingin menikah karena pertimbangan dorongan biologis dan sosial.
Bagi mereka, pernikahan adalah ruang untuk berbagi hidup dan nilai, bukan proyek reproduksi. Akan tetapi, mereka memiliki pandangan bahwa tanggung jawab pengasuhan masih sangat timpang dan cenderung membebani perempuan secara fisik, emosional, dan sosial.
Penelitian kecil-kecilan di atas tentu tidak untuk menggeneralisasi, akan tetapi untuk meningkatkan kesadaran kita tentang apa yang ada di kepala sebagian generasi kita saat ini. Pergeseran ini tentu tidak muncul begitu saja.
Pasti ada sejumlah faktor yang melatari, seperti: pendidikan dan literasi gender, narasi alternatif dari pernikahan terutama di media sosial, trauma tumbuh di lingkungan dengan pernikahan disfungsional, atau situasi ekonomi dan sosial kekinian.
Ada temuan menarik dari Stephanie Coontz (2005) dalam “Marriage, a History: From Obedience to Intimacy, or How Love Conquered Marriage”, yang melakukan pembabakan dalam sejarah pernikahan. Temuannya, di Amerika Serikat era 1920an, anak muda mulai bertemu di restoran atau mobil untuk merajut cinta, jauh dari pengawasan keluarga. Di era ini mulai ada kritik tentang hilangnya kesakralan pernikahan akibat kelakuan para remaja tadi.
Babak kedua pada 1950an, yang kala itu pernikahan dinilai sebagai kewajiban dan satu-satunya cara membina keluarga. Survei tahun 1957 menunjukkan bahwa empat dari lima orang menganggap pilihan untuk tetap melajang sebagai sesuatu yang “sakit,” “neurotik,” atau “tidak bermoral.”
Babak ketiga pada 1970-an. Di era ini, perempuan mulai mandiri dan aturan sosial berubah—pernikahan tidak lagi dianggap keharusan. Pasangan yang sering cekcok cenderung bercerai daripada bertahan, dan angka perceraian mulai meroket.
Angka Pernikahan Menurun
Terbaru, angka pernikahan menurun tetapi orang tetap memiliki fantasi tentang pernikahan yang sempurna. Pernikahan dianggap sebagai bentuk cinta paling tinggi, bahkan mendorong kelompok minoritas untuk memperjuangkan hak menikah.
Pasangan memilih kumpul kebo terlebih dulu sampai mereka yakin telah cocok, baru mereka menikah untuk menghindari perceraian. Angka perceraian di AS mulai melejit dekade 1970an dan mencapai puncak pada dekade 1980an.
Sulit menemukan riwayat sejarah pernikahan di Indonesia seperti di atas. Akan tetapi, berkaca dari situ, generasi kita mungkin mulai menginjak babak ketiga seperti di AS itu. Perceraian tinggi dan pernikahan tidak menjadi prioritas dalam hidup, yang dibuktikan dengan menurunnya angka pernikahan di kalangan kawula muda.
Dunia pendidikan, institusi keagamaan, dan pembuat kebijakan perlu merespon pergeseran pandangan tentang pernikahan ini. Suara-suara baru yang muncul dari generasi muda perlu kita dengar untuk memperbaiki keadaan.
Tentu saja semangatnya bukan untuk menggiring mereka ke dalam budaya lama. Melainkan untuk membuka ruang bagi keberagaman pandangan hidup yang berakar pada keberdayaan yang berbasis mubadalah, yang sama-sama menguntungkan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pernikahan.
Sebab, pada akhirnya, kehidupan yang kita jalani dengan kesadaran memilih jauh lebih bermartabat daripada kehidupan yang sekadar kita jalani karena kendali dan kekangan tradisi. []