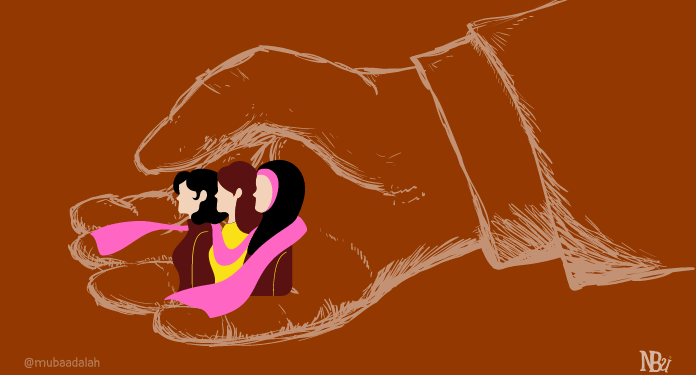Mubadalah.id – Dalam praktiknya, jihad kerap dipahami sebagai wujud nyata perintah amar ma’ruf nahi munkar yaitu mendorong kebaikan dan mencegah kemungkaran.
Sayangnya, bagi sebagian kelompok yang mengedepankan ideologi kekerasan, aspek nahi munkar justru lebih ditonjolkan dibanding amar ma’ruf. Mereka merasa berhak memakai kekuatan fisik demi menghapus apa yang ia yakini sebagai kemungkaran, berpegang pada sabda Nabi:
“Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman.”
Sepanjang sejarah umat Islam, konsepsi jihad, amar ma’ruf, dan penegakan hukum Allah tak jarang menjadi justifikasi tindakan kekerasan.
Terlebih jika dengan sikap “komunalisme”, yakni keyakinan sempit bahwa kebenaran mutlak hanya milik kelompok sendiri, sementara kelompok lain pasti sesat.
Dari sinilah kekerasan sering lahir, bahkan untuk alasan-alasan yang sepele. Karena punya legitimasi teologis, kekerasan menjadi sakral, dinilai ibadah, dan justru diperebutkan untuk dilaksanakan.
Tragisnya, kekerasan ini tak hanya terjadi antara muslim dan non-muslim. Justru lebih banyak menyasar sesama muslim yang berbeda tafsir dan pandangan.
Ini seharusnya menjadi refleksi penting: sudah waktunya kita merumuskan fikih relasi sosial yang tak lagi bertumpu pada dikotomi mu’min-kafir, kawan-lawan, atau cinta-benci. Tapi berlandaskan kesepakatan bersama untuk menjamin setiap orang memiliki hak yang sama dalam hidup, berpendapat, dan berkarya.
Kita juga tak bisa menutup mata bahwa fikih klasik telah lama merumuskan pidana murtad (hadd ar-riddah) yang dalam praktiknya kerap mengancam kebebasan beragama dan berekspresi di tengah masyarakat muslim.
Lebih jauh lagi, istilah-istilah seperti kufr, zindiq, bid’ah, dan khurafat sering menjadi cap yang menyingkirkan. Bahkan menumbangkan, banyak pemikir dan ulama besar yang justru kelak berkontribusi besar pada perkembangan ilmu.
Perumusan fikih keras semacam ini tentu tidak lahir di ruang hampa. Ia muncul dalam konteks sosial-politik tertentu pada zamannya.
Karena itu, seperti pandangan Dr. Faqihuddin Abdul Kodir dalam bukunya Pertautan Teks dan Konteks dalam Muamalah, kita perlu membaca ulang seluruh khazanah tradisi ini dengan kacamata baru, agar dapat melahirkan pemahaman fikih yang lebih selaras dengan prinsip dasar Islam: rahmah (kasih sayang), kebebasan, dan keadilan. []