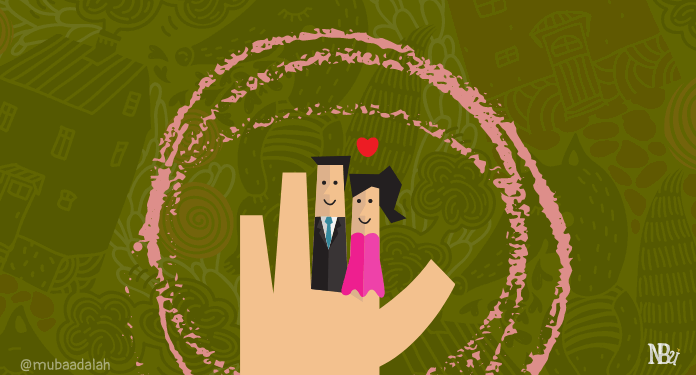Mubadalah.id – Kemarin, setelah menonton film Sore: Istri Dari Masa Depan, otak dan pikiran serasa penuh. Rasanya perlu “mengunyah” lebih lama agar benar-benar bisa mencerna banyak-banyak.
Tulisan ini adalah refleksi difabel dalam narasi film yang sedang hangat di bahas di lini masa. Melihat bagaimana film tersebut bisa jadi cermin bagi isu inklusi dan harapan para difabel di negeri ini. Disclaimer, tulisan ini mungkin mengandung sedikit spoiler, jadi yang tak nyaman boleh skip dulu.
Untuk yang sudah menonton, kita tentu paham bahwa dalam film tersebut, ada Jonathan yang tak kunjung berubah, dan ada Sore yang terus sabar menunggu dan mengusahakan perubahan. Dua tokoh utama yang entah kenapa membuat saya kepikiran kalau mereka berdua seolah mewakili hubungan Indonesia dengan rakyatnya.
Kalau dalam film Sore: Istri Dari Masa Depan, Jonathan bisa dilihat sebagai simbol Indonesia: yang bebal untuk melihat bahwa ada hal yang perlu diperbaiki dan trauma yang perlu disembuhkan. Sementara itu, difabel di negeri ini barangkali adalah “Sore” itu sendiri — sosok yang tetap tinggal, mendampingi, menunggu perubahan, meski berkali-kali diabaikan, berkali-kali pula merasa usahanya seolah sia-sia.
Difabel adalah bagian dari warga negara yang sabar (dengan tetap mengusahakan perubahan). Mereka sabar menunggu pintu akses yang layak, trotoar yang rata, bus yang ramah kursi roda, sekolah yang mau membuka kelas inklusi, dan kebijakan yang betul-betul memeluk semua spektrum.
Seperti Sore, difabel bukan hanya bertahan, melainkan merawat keyakinan bahwa Jonathan (read: Indonesia) bisa berubah menjadi lebih sehat sejak dari pikiran.
Time-Loop, Siklus Harapan
Salah satu elemen kuat dari film ini adalah time-loop, atau putaran waktu yang berulang. Beberapa penonton merasa itu membosankan, tapi justru di situlah bagian krusialnya, yang menegaskan kesungguhan Sore untuk mengubah Jonathan. Pun siklus advokasi difabel juga sering terasa seperti time-loop: berulang, berputar, dan jalan di tempat.
Di atas kertas memang ada regulasi. Ada undang-undang, peraturan, bahkan Komisi Nasional Disabilitas. Tapi di lapangan, masih banyak gedung bertangga tanpa jalur landai, halte tanpa lift, trotoar penuh lubang. Sama seperti time-loop di film Sore, ia datang, mengulang, dan mengecewakan. Pun Indonesia juga demikian: setiap ganti pemimpin, rakyat berharap, lalu kecewa lagi.
Tapi, seperti Sore, difabel tidak pergi. Tidak kabur. Tidak kapok mencintai negeri ini. Mereka tetap hadir, menulis, mendampingi, membuat poster, mendidik publik, menuntut pemerintah. Bukan karena mereka lemah, melainkan karena ada cinta. Cinta yang matang: berani mengkritik, berani menuntut, berani menagih perubahan.
Islam, dan Kesetiaan yang Menggugat
Dalam kerangka Mubadalah, suara difabel bukan sekadar tuntutan, tetapi bagian dari keberkahan hidup bersama. Islam sendiri mengajarkan rahmatan lil alamin — rahmat bagi semesta. Maka, siapa pun yang sengaja menutup akses bagi difabel, sama artinya menutup sebagian pintu rahmat Allah di bumi.
Fahruddin Faiz, dalam banyak ngaji filsafatnya, sering menekankan bahwa agama bukan sekadar ibadah ritual, melainkan ruang pembebasan manusia. Beliau pernah mengatakan, “Hidup yang baik itu bukan hanya soal taat pada Tuhan, tapi juga soal memanusiakan manusia. Kalau di sekitar kita masih ada manusia yang tertindas, itu tanda kita belum sungguh-sungguh beragama.”
Begitu pula Gus Dur, yang menempatkan difabel bukan sebagai objek belas kasihan, melainkan warga negara dengan hak-hak sama. Gus Dur selalu menekankan, “Tidak penting apa agamamu atau sukumu. Kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak akan tanya apa agamamu.” Prinsip ini adalah kunci inklusi: difabel tak butuh dikasihani, tapi diberi ruang setara untuk tumbuh.
Tumbuh Bersama Difabel
Kita mungkin bukan pembuat undang-undang, tapi kita semua bisa jadi bagian dari perubahan: mulai dari menyediakan kursi prioritas di bus, tidak memarkir motor di jalur kursi roda, mendukung produk kreatif difabel, atau sekadar membuka ruang untuk mendengar cerita dan pengalaman hidup mereka. Karena, sabda Rasulullah, “Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain.” (HR. Ahmad).
Di banyak kota, teman-teman difabel masih harus “meminjam” pundak keluarga hanya untuk sekadar naik bus kota. Di Jogja, beberapa komunitas seperti SAPDA, SIGAB, dan Difa Bike membuktikan bahwa advokasi bukan sekadar wacana, tetapi kerja kolektif yang nyata. Mereka merancang program, mendampingi korban diskriminasi, membangun jalur akses, hingga melahirkan fasilitas yang lebih ramah bagi semua.
Semua ini mengingatkan: kebaikan tak pernah sia-sia, sekecil apa pun upayanya. Menjadi bagian dari ekosistem inklusi adalah cara sederhana merawat cinta pada sesama. Semoga kita pun, seperti Sore yang setia menunggu Jonathan berubah, tetap sabar merawat negeri ini — agar tumbuh bersama, bukan meninggalkan siapa pun di belakang.
Terakhir, ada satu kalimat dalam film ini patut kita renungkan: “Orang berubah bukan karena rasa takut, tetapi karena dicintai.” Semoga Indonesia pun demikian: berubah bukan karena tekanan semata, tetapi karena rakyatnya, termasuk difabel, selalu setia merawat cinta, meski sering kecewa atas cintanya.
Karena pada akhirnya, relasi negara dan warga haruslah relasi yang saling bertumbuh, saling mendukung, dan saling menguatkan. Bukan menutup akses, tapi membuka jalan. Bukan membiarkan minoritas terpinggirkan, tapi memastikan semua tetap pulang ke rumah besar bernama Indonesia. []