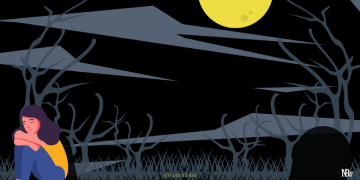Mubadalah.id – Pasca mendapatkan penguatan perspektif mengenai pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas dalam kegiatan Akademi Mubadalah beberapa bulan lalu, saya merasa seperti terlahir kembali. Materi yang disampaikan telah berhasil merekonstruksi pandangan saya mengenai penyandang disabilitas.
Awalnya saya melihat penyandang disabilitas dengan tatapan aneh dan takut, pandangan yang akhirnya saya sadari bersifat diskriminatif. Kemudian saya mulai berusaha dan belajar untuk memahami realitas sosial dari sudut pandang penyandang disabilitas. Tentu proses ini tidaklah mudah karena masih ada bias dalam pikiran. Perlu melatih diri agar semakin tajam dalam membaca keadaan sekitar.
Hal mendasar yang kemudian saya lakukan untuk mengasah kesadaran adalah mengamati lingkungan di sekitar. Apakah akses di ruang-ruang publik telah menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas, atau malah justru terabaikan sama sekali. Semakin sering saya mengamati, ternyata semakin banyak realitas pahit yang terbaca.
Mulai dari absennya guiding block di trotoar, jika ada pun banyak yang tidak layak. Selain itu trotoar sering kali menjadi area berjualan oleh pedagang kaki lima, yang menyebabkan pejalan kaki dan penyandang disabilitas netra kehilangan haknya.
Kemudian, tidak adanya papan ramp untuk mempermudah mobilitas disabilitas daksa. Ironisnya, ketika papan rampa sudah tersedia ternyata hanya tersandar begitu saja di tembok, alih-alih terpasang untuk akses disabilitas yang optimal. Lalu, ketika berkegiatan di taman kota, saya menjumpai kamar mandi khusus disabilitas yang terkunci.
Standar Tunggal di Ruang Digital
Suatu hari ketika menonton sebuah podcast di salah satu channel YouTube yang memiliki 24,7 juta subscriber saya menjumpai komentar dari teman Tuli. Ia menyampaikan permintaan untuk menambah subtitel agar ia dapat turut menikmati podcast tersebut.
Ternyata fitur subtitel otomatis yang ada di video tersebut non-aktif. Ketika saya mencoba memutar beberapa video yang ada di channel tersebut memang tidak tersedia subtitel otomatis. Hal ini tentu menjadi fenomena yang miris sekaligus ironis. Pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitas belum menyentuh ranah-ranah digital yang menyuguhkan banyak informasi dan menjadi ruang ekspresi.
Tetapi, hal lain yang membuat saya sedikit tersentuh adalah 21 ribu akun telah menyukai komentar tersebut dan memberikan respons positif. Selain itu ada balasan “Up” sebanyak 990 komentar yang membuat komentar tersebut di posisi paling atas, sehingga berpotensi menarik perhatian pemilik channel. Barangkali ini menjadi cerminan bahwa memang empati belum benar-benar mati.
Namun sayangnya, pemilik channel belum juga mengaktifkan fitur subtitel otomatis pada beberapa video terbaru yang ia unggah setelah munculnya komentar tersebut. Hal ini juga menjadi gambaran bahwa akses yang ada dalam media sosial belum sepenuhnya merata untuk penyandang disabilitas.
Cara pandang yang berlaku masih berdasar pada standar tunggal yang berpusat pada non-disabilitas. Sehingga membuat keberadaan penyandang disabilitas terabaikan, bahkan tidak terlihat dalam berbagai lini kehidupan, termasuk di ruang digital.
Norma di Atas Kertas
Berbicara mengenai regulasi, sejatinya amanat pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas telah termaktub dalam UU Nomor 8 Tahun 2016. Dalam UU tersebut menyebutkan bahwa terdapat 22 hak yang harus terpenuhi. Beberapa di antaranya adalah hak Aksesibilitas, hak Pelayanan Publik, dan hak Berekspresi, Berkomunikasi, dan Memperoleh Informasi.
Dalam pasal 18, dijelaskan bahwa Hak Aksesibilitas meliputi hak untuk memanfaatkan fasilitas publik, serta mendapatkan akomodasi yang layak sebagai aksesibilitas bagi individu.
Kemudian dalam pasal 19, hak Pelayanan Publik meliputi hak memperoleh akomodasi yang layak, optimal, wajar dan bermartabat tanpa diskriminasi dalam Pelayanan Publik. Selain itu juga berhak mendapatkan pendampingan, penerjemah, dan penyediaan fasilitas yang memudahkan akses di tempat layanan tanpa tambahan biaya.
Lalu dalam pasal 24, dijelaskan bahwa dalam hak Berekspresi, Berkomunikasi, dan Memperoleh Informasi untuk penyandang disabilitas mencakup hak kebebasan berekspresi dan berpendapat. Kemudian mendapatkan informasi dan dapat berkomunikasi melalui media yang mudah diakses. Serta memperoleh fasilitas berupa bahasa isyarat, braille, komunikasi augmentatif, termasuk dalam konteks podcast mengaktifkan fitur subtitel.
Realita di Lapangan
Jika merujuk pada ketiga pasal yang menjelaskan pemenuhan hak penyandang disabilitas di atas, secara regulasi negara telah mengatur dengan komprehensif. Namun, pada pada kenyataannya praktik di lapangan masih jauh panggang dari api. Pun jika UU di atas telah terimplementasi dengan optimal, barangkali tidak akan ada fenomena papan rampa yang hanya tersandar di tembok. Barangkali teman Tuli akan sama-sama dapat menikmati podcast dan mengambil informasi dengan setara.
Perjuangan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas memang kerap kali terasa seperti menapaki jalan yang terjal. Persoalan ini terjadi karena penyandang disabilitas hanya dilihat sebagai liyan. Sehingga menjadikan mereka sebagai objek kebijakan semata, alih-alih melibatkan secara aktif untuk turut serta mengambil peran.
Siklus ini akan terus berkelindan dan berlanjut jika masih ada segregasi dalam bidang pendidikan. Padahal sebagai basis pemahaman, pendidikan yang inklusif adalah sarana untuk memaknai keberagaman, membangun kesadaran kolektif dan membuka partisipasi yang setara.
Bukan Sebatas Merayakan, Tetapi Mengawal
Di tengah wacana cita-cita keadilan yang cukup kompleks, program madrasah inklusif yang dicanangkan oleh Kementerian Agama seolah menjadi angin segar untuk perjuangan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. Boleh jadi ini menjadi salah satu langkah konkrit pemerintah untuk berkomitmen untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas.
Harapannya kelak madrasah yang merupakan lembaga pendidikan bukan hanya menjadi ruang pendidikan formal saja. Tetapi juga menjadi ruang untuk memahami realitas sosial sehingga dapat menumbuhkan empati, toleransi serta prinsip kesalingan dan kesetaraan.
Jika program ini berjalan dengan optimal, niscaya stigma masyarakat terhadap penyandang disabilitas yang telah mengakar perlahan akan terkikis. Sehingga pada akhirnya program ini bukan sekedar pemenuhan hak pendidikan, tetapi melahirkan generasi yang lebih peka dan terbuka terhadap keberagaman.
Komitmen dari Kementerian Agama ini tentu menjadi langkah yang membahagiakan bagi masyarakat. Tetapi kita tidak boleh hanya berhenti dengan euforia semata. Karena tidak menutup kemungkinan akan muncul berbagai tantangan, seperti keterbatasan guru pendamping, minimnya pelatihan inklusi, dan sarana prasarana yang belum cukup memadai sering kali menjadi hambatan tersendiri.
Maka, tugas kita selanjutnya adalah mengawal program, merefleksikan kembali apa-apa yang perlu dikritisi agar dapat menambal sulam kekurangan yang harus dilengkapi. []