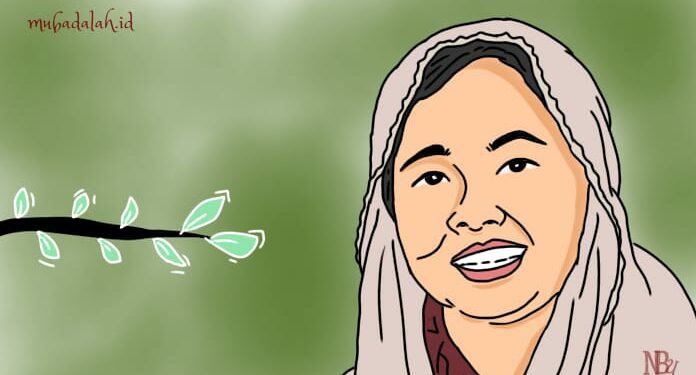Mubadalah.id – Gelombang protes dari berbagai daerah terhadap kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menandai potensi krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Puncaknya, aksi puluhan ribu warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pada Rabu (13/8), yang menuntut Bupati Sudewo mundur setelah menaikkan tarif pajak hingga 250 persen, menjadi alarm keras bagi pejabat daerah maupun pusat agar tidak gegabah membuat kebijakan.
Kenaikan pajak yang dinilai memberatkan ini bukan hanya terjadi di Pati. Data lapangan menunjukkan, Cirebon memberlakukan kenaikan hingga 1.000 persen, Jombang 400 persen, dan Semarang 400 persen. Aksi serupa pun meletus di Bone, Sulawesi Selatan, menentang kebijakan PBB-P2 yang melonjak 400 persen.
Fenomena ini memunculkan pertanyaan: mengapa kebijakan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak bisa lahir tanpa kajian mendalam dan tanpa pelibatan masyarakat?
Demokrasi yang Merosot
Direktur Jaringan GUSDURian, Alissa Wahid, menilai gejolak ini bukan sekadar soal pajak, tetapi gejala penurunan kualitas demokrasi. Ia menyebut indeks demokrasi Indonesia tengah mengalami kemunduran. Sementara praktik korupsi justru marak, dengan kerugian negara yang nilainya jauh melampaui masa lalu.
“Kebijakan pemerintah dibuat tanpa kajian yang cukup. Suara rakyat semakin ditekan, sehingga muncul berbagai bentuk perlawanan, mulai dari kabur aja dulu sampai gerakan Indonesia gelap,” kata Alissa.
Menurutnya, demokrasi hanya dapat tegak jika kedaulatan sipil kuat dan menjadi pengendali utama jalannya negara. “Kalau kekuasaan sipil berada di bawah kendali militer, suara rakyat tidak akan pernah menjadi yang utama,” tegasnya.
Bagi GUSDURian, inti dari demokrasi adalah keterlibatan publik dalam proses pengambilan keputusan. Ketiadaan dialog dengan rakyat hanya akan melahirkan kebijakan yang serampangan dan merugikan banyak pihak.
Selain memperjuangkan penguatan demokrasi, GUSDURian juga menaruh perhatian besar pada isu ekologi. Dalam pandangan Alissa, krisis iklim global yang kini melanda dunia diperparah di Indonesia oleh dominasi industri ekstraktif yang dijalankan dengan pendekatan kekuasaan.
“Hampir tidak ada pertambangan yang benar-benar memulihkan lingkungan. Pemerintah masih abai pada aturan hukum. Kewajiban reklamasi tidak dilakukan, dan akibatnya masyarakat menjadi korban—ada yang jatuh ke lubang tambang, ada pula tanah yang dibiarkan tandus tanpa penghijauan kembali,” jelasnya.
Baginya, isu lingkungan bukan hanya masalah teknis, melainkan bagian dari keadilan ekologis, yang mencakup perlindungan masyarakat adat sekaligus hak-hak alam.
TUNAS GUSDURian 2025: Meneguhkan Nilai, Menyusun Rekomendasi
Seluruh isu ini akan menjadi sorotan dalam Temu Nasional (TUNAS) Jaringan GUSDURian yang akan berlangsung di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, pada 29–31 Agustus 2025. Mengusung tema Meneladani Gus Dur, Menguatkan Indonesia, acara ini diikuti sekitar 2.000 peserta dari berbagai komunitas GUSDURian, sahabat dan murid Gus Dur, tokoh lintas agama, akademisi, hingga jejaring masyarakat sipil dari seluruh Indonesia.
Agenda kegiatan meliputi Konferensi Pemikiran Gus Dur, Forum Gerakan, dan Festival Gerakan. Dalam Community Space, akan ada bazar dan pameran gerakan; Learning Space menyediakan ruang berbagi pengetahuan dan keterampilan. Serta Malam Budaya yang memadukan seni, musik, dan nilai perjuangan Gus Dur.
Sejumlah tokoh nasional dijadwalkan hadir, seperti KH. Husein Muhammad, Dewi Kanti Setianingsih, Greg Barton, Mahfud MD, Badriyah Fayumi, Kamala Chandrakirana, Laode M. Syarif, Tantowi J. Musaddad, Nissa Wargadipura, dan Sandra Moniaga.
Alissa memastikan, pertemuan ini tak hanya jadi ajang silaturahmi, tapi juga forum strategis untuk menghasilkan rekomendasi konkret. “Gus Dur bekerja berbasis nilai. Nilai-nilai itu harus kita turunkan ke bentuk kebijakan dan aksi nyata,” pungkasnya.
Sementara itu, gelombang protes pajak yang merebak di berbagai daerah dan sorotan GUSDURian terhadap penurunan kualitas demokrasi menunjukkan bahwa persoalan bangsa ini tidak hanya terletak pada teknis kebijakan. Tetapi pada cara kekuasaan yang mereka jalankan.
Demokrasi akan tetap rapuh jika suara rakyat diabaikan, dan ekologi akan terus terancam jika orientasi pembangunan hanya berpatokan pada keuntungan jangka pendek.
Pertanyaan yang tersisa: apakah pemerintah siap mendengar peringatan ini. Atau justru membiarkan lonceng alarm terus berbunyi hingga suara rakyat berubah menjadi badai? []