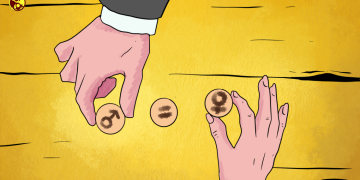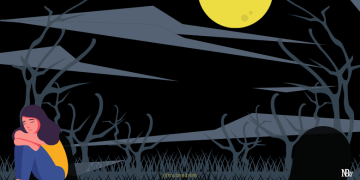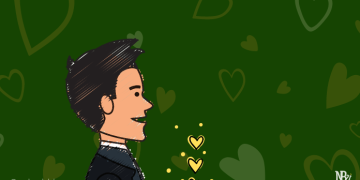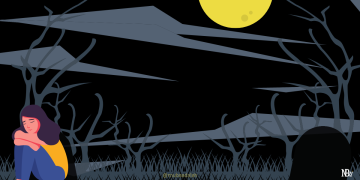Mubadalah.id – Saya mengikuti kelas Adat dan Gender di komunitas Logos ID yang bekerja sama dengan Gerakan Surah Buku. Melalui kelas ini saya mengenal keragaman gender yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah Bissu. Berbicara mengenai gender, hal tersebut adalah sama sekali berbeda dengan seks.
Dalam perspektif masyarakat adat, identitas atau ekspresi gender tidak selalu biner antara feminin dan maskulin. Namun, masyarakat adat mengenal kategori gender dengan lebih beragam. Meskipun membicarakan isu gender telah mainstream, baik dalam forum, artikel ilmiah maupun buku-buku, mempelajari gender dari perspektif masyarakat adat sangatlah penting.
Yakomina Mangmah, pemantik dalam diskusi kelas tersebut menyebutkan alasan pentingnya belajar adat dan gender. Pertama, konsep gender yang saat ini kita kenal banyak terpengaruhi oleh modernitas/kolonial.
Kedua, ketika kolonial datang ke Indonesia, mereka bukan hanya merampas kekayaan Sumber Daya Alam (SDA), tetapi juga membentuk ulang tatanan dan pengetahuan masyarakat. Dalam penyampaian materi, Yakomina merujuk pada artikel penelitian Petsy Jessy Ismoyo dengan judul Decolonizing Gender Identities in Indonesia: A Study of Bissu ‘The Trans-Religious Leader’ in Bugis People.
Jika kita tarik dalam lingkup global, kita akan mengenal banyak keragaman gender. Misalnya Two-Spirits di Amerika Utara, Hijra di India dan Pakistan, Fa’afafine di Samoa, Māhū di Hawaii, dan Muxes di Zapotec (Meksiko).
Di Indonesia sendiri, khususnya di Bugis, Sulawesi Selatan mengenal lima konsep gender: Oroané (laki-laki), Makkunrai (perempuan), Calalai (perempuan dengan ekspresi maskulin), Calabai (laki-laki dengan ekspresi feminin), dan Bissu (androgini/interseks). Dalam tulisan ini, kita akan berfokus membahas Bissu.
Definisi Bissu
Definisi Bissu dapat kita lihat melalui tiga sudut pandang. Menurut masyarakat Bugis, Bissu berasal dari kata ‘bessi’ yang mempunyai arti bersih. Dalam tatanan sosial, Bissu menempati posisi yang istimewa karena ia adalah kombinasi dari semua gender.
Keistimewaan tersebut bukan hanya bersandar pada performativitas yang khas saja, tetapi terutama karena peran spiritual dan sosial di tengah masyarakat. Kemudian menurut Attoriolong, sebuah agama suku Bugis pra-Islam, mendefinisikan Bissu sebagai pemimpin agama/ritual. Dalam Attoriolong sendiri mengajarkan dua nilai penting kepada penganutnya, yakni Malebbi (kemuliaan) dan Malempu (kejujuran).
Lalu yang ketiga, definisi Bissu yang ada dalam I La Galigo, kitab epik yang terakui sebagai karya sastra terpanjang di dunia. Dalam I La Galigo, definisi Bissu adalah sosok yang membantu Batara Guru untuk mengatur kehidupan di Lino (dunia tengah/bumi). Meliputi norma, etika, hingga aturan-aturan lain yang berlaku dalam masyarakat.
Selain itu, Bissu juga turut menciptakan karya dan tradisi melalui komunikasi dengan masyarakat. Bissu terpercaya karena ia menjadi penghubung dunia atas (langit) dan dunia bawah. Jika merujuk pada ketiga definisi di atas, Bissu memiliki kedudukan yang berpengaruh pada lini kehidupan, baik dalam tatanan sosial maupun spiritual.
Pergeseran Makna dan Tantangan
Namun, seiring dengan adanya kolonialisme, posisi Bissu semakin termarjinalkan. Dalam kelas Adat dan Gender yang berlangsung, Yakomina menjelaskan beberapa hal yang menyebabkan pergeseran makna Bissu sekaligus tantangan bagi mereka.
Pertama, adanya warisan kolonial yang hanya membenarkan oposisi biner gender, yakni laki-laki dan perempuan saja. Hal ini merujuk pada catatan perjalanan Antonio de Paiva, seorang pedagang dan misionaris asal Portugal yang mengunjungi Sulawesi Selatan pada tahun 1540-an.
Dalam tulisan tersebut de Paiva yang memiliki latar belakang sebagai Kristen Ortodoks menyatakan kekecewaannya terhadap Bissu yang menurutnya tidak sesuai dengan norma heteroseksual.
Selain itu dapat kita temukan pula dalam tulisan James Brooke yang berasal dari Inggris. Dalam catatan perjalanannya ke Sulawesi Selatan ia menyebut “kebiasaan paling aneh” ketika menjumpai laki-laki dengan ekspresi feminin, dan perempuan dengan ekspresi gender maskulin.
Operasi Toba
Penyebab yang lain adalah paradigma agama dunia (world religion perspective), di mana akibat masuk dan berkembangnya agama Islam pada abad 17 menggeser pluralitas gender menjadi gender biner. Tantangan selanjutnya adalah adanya Operasi Toba (Operasi Taubat) yang menjadi penanda adanya praktik Islamisasi terhadap suku Bugis.
Operasi Toba (Operasi Taubat) yang terjadi pada tahun 1966 merupakan tragedi penumpasan terhadap para Bissu yang dilakukan oleh Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII). Kahar Muzakar meluncurkan operasi tersebut karena menganggap Bissu tidak sesuai dengan ajaran Islam.
Perlengkapan ritual Bissu dibakar dan ditenggelamkan ke laut. Bahkan dalam operasi ini memaksa Bissu untuk menjadi “laki-laki”. Tidak berhenti sampai di situ saja, selama era Orde Baru Bissu dikaitkan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) karena dianggap menganut ajaran animisme.
Karena diskriminasi dan persekusi yang diperoleh terus menerus sejak adanya Operasi Toba, Bissu kemudian bersembunyi dari ancaman. Orang-orang tidak berani mempertahankan tradisi mereka karena takut dibunuh. Bissu yang mulanya memiliki kedudukan berpengaruh dalam institusi komunitas kemudian kehilangan posisinya.
Operasi Toba ini menjadi gambaran bahwa manusia dan kemanusiaan mengalami keterputusan hubungan. Menghilangkan kebebasan berekspresi terhadap sesama manusia. Hal ini terjadi karena adanya pembentukan ulang “pengetahuan” yang didukung oleh negara dan agama yang menyebabkan berkurangnya peran Bissu.
Karena konsep gender biner yang dilembagakan, masyarakat kemudian mempermasalahkan orientasi seksual Bissu yang kemudian melahirkan persekusi. Padahal ekspresi gender adalah hal yang berbeda sama sekali dengan orientasi seksual.
Mengapa Perlu Dekolonialisasi Identitas Gender?
Dekolonialisasi adalah proses kritis untuk melepaskan cara berpikir kita dari dominasi logika kolonial Barat yang telah menjadi residu dalam alam bawah sadar. Residu tersebut mengendap sangat dalam karena internalisasi kolonial terhadap masyarakat jajahan.
Merealisasikan proyek dekolonialisasi identitas gender sangatlah perlu. Karena masuknya kolonial ke Indonesia menghilangkan keberagaman gender yang telah lama dipahami oleh masyarakat adat. Kolonialisme yang mewariskan konsep gender biner pada akhirnya melahirkan penindasan bagi keberagaman gender yang telah ada.
Dengan menggunakan sudut pandang dekolonialisasi ini kita bisa melihat pluralitas gender lebih luas. Menghargai keberagaman pengetahuan dan tradisi lokal yang memiliki konsep gender cair. Kemudian kita bisa melawan dominasi sistem patriarki yang telah lama mengungkung pemikiran manusia.
Lalu membongkar prinsip heteronormativitas, di mana konsep heteronormatif (ketertarikan pada lawan jenis) dianggap sebagai satu-satunya yang “normal”. Yang terakhir, tujuan dekolonialisasi gender yang paling final adalah mengembalikan martabat kelompok termarginalkan dari konstruksi gender biner yang telah lama dihidupi oleh masyarakat. Merekatkan kembali hubungan antara manusia dan kemanusiaan yang sempat terputus. []
References
Ismoyo, P. J. (2020). Decolonizing Gender Identities in Indonesia: A Study of Bissu ‘The Trans-Religious Leader’ in Bugis People. Jurnal Kajian Budaya, Vol. 10 No. 3, 277-288. https://www.researchgate.net/publication/347584613_DECOLONIZING_GENDER_IDENTITIES_IN_INDONESIA_A_STUDY_OF_BISSU_’THE_TRANS-RELIGIOUS_LEADER’_IN_BUGIS_PEOPLE