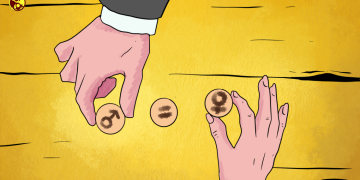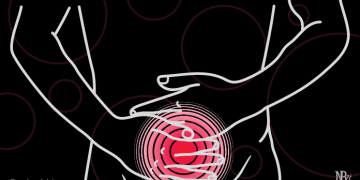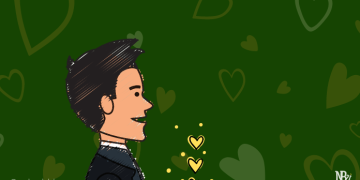Mubadalah.id – Ada seorang teman pernah berkata dengan nada bercanda, “cinta itu anugerah, sementara nikah itu nasib.” Mengapa disebut nasib? Karena pernikahan sering dianggap sebagai pintu dari segala kesusahan mulai dari urusan ekonomi, relasi antar keluarga, persoalan dengan tetangga, hingga beban rumah tangga yang tidak ada habisnya.
Tak jarang, pernikahan yang digadang-gadang sebagai jalan kebahagiaan justru berakhir menjadi sumber masalah hingga perceraian.
Lalu pertanyaanya, jika menikah pada akhirnya hanya akan berujung perceraian, mengapa banyak orang begitu terburu-buru untuk segera menikah? Bukankah menikah sering dikampanyekan sebagai penyempurna agama, tetapi kenyataannya banyak pasangan justru berakhir tidak bahagia?
Menikah sebagai Separuh Agama
Dalam berbagai prosesi khitbah hingga akad nikah, hadis Nabi yang berbunyi “Apabila seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agama, dan bertakwalah kepada Allah untuk separuh yang sisanya” hampir selalu kita dengar. Hadis ini kerapkali dijadikan pengingat bahwa menikah adalah ibadah besar yang mendatangkan pahala.
Namun, sayangnya, pemahaman itu sering berhenti pada tataran simbolis. Bahkan kalimat “menikah adalah separuh agama” terdengar manis di telinga. Tetapi jarang dibarengi dengan melihat realitas di masyarakat.
Karena tidak sedikit yang menyadari bahwa pernikahan juga bisa berubah menjadi sarana keburukan seperti kekerasan, penelantaran, pemerkosaan dalam rumah tangga, hingga trauma anak.
Sementara itu, bagi sebagian orang, menikah bahkan hanya dipahami sebagai “legitimasi hubungan biologis.” Alasannya adalah lebih baik menikah daripada terjerumus dalam zina.
Padahal, logika ini justru berbahaya. Karena pernikahan bukan sekadar status halal-haram hubungan intim, tetapi sebuah komitmen yang menuntut kesiapan fisik, emosional, spiritual, dan finansial.
Tanpa kesiapan itu, rumah tangga bisa menjadi ladang konflik. Bahkan, dalam pandangan sebagian ulama, pernikahan dengan paksaan apalagi tidak kesiapan justru bisa berstatus haram karena lebih banyak menimbulkan mudarat daripada manfaat.
Perjanjian Kokoh
Dalam sebuah pengajian tadarus subuh bertema akad pernikahan, Dr. Faqihudin Abdul Qodir mengingatkan bahwa pernikahan bukan sekadar seremonial. Ia adalah perjanjian kokoh yang keduanya jaga dengan baik.
Setidaknya ada tiga hal penting yang harus suami istri jaga dalam pernikahan:
Pertama, adanya kerelaan dari kedua belah pihak, baik pasangan maupun keluarga besar. Tanpa kerelaan, pernikahan kehilangan makna dasarnya.
Kedua, tidak boleh ada pihak yang merasa terugikan. Hal ini sejalan dengan sabda Nabi, “Jangan merugikan diri sendiri dan jangan pula merugikan orang lain.”
Konsep inilah yang melahirkan prinsip kafa’ah, yaitu kesetaraan antara pasangan, baik dalam status sosial, relasi, maupun latar belakang. Tujuannya agar pernikahan berjalan lebih harmonis dan minim konflik. Meski begitu, jika kerelaan sudah terwujud, kesetaraan ini tidak lagi menjadi penghalang.
Ketiga, kejujuran mutlak diperlukan. Tidak boleh ada kebohongan terkait kesehatan, kondisi ekonomi, atau hal-hal krusial lainnya. Pernikahan yang dibangun di atas kebohongan hanya akan rapuh sejak awal, bahkan berisiko hancur ketika kebenaran terungkap.
Jika tiga aspek ini keduanya jalankan dengan sungguh-sungguh, maka pernikahan tidak mudah goyah. Karena landasan kuat akan menopang pasangan menghadapi gelombang kehidupan, sehingga perceraian bisa mereka minimalisir.
Saling Mendukung
Pada akhirnya, menikah hanya bisa kita sebut ibadah jika hal tersebut menjadi ruang belajar bersama. Sebuah ruang kesalingan antara suami dan istri. Keduanya harus saling menghargai, saling mendukung, saling menguatkan.
Sehingga menikah bukanlah jalan pintas untuk “menghalalkan” yang sebelumnya haram, melainkan komitmen panjang untuk merawat relasi dengan penuh tanggung jawab.
Hadis tentang menikah sebagai separuh agama seharusnya menjadi ajakan untuk memaknai pernikahan sebagai komitmen bersama. Komitmen untuk berbuat baik satu sama lain, menjadikan rumah tangga sebagai ladang amal kebaikan, bukan sarang penderitaan.
Jika pernikahan dijalani dengan kerelaan, kejujuran, dan semangat saling berbuat baik, ia bisa benar-benar menjadi ladang ibadah. Tetapi jika hanya dijadikan kewajiban sosial atau sekadar formalitas, ia bisa berubah menjadi separuh masalah.
Dengan begitu, pernikahan memang bisa menjadi nasib—baik atau buruk—tergantung bagaimana kita memaknainya. Ia bisa menjadi separuh agama bila ia jalani dengan kesadaran penuh, tetapi bisa pula menjadi separuh masalah bila ia lakukan hanya karena tuntutan lingkungan atau dorongan nafsu sesaat.
Di tengah maraknya perceraian, kasus kekerasan dalam rumah tangga, dan rapuhnya ikatan keluarga, kita perlu kembali menafsirkan ulang makna pernikahan. Bukan sekadar akad di hadapan penghulu, bukan pula sekadar simbol status sosial, melainkan perjanjian suci yang menuntut kerelaan, kesetaraan, dan kejujuran.
Pertanyaan yang tersisa adalah: apakah kita ingin menjadikan pernikahan sebagai jalan ibadah menuju kebahagiaan, atau justru membiarkannya berubah menjadi pintu masuk menuju masalah? []