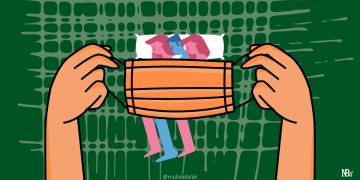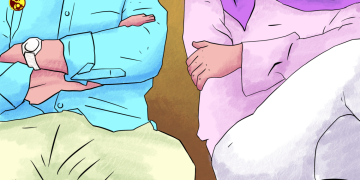Mubadalah.id – Setiap hari, linimasa kita disesaki oleh narasi yang berlomba merebut perhatian. Namun, di balik segala keramaian itu, ada isu yang sering kali terpinggirkan, yakni isu disabilitas. Isu ini bukan sekadar soal keterbatasan fisik atau mental, melainkan tentang bagaimana kita, sebagai masyarakat memperlakukan mereka. Apakah kita benar-benar memberikan ruang yang setara bagi mereka untuk merayakan keberagaman ke dalam dunia maya?
Perjuangan untuk isu disabilitas di media sosial masih akan dan terus menempuh perjalanan panjang. Media sosial memang memberikan kebebasan untuk berbagi, namun juga sering kali membungkam cerita-cerita yang tak cukup “klik” menurut algoritma.
Isu disabilitas berjuang untuk mendapatkan perhatian yang setara, karena hak untuk didengar seharusnya tidak hanya diberikan kepada yang paling “viral” atau “trending”. Semua orang, tanpa terkecuali, berhak menjadi bagian dari percakapan publik ini.
Media Sosial: Antara Ruang Demokratis dan Ruang Tertutup
Media sosial sering kali dipandang sebagai ruang terbuka bagi siapa saja untuk berbicara. Namun, apakah ruang ini benar-benar terbuka untuk semuai isu? Pada kenyataannya, media sosial dikelola oleh algoritma yang mengelompokkan informasi dan menentukan siapa yang didengar. Apa yang seharusnya menjadi tempat untuk membahas isu-isu penting, kerap kali terhalang oleh popularitas atau daya tarik sensasional.
Isu disabilitas, jika kita melihatnya dari sudut pandang ini, sering kali mendapatkan ruang terbatas dan perhatian sekilas, tanpa mendalam. Dalam hal ini, media sosial bukan sekadar ruang untuk menyuarakan kebebasan.
Media sosial dapat menjadi ekosistem yang menerjemahkan kebebasan itu menjadi dialog dan perhatian yang adil bagi semua isu, termasuk disabilitas. Suara mereka yang hidup dengan disabilitas sering kali terpinggirkan dalam narasi besar ini, meskipun sebenarnya isu disabilitas membutuhkan ruang untuk berkembang.
Counterpublic Disabilitas: Menembus Arus Utama
Alih-alih melihatnya semata sebagai persoalan “kekuasaan-pengetahuan” dalam gerak media dominan ala Foucauldian, kerangka Nancy Fraser lebih operasional. Ruang publik itu berlapis, bukan tunggal dan netral. Ada ruang publik dominan, yakni tempat arus utama menentukan apa yang “layak” dibicarakan dan ada counterpublic, ruang tandingan yang dibangun kelompok terpinggirkan untuk menata bahasa, pengalaman, dan tuntutan mereka sendiri.
Dalam ekosistem algoritmik yang mengejar jangkauan dan sensasi, isu disabilitas sering kalah sorotan. Oleh karena itu, kita tidak cukup sekadar mengangkat isu, tapi juga membangun arena tempat suara disabilitas tumbuh, saling menguatkan, dan menembus arus utama.
Fraser menyebut syarat keadilan berkomunikasi sebagai paritas partisipasi: bukan hanya boleh bicara, melainkan pengakuan setara dalam menentukan arah percakapan. Paritas ini runtuh ketika tiga hal saling mengunci: maldistribusi (akses internet, alat bantu, dukungan produksi konten yang timpang membuat jangkauan selalu tertinggal), disrecognition (pengenalan yang keliru, misalnya framing “inspiratif” yang justru mereduksi kompleksitas pengalaman), dan misrepresentation (aturan wacana, dari moderasi hingga logika trending, yang membuat suara tertentu terus kalah relevansi).
Ketika tiga simpul itu mulai longgar, isu disabilitas bergerak dari pinggiran ke pusat wacana bukan karena gemuruh eksposur, melainkan karena syarat keadilan berkomunikasi terpenuhi.
Ruang publik dominan membuka diri pada koreksi dari counterpublic, pengakuan bergeser dari tokenisme ke pengakuan substantif, dan representasi tidak lagi meminjam suara, tetapi menghadirkan subjeknya.
Di titik ini, media sosial bukan sekadar etalase isu; ia menjadi arena penetapan norma tempat aktor-aktor menegosiasikan ulang definisi yang “layak” dibicarakan.
Membangun Ruang Inklusif untuk Semua Keberadaan
Sering kali, kita mendengar term “inklusi” dalam konteks disabilitas. Namun, sering kali juga, inklusi itu tidak lebih dari sekadar pemberian aksesibilitas. Mungkin seribu definisi inklusi bisa muncul, namun inti dari inklusi yang sesungguhnya adalah pengakuan bahwa setiap individu, tanpa terkecuali, memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam masyarakat.
Jika kita merujuk Martin Heidegger, yang menekankan pentingnya “keberadaan,” kita menilai keberadaan seseorang bukan dari apa yang mereka miliki, melainkan dari sejauh mana mereka bisa berpartisipasi setara dalam dunia sosial yang lebih besar. Heidegger menegaskan konsep “being in the world”: kita selalu mengaitkan keberadaan kita dengan dunia sekitar.
Dalam kerangka ini, kita memandang isu disabilitas bukan semata persoalan fisik; kita menempatkannya sebagai soal bagaimana kita mengakui keberadaan orang dengan disabilitas dalam dunia sosial yang lebih luas. Karena itu, kita menolak memisahkan mereka hanya karena perbedaan fisik atau mental.
Heidegger menekankan bahwa keberadaan manusia bersifat terbuka dan selalu terhubung dengan dunia. Konsekuensinya, tatanan sosial tidak boleh mengisolasi penyandang disabilitas.
Mereka berhak hadir dalam narasi bersama sebagai subjek yang publik akui. Karena itu, media sosial harus menjadi ruang yang bukan hanya menerima, tetapi juga menghargai dan memberi kesempatan untuk berpartisipasi setara dalam percakapan sosial.
Narasi yang Menyentuh Hati: Menggugah untuk Tindakan Nyata
Seperti yang telah dikemukakan oleh Ainum Chomsun dalam sebuah webinar dengan tajuk “Strategi Kampanye Inklusivitas di Media Sosial”, Ainum mengatakan bahwa storytelling yang menyentuh hati merupakan elemen penting dalam kampanye isu disabilitas di media sosial. Berangkat dari itu, narasi yang kita bagikan seharusnya tidak hanya menggugah perasaan, tetapi juga harus mendorong tindakan nyata.
Isu disabilitas tidak hanya butuh simpati, tetapi tindakan nyata. Cerita yang menyentuh perasaan kita harus menjadi katalis untuk perubahan nyata dalam masyarakat. Perubahan yang memperjuangkan keadilan dan kesetaraan bagi mereka yang sering kali tidak diberi ruang yang layak.
Jika kita berbicara tentang isu disabilitas, kita tidak hanya berbicara tentang pengakuan, tetapi tentang aksi konkret untuk menciptakan perubahan dalam cara kita memandang dan memperlakukan mereka. Media sosial, dengan semua kemampuannya, harus mampu menggerakkan kita menuju aksi nyata. Baik itu dalam bentuk kebijakan yang lebih inklusif, dukungan terhadap komunitas disabilitas, atau sekadar memberikan ruang bagi isu ini untuk dibicarakan lebih banyak.
Pentingnya Media Alternatif dalam Memperjuangkan Keadilan untuk Disabilitas
Di tengah kebisingan narasi besar yang ada di media sosial mainstream, media alternatif memainkan peran penting dalam memperjuangkan keadilan bagi disabilitas. Media alternatif berperan memberikan ruang yang lebih adil dan memperkecil bias dalam membicarakan isu disabilitas. Media alternatif dapat melibatkan langsung suara mereka yang hidup dengan disabilitas dalam membangun narasi yang lebih inklusif.
Platform digital alternatif ini berupaya menghadirkan perspektif yang autentik dan akurat. Bukan sekadar memberi ruang, melainkan sungguh-sungguh mendengarkan kebutuhan komunitas disabilitas. Landasannya adalah pengalaman disabilitas sendiri, bukan asumsi dari luar.
Fokusnya tidak berhenti pada aspek fisik atau fasilitas. Lebih jauh, platform ini memperjuangkan pengakuan suara dan kesetaraan hak di ruang maya. Dengan begitu, komunitas disabilitas berpartisipasi sebagai pihak setara dan ikut menentukan arah percakapan.
Dengan begitu, media alternatif dapat memperkaya ruang digital dengan kesadaran sosial yang lebih mendalam tentang makna inklusif. Inklusif bukan hanya soal aksesibilitas fisik atau fasilitas. Ia juga menyangkut cara kita memahami dan merayakan keberagaman pengalaman hidup.
Karena itu, narasi perlu bertumpu pada pengalaman disabilitas sendiri, bukan asumsi dari luar. Tujuannya jelas: ruang maya yang tidak sekadar terbuka, tetapi juga mengakui dan memuliakan setiap keberadaan. Media alternatif juga berfungsi mengimbangi nyaringnya gaung-gaung narasi populer lainnya.
Keberadaan yang Berhak Dikenal, Diakui, dan Dirayakan
Dengan kacamata Fraser, coba kita kembali ke pertanyaan yang mendasar: “Mengapa isu disabilitas harus diperjuangkan di media sosial?” Sederhananya karena di media sosial pertarungan atas syarat-syarat keadilan berkomunikasi berlangsung. Perjuangan di media sosial tidak berhenti pada visibilitas, tetapi meliputi perombakan kondisi percakapan agar setara.
Mulai dari memastikan aksesibilitas konten, misalnya teks alternatif, caption, dan desain ramah pembaca layar. Berikutnya, utamakan narasi yang lahir dari pengalaman disabilitas sendiri, bukan sekadar cerita tentang mereka. Setelah itu, jaga konsistensi prinsip inklusif di semua kanal dan format. Agar dampaknya melampaui wacana, hubungkan kerja-kerja edukasi dengan advokasi kebijakan yang konkret.
Dengan cara ini, counterpublic tidak hanya bergema ke dalam, melainkan menembus ruang publik dominan. Pada akhirnya, isu disabilitas hadir sebagai agenda publik; publik memperdebatkannya dan memperjuangkannya bersama, alih-alih muncul lalu tenggelam oleh arus sensasional.
Media sosial bukan sekadar saluran komunikasi. Ia adalah panggung besar, tempat di mana kita bisa bersama-sama menciptakan dunia yang lebih inklusif, lebih adil, dan lebih manusiawi.
Sebuah dunia yang mengakui keberagaman setiap individu, termasuk mereka yang hidup dengan disabilitas. Dunia maya harus menjadi ruang yang merayakan setiap keberadaan, tanpa terkecuali. Karena setiap suara, setiap cerita, setiap keberadaan, berhak untuk terdengar, diakui, dan kita rayakan. []