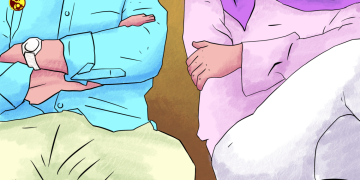Mubadalah.id – Perkembangan dunia psikologi makin hari lumayan meyakinkan. Walaupun salah satunya soal penggunaan bahasa. Yang jelas hal tersebut merupakan bentuk kemajuan. Seperti kita tahu penggunaan bahasa dalam diskursus ilmu mental dan jiwa terjadi penghalusan. Misalnya untuk menyebut cacat kini berganti menjadi disabilitas, kelainan menjadi kebutuhan, atau istimewa. Tak terkecuali istilah gila menjadi ODGJ.
Sebenarnya bentuk derivasi kata ODGJ beragam seperti stress, hilang akal, hilang kesadaran, halusinasi hingga gangguan jiwa dan mental. Akan tetapi fakta di lapangan sebelum ada kata ODGJ masyarakat sering memberi label pada mereka yaitu “orang gila” atau orang tidak waras. Tapi apakah realita ODGJ demikian atau hanya sangkaan masyarakat saja yang tidak tahu.
Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa, istilah orang gila dihilangkan. Hal tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang larangan penyebutan atau pelabelan negatif terhadap individu. Undang-undang tersebut hadir setidaknya untuk mengedukasi masyarakat bahwa orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) itu komplek. ODGJ tidak sesimpel yang masyarakat tahu seperti tertawa atau bicara sendiri.
Memahami ODGJ dari Akar Ilmu Bukan dari Mitos
Masyarakat perlu mengetahui apa latar penyebab mengapa ODGJ hadir di tengah-tengah mereka. Yang terpenting dari sekadar tahu yaitu bagaimana cara kita memperlakukan ODGJ sebagai sesama manusia. Karena ODGJ bagaimana pun juga merupakan ujian bagi kita yang menganggap diri ini normal. Padahal bisa jadi secara hakikat yang menganggap normal justru abnormal.
Soal labelisasi tersebut tentu saya memiliki pengalaman yang tentu terjadi pada tetangga sendiri. Sebut saja Mang Anto. Dia menjadi ODGJ sekitar 25 tahun lalu. Awalnya karena sakit panas yang luar biasa sampai terjadi reaksi kejang. Tapi tetangga bilang ia depresi karena diputus oleh pacarnya. Ada yang bilang juga gangguan tersebut karena Mang Anto memiliki keturunan lewat jalur bapak. Dulu keluarga Mang Anto kaya karena sawah dan kerbaunya banyak. Tapi semua harta itu habis untuk membiayai Mang Anto berobat.
Singkat kisah kini Mang Anto hanya berjalan mondar-mandir dari satu gang ke gang lainnya. Dia duduk termangu kadang tertawa, diam hingga berjingkrak. Dulu saat awal-awal masih dalam ikhtiar berobat Mang Anto masih sering ke mushola. Walaupun kadang jadi objek candaan anak-anak akan tetapi ia masih bisa diajak komunikasi. Tapi kini cerita hanya tinggal cerita.
Mang Anto yang sejak kecil dirawat ibunya harus menerima kenyataan pahit. Ibunya wafat dan memang sejak kecil ia juga belum melihat bagaimana wajah bapaknya. Sosok ibu yang paling mengerti kebutuhan Mang Anto harus pergi meninggalkannya sendiri. Kini Mang Anto dirawat oleh kakak perempuannya yang juga baru kehilangan anak dan suami keduanya.
Melihat Realitas ODGJ Di Sekitar Kita
Rasanya miris, pilu dan saya sebagai tetangga merasa tidak bisa berbuat banyak buat keluarga Mang Anto. Sesekali keluarga kami memberikan sejumlah uang atau beras ketika panen tiba. Mang Anto juga mendapatkan beberapa uang dari kas mushala itupun teramat kecil. Ironisnya sebenarnya keluarga Mang Anto yaitu pakdenya merupakan pejabat di KUA. Tapi akhirnya pakdenya pun tidak lagi memperhatikanya.
Dalam kondisi itu kadang saya merenung seperti yang dijelaskan oleh Bu Nur Rofiah (KUPI) dan Bu Aci (Komisioner Disabilitas Indonesia) bahwa kegetiran hidup seperti disabilitas justru karena faktor ilmu dan ekonomi. Saya bertanya apakah benar nasib kaum papa selalu tidak beruntung seperti yang dialami Mang Anto.
Dalam lagu Pantura nampaknya opini saya tersebut seperti benar. Karena selama ini kaya miskin seolah hoki dan hanya menguntungkan sebelah pihak. Misalnya syair yang ditembangkan Mimi Hj Duniawati bunyinya begini :
Wong mlarat sinandingan bli gableg. Mulek bae penyakite. Parek bae blaine. Adoh bae rezekine. Klantung-klantung ana sing mentung. Klendang-klendang ana sing ngemplang. Lagi dodok ana sing nabok. Miyang meng kali ana sing biti. Dolan ning tangga ana ilang-ilangan. Balik meng umah ana mantri bank nagih utang. Bank dinaan, mingguan, wulanan lan taunan.
Nanging ari wong sugih sih sinandingan drajat kang mulya. Akeh bae rezekine. Adoh bae penyakite. Nantung-nantung ana kang ngupai kalung. Klendang-klendang ana sing ngupai gelang. Lagi dodok mama kuwu liwat kokon nyambut bengkok. Miyang ning kali nemu peti. Dolan ning tangga lagi slametan gadis papat ngenteni dikawin.
Coba bayangan dari syair itu kita bisa menganalisa. Rasanya tentu campur aduk. Ada rasa humor yang terselip. Tapi di sisi lain ada jiwa yang retak bahkan bolong menganga. Rasanya pilu sekali jika kita sandarkan pada keluarga Mang Anto. Keluarga terasa ammul huzni yang bertubi-tubi. Bahkan masih banyak keluarga serupa di luar sana yang tidak bernasib baik sudah melarat, salah satu anggota keluarga ODGJ pula.
Ironis Menyayat Batin, Tapi Fakta Hadir di Tengah Kita
Kadang saya juga berpikir sebenarnya siapa yang gila ketika ODGJ dianggap tidak waras oleh masyarakat. Bukankah kata gila bermakna ganda yaitu sebagai ungkapan wow atau menunjukan kondisi tertentu.
Misalnya kalimat, “Benar-benar gila lu, lagi-lagi bisa juara”. Tapi seringnya kata gila selalu menjadi objek atas kondisi mental seseorang. “Ituloh masnya ketawa-ketiwi sendiri, emang orang gila baru”. Coba perhatikan kata tersebut dan sangat tidak ramah, tidak manusiawi serta bernada negatif.
Mengapa orang sulit sekali berkata yang baik seperti, “Ia tengah mengalami ujian hidup berupa gangguan jiwa dll”. Kemudian saya menyadari bahwa kata demikian hanya dapat terlontar dari mereka yang mengetahui. Itu pun tentu sangat minoritas sekali bahkan kadang diskriminasi datang dari orang pintar. Hal ini terjadi karena masih ada kesenjangan antara intelektual dan fungsi praktis di masyarakat.
Jika perhatikan lebih jauh sebenarnya siapa yang gila. Ada orang waras justru menyalahgunakan jabatan untuk kekayaan. Ada orang yang tega membunuh orang tuanya bahkan kasus mutilasi masih sering terjadi. ODGJ justru terkadang memiliki perasaan ketika mereka dizalimi. ODGJ bahkan batinnya tidak mati dan masih merasakan kepedulian sekitar. Dari sanalah akhirnya kita menyimpulkan siapa sebenarnya yang gila.
Jangan Berhenti Peduli, Terus Nyalakan Harapan
Tentu kita tak kehilangan empati untuk terus membantu. Dalam arti tak boleh menutup mata. Bahwa hal demikian begitu dekat dengan kita. Tinggal sekarang bagaimana kita hadir buat mereka. Karena bagi orang miskin berobat itu mahal. Pendidikan itu seperti di atas bukit sulit diraih. Bagi mereka bisa makan saja sudah lebih baik. Tapi tentu kehidupan bukan soal makan melainkan memberi arti.
Apalah artinya pendidikan tinggi jika di tengah masyarakat kita terasing? Apa gunanya jabatan jika pada akhirnya memberi jarak dengan masyarakat? Sungguh kepedulian kepada sesama bukan soal mereka masuk kelompok rentan melainkan titah agama.
Sesungguhnya orang yang baik adalah dapat bermanfaat buat sesama. Salah satu kebaikan tersebut adalah dimulai dengan memilih bahasa. Seperti ODGJ tersebut bukan gila mereka hanya tidak sadar karena harapan telah pupus oleh kepahitan dunia. []