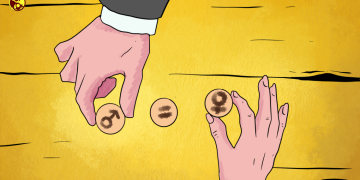“Kalau bukan kita yang mengisi dakwah inklusivitas di medsos, maka konten tak inklusiflah yang bakal bertebaran, ” kata seorang aktivis.
Mubadalah.id – Ungkapan di atas tentu tak asing di telinga para pejuang inklusivitas yang perlahan mengalihkan atensi kampanyenya ke ruang media sosial (medsos).
Tentu, siapapun tak bakal bisa memungkiri bahwa medsos memang telah banyak menyedot arah pandang kehidupan umat. Adagium semisal “No Viral No Justice” bahkan menunjukkan betapa kuatnya hegemoni ruang maya dalam hajat hidup publik.
Kita bisa saja—tentu jika kita mau—mengadopsi adagium semacam itu menjadi “No Viral No Inclusivity” untuk menunjukkan krusialnya peran medsos hari-hari ini. Namun, sadarkah kita bahwa kampanye baik tentang inklusivitas di ruang invisible itu senantiasa dibayang-bayangi oleh ancaman kapitalisme modern?
Medsos dan kapitalisme digital
Dominasi medsos sejatinya tidak dapat lepas dari perkembangan kapitalisme modern yang berekspansi menginvasi ruang digital.
Medsos kini menjelma menjadi raksasa adidaya yang memegang kendali atas produksi sekaligus distribusi informasi (Gabul, 2024). Di Indonesia, dengan rata-rata konsumsi orang lebih dari tiga jam per hari, medsos berperan besar dalam membentuk opini publik.
Merujuk pada analisis wacana Van Dijk, hal ini berarti bahwa medsos menjelma menjadi otoritas simbolik yang punya peran kuasa. Konsekuensinya, medsos berubah menjadi arena persaingan terbuka lagi bebas yang menjanjikan keuntungan simbolik maupun material.
Wacana tentang kampanye inklusivitas pada akhirnya mesti bersaing dengan jutaan narasi lain—baik afirmatif maupun resisten—dalam situasi information overload alias banjir kabar. Dan seperti yang kita tahu, banjir tak pernah jernih. Selalu ada sampah dan kotoran yang turut hanyut lalu menyangkut di otak manusia.
Medsos dan bias ruang
Tren penggunaan medsos untuk kampanye inklusivitas yang terus menanjak menunjukkan deliberasi dan demokratisasi ruang publik. Siapapun, tanpa terikat pada perbedaan modal (capital distinction) seperti ujaran Bourdieu, kini dapat menyuarakan gagasan ini secara bebas.
Namun, agaknya hal ini bersifat subjektif saja. Maksudnya, pada peninjauan yang lebih luas, medsos nyatanya juga tak lepas dari sekat pembatas. Ruang digital yang katanya bebas lagi merdeka ternyata masih harus tunduk pada otoritas super otoriter bernama algoritma.
Ini menunjukkan adanya bias ruang yang sangat nyata. Kemerdekaan yang medsos janjikan, pada tahap kritisnya, agaknya sekadar kesemuan yang terfetisisasi. Demokratisasi yang semula gembar-gembor nyaring, sepertinya tak lebih dari janji manis yang kini berasa sepah dan kadangkala menyakitkan.
Ruang kreatif-alternatif, bukan jalan tunggal
Kesadaran publik akan realita medsos yang tak pernah murni bebas dan tetap ditunggangi kapitalisme modern semestinya memantik sebuah kesadaran. Yakni, medsos seyogyanya berdiri sebagai ruang kreatif-alternatif, alih-alih menjadi jalan tunggal mainstream sebagaimana shirath al mustaqim.
Untuk kepentingan apapun, kampanye inklusivitas utamanya, orientasi publik penting untuk bergeser pada aktivitas-aktivitas di ruang lain yang tak terpagari oleh algoritma. Sebelum media sosial hadir, kerja-kerja inklusivitas telah berlangsung dan juga membawa dampak. Kesadaran ini mestinya membuat kita tak melulu bergumul pada dependensi mutlak.
Kerja-kerja lapangan
Perlahan, kita perlu berangsur hijrah dari zona nyaman platform digital menuju kerja-kerja lapangan di dunia nyata yang sungguh melibatkan manusia.
Bagaimanapun, manusia selaku sang khalifah sekaligus sang abdi tuhan merupakan subjek utama peradaban (al hadlarah wa al ‘umran). Misalnya, kita perlu mulai lebih banyak membangun diskusi bersama kalangan marjinal, melakukan advokasi di rumah-rumah ibadah, merimbuk kalangan “beruntung”, juga kerja-kerja teknis lain.
Kita bisa mencontoh inisiatif positif nan progresif dari Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta yang baru-baru ini bekerja sama dengan Yayasan Yakkum guna membangun kota inklusif. Keteladanan ala Pemkot Yogyakarta ini menunjukkan bahwa inklusivitas mesti bermanifestasi di dunia nyata, bukan melulu menjadi realitas maya di bawah represi algoritma.
Hijrah dari ketergantungan terhadap medsos berarti selangkah membebaskan generasi mendatang dari ancaman kapitalisme gaya baru yang sangat mungkin bakal lebih mengerikan. Tentu, tak ada di antara kita yang rela bila mereka terjajah bahkan sebelum beranjak dewasa. []