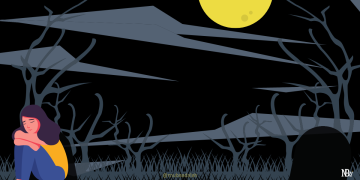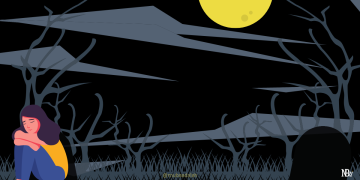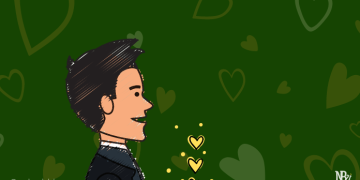Mubadalah.id – Sebagai ruang kolaborasi, inklusi, dan refleksi, forum internasional 2R: Ruang Riung banyak memberikan oleh-oleh pengetahuan yang saya bawa pulang. Perihal refleksi, fokus saya tertuju pada satu materi yang dipaparkan dengan jenius oleh Mohamed Imran Mohamed Taib dari Dialogue Centre, Singapura. Ia membawakan materi dengan tajuk “Beyond the Echo Chamber: Brave Space for Genuine Dialogues”.
Dari sini, saya mulai membaca dua istilah yang Ia bawakan dengan cara yang lebih hidup. Echo Chamber, dapat saya definisikan sebagai ruang gema yang membuat kita mendengar yang seirama dan menepis liyan. Sebagai tandingan, brave space hadir sebagai ruang negosiasi yang cukup aman dan saling menghormati.
Brave space, ibarat sebagai ruang berani yang dapat mendengar perbedaan utuh, menguji argumen tanpa merendahkan, dan percakapan untuk mengarusutamakan isu-isu kelompok rentan dapat menemukan momentumnya.
Dalam konteks ini, media alternatif dapat menjelma sebagai wujud brave space yang paling mungkin menembus gema, terutama untuk mengarusutamakan isu disabilitas. Narasi-narasi inklusif yang terbangun di dalamnya dengan melibatkan pengalaman difabel sendiri, dapat menautkan pengalam ke meja kebijakan yang lebih adil.
Polarisasi, Ruang Digital, dan Isu Disabilitas yang Mudah Tenggelam
Sebagai digital society, tak terasa kita sering terjebak ke dalam polarisasi. Dalam presentasinya, Mohamed Imran menyatakan bahwa polarisasi itu sendiri yang kemudian mengikis kohesi sosial, memperlemah ekonomi, dan membuat masyarakat retak ke dalam kelompok yang saling curiga.
Jarak ideologis berubah menjadi jarak psikologis, sehingga pihak lain terasa sebagai ancaman. Ketika jarak itu melebar, percakapan lebih sering berkisar pada adu posisi tentang politik harian, sentimen keagamaan, dan perang budaya di ruang digital. Kecurigaan lalu mudah berpindah ke afiliasi dan sumber kabar, sehingga isu yang memerlukan penjelasan tenang seperti hak dan akses kelompok rentan tenggelam.
Dalam iklim seperti itu, isu kelompok rentan harus berebut panggung dengan banyak isu lain. Isu tersebut bukan hilang, namun mudah tenggelam meski menyentuh kebutuhan yang begitu nyata.
Ruang digital memperkuat pusaran ini. Ada empat efek yang menonjol: ruang gema yang hanya memantulkan suara seirama, bias seleksi yang menyempitkan jangkauan, penyebaran disinformasi yang melaju lebih cepat daripada klarifikasi, serta tata kelola yang lemah. Di tengah arus itu, alih-alih membincang inklusivitas aksesibilitas bagi difabel, inspirational porn kerap menjadi label bagi mereka.
Selain itu, ada beberapa hal yang membuat polarisasi kian cepat. Ketimpangan yang membuat akses tidak merata, defisit kepercayaan yang membuat klarifikasi sulit diterima, dan pudarnya rasa kebersamaan yang membuat pengalaman difabel bukan urusan bersama.
Bagi kelompok difabel, ketimpangan ini berubah menjadi hambatan yang berlapis terhadap aksesibilitas. Hal tersebut bertemu dengan pusaran ruang digital tadi. Isu disabilitas makin mudah tenggelam. Pada titik ini, kita memerlukan tandingan yang menjaga percakapan tetap waras dan manusiawi.
Empat sikap yang Membuka Ruang
Agar sebuah percakapan tidak terseret ke dalam polarisasi tertentu, Mohamed Imran menawarkan bekal dasar untuk berdialog. Kita perlu mengawali dari kepedulian yang sama, bukan dari posisi yang kaku. Yang berbeda pandangan, kita perlakukan sebagai lawan bicara, bukan musuh.
Kita longgarkan cara pandang yang serba biner, keluar dari label, mencari irisan kepentingan, lalu menaruh pengalaman nyata sebagai kompas. Dari sini, ada harapan tumbuh empat sikap sederhana curiosity, courage, commitment, dan compassion untuk menjaga ritme interaksi tetap jernih.
Curiosity membuat kita berangkat dari pertanyaan yang tepat: apa yang luput dari pandangan kita, siapa yang terdampak, dan seperti apa hambatannya di kehidupan sehari-hari. Sikap ini menuntun kita mendengar pengalaman difabel sampai tuntas, memeriksa data, lalu menautkannya dengan kewenangan yang relevan.
Courage memberi tenaga untuk mengangkat temuan yang tidak populer, serta merombak narasi yang hanya mengharukan menjadi narasi yang memulihkan hak.
Commitment memastikan perhatian tidak berhenti. Setelahnya, kita kembali menengok, membenahi jika perlu, dan mencatat kemajuan sehingga arah perubahan tampak.Compassion memastikan subjek yang kita hadirkan sebagai narasi, diperjuangkan sebagai pribadi bermartabat, bukan sekadar objek liputan.
Media Alternatif sebagai Brave Space: Mengapa Penting bagi Isu Disabilitas?
Media alternatif bekerja pada lapis narasi. Ia menjadi brave space ketika cara bercerita memusat pada kepedulian bersama, memberi tempat bagi pengalaman difabel sebagai sumber pengetahuan, dan menjaga nada dialog tetap mengakomodasi perbedaan. Dengan itu, isu disabilitas terasa dekat dan relevan bangi banyak orang.
Praktiknya sederhana. Media alternatif mengekspresikannya melalui artikel, feature mendalam, testimoni, foto, cerita, maupun esai reflektif yang memusat pada pengalaman difabel. Cerita yang lahir dari pengalaman diverifikasi seperlunya, pemilihan diksi yang memuliakan, dan narasi dijahit dengan data sederhana serta rujukan layanan atau kebijakan yang relevan.
Dari sini, hasilnya adalah aliran yang lebih jernih. Perhatian beralih dari sensasi ke perbaikan yang nyata sehingga percakapan menguatkan ekosistem aksesibel inklusif: kota yang dapat dijangkau, sekolah yang adaptif, tempat kerja yang menyediakan akomodasi, dan layanan digital yang ramah teknologi bantu. Inilah cara media alternatif menyimbangi nyaringnya arus wacana agar isu disabilitas juga masuk di pusaran pembahasan publik.
Membingkai Pengalaman menjadi Aksesibilitas
Brave space akan menjadi sebuah arena yang berpotensi mengarahkan pada tujuan meski perjuangan itu masih panjang. Setiap kisah yang telah diverifikasi menuntun ke tiga pertanyaan sederhana: apa yang bisa diubah, siapa yang berwenang, dan bagaimana mengukurnya.
Bila jawaban mulai tampak, misalnya akses setara dijadikan patokan, partisipasi difabel bermakna di setiap tahap, serta keberpihakan pada yang rentan menjadi acuan keputusan, maka empati dan pengalaman berubah menjadi akses.
Di sini, media alternatif berperan sebagai jembatan yang menautkan. Mendengarkan pengalaman, mendokumentasikannya, menjaganya agar seimbang dari nyaringnya gaung narasi arus utama. Media alternatif menjaga agar cerita tidak berhenti di linimasa melainkan bergerak menuju meja kebijakan untuk mewujudkan aksesibilitas.
Dari presentasi Muhamed Imran saya belajar bahwa melampaui echo chamber bukan perkara memenangkan teriakan, melainkan menyiapkan ruang di mana orang boleh berbeda tanpa saling meniadakan.
Media alternatif menyediakan ruang itu dengan cara yang Intinya adalah menjaga kualitas percakapan agar cerita bertemu data dan jalan kebijakan. Ketika kebiasaan kecil ini berjalan konsisten, isu disabilitas tidak lagi muncul sebagai momen yang sentimental. Namun sebagai urusan bersama yang mewujudkan ekosistem aksesibel‑inklusif. []