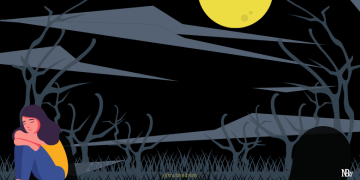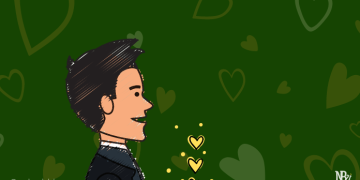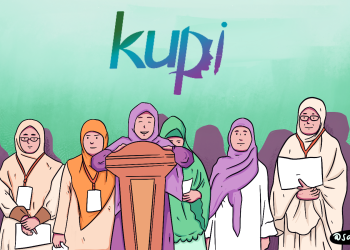Mubadalah.id – Fenomena pengalaman perempuan yang mengajukan gugatan cerai semakin sering muncul di ruang publik. Dalam masyarakat yang masih menempatkan laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan pengambil keputusan utama, langkah perempuan untuk mengakhiri pernikahannya melalui jalur hukum sering kita pandang sebagai tindakan yang melampaui peran pada umumnya.
Padahal, keputusan tersebut umumnya berdasarkan pada pertimbangan rasional dan pengalaman nyata dalam menghadapi kekerasan, ketimpangan relasi, atau ketidakadilan yang terjadi di dalam rumah tangga.
Di banyak kasus, perempuan menggugat cerai bukan karena tidak menghargai ikatan pernikahan, melainkan karena ikatan itu sendiri telah menjadi beban dan ruang ketidakadilan. Keputusan mereka sering muncul setelah melalui pergulatan panjang antara keinginan untuk bertahan demi anak dan keluarga, dengan kenyataan bahwa kebahagiaan dan keselamatan diri terancam.
Gugatan cerai bukanlah puncak egoisme, melainkan puncak kesadaran diri bahwa mereka berhak hidup dengan layak, terhormat, dan mendapatkan cinta tanpa kekerasan atau penindasan. Namun sayangnya, pandangan publik terhadap perempuan penggugat cerai masih penuh dengan stigma.
Dalam masyarakat patriarkal, perempuan yang berani mengambil keputusan keluar dari pernikahan sering kita anggap tidak sabar, tidak setia, bahkan tidak tahu diri. Sebaliknya, laki-laki yang menceraikan istrinya justru kita nilai “berani”, “tegas”, atau “punya alasan logis.” Ketimpangan cara pandang inilah yang membuat perjuangan perempuan sering kali tidak mendapat tempat yang adil.
Perceraian Hamish Daud dan Raisa
Fenomena terbaru tentang perceraian Hamid Daus dan Raisa, seorang publik figur yang menggugat cerai istrinya karena dianggap terlalu sibuk bekerja, mencerminkan betapa kuatnya stigma terhadap peran perempuan. Istri yang berkarier ia anggap mengabaikan kewajiban domestik. Seolah-olah tugas perempuan hanya berputar di dapur, sumur, dan kasur.
Padahal, bekerja bagi banyak perempuan bukan hanya soal ekonomi, melainkan bentuk aktualisasi diri dan kontribusi terhadap keluarga. Ketika kesibukan suami kita anggap wajar, namun menganggap kesibukan istri sebagai ancaman, maka jelas ada standar ganda dalam menilai peran gender.
Sementara itu, muncul juga dalam tayangan salah satu podcast Denny Sumargo. Di mana seorang istri yang bercerai setelah suaminya naik pangkat menjadi aparatur PPPK. Perceraian tersebut berkaitan dengan anggapan bahwa sang istri “kurang memperhatikan penampilan” dan “tidak lagi mengurus diri.”
Fenomena ini menunjukkan bagaimana masyarakat masih sering menilai relasi rumah tangga dari perspektif yang bias gender, di mana tanggung jawab menjaga keharmonisan dan penampilan lebih banyak terbebankan pada perempuan.
Dua peristiwa ini , memperlihatkan wajah nyata dari ketimpangan gender di Indonesia. Perempuan kita tuntut untuk selalu mengalah, berkorban, dan setia, bahkan ketika hak-haknya terabaikan. Mereka diajarkan untuk “tahan demi anak” dan “ikhlas demi keluarga,” tanpa kita beri ruang untuk menyuarakan penderitaan yang ia rasakan.
Perempuan penggugat cerai justru sering kali datang dari situasi rumah tangga yang tidak sehat, adanya kekerasan psikis, tekanan ekonomi, atau ketidaksetaraan peran. Mereka bukan ingin memutus ikatan, melainkan ingin menyelamatkan diri dan anak-anak dari situasi yang lebih buruk. Dalam konteks ini, gugatan cerai bukanlah tindakan melawan suami, tetapi tindakan melawan ketidakadilan.
Menilik Pengalaman Perempuan
Berpihak pada pengalaman perempuan berarti memberi ruang untuk mendengarkan suara mereka tanpa prasangka. Kita perlu bertanya, mengapa perempuan harus selalu menanggung beban moral lebih berat daripada laki-laki? Mengapa perempuan yang bercerai kita anggap gagal, sementara laki-laki yang menikah lagi dianggap berhasil? Keadilan gender menuntut kita untuk memandang hubungan pernikahan secara setara sebagai kemitraan, bukan hierarki.
Hukum dan agama sebenarnya telah memberi ruang bagi perempuan untuk memperjuangkan haknya. Dalam hukum Islam, kita mengenal konsep khulu’, yaitu hak perempuan untuk meminta cerai ketika tidak lagi mendapatkan ketenangan batin. Namun dalam praktik sosial, hak ini sering dipersulit oleh budaya yang menilai perempuan harus selalu patuh. Maka, perjuangan perempuan bukan hanya di meja pengadilan, tetapi juga di medan sosial yang terpenuhi stigma.
Fenomena seperti ini seharusnya membuka kesadaran baru bagi masyarakat. Bahwa perempuan bukan sekadar pelengkap rumah tangga, melainkan subjek yang memiliki hak penuh atas kehidupannya. Ia berhak memilih, menentukan, dan memperjuangkan kebahagiaannya tanpa harus menunggu “izin” dari pandangan sosial yang bias.
Berpihak pada pengalaman perempuan bukanlah upaya untuk memusuhi laki-laki, tetapi usaha menegakkan keadilan di ruang paling personal dalam rumah tangga. Ketika perempuan memiliki keberanian untuk berkata “cukup,” sesungguhnya mereka sedang menegaskan kemanusiaannya. Gugatan cerai, dalam konteks ini, bukanlah akhir dari kisah cinta tetapi awal dari kebebasan dan pemulihan. []