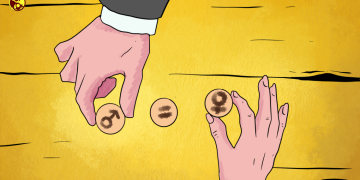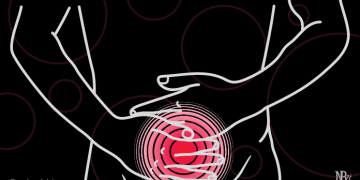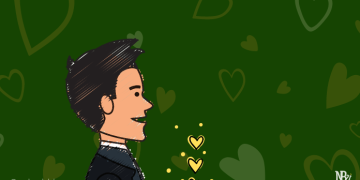Mubadalah.id – Dalam konsepsi pria dan wanita sebagai makhluk yang setara, kedudukan wali nikah kerap dipandang sebagai bentuk ketidaksetaraan.[1] Karenanya, dalam dokumen CLD-KHI (Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam) digagas bahwa wali tidak lagi meletakkannya sebagai salah satu rukun perkawinan.
Menurut Ibnu Rusyd sebagaimana diringkas oleh Jasser Auda, perbedaan pendapat mengenai perlu tidaknya seorang wali dalam suatu pernikahan disebabkan tidak adanya ayat maupun sunnah yang secara eksplisit menyebut syarat wali dalam nikah.
Sejumlah hadist yang menyiratkan kewajiban wali dinilai tidak seluruhnya layak menjadi hujjah untuk memasukkan wali sebagai rukun perkawinan. Jika memang merupakan hal yang wajib ada dalam suatu akad nikah, maka seharusnya terdapat ayat maupun riwayat yang menjelaskan jenis, tingkatan dan klasifikasi wali.[2]
Pada sisi lain, dalam menjelaskan kewajiban wali nikah Sayyid Sabiq mengutip uraian Thabari yang mengisahkan pernikahan Sayyidah Hafshah-putri sahabat Umar bin Khattab-dengan Rasulullah. Pada saat itu Sayyidah Hafshah berstatus janda, akan tetapi Ia tidak menikahkan diri sendiri melainkan dinikahkan oleh Umar bin Khattab. Seandainya Sayyidah Hafshah dapat menikahkan dirinya sendiri, maka Rasulullah tidaklah perlu meminang kepada sahabat Umar bin Khattab.[3]
Keengganan Wali
Perdebatan perihal kedudukan wali sebagai rukun pernikahan kiranya merupakan khilafiyah yang memang niscaya. Kedua pendapat tersebut sama-sama memiliki landasan dalil syar’i. Secara de jure, Kompilasi Hukum Islam nyatanya telah mendudukkan wali sebagai salah satu rukun perkawinan. Kecil kemungkinan untuk berharap perkawinan yang terlaksana tanpa wali kita anggap sah di hadapan hukum Indonesia.
Namun demikian, gagasan peniadaan wali kiranya perlu kita lihat sebagai satu indikasi adanya persoalan dalam pelaksanaan perwalian nikah di Indonesia. Salah satu permasalahan tersebut ialah kerap terhambatnya kehendak nikah karena wali dari seorang perempuan menolak untuk menikahkan.
Dalam fiqh, wali memang berhak untuk untuk menolak, akan tetapi penolakan tersebut harus berdasarkan pada alasan-alasan tertentu yang sah. Salah satu alasan sah tersebut adalah tidak adanya kesetaraaa (kafa’ah) antara kedua mempelai.
Seorang wanita yang terjaga dari perbuatan tercela misalnya, tidak setara dengan lelaki yang seringkali berbuat tercela. Dalam kondisi ini wali memang berwenang menolak perkawinan. Akan tetapi yang perlu kita ingat, para ulama berbeda pendapat terkait kriteria kafa’ah.
Musyawarah Wali
Kewenangan ini pada satu sisi seperti mengebiri hak perempuan untuk menentukan hal yang terbaik bagi dirinya. Akan tetapi pada sisi lain kewenangan ini dapat menjadi media bagi wali untuk memastikan sang anak memilih pasangan yang tepat. Agar anak tidak memilih pasangan karena buta oleh cinta dan nafsu belaka.
Perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban di antara suami dan istri. Pada umumnya dalam suatu perkawinan akan mengalami fase kehamilan, kelahiran anak, hingga merawat anak yang menimbulkan berbagai tanggung jawab. Seluruh hal tersebut tidak hanya membutuhkan cinta agar dapat terlalui, namun juga membutuhkan kesabaran, ketekunan dan rasa tanggung jawab baik dari suami dan juga istri.
Orang tua yang telah menjalani bahtera rumah tangga pada umumnya lebih memiliki kemampuan untuk menilai, siapa yang pantas dan mampu menemani anaknya menjalani hidup berumah tangga. Sebagai seorang wali yang menyayangi anaknya, Ia akan berupaya memastikan anaknya menikahi seorang lelaki yang berpotensi mampu mewujudkan perkawinan yang sakinah, mawaddah wa rahmah.
Seyogyanya pasangan yang tidak memperoleh restu, segera bermusyawarah dengan wali untuk memahami alasan penolakannya. Melalui musyawarah, kedua calon mempelai dapat berupaya menepis kekhawatiran wali. Utamanya juga untuk membuktikan bahwa keduanya siap menjalani bahtera rumah tangga dengan baik.
Penetapan Wali Adhal
Tetapi tidak jarang wali memang bertindak sewenang-wenang. Misalnya wali tidak mau menikahkan anak sebelum sang anak memberikan sejumlah uang tertentu. Atau wali menolak semata-mata karena calon suami berasal dari suku atau daerah tertentu. Singkatnya penolakan tersebut tidak berdasar pada rasa kasih sayang kepada anak.
Dalam kondisi di mana wali menolak perkawinan karena suatu alasan yang tidak sah atau tidak patut, maka calon mempelai perempuan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama agar wali ditetapkan sebagai wali yang adhal. Berdasarkan penetapan ini, perkawinan dapat wali hakim lakukan, yaitu Penghulu yang ada pada kantor urusan agama.
Namun demikian, tidak semua permohonan wali adhal pasti terkabulkan. Jika alasan wali menolak merupakan alasan yang sah, sudah barang tentu permohonan akan ditolak. Kompilasi Hukum Islam sendiri tidak mengatur apa yang tergolong sebagai alasan yang sah dan tidak pula memberikan suatu pengaturan yang terperinci mengenai alasan apa yang mengakibatkan wali dapat dinyatakan adhal.
Karena ketiadaan aturan tersebut, maka Hakim Pengadilan Agama akan merujuk kembali kepada kitab-kitab fikih sebagai dasar penilaian atas alasan penolakan perkawinan oleh wali. Karenanya, antara satu putusan dan putusan lainnya bisa berbeda-beda bergantung dengan dalil fikih yang dijadikan landasan.
Salah satu alasan sah yang dapat wali gunakan untuk menolak perkawinan ialah berbedanya agama suami dengan perempuan yang akan Ia nikahkan.
Yang Mulia Hakim Agung Kamar Agama, Edi Riadi dalam disertasinya yang berjudul Dinamika Putusan Mahkamah Agung RI Dalam Bidang Perdata Islam menemukan bahwa menurut sejumlah putusan Mahkamah Agung, wali yang menolak perkawinan atas dasar tidak beragama islamnya suami tidak dapat dinyatakan sebagai wali yang adhal.[4] Selain itu adalah sah kiranya jika wali menolak perkawinan karena adanya halangan perkawinan seperti kedua calon mempelai masih merupakan saudara sesusuan (vide Pasal 39 KHI).
Memaksimalkan Jalan Keluar
Tidak jarang penolakan wali berujung pada praktik perkawinan tidak tercatat oleh wali yang tidak berwenang. Hal ini tentu cenderung merugikan karena selain tidak memiliki bukti Akta Nikah, perkawinan tersebut juga berpotensi tergolong sebagai perkawinan yang tidak sah.
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mencatat terdapat 1.530 permohonan wali adhal pada tahun 2024. Jumlah ini menunjukkan ada cukup banyak anak yang memohon agar walinya dinyatakan sebagai wali yang adhal. Daripada kedua calon mempelai memaksa untuk melangsungkan perkawinan secara tidak tercatat.
Lebih baik mengajukan penetapan wali adhal dan meminta agar perkawinan dilangsungkan oleh seorang wali hakim. Sehingga perkawinan dapat berlangsung secara tercatat dan lebih memberikan kepastian hukum kepada kedua mempelai. []
[1] Marzuki Wahid, Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam Dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia (Cirebon: Institut Studi Islam Fahmina, 2014). Hlm 216
[2] Jasser Auda, Ringkasan Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid (Jakarta: Qaf Media, 2019). Hlm. 331
[3] S Sabiq, Fikih Sunnah Vol 3 (Cakrawala Publishing, n.d.). Hlm. 372
[4] Edi Riadi, Dinamika Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Bidang Perdata Islam (Jakarta: Gramata, 2011). Hlm. 85