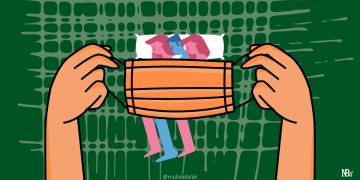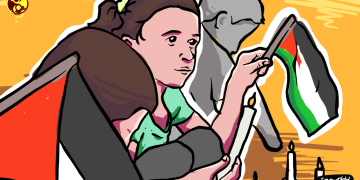Mubadalah.id – Sejarah ditulis oleh para pemenang, sedangkan sastra memberi ruang bagi suara-suara yang tak masuk dalam daftar fakta sejarah. Jika sebuah fakta tak termuat dalam catatan sejarah, sastra mengambil alih untuk mengisi kekosongan tersebut.
Orang yang menulis sastra tergolong berani. Jikalau mencatat kebenaran yang tersembunyi, mengabadikan peristiwa yang hendak terlupakan, dan memberi wajah manusia pada derita yang ingin terhapuskan oleh penguasa yang tak jujur.
Sosok Gunawan Budi Susanto, yang akrab dipanggil Kang Putu melalangbuana bergelut di dunia sastra. Karya-karyanya, seperti Nyanyian Penggali Kubur (2011, 2016) dan Penjagal Itu Telah Mati (2016) tergolong menggemparkan dunia sastra, karena mengangkat peristiwa kelam tahun 1965.
Salah satu yang penulis ulas adalah novel berjudul Dendam (Penerbit Cipta Prima Nusantara, 2019). Novel ini menghadirkan dua luka besar yang jarang terakui secara terbuka dalam sejarah formal. Tragedi pasca G30S 1965 di Blora dan penderitaan rakyat akibat proyek pabrik semen di Peguungan Kendeng. Keduanya merupakan kisah luka panjang rakyat kecil. Mereka tidak hanya menderita secara politik dan ekonomi, melainkan batin dan spiritual.
Dengan jeli, Gunawan menyulam dua konteks sejarah dalam satu lintas generasi. Dalam tangkapan penulis, ia menyajikan kisah perempuan tangguh yang hidup dalam bayang stigma politik dan eksploitasi kapital.
Melalui Dendam, sastra menjadi ruang rekonsiliasi dan untuk pembaca yang hidup dalam suatu bangsa yang memikul trauma kolektif 1965 dan luka ekologis hari ini. Novel Dendam mengisahkan dua bentuk kekerasan. Baik politik dan ekonomi berwujud dalam kehidupan masyarakat sekitar hutan jati Blora dan pegunungan kapur Kendeng.
Pembunuhan Ekologi dan Kemanusiaan
Pertama, tragedi kelam 1965 adalah luka masa lalu. Pasca G30S 1965, operasi “Kikis” di Blora sebagai alat pembersihan ideologis. Seperti terkontaminasi “Komunisme” dilenyapkan. Bahkan, yang tertuduh PKI tanpa bukti, harus menelan pil pahit. Mereka tertangkap, dipenjara, disiksa, dan dicap sebagai antek PKI sebagai organisasi terlarang.
Tak hanya itu, peristiwa kelam 1965 membersihkan “Komunisme” merupakan agenda CIA sekaligus menggulingkan kekuasaan Soekarno sebagai Presiden Indonesia. Sehingga stigma PKI melekat hingga ke anak cucu. Menutup ruang hidup dan masa depan.
Kedua, proyek pembangunan pabrik semen di Pegunungan Kendeng membawa petaka ekologis dan sosial. Gunung kapur yang seharusnya menjadi sumber air dan kehidupan bagi petani kecil, harus gigit jari. Sumber daya alam itu terancam habis tergali. Atas peristiwa tersebut, justru perempuan menjadi garda terdepan dalam menyuarakan. Ibu-ibu kendeng menolak logika pembangunan yang menindas alam.
Oleh karena itu, kedua peristiwa tersebut, Gunawan Budi Santoso secara cermat menunjukkan benang merahnya. Keduanya merupakan bentuk kekerasan negara terhadap rakyat. Dari pembunuhan fisik menjadi pembunuhan ekologi dan kemanusiaan.
Perempuan dalam Sastra Novel “Dendam”
Novel Dendam menghadirkan tiga generasi perempuan dalam pusat narasi. Ibu Rini, Rini, dan Tinuk. Ketiganya merupakan representasi perempuan yang harus menanggung luka sejarah, namun juga perempuan yang menolak tunduk pada nasib. Dalam novel tersebut, tergambarkan sosok Ibu Rini, tubuh yang terlecehkan, jiwa yang tetap menjaga. Sosok Ibu Rini merupakan simbol generasi 1965, ia tertuduh tanpa bukti, diperkosa bahkan dihancurkan martabatnya.
Gunawan tidak memposisikannya sebagai korban pasif, Ibu Rini menjadi ibu yang melindungi, mendidik, dan mengajarkan nilai kemanusiaan pada anaknya. Dalam diamnya, Ibu Rini mengajarkan bahwa penderitaan tidak harus melahirkan kebencian.
Meskipun tubuhnya rusak oleh kekuasaan, jiwanya tetap merawat kehidupan. Ia “membunuh” suaminya dalam cerita agar anaknya bisa hidup tanpa stigma. Sebuah metafora pengorbanan ibu yang menanggung beban sejarah sendirian demi anaknya.
Rini, sosok perempuan yang melawan nasib, menjadi cerminan perempuan yang tumbuh di antara stigma dan trauma. Sejak kecil ia diejek sebagai “anak PKI”. Pernikahan dengan Murdani dianggap menjadi titik terang, namun retak kembali ketika trauma masa lalu menghantam rumah tangganya. Saat suaminya selingkuh, Rini tidak larut dalam “pasrah”.
Ia memutuskan pergi menjadi TKW di Hongkong. Keputusan itu menegaskan bahwa posisi perempuan bisa mandiri dan berdikari. Rini menunjukkan bahwa perempuan dapat menentukan hak untuk memilih jalan hidupnya. Bahkan lingkungan sekitarnya menganggap bahwa perempuan hanya sebagai pelengkap laki-laki. Keberanian Rini mengakui asal-usulnya dan menanggung masa lalu menunjukkan bahwa perempuan hanya menjadi agen penyembuhan. Bukan sebagai korban dari sejarah yang bengis.
Keberpihakan terhadap Rakyat Kecil
Tinuk, anak tunggal Rini, menjadi representasi generasi baru. Sosok perempuan yang cerdas, sensitif, dan memiliki kesadaran sosial. Ia tumbuh dalam nuansa konflik keluarga. Keadaan yang justru ia menempa kepekaan dan kekuatan. Tinuk menjadi aktivis yang mendukung perjuangan ibu-ibu Kendeng menolak pabrik semen.
Keberpihakannya terhadap rakyat kecil merupakan bentuk “reinkarnasi” dari semangat korban 1965. Ia menolak ketidakadilan dalam bentuk baru. Melalui Tinuk, Gunawan dalam novel Dendam, menyiratkan bahwa sejarah tak hanya berhenti masa lalu, ia terus berkembang dan menuntut keberanian untuk melawan.
Sehingga, sastra dalam Dendam sebagai arsip yang hidup. Gunawan menulis apa yang tersembunyikan dalam sejarah. Ia mengubah luka menjadi narasi, trauma menjadi kesadaran. Sastra dalam hal ini berfungsi sebagai dokumentasi emosional dan moral dari bangsa yang enggan mengakui kesalahannya.
Sementara, sejarah resmi negara menulis kisah 1965, peralihan kekuasaan jatuhnya Presiden Soekarno (Revolusi Kemerdekaan) ke tampuk kekuasaan Presiden Suharto (Orde Baru). PKI dan anteknya dianggap “pemberontakan yang harus diberantas”. Gunawan menulis sebagai kisah kemanusiaan yang terinjak. Ia menulis dalam sudut pandang rakyat biasa, terutama perempuan. Tubuh dan batin perempuanlah, kekerasan negara paling nampak terlihat.
Narasi Ekofeminisme dalam Novel Dendam
Konflik Kendeng tersiar dalam berita hanya muncul sesekali saat aksi besar, namun Gunawan mampu memoles dalam suatu kisah yang menyentuh. Ia menyoroti posisi perempuan menjadi garda terdepan dalam menjaga tanah dan air. Dalam konteks ini, Dendam merupakan narasi ekofeminisme, menggambarkan bahwa kerusakan alam dan penindasan terhadap perempuan mempunyai akar yang sama, patriarki dan keserakahan kekuasaan.
Menariknya, Gunawan tidak berhenti pada penderitaan. Ia memunculkan gagasan rekonsiliasi, yakni pengakuan dan pengampunan. Ibu Rini berani mengakui trauma masa lalunya kepada anak dan cucunya. Rini menyadari kesalahannya sendiri dalam keluarga, Tinuk memaafkan ayahnya. Pengakuan membuat luka menjadi terang, pengampunan yang dapat membuat hidup kembali bergerak.
Filosofi Jawa yang bernilai luhur “Sura dira jayaningrat, lebur dening pangastuti” (kekuasaan dan amarah akan luluh oleh kelembutan dan kasih). Gunawan mengingatkan bahwa dendam hanyalah racun yang terwariskan dari generasi ke generasi. Pengakuan dan pengampunan adalah jalan untuk memutus rantai kekerasan sejarah.
Perempuan sebagai Penjaga Kemanusiaan: Membaca Dendam Konteks Indonesia Kini
Novel yang Gunawan tulis, dengan jelas menolak sub-ordinasi perempuan. Perempuan dalam Dendam bukan hanya sebatas “pendamping” laki-laki, melainkan subjek yang berpikir, memutuskan, dan bertindak. Mereka menjadi tulang punggung moral masyarakat ketika laki-laki terperangkap dalam kompromi dan kelemahan.
Gunawan menghadirkan potret perempuan yang kompleks, menghadirkan sosok Ibu Rini yang penuh luka, namun tetap mencintai. Rini yang tegar dalam kehilangan. Tinuk yang berani menentang struktur kekuasaan. Ketiganya saling berhubungan menjadi mata rantai kekuatan yang menyembuhkan luka sejarah.
Posisi perempuan dalam novel ini menunjukkan bahwa perjuangan melawan ketidakadilan tidak hanya menyoal ideologi, melainkan keberanian menjaga kemanusiaan di tengah reruntuhan kekuasaan. Konteks itu, perempuan menjadi simbol melawan lupa.
Dalam masa kini, novel Dendam sangat relevan. Situasi ketika luka tahun 1965 belum selesai dan konflik agraria terus terjadi, novel ini menyuarakan pentingnya mendengar suara korban, khususnya perempuan.
Novel ini mengingatkan bahwa pembangunan tanpa keadilan adalah bentuk kekerasan baru. Seperti perempuan Kendeng yang bersuara memperjuangkan bumi untuk layak menjadi sumber kehidupan yang adil dan sehat. Novel Dendam menegaskan kembali antara kemanusiaan dan ekologi, sejarah dan masa depan.
Melalui novel Dendam ini memperlihatkan bahwa sastra menjadi ruang alternatif mengungkapkan kebenaran yang tak tercatat dalam arsip kenegaraan. Novel tak hanya menyoal tutur tragedi, melainkan jalan untuk penyembuhan. Tiga generasi, Ibu Rini, Rini, dan Tinuk, yang menjadi simbol perjalanan bangsa.
Mereka menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada amarah, melainkan keberanian untuk mengakui dan memaafkan. Novel Dendam mengajarkan tentang keluarga yang hancur karena sejarah, namun berdiri karena mencari jati dirinya kembali. Novel ini menegaskan bahwa perempuan dapat berdiri di garda depan dalam menjaga ingatan dan kemanusiaan, agar sejarah bukanlah alat kekuasaan, melainkan cermin bagi nurani. []