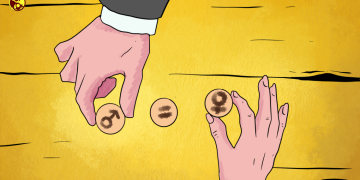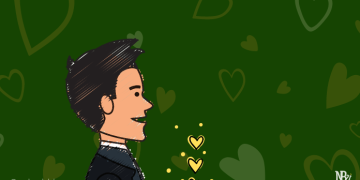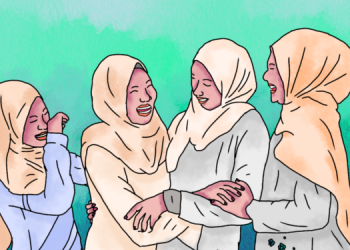Mubadalah.id – Ta’limul Muta’allim, sebagaimana makna literalnya (lughawi), merupakan sebuah kitab yang berisi panduan untuk para pelajar (santri). Seringkali, pelbagai pesantren tradisional (salaf) di Indonesia menjadikan kitab ini sebagai rujukan utama dasar pembelajaran akhlak—juga adab.
Namun, pembacaan Ta’limul Muta’allim sekadar sebagai manual bagi para pelajar / santri semata rasanya terlalu mengandung ketimpangan. Seolah, hanya santrilah yang mesti menekuni manual, sementara pengajar (mu’allim) tidak perlu beristifadah dari kitab karya Syaikh Az Zarnuji ini.
Padahal, sekiranya pengajar juga berkenan mengambil faidah dari kitab ini, tentu kemanfaatannya menjadi lebih besar. Misalnya saja, di dalam kitab ini, muncul anjuran bagi seorang pelajar untuk tidak mudah bosan terhadap ilmu.
Bahkan, manakala ia telah mengetahui suatu pelajaran dan mendengar tentang materi itu lagi sebanyak seribu kali, seorang pelajar tulen akan bersikap antusias.
Seolah, ia baru mendengar pelajaran tersebut pertama kali dalam hidupnya. Ia mesti mengosongkan gelasnya kembali. Bila tidak, maka sungguh ia tidak masuk kategori thalib sejati.
Tentu, perumpamaan ini cukup berat. Apalagi di era banjir informasi (information overload) seperti sekarang. Repetisi terhadap informasi sejenis sangatlah terasa menjemukan.
Resiprokalitas sebagai keniscayaan
Kiranya, akan lebih baik bila pembacaan terhadap anjuran tersebut berlaku secara lebih resiprokal. Artinya, imbauan yang sama juga harus menyasar pengajar / pendidik.
Selain dapat menjadi media refleksi, pembaharuan pembacaan semacam ini juga dapat mengikis secara perlahan relasi kuasa antara pendidik dan anak didik.
Lantas, apakah memungkinkan bila kita membaca kitab ini dengan perspektif demikian? Bila iya, bagaimana pendekatannya?
Pembacaan Ta’limul Muta’allim dengan pendekatan yang lebih resiprokal dapat berkaca pada perspektif Friedrich Nietzsche (1844-1900). Sosok pengabar “Tuhan telah mati” itu punya cara pandang yang tak biasa dalam merespon sebuah realitas.
Ketak-biasaaan perspektif Nietzsche tampak gamblang dalam karya-karyanya yang kompleks alias rumit. Baik berupa esai-esai panjang maupun sajak-sajak dithyrambosnya, Nietzsche menawarkan pandangan avant garde yang seringkali membuat publik jamak tersentak.
Hujjah Nietzsche: multi-interpretasi dan non-gkorifikasi
Alih-alih melihat sebuah fenomena dengan monointerpretasi mayoritas, Nietzsche acap datang dengan benderang berbeda. Ia serupa dengan sebatang oncor yang berkilauan di dalam pekat gulita gua bawah tanah.
Suatu kali, profesor filsafat yang hidupnya berakhir kelam ini pernah berpesan: “Kamu punya caramu. Aku punya caraku. Soal mana yang paling tepat, itu tidak ada.”
Pesan ringkas Nietzsche tersebut hendak mencambuk sekalangan insan pesantren yang acap masuk jerembab monointerpretasi. Nietzsche menyanggahnya dengan gilang-gemilang.
Tak pernah ada, bagi Nietzsche, standar tunggal kebenaran. Ia bahkan banyak mengkritik dualisme kontras nan absolut antara kebenaran dan keburukan (lihat: Thus Spoke Zarathustra).
Selain itu, wejangan Nietzsche di atas juga bermaksud merobohkan glorifikasi terhadap satu jenis kitab. Ta’limul Muta’allim, dengan segenap kualitasnya, bukanlah referensi tunggal yang mesti menjadi standar akhlak publik.
Nietzsche seakan duduk membersamai pihak-pihak yang sering diberkati vonis, “Pasti nggak ngaji Ta’limul Muta’allim. Pantesan nggak punya adab.”
Perlunya inovasi dan kontekstualisasi
Lebih lanjut, soal inovasi interpretasi, Nietzsche membilang, “Ular yang tak mampu berganti kulit harus mati. Begitu pula pikiran yang tak mampu mengubah pendapatnya; mereka berhenti menjadi pikiran.”
Aforisme ala Nietzsche akan ular yang tak mampu mlungsungi merupakan sindiran atas kejumudan metode. Di banyak tradisi, pewarisan bersambung (sanad) seringkali lebih dinomor-satukan. Sementara, kontekstualisasi justru sering mengalami peminggiran.
Dari Nietzsche, kita dapat menarik ikhtisar bahwa kitab Ta’limul Muta’allim memungkinkan pula diberikan pembacaan sebagai Ta’limul Mu’allim. Deduksi berani ini hadir sebagai usaha pembaharuan sekaligus perluasan bentang kemanfaatan.
Dalam kasus “mendengar seribu kali” tadi, misalnya, seorang pendidik dapat berinterpretasi begini: “Oh, sekiranya materi ini tidak menyuntukkan untuk anak didik yang telah paham, saya mesti bisa berinovasi.”
Membuka ruang interpretasi
Interpretasi sang pendidik tersebut mendorongnya untuk dapat menghadirkan kemasan pembelajaran yang lebih variatif. Sekalipun kontennya sama, sedikit sentuhan segar dapat menghilangkan kejenuhan murid.
Selain dari segi kemasan, inovasi pembelajaran juga dapat berbentuk ekstensifikasi konten. Alih-alih melulu berkutat pada topik yang terbatas, pengajar seyogianya memperluas cakrawala materi.
Hidangan yang tersedia di hadapan murid dapat ditali-hubungkan dengan topik-topik lain. Alhasil, intisari materi atau pokok bahasan dapat beroleh penjelasan tambahan (syarh) maupun konteks yang lebih luas.
Segenap insan pendidik mesti terus menyadari kebutuhannya untuk selalu dididik. Status pendidik tak berarti menjadi purna tugas dari kebutuhan akan pendidikan. Sekali seorang pendidik merasa puas dengan keterdidikannya, di titik itulah mutu pendidikan beranjak ambles.
Bukankah seorang pendidik yang baik semestinya tak pernah merasa lebih terdidik? Nietzsche yang profesor bahkan tak ragu memeluk seekor kuda dungu.
Oh, andai guru ia adalah Ta’limul Muta’allim kita! []