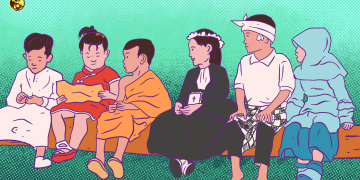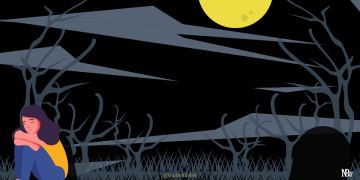Mubadalah.id – Zakat profesi merupakan salah satu bentuk aktualisasi zakat mal yang berkembang di era modern. Ia muncul sebagai respons terhadap sumber penghasilan baru yang tidak terkenal di masa klasik, seperti gaji bulanan pegawai. Banyak lembaga dan perusahaan, termasuk BUMN, mengadopsi sistem pemotongan zakat secara otomatis dari gaji karyawan muslim atau yang lebih kita kenal dengan istilah payroll zakat.
Pada satu sisi, sistem zakat profesi ini dianggap lebih praktis, efisien, dan memastikan kepatuhan. Namun, jika kita mencermati lebih dalam, ada pertanyaan besar yang perlu kita ajukan: apakah sistem zakat profesi ini sudah adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menjadi ruh dari zakat itu sendiri?
Sebuah penelitian menarik dilakukan oleh Sulkifli H., Saifullah bin Anshor, Akhmad Hanafi D.Y., dan Siti Munawira S. (2020) terhadap sistem zakat profesi di PT. PLN (Persero) Wilayah Sulselbar. Temuannya cukup mencengangkan.
Seluruh karyawan muslim di perusahaan itu dipotong zakatnya secara otomatis setiap bulan, tanpa terlebih dahulu melihat apakah penghasilannya sudah memenuhi syarat minimal wajib zakat. Yakni mencapai nisab dan sudah lewat satu tahun atau haul. Padahal, dalam fikih zakat, dua hal itu menjadi syarat utama seseorang baru boleh kita kenai zakat.
Kita bisa membayangkan, ada karyawan yang gajinya hanya Rp 4 juta per bulan, dan itu pun belum tentu cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Apalagi kalau tinggal di kota besar dengan biaya tinggi.
Namun karena sistemnya otomatis, gaji mereka tetap terpotong zakat, meskipun setelah setahun jumlah total penghasilannya belum tentu mencapai nisab sekitar Rp 52 juta. Dalam konteks ini, pemotongan zakat bukan lagi soal ibadah, tapi bisa menjadi tekanan ekonomi baru bagi yang justru belum mampu.
Menyoal Sistem Payroll
Sistem payroll ini juga tidak memberi ruang bagi karyawan untuk menyatakan bahwa mereka belum wajib zakat. Semua anggapannya sama, padahal situasi hidup tiap orang jelas berbeda.
Ada yang masih menanggung orang tua, ada yang membiayai kuliah adik, ada pula yang menanggung cicilan. Zakat, yang seharusnya hanya terbayarkan oleh orang yang benar-benar mampu, justru jadi beban bagi sebagian orang karena tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi secara personal.
Para ulama seperti Yusuf al-Qaradawi telah lama menegaskan bahwa zakat harus memperhatikan konteks kemampuan. Ukuran nisab, misalnya, mencerminkan batas kecukupan seseorang untuk hidup selama satu tahun. Jika belum mencapai nisab, maka seseorang belum dianggap wajib zakat.
Bahkan Faqihuddin Abdul Kodir dalam bukunya Fiqh Zakat Progresif mengkritik adanya standar ganda dalam penetapan nisab zakat. Petani yang hanya memperoleh Rp10 juta per tahun bisa diwajibkan zakat, sementara pedagang atau pemilik aset besar baru terkena kewajiban jika hartanya mencapai ratusan juta.
Ia menyebut ini sebagai bentuk ketidakadilan dalam penetapan standar kekayaan. Faqihuddin mengajak kita untuk meninjau kembali sistem zakat dengan pendekatan yang lebih adil, kontekstual, dan berpihak pada mereka yang lemah secara ekonomi. Kritik tersebut sangat relevan untuk kita bawa ke dalam konteks zakat profesi berbasis payroll.
Meninjau Ulang Sistem Zakat Payroll
Karena itu, sudah waktunya kita meninjau ulang sistem zakat payroll ini. Lembaga zakat dan bagian penggajian perlu menyusun ulang kebijakan ini dengan prinsip kehati-hatian dan pendekatan yang adil. Edukasi zakat juga harus kita perkuat.
Karyawan perlu kita beri pemahaman, diberi pilihan, dan kita ajak untuk secara sadar menghitung zakatnya sendiri berdasarkan penghasilan bersih dan kondisi riil. Jangan sampai, zakat berubah menjadi sekadar angka potongan di slip gaji tanpa makna spiritual dan sosial apa pun.
Maka dengan demikian bahwa, payroll zakat memang efisien, tapi tidak selalu adil. Efisiensi tidak boleh menyingkirkan nilai-nilai utama dalam zakat: keikhlasan, kesadaran, dan kemampuan. Kita tidak menolak zakat profesi, apalagi niat baik institusi untuk menyalurkannya secara terorganisir.
Tapi kita menolak jika zakat kita laksanakan secara kaku, tanpa memanusiakan para muzaki, dan tanpa mempertimbangkan penetapan syarat-syarat syar’i dalam hukum Islam. Zakat bukan pajak. Ia bukan kewajiban negara yang kita paksakan, melainkan ibadah yang suci dan penuh makna. Jika cara penarikannya justru menyakiti atau menindas, maka ruh zakat itu sendiri telah hilang. []