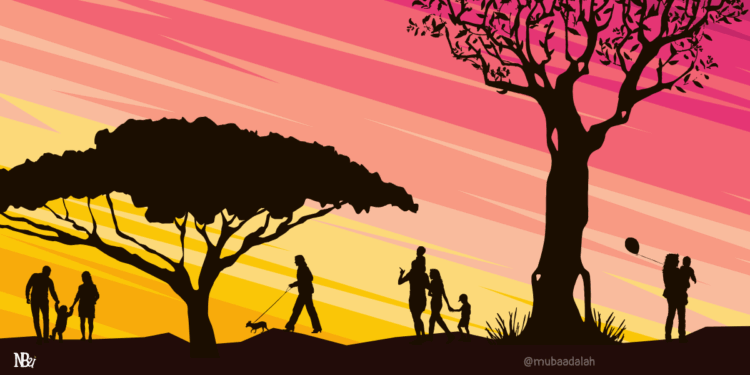Mubadalah.id – Percayakah Anda bila kalangan disabilitas punya komitmen yang tinggi terhadap isu iklim? Hari-hari ini kita tengah gerah (sekaligus mungkin geram) dengan diskursus serius (juga ketus) seputar masa depan lingkungan global.
Eskalasi pemanasan global (global warming) yang kian menanjak mengindikasikan bahwa bumi sedang tidak baik-baik saja. Sayangnya, alih-alih menyadarkan, narasi seperti ini justru kini acap beroleh cap sebagai fear forming alias penakut-nakutan.
Salah seorang intelektual muslim dari sebuah organisasi besar bahkan sampai memunculkan label “wahabi lingkungan” yang akhir-akhir ini populer.
Label itu ia gunakan untuk menyudutkan pihak-pihak yang baginya terlampau peduli terhadap masa depan iklim dunia. Beruntung, di tengah keterjepitan dan ketersudutan itu, kawan-kawan disabilitas justru menggeliat dan menunjukkan antusiasme positif.
Sebuah rilisan riset Tim Riset Teknik Lingkungan Universitas Islam Indonesia (UII) menyebut bila para penyandang disabilitas menaruh komitmen lebih terhadap aksi iklim. Penelitian tersebut berlangsung di dua daerah di wilayah Indonesia timur, yakni Kota Ternate di Provinsi Maluku Utara serta Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Kedua daerah tersebut pada dasarnya memang masuk kategori rawan bencana. Namun, hal yang menarik justru di tempat itulah berdiri rumah bagi komunitas disabilitas yang punya ikatan batin dengan isu aktual ini.
Ancaman isu iklim pada kalangan disabilitas
Kita perlu menyadari bersama bahwa baik secara langsung maupun tidak, degradasi dan dekadensi lingkungan tetaplah akan berdampak terhadap masa depan penyandang disabilitas.
Misalnya saja, dalam kasus pertambangan yang berdampak destruktif terhadap iklim, riset gagasan Elvis Agyei-Okyere dan koleganya (2019) menunjukkan dua risiko klinis: hilangnya tempat tinggal serta meningkatnya biaya hidup (living cost).
Selain itu, sebagaimana tuturan Ikrom Mustofa selaku Ketua Tim Riset Teknik Lingkungan Universitas Islam Indonesia (UII), kelompok disabilitas masih mengalami hambatan perihal akses informasi terkait iklim ataupun layanan kebencanaan.
Misalnya saja, dalam deklarasi komitmen penanganan iklim 2030 di Paris pada 2015 silam, baru seperlima dari negara-negara peserta yang telah mencantumkan kelompok disabilitas dalam rancangan penanganan iklim di negaranya.
Lagi-lagi kita tertinggal. Tidak ada nama Indonesia dalam daftar rilisan resmi. Sementara, negara-negara tetangga seperti Vietnam, Myanmar, serta Papua Nugini justru selangkah lebih inklusif.
Mereka secara sadar memuat kelompok disabilitas dalam agenda Nationally Determined Contributions (NDCs) negaranya. Praktis, menjadi tidak mengherankan bila selama ini kita jarang mendengar partisipasi kelompok disabilitas dalam pelbagai narasi. Alih-alih mereka bersikap pasif, mereka justru tak banyak diberi tahu.
Kita juga mesti menyadari bahwa problematika iklim turut menyumbang tambahan stigma sosial pada kawan disabilitas. Sementara mereka mesti berjuang dengan kekhasan yang dimiliki, isu iklim yang kian ndrawasi justru melahirkan ancaman bayang-bayang risiko dampak bencana yang empat kali lebih besar ketimbang kelompok mayoritas.
Pun, dalam situasi pengungsian misalnya, kelompok disabilitas jelas akan beroleh kesulitan lebih untuk memenuhi hajat hidupnya. Kita tahu, dalam situasi normal saja, aksesibilitas bagi mereka masihlah dalam fase perjuangan.
Pentingnya pengarusutamaan
Kini, kita mesti bangun dengankesadaran ekstra. Keseriusan kawan disabilitas dalam menaruh concern terhadap isu iklim memperkuat pentingnya pengarusutamaan peran mereka pada berbagai kerja-kerja kelingkungan (environmentalism).
Karenanya, sebagai bagian dari tanggung jawab inklusif, penyandang disabilitas harus mendapatkan kesempatan untuk menyuarakan keresahan mereka dalam proses pengambilan kebijakan seputar iklim. Selama ini, dalam semangat antroposentris mayoritas, kita cenderung melihat masa depan iklim dengan kalkulasi risiko untuk orang kebanyakan; alih-alih menyertakan kawan disabilitas.
Kita sangsi manakala nantinya anak-cucu kita tak lagi bisa menikmati sejuknya hawa atau bersihnya udara yang kini bahkan terus menipis.
Sementara, kelompok marjinal seperti penyandang disabilitas masih acap ternegasikan dari proses-proses atau kerja-kerja iklim. Jadi, sudah siapkah kita untuk berkolaborasi menangani isu iklim bersama mereka?