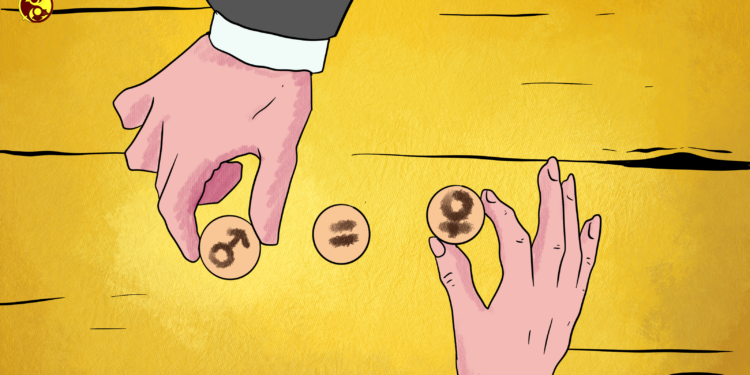Mubadalah.id – Jauh-jauh sebelum serius mendalami fikih, saya acap kali mendengarkan qaul yang berpangkal kepada Imam Daud aẓ-Ẓahiri terkait pernikahan tanpa wali dan saksi. Meski tak tahu pasti sumber dari pendapat tersebut, makin hari, saya kian tahu bahwa pendapat ini memang populer di berbagai kalangan.
Bahkan beberapa kali saya menjumpai pendapat ini menjadi pegangan bagi sebagian orang yang ingin “menikmati” tubuh perempuan tanpa mau rumit-rumit dengan sederet ritual pernikahan pada umumnya. Sayangnya, tak banyak dari mereka yang membaca secara utuh rujukan qaul yang terinisbatkan kepada Imam Daud itu.
Setelah puas mencari, saya akhirnya mendapati bahwa pendapat tersebut tidak termaktub dalam kitab-kitab otoritatif yang merepresentasikan Mazhab Ẓahiriyah. Pendapat Imam Daud, terkait pernikahan tanpa wali dan saksi, hanya sebuah riwayat yang tercecer di sumber-sumber luar Mazhab Ẓahiriyah. Misalnya dalam Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtasid karya Ibn Rusyd, ulama kenamaan dari kalangan Mazhab Malikiyah.
Kita jumpai riwayat yang mengatakan bahwa Imam Daud memilah antara pernikahan gadis dan janda. Pendiri Mazhab Ẓahiriyah itu mengharuskan adanya wali pada pernikahan gadis (bikr). Dan tidak mensyaratkan adanya wali dalam pernikahan seorang janda (tsayyib). Hematnya, qaul ini tidak bisa berlaku secara umum kepada semua perempuan. Sebagaimana pemahaman banyak orang.
Penolakan Ibn Hazm
Sementara dalam internal Mazhab Ẓahiriyah sendiri tak kita jumpai pendapat semacam itu. Sebaliknya, pencarian saya mengantarkan kepada pendapat yang menolak keras melakukan pernikahan yang tanpa sepengetahuan wali. Ibnu Hazm sebagai pendiri kedua dari Mazhab Ẓahiriyah menuliskan pembahasan khusus ihwal pernikahan perempuan tanpa kita ketahui walinya dalam kitab al-Muhallā bi al-Ātsār.
مَسْأَلَةٌ: وَلا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ نِكَاحٌ – ثَيِّبًا كَانَتْ أَوْ بِكْرًا – إلا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا الأَبِ، أَوْ الإِخْوَةِ، أَوْ الْجَدِّ، أَوْ الأَعْمَامِ، أَوْ بَنِي الأَعْمَامِ – وَإِنْ بَعُدُوا – وَالأَقْرَبُ فَالأَقْرَبُ أَوْلَى.
“Seorang perempuan (baik janda atau gadis) tidak diperkenankan menikah tanpa sepengetahuan walinya, (dalam hal ini adalah) bapak, saudara-saudanya, kakek, paman-pamannya atau anak laki-laki dari pamanya…….”
Dengan kata lain, teks ini secara lugas membantah pendapat yang meyakini keabsahan melakukan pernikahan tanpa adanya wali. Penolakan Ibnu Hazm terhadap keabsahan praktik nikah jenis ini (tanpa wali), di antaranya merujuk kepada sabda Nabi yang Aisyah ra riwayatkan.
“Seorang Perempuan tidak boleh dinikahi tanpa sepengetahuan walinya. Dan kalaupun terjadi (pernikahan tanpa sepengetahuan wali) maka pernikahannya dihukumi batal…….”. Pendapat ini makin tak terbantahkan (minimal menurut Ibn Hazm) lantaran Umar bin Khattab ra pernah menolak keabsahan pernikahan yang dilakukan tanpa izin wali nikah. Bahkan Umar ra menjatuhkan sangsi cambuk kepada mempelai pria dan orang yang menikahkan.
Ibn Hazm Memperkokoh Argumentasinya
Dalam kitab yang sama, Ibnu Hazm juga memperkokoh argumentasinya dengan menyajikan riwayat Ibn Sirin yang bermuara kepada Abu Hurairah. Sahabat Nabi yang terkenal banyak memiliki riwayat hadis ini beranggapan bahwa perempuan tidak memiliki hak melakukan akad nikah dengan sendirinya. Pasalnya, hanya perempuan pezina yang mau menyerahkan tubuhnya (kepada laki-laki) tanpa kita ketahui wali nikahnya.
Bila kita cermati dengan seksama, sejatinya pendapat yang tidak mensyaratkan adanya wali dalam pernikahan bukan hanya berasal dari Imam Daud saja. Abu Bakar Muhammad bin Sirin atau yang lebih terkenal dengan Ibn Sirin. Yakni salah seorang pemuka di kalangan tabi’in pernah mendapat pertanyaan mengenai status pernikahan perempuan yang tak memiliki wali, dan memasrahkan urusan (pernikannya) kepada orang lain.
Ibn Sirin memberikan jawaban bahwa itu bukan persoalan serius. Artinya, pernikahannya tetap terhukumi sah. Sebab menurutnya, seorang mukmin adalah wali dari mukmin lainnya, al-mu’minūna ba’ḏuhum awliyā’u ba’ḏ. Di sini kita akan tahu, riwayat Ibn Sirin terhadap perkataan Abu Hurairah berbeda dengan pendapat pribadinya.
Pendapat Imam Malik
Menurut Imam Malik, penentuan hukum pernikahan tidak ada wali ini oleh kedudukan perempuan yang akan menikah. Bila ia terlahir dari golongan yang memiliki status sosial rendah (danīah). Seperti perempuan berkulit hitam,baru masuk Islam, perempuan miskin, bukan bangsawan, atau mantan budak, maka dia boleh dinikahkan oleh selain wali nikahnya seperti tetangganya dan seterusnya.
Di sisi lain, perempuan yang terlahir sebagai keluarga bangsawan atau memiliki posisi prestisius di tengah-tengah masyarakatnya tidak boleh dinikahkan oleh sembarang orang, selain walinya sendiri. Dengan kata lain apabila orang lain yang menikahkan, wali punya hak penuh untuk memisah. Atau membiarkan keduanya (pasutri) hidup bahagia dalam mengarungi bahtera rumah tangga.
Sementara di luar pendapat di atas, Imam Abu Hanifah dan santri kinasihnya yang bernama Zufar membolehkan seorang perempuan menikahkan diri sendiri dengan lelaki yang selevel (sekufu’) dan wali tidak boleh ikut campur dalam pernikahan keduanya. Pernikahan tetap dihukumi sah bila ternyata suaminya tak berada di level yang sama. Bedanya, pada kondisi ini wali punya hak untuk membatalkan pernikahannya.
Oleh Ibn Hazm, semua pendapat yang berpangkal pada bolehnya pernikahan tanpa wali ia kuliti habis-habisan. Terhadap qaul Imam Abu Hanifah, Ibnu Hazm mengomentarinya sebagai orang yang tidak konsisten. Membuka ruang perempuan untuk menikahkan diri dengan lelaki yang tak setara. Tetapi membolehkan wali untuk memfasakh (membatalkan) akad nikahnya.
Pendapat ini Ibn Hazm menilai sebagai pendapat yang tak memiliki keterkaitan (lā muta’alliqa lahā) dengan al-Qur’an, sunnah, qaul ṣahabi, nalar, qiyas dan raisonal yang dapat dipertanggung jawabkan. Ijtihad model begini hanya boleh Rasulullah saw lakukan. Bila dilakukan oleh selain Rasul, yang ada hanya membuat-buat agama baru (din jadid) dan akan mendapat perhitungan kelak di hari akhir. (bebarengan)