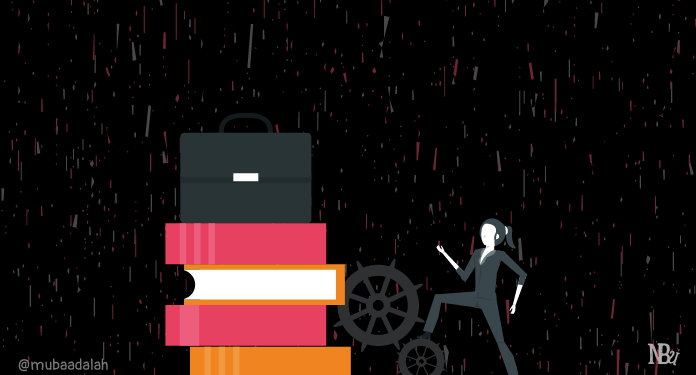Mubadalah.id – Pendidikan adalah fondasi masa depan. Bukan sekadar alat untuk memperoleh ilmu, tetapi juga sarana strategis dalam membentuk akses ekonomi, sosial, dan politik yang setara. Namun, untuk perempuan, akses terhadap pendidikan masih terbayangi oleh berbagai bias sosial yang sering kali tertanam dalam narasi budaya, agama, dan norma masyarakat.
Ketika diskusi tentang pilihan hidup perempuan muncul, seperti yang ramai diperbincangkan belakangan ini mengenai perempuan yang memilih menikah di usia 19 tahun tanpa menunda pendidikan atau karier. Kita perlu refleksi terhadap bias pendidikan tinggi perempuan menjadi semakin penting.
Pendidikan Tinggi sebagai Kebebasan Pilihan Hidup
Pernyataan perempuan yang menikah di usia 19 tahun yang viral di media sosial berupaya menegaskan bahwa kedewasaan tidak semata ditentukan oleh angka usia, tetapi oleh kesiapan mental, spiritual, dan pilihan hidup individu.
Dalam unggahan tersebut, perempuan itu menolak “dijebak” dalam mentalitas extended adolescence. Sebuah fenomena sosial di mana banyak anak muda merasa belum siap mengambil peran dewasa seperti menikah, bekerja, atau berkarya karena norma budaya yang menetapkan batasan-batasan tidak tertulis tentang “kesiapan”.
Pernyataan ini memicu pro-kontra. Sebagian melihatnya sebagai legitimasi untuk menentukan waktu sendiri dalam hidup. Sementara lainnya mengkhawatirkan bahwa keputusan seperti menikah muda bisa mengorbankan kesempatan pendidikan yang lebih tinggi. Di mana secara struktural justru perempuan butuhkan untuk merdeka secara sosial dan ekonomi.
Poin pentingnya adalah bahwa pilihan hidup, apakah itu menikah muda, melanjutkan pendidikan tinggi, atau menunda pernikahan demi studi, adalah hak setiap perempuan. Kebebasan ini hanya sesungguhnya kalau setiap pilihan itu bisa kita jalani dengan akses yang setara dan tanpa bias struktural.
Dampak Sosial dari Pembatasan Pendidikan Perempuan
Berbagai studi internasional menunjukkan bahwa pembatasan akses pendidikan, terutama bila beriringan dengan praktik pernikahan dini, berdampak negatif pada pendidikan perempuan. Menurut penelitian, menikah atau memasuki ikatan keluarga pada usia muda sering kali berkorelasi dengan penurunan kelanjutan pendidikan, karena tanggung jawab baru seperti rumah tangga dan anak mengalihkan fokus dari studi.
Selain itu, data global menyatakan bahwa semakin lama seorang perempuan berada di bangku pendidikan, semakin kecil kemungkinan dia mengalami pernikahan dini. Sebaliknya: rendahnya tingkat pendidikan perempuan sering menjadi pendorong pernikahan usia muda.
Dampak lain dari pembatasan pendidikan perempuan adalah ketidaksetaraan jangka panjang dalam peluang ekonomi dan sosial. Ketika perempuan tidak mendapatkan akses penuh ke pendidikan tinggi, mereka cenderung mengalami keterbatasan dalam pasar kerja yang berkualitas. Lalu akses terhadap posisi kepemimpinan, hingga independensi ekonomi. Hal ini memperkuat ketimpangan gender yang sudah ada sejak lama.
Lebih jauh lagi, hambatan dalam akses pendidikan memperkuat stereotipe budaya yang menyiratkan bahwa perempuan cukup sampai jenjang tertentu saja. Bahkan saat norma hukum mengizinkan mereka menikah atau berkarier lebih awal. Padahal, pendidikan tinggi perempuan seharusnya menjadi alat pemberdayaan diri yang memperluas pilihan hidup, bukan membatasi.
Menata Ulang Relasi Pendidikan dan Pilihan Hidup Perempuan
Perdebatan publik tentang pilihan perempuan menikah di usia muda menunjukkan masih kuatnya asumsi bahwa pendidikan tinggi memiliki batas waktu tertentu bagi perempuan. Terutama setelah memasuki fase pernikahan.
Persoalannya bukan terletak pada pilihan menikah itu sendiri. Melainkan pada bias sosial yang kerap memosisikan pendidikan sebagai sesuatu yang boleh terhenti ketika perempuan kita anggap telah memenuhi peran domestik.
Pandangan semacam ini mempersempit makna pendidikan dan mengabaikan hak perempuan untuk terus bertumbuh secara intelektual sepanjang hidupnya.
Pendidikan tinggi seharusnya kita pahami sebagai ruang pembebasan yang memperluas kapasitas berpikir, kemandirian, dan kontribusi sosial. Tanpa harus kita pertentangkan dengan pilihan hidup personal. Dengan menata ulang relasi antara pendidikan dan pilihan hidup perempuan, masyarakat dapat bergerak melampaui dikotomi sempit yang selama ini membatasi masa depan perempuan itu sendiri.
Membuka akses pendidikan tinggi dan meruntuhkan bias gender terhadap perempuan bukanlah pekerjaan satu hari. Ini merupakan proses panjang yang melibatkan reformasi sosial, kebijakan publik, dan perubahan budaya.
Debat publik seperti yang muncul dari kasus perempuan yang menikah di usia 19 tahun membuka ruang refleksi penting. Bahwa setiap perempuan berhak memilih jalan hidup yang ia percaya, termasuk pendidikan dan rumah tangga. Tanpa terpaksa menanggalkan salah satunya karena tekanan sosial atau bias kultural.
Pendidikan tinggi bukan sekadar simbol prestise. Ia adalah alat pemberdayaan sejati, yang harus kita akses tanpa prasangka bahwa peran perempuan terbatas pada satu domain saja. Ketika perempuan kita beri akses pendidikan setara, pilihan hidupnya pun semakin bermakna dan masa depan bersama menjadi lebih inklusif. []