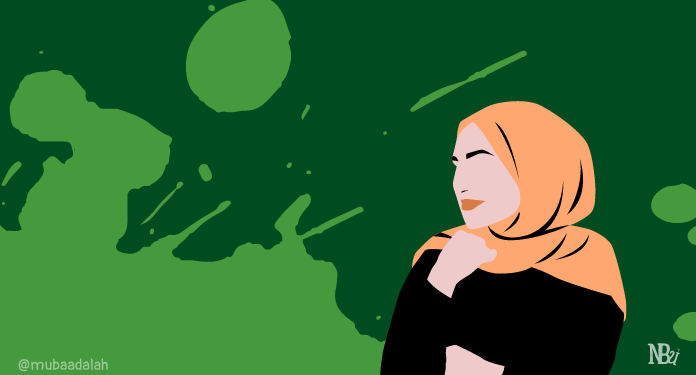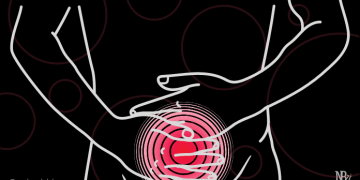Mubadalah.id – Dalam literatur klasik Islam, posisi perempuan kerap dilekatkan pada aspek biologisnya, terutama tubuh perempuan yang dinilai membawa daya tarik seksual bagi laki-laki.
Seperti dikutip Dr. Faqihuddin Abdul Kodir dalam Pertautan Teks dan Konteks dalam Muamalah, ada ungkapan tajam: “Andaikata syahwat (baca: libido) ini tidak ada, niscaya perempuan tidak punya kuasa (baca: posisi) di mata laki-laki.”
Karena itu, standar kebaikan seorang perempuan (ishlah) sering kali kita mengukur dari sejauh mana ia mampu meredam potensi-potensi sensualnya di hadapan publik. Sambil pada saat yang sama justru ia harus menawarkan sisi sensual tersebut secara penuh kepada suaminya.
Hal ini misalnya ditegaskan dalam hadis sahih riwayat Abu Dawud: “Perempuan yang shalihah adalah perempuan yang jika dilihat olehmu (suami) menyenangkan, jika diperintah bersedia melaksanakan, jika ditinggalkan mau menjaga dirinya dan harta suaminya” (Sunan Abu Dawud, Juz II/126, No. Hadis 1664).
Lebih jauh, dalam fikih klasik pandangan sejumlah ulama bahkan mereduksi kewajiban istri hanya pada satu hal yaitu menyediakan tubuh perempuan (tamkin) untuk suaminya nikmati kapan saja dan di mana saja. Hal ini bersandarkan pada hadis yang menyatakan:
“Ketika suami mengajaknya berhubungan intim, istri harus memenuhinya. Sekalipun ia sedang di dapur atau di punggung unta” (HR. at-Turmudzi, No. Hadis 1160, III/465).
Bahkan dalam riwayat Bukhari menyebutkan, jika seorang istri menolak ajakan suaminya. Lalu suami tidur dalam keadaan kecewa, “ia mendapat laknat oleh para malaikat sampai pagi” (HR. Bukhari No. 3065 dan 4898).
Cerita serupa juga tampak dalam kisah Rabi’ah al-Adawiyyah yang tercatat dalam beberapa literatur sufi. Setiap malam, Rabi’ah berhias, mengenakan pakaian paling indah, menyemprotkan tubuhnya dengan wewangian. Lalu menyiapkan diri sambil berkata pada suaminya, “Silakan, aku persembahkan tubuhku untukmu.”
Jika suaminya tak berminat, Rabi’ah segera menanggalkan pakaiannya, mencuci tubuhnya dari harum-haruman. Lalu menghadap Allah dalam sembahyang dan zikir sepanjang malam.
Dalam pandangan ini, tugas utama seorang istri memang tereduksi sebatas menyiapkan tubuhnya untuk suami nikmati.
Imam al-Ghazali dalam Ihya’ Ulum ad-Din juga menegaskan bahwa harga perempuan di mata suaminya terletak pada fantasi sensualnya.
Karena itu, tubuh perempuan mesti “dijinakkan” terlebih dahulu di dalam rumah, sebelum kemudian dikendalikan oleh aturan sosial agar tidak menggoda lelaki lain. []