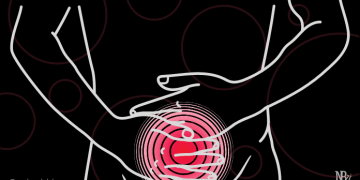Mari kita bayangkan kita berada di situasi seperti ini: ada sebuah kereta yang sedang melaju sangat cepat karena remnya tidak berfungsi. Di saat yang sama, di hadapannya ada dua jalur kereta yang dua-duanya terdapat manusia yang sedang terikat, tidak dapat melepaskan diri. Bedanya, jalur pertama terdapat lima orang yang sedang terikat. Sedangkan jalur lainnya, hanya ada satu orang yang tidak dapat melepaskan diri.
Dan, tentu bisa diprediksi mereka akan segera terlindas oleh kereta bila kita tidak segera bertindak cepat. Nah, jika kita diberikan otoritas untuk memilih opsi pemecahan masalah dengan menarik tuas pengatur jalur. Mana yang akan kita pilih? Bila kita tidak menarik tuas itu, kereta akan melaju dan melindas lima orang di depannya. Jika kita menarik tuasnya, kereta akan berbelok ke jalur yang lain dan melindas satu orang yang ada di lintasan itu. Apa yang akan kita lakukan?
Ilustrasi di atas adalah sebuah thought experiment dalam etika dan psikologi yang biasa disebut dengan Trolley Problem. Philippa Foot memperkenalkan diskursus problematis ini pada tahun 1967 sebagai bagian dari sebuah analis dalam perdebatan mengenai aborsi dan doktrin double effect. Ini merupakan rangkaian pertanyaan filosofis yang akan memaksa kita berfikir untuk mendefinisikan kembali apa itu moralitas dari perspektif yang berbeda. Menakar kembali nilai moral mana yang lebih baik, atau mungkin yang kita anggap lebih baik itu hanya tipuan belaka.
Jika kita memilih untuk mejawab pertanyaan diatas dengan memilih menyelamatkan lima orang dan mengorbankan yang satu, mungkin kita sedang menjadi Thanos dalam film Avenger, Zobrits dalam film Inferno, atau bahkan Hitler dalam sejarah Nazi. Ya, mengorbankan yang sedikit untuk menyelamatkan yang lebih banyak, itu memang opsi yang sangat lumrah dan cenderung dipandang sebagai tindakan moral yang baik.
Pola seperti ini, mengorbankan minoritas untuk kepentingan mayoritas, merupakan ciri khas patriarkhi. Perempuan yang dianggap sebagai bagian minor dari sebuah komunitas cenderung selalu menjadi ‘yang dikorbankan’ untuk kepentingan laki-laki sebagai bagian mayornya. Dulu, masyarakat kita pun demikian (meskipun ada hal-hal yang sampai sekarang masih belum berubah). Di tahun ‘98 rokok pernah masuk sebagai kebutuhan pokok sehingga memengaruhi UMR buruh laki-laki. Sedangkan pembalut tidak dianggap sebagai bagian dari kebutuhan pokok.
Dalam kehidupan beragama pun demikian. Masih banyak masyarakat yang mengukur moralitas keagamaannya dari ukuran mayoritas seperi trolley problem tadi. Pernah suatu ketika ada seorang mubaligh yang sedang memberikan ceramah dalam suatu majlis. Si mubaligh menyerukan agar para perempuan menutup auratnya apabila hendak keluar karena “kalau kami (laki-laki) setengah mati jaga mata, kalau kalian (perempuan) keluar gentayangan, habis amal kami. Dilihat dosa, gak dilihat, barang bagus..”. Demikian pesan moral yang disampaikan dengan dibungkus candaan yang berhasil membuat jamaahnya terpingkal-pingkal.
Terlepas dari kenyataan bahwa memang masyarakat kita masih sulit membedakan antara dagelan dan sexism, pesan moral keagamaan itu cukup untuk dijadikan contoh bagaimana dilema etik dan moral keagamaan kita masih menempatkan faktor mayoritas sebagai ukuran untuk mengatakan apakan sebuah tindakan itu bermoral atau tidak. Padahal konsep moralitas dalam Islam tidak demikian.
Landasan dari suatu tindakan dapat dikatakan baik atau bermoral, apabila didasarkan kepada kemaslahatan. Kemaslahatan dalam Islam sendiri, seperti yang selalu dijelaskan Dr. Nur Rofiah merupakan pondasi utama yang harus ada dalam setiap tindakan. Kemaslahatan yang dimaksud Islam bukan kemaslahatan untuk sebagian besar kelompok saja, tetapi untuk semua bagiannya tanpa terkecuali. Untuk itu kita perlu berfikir kembali apa yang kita pahami sebagai etika dan nilai moral dalam agama. Apakah selama ini kita sudah termasuk yang beretika dan bermoral lebih baik, atau yang kita yakini kebaikan itu hanya tipuan saja seperti trolley problem di atas? []