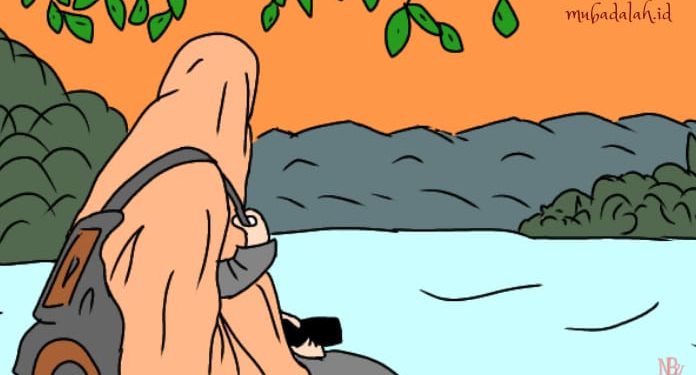Mubadalah.id – Banyak orang percaya bahwa pernikahan adalah gerbang menuju kehidupan baru yang membahagiakan. Saya mengibaratkan menikah itu seperti burung yang bersayap lengkap, yaitu saat dua tubuh yang saling melengkapi. Mampu mengarungi kehidupan bersama, berbagi beban, dan saling belajar.
Namun, di balik diksi indah itu, ada kenyataan yang jarang terucapkan padahal melekat dalam pengalaman dan melebur dalam kehidupan perempuan yang telah menikah: mereka sering kali menanggung konsekuensi yang lebih besar. Menikah dan Hilangnya Separuh Hidup Perempuan.
Tidak selalu dalam bentuk paksaan kasar atau aturan patriarkal yang kaku, melainkan lewat mekanisme halus yang membuat mereka lebih sering menyesuaikan, mengalah, dan menunda sebagian dari dirinya sendiri.
Mbak Nana (Najwa Shihab) dalam sebuah kesempatan pernah mengungkapkan dengan narasi yang kurang lebih begini, “mengapa perempuan harus memilih antara menjadi ibu bekerja atau ibu rumah tangga?”
Bentuk pilihan tak melulu terbalut oleh sosok suami yang otoriter maupun dikte kasar keluarga besar. Saya misalnya, menjalani rumah tangga tanpa tekanan langsung, tanpa suara keras yang memaksa tunduk.
Meski begitu, ruang hidup saya tetap bergeser. Banyak rencana pribadi yang harus tertunda, ritme harian yang mengikuti arah suami, dan penyesuaian yang seakan datang otomatis demi menjaga keseimbangan keluarga. Bukan karena terpaksa, melainkan karena begitulah “aturan tak tertulis” pernikahan bekerja.
Jadi, apakah menikah dan hilangnya separuh hidup Perempuan itu adalah konsekuensi tak terhindarkan dari pernikahan, ataukah hasil dari struktur sosial yang sejak awal menempatkan perempuan pada posisi subordinat?
Mari kita selisik beberapa hal yang barangkali bisa membuka rahasia, kenapa pernikahan sering terasa lebih mahal bagi perempuan daripada bagi laki-laki? Mengapa menikah bisa membuat hilangnya separuh hidup Perempuan?
Norma Gender: Aturan Tak Tertulis
Kita semua tahu, tidak ada kitab hukum negara yang menuliskan, “istri wajib mengalah dalam segala hal.” Tapi norma sosial sering bekerja lebih kuat daripada KUHP. Istri yang terlalu sering terlibat kegiatan di luar rumah kerap dipandang “lupa diri.”
Padahal ketika suami melakukan hal yang sama, dianggap sedang membangun jaringan. Yang memilih karier daripada tinggal serumah dengan mertua dianggap kurang berbakti. Norma gender inilah yang memoles wajah patriarki menjadi halus, sehingga sulit tertolak tanpa meninggalkan rasa bersalah.
Di ruang-ruang publik, narasi ini terus direproduksi. Dari sinetron sampai khotbah Jumat, perempuan tergambarkan sebagai “penopang rumah tangga” yang idealnya sabar, manut, dan berkorban.
Tak jarang pula stigma “perempuan modern yang kebablasan” mewarnai gerak gerik perempuan yang ingin memberdayakan diri. Norma ini bekerja seperti lalu lintas tanpa lampu merah: semua orang tahu arah jalan, tapi tidak ada yang benar-benar berani menabraknya.
Ketergantungan Ekonomi: Dompet Siapa, Hidup Siapa?
Kita boleh romantis berkata “uang bukan segalanya,” tapi dalam rumah tangga, dompet tetap jadi sumber kekuasaan. Banyak perempuan yang kehilangan daya tawar karena posisinya tidak menghasilkan pendapatan atau terpaksa meninggalkan pekerjaannya demi mengurus anak. Akhirnya, keputusan rumah tangga mengikuti suara pemilik dompet terbesar.
Saya sering heran, kenapa ungkapan “suami kepala rumah tangga” nyaris selalu kita terjemahkan jadi “suami kepala finansial.” Mereka lupa, bahwa bisa jadi justru leher keluarga adalah perempuan: tempat bertumpu yang menentukan arah, ke mana kepala itu menoleh.
Jangan lupa pula bahwa kepala rumah tangga mestinya bisa kita artikan juga sebagai “kepala dalam urusan ganti popok” atau “kepala dalam hal menidurkan anak.” Sayangnya, tafsir populer cenderung menguntungkan laki-laki. Akibatnya, banyak perempuan yang bahkan untuk membeli lipstik pun harus menunggu persetujuan atau “izin tidak langsung.”
Dan ini bukan cuma keluhan pribadi. Beberapa penelitian belakangan juga menguatkan hal serupa. Nurul Badriyah (2022) menemukan bahwa perempuan yang menikah muda sering kehilangan kemandirian mulai dari urusan ekonomi sampai keputusan pribadi yang sederhana.
Sementara itu, riset Evitasanti (2021) menunjukkan bagaimana fase awal pernikahan membuat perempuan harus “ganti kulit”: mengubah ritme hidup, menunda mimpi, atau sekadar belajar tahan telinga dengan standar keluarga.
Hidup Bersama Orang Tua: Antara Bakti dan Batas Diri
Di banyak keluarga, terutama di Indonesia, tinggal bersama orang tua atau mertua setelah menikah bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan. Ada orang tua yang sudah sepuh dan butuh kita temani, ada yang sakit, atau memang kondisi ekonomi menuntut anak untuk tetap tinggal bersama. Semua itu bentuk bakti yang mulia Yang tidak perlu kita cari siapa yang salah.
Namun, di sisi lain, pola hidup bersama generasi berbeda ini membawa tantangan tersendiri. Privasi pasangan sering tergerus, batas pengasuhan anak bisa kabur, dan keputusan rumah tangga terkadang ikut ditentukan oleh suara generasi di atas. Masalah muncul bukan lagi karena mertua jahat atau anak durhaka, melainkan karena kultur kita belum terbiasa memberi ruang otonomi bagi pasangan muda meski mereka tinggal serumah dengan orang tua.
Idealnya, hidup bersama bisa menjadi ruang saling belajar. Generasi tua mendapat perhatian, generasi muda mendapat pengalaman dan dukungan. Tetapi tanpa komunikasi yang sehat dan kesepakatan batas, situasi ini justru bisa menempatkan istri (lebih sering daripada suami) di posisi paling sibuk menyesuaikan diri.
Dari sinilah penting untuk membicarakan ulang. Bagaimana cara membagi ruang dan peran agar bakti pada orang tua tetap berjalan, tanpa harus mengorbankan ruang hidup rumah tangganya.
Pekerjaan Reproduktif: Seumur Hidup Tanpa Slip Gaji
Kalau ada pekerjaan dengan kontrak seumur hidup, tanpa cuti, tanpa gaji, tanpa jaminan pensiun, itulah pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak. Laporan ILO menyebut ada sekitar 708 juta perempuan di dunia yang tidak bisa masuk pasar kerja karena tugas perawatan tidak berbayar.
Angka ini bukan sekadar statistik. Ia adalah cerita sehari-hari tentang perempuan yang meninggalkan kuliah, karier, atau mimpi, karena harus menyiapkan sarapan atau menenangkan anak yang demam.
Yang lebih ironis, pekerjaan ini tidak dianggap sebagai “kerja.” Padahal, kalau negara membayar setiap jam masak, mencuci, dan mengasuh dengan upah minimum, bisa jadi APBN langsung jebol. Tapi entah kenapa, kerja yang membuat generasi baru bisa lahir dan tumbuh sehat malah dianggap sekadar kewajiban kodrati. Dan di sini, perempuan kembali kehilangan ruang untuk dirinya.
Kekerasan Simbolik: Ketika “Pengorbanan” Jadi Alat Kontrol
Pernahkah kita dengar kalimat, “namanya juga perempuan, harus bisa berkorban demi keluarga?”
Kalimat itu terdengar mulia, tapi sesungguhnya adalah bentuk kekerasan simbolik. Ia membuat perempuan merasa bersalah kalau tidak menyingkirkan keinginannya sendiri. Bahkan ketika istri bekerja keras, masyarakat tetap bisa mengingatkan: jangan sampai melupakan “kewajiban utama” di rumah.
Sosiolog Pierre Bourdieu menyebut ini symbolic violence: kekerasan yang tidak kita sadari sebagai kekerasan, karena sudah dinormalisasi. Perempuan yang terjebak di dalamnya sering merasa semua pilihan yang ia buat adalah “kesadaran sendiri,” padahal ia hanya menyesuaikan dengan ekspektasi sosial yang sudah dipatok.
Solusi: Membayangkan dan mewujudkan Pernikahan yang Lebih Setara
Apakah ini berarti perempuan sebaiknya tidak menikah? Jawabannya tidak sesederhana itu. Justru yang kita butuhkan adalah membayangkan ulang dan merajut kembali bentuk pernikahan.
Tidak ada pernikahan yang ideal. Pernikahan adalah pelajaran dan ibadah yang dilangsungkan seumur hidup.
Di tingkat mikro, pasangan bisa mulai dari hal-hal sederhana. Membagi tugas rumah tanpa rasa gengsi, mendiskusikan rencana karier istri dengan sungguh-sungguh, dan menetapkan batas jelas dengan keluarga besar. Sesederhana suami yang mau ikut gantian begadang dengan bayi, itu sudah bisa menggeser norma lama.
Di tingkat makro, negara juga harus hadir. Cuti ayah yang layak, subsidi daycare seperti negara Jepang misalnya, atau pengakuan kerja rumah tangga sebagai bagian dari ekonomi, tak lupa untuk memberikan ruang publik nyaman bagi ibu dan anak.
Tentu semua itu akan memberi ruang baru bagi perempuan. Tanpa kebijakan struktural, perempuan akan terus dibebani “konsekuensi pernikahan” yang sebetulnya adalah konsekuensi dari desain sosial yang timpang.
Kami Menolak Hilang, jadi Mari Menyusun Ulang
Pernikahan, pada dasarnya, bisa menjadi ruang berkembang. Tapi proses itu harus untuk dan bagi kedua belah pihak, bukan hanya satu. Jika istri selalu menyesuaikan, sementara suami tetap di orbitnya sendiri, maka pernikahan hanya melahirkan satu bintang dan satu satelit. Jadi semakin menegaskan adanya menikah dan hilangnya separuh hidup perempuan.
Saya memilih tidak ingin menjadi satelit. Saya ingin tetap berputar di orbit saya sendiri, sambil membangun lintasan bersama dengan pasangan dan rumah pulang yang nyaman bagi anak-anak sebagai orang tua yang utuh.
Pertanyaannya, beranikah kita baik sebagai individu, keluarga, maupun masyarakat untuk mendefinisikan ulang pernikahan, sehingga ia tidak lagi menjadi alasan bagi perempuan kehilangan hidupnya, melainkan ruang baru bagi kebebasan yang saling bertaut dan menguatkan? Wallahu a’lam. []