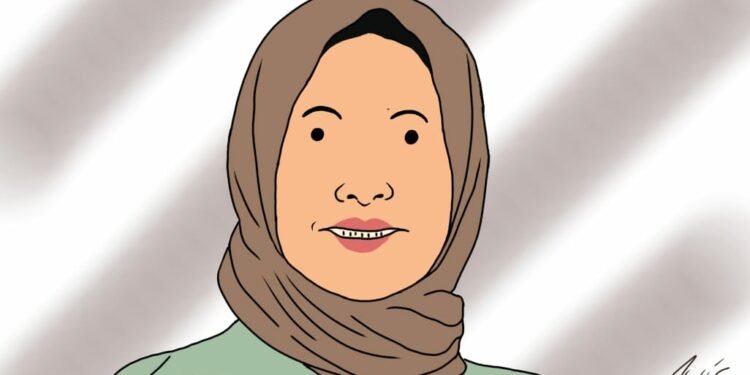Mubadalah.id – Bukan Eropa yang mengislamkan Kartini. Bukan pula Belanda yang mengenalkannya pada makna. Justru peran pesantren, lembaga yang dulu dianggap pinggiran, yang membalikkan arah pikirnya tentang iman. Kartini pernah kecewa pada agama, tapi bukan karena ia membenci nilai-nilainya.
Kartini kecewa karena berhadapan dengan agama tanpa pemahaman. Kitab suci disucikan sampai-sampai tak boleh kita terjemahkan. Bahasa Arab dianggap terlalu mulia untuk terjamah lidah Jawa. Dan di situ, kebutaan spiritual justru terlanggengkan oleh semangat semu menjaga kesakralan.
Kartini tidak melawan Islam, tetapi menantang kebekuan dalam cara menyampaikan Islam. Ia resah pada pendidikan agama yang membungkam tanya, menumpulkan logika, dan meminggirkan makna. Kartini rindu Islam yang hidup, yang masuk akal, menyentuh hati, dan dekat dengan keseharian.
Maka, ketika tafsir pegon dari Mbah KH Sholeh Darat datang menghampirinya, kegelisahan itu seperti menemukan rumah. Untuk pertama kalinya, Surat Al-Fatihah tak sekadar ia dengar, tetapi mampu ia pahami. Dari situlah muncul kembali cinta, bukan karena terwariskan, tapi karena kita kenali.
Menilik Peran Pesantren
Di sinilah peran pesantren menunjukkan kelasnya. Bukan hanya institusi pendidikan, tetapi ruang budaya, spiritual, dan intelektual yang menyatukan wahyu dan realitas. Pesantren membumikan kitab-kitab dengan bahasa rakyat. Mengajak santri berpikir, bukan sekadar tunduk, seperti yang hari ini banyak dituding atau orang-orang salahpahami.
Guru di pesantren tidak hanya mengajar, tetapi menanamkan adab berpikir dan kerendahan hati. Inilah Islam yang Kartini cari, Islam yang diterjemahkan, kita mengerti, dan kita rasakan. Islam yang tidak anti tanya, tidak menakutkan, dan tidak asing dari kehidupan.
Karena, sebagaimana firman Allah Swt:
ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا۟ يُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَـٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ
“Allah Pelindung orang-orang beriman; Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya.” (QS. Al-Baqarah: 257)
Ayat ini adalah bentuk kehadiran Allah dalam membimbing orang-orang beriman menuju ilmu dan pemahaman yang mengeluarkan mereka dari kebodohan. Dan dalam konteks Kartini, cahaya itu datang dari metode pesantren yang tidak memisahkan nalar dari iman. Model inilah yang berhasil menyelamatkan Kartini dari kekecewaan, bukan dogma yang tak bisa ia pertanyakan, bukan pelajaran agama yang berjarak dengan nalar dan batin.
Meneguhkan Kembali Peran Pesantren
Akan tetapi, hari ini, pesantren tidak hanya perlu bangga karena pernah menerangi Kartini. Lebih dari itu, pesantren harus kembali meneguhkan jati diri sebagai tempat bertemunya kitab dan konteks, antara teks dan akal, antara wahyu dan budaya.
Tafsir pegon bukan sekadar warisan, tapi metode berpikir. Islam tidak hanya perlu kita ajarkan, tapi kita manusiakan. Sebab keimanan tanpa pemahaman akan mudah tergelincir, dan pemahaman tanpa kehangatan akan kehilangan ruh.
Di tengah ledakan digital, banjir informasi, dan kebisingan ideologi hari ini, model pendidikan ala pesantren menjadi semakin relevan. Pesantren harus tetap menjadi ruang yang ramah untuk berpikir, bersuara, dan mencari makna.
Di sanalah tempat paling mungkin bagi lahirnya Kartini-Kartini baru yang kritis tetapi taat. Salehah tetapi intelektual, yang tidak takut bertanya dan tidak ragu mencintai agamanya. Dan semua itu kita mulai dari cara menjelaskan Tuhan kepada manusia, seperti yang Mbah Sholeh Darat lakukan kepada Kartini.
Peran pesantren yang seperti itulah, yang layak menyandang nama “Pesantren Kartini.” Wallahu a’lam bis-shawab. []