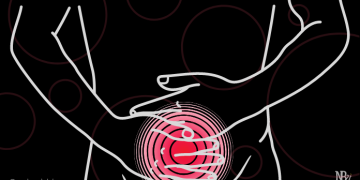Mubadalah.id – Keberpihakan gender tidak pernah netral dalam urusan krisis iklim—yang mana di berbagai wilayah dunia, perempuan tidak mendapatkan perlakuan yang selayaknya. Perempuan kelompok yang paling terdampak dalam bencana ekologis, krisis pangan, kelangkaan air hingga konflik akibat perubahan iklim.
Timur Tengah, menjadi kawasan yang rentan terhadap krisis lingkungan menyimpan paradoks besar. Di sisi lain menjadi ladang eksploitasi sumber daya dan konflik geopolitik kawasan, tetapi di sisi lain kawasan tersebut menjadi basis gerakan perlawanan berbagai komunitas, spiritual dan gender. Jadi mari kita lihat bagaimana gerakan ekofeminisme di Timur Tengah?
Ekofeminisme: Respon Perempuan terhadap Ekologi Terkolonialisasi
Lahirnya wacana ‘Ekofeminisme’ berangkat dari kegelisahan pemikir feminis atas relasi dominasi ganda. Antara laki-laki terhadap perempuan dan manusia terhadap alam. Ekofeminisme dipopulerkan oleh Françoise d’Eaubonne pada 1974. Kemudian berkembang melalui karya-karya Vandana Shiva, Maria Mies, dan Carolyn Merchant.
Dalam suatu diskursus berbagai konteks, ekofeminisme menentang logika patriarki-kapitalistik yang eksploitasi alam secara serakah. Sekaligus mempersempit hingga menindas perempuan di berbagai struktur sosial, ekonomi maupun politik yang timpang.
Seandainya gagasan ini terbawa dalan nuansa wacana Timur Tengah, maka ia melalui proses adaptasi yang kompleks. Tidak semua ekspresi ekofeminisme terwujudkan dalam bentuk gerakan protes terbuka. Ia lahir dalam bentuk praksis lokal, spiritual Islam, komunitas agraris maupun solidaritas perempuan dalam keterbatasan. Namun dalam banyak hal, gerakan ekofeminisme ini membawa semangat resistensi terhadap eksploitasi dan penindasan yang sistemik.
Timur Tengah menjadi kawasan penuh dengan sejarah panjang sebagai objek kolonialisme dan imperialisme—baik melalui kekuatan Eropa maupun sistem ekonomi global kontemporer. Seperti halnya eksploitasi minyak, penggurunan (desertification), degradasi air, dan polusi industri merupakan warisan dari logika ekonomi ekstraktif yang mengabaikan keberlanjutan.
Kolonialisme Lingkungan dan Patriarki Budaya
Di sisi lain, perempuan kawasan Timur Tengah tidak mempunyai ruang yang luas dalam menyuarakan dan berperan dalam pengambilan keputusan penting soal lingkungan. Padahal perempuan yang paling terdampak.
Gerakan ekofeminisme di Timur Tengah, secara senyap menantang dua lapis dominasi: kolonialisme lingkungan dan patriarki budaya. Misalnya, perempuan Palestina bukan hanya menghadapi pendudukan Israel, melainkan menghadapi krisis air dan tanah akibat kebijakan apartheid lingkungan.
Tempat lain seperti Mesir dan Yaman, perempuan petani dan aktivis lingkungan berjuang dalam mempertahankan akses terhadap lahan, benih, dan sumber daya alam yang langka. Bagi mereka, krisis iklim di kawasan bukan sekadar menyoal cuaca ekstrem, melainkan siapa yang berkuasa atas sumber daya.
Hal ini menjadikan ekofeminisme tidak sekadar menjadi diskursus akademik. Melainkan menjadi gerakan sosial yang menyuarakan keadilan ekologis dan kesetaraan gender secara bersamaan.
Ekofeminisme Islam: Spiritualitas sebagai Perlawanan
Ekspresi khas ekofeminisme di Timur Tengah merupakan gerakan yang muncul dengan menghubungkan spiritualitas Islam dengan kesadaran ekologis dan kesetaraan gender. Berbagai tradisi Islam, alam dipandang sebagai ayat-ayat yang bersumber dari Tuhan (tanda tanda kebesaran Allah). Manusia sebagai khalifah yang dapat menjaga keseimbangan bumi. Konsep tawhid, mizan (keseimbangan), dan amanah (tanggung jawab) menjadi landasan etis dalam hubungan manusia-alam.
Perempuan muslim di kawasan Timur Tengah memulai dalam penggalian ulang nilai-nilai untuk menantang narasi patriarkis dan eksploitatif yang seringkali menggunakan narasi keagamaan.
Misalnya, tokoh perempuan dari Iran yakni Mahlagha Mallah (terkenal sebagai “Ibu Lingkungan Iran” karena mendirikan Perkumpulan Perempuan melawan Pencemaran Lingkungan) dan Shina Ansari (yang pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Iran dan Kepala Departemen Lingkungan Hidup, dan meraih gelar doktor bidang manajemen lingkungan).
Fatimah Mernissi (intelektual feminis muslim asal Maroko, yang menyarakan ketidakadilan yang perempuan alami dalam masyarakat Arab-Islam). Hal ini menunjukkan bahwa Islam menjadi sumber energi spiritual dan politik dalam membangun gerakan ekofeminisme.
Ekofeminisme Islam hadir menolak dikotomi antara publik dan domestik. Dalam konteks krisis lingkungan, pekerjaan rumah seperti mengelola air, memasak, dan bertani bukan sekadar kerja reproduktif, melainkan bagian dari praktik ekologis bermakna.
Ketika perempuan terlibat dalam komunitas pertanian urban, pengelolaan limbah maupun pengelolaan air bersih, mereka tidak hanya “membantu” melainkan membangun alternatif terhadap sistem industri yang rusak.
Tantangan dan Harapan
Gerakan ekofeminisme di Timur Tengah menghadapi tantangan tersendiri. Di tengah rezim otoriter, kontrol negara terhadap organisasi masyarakat sipil, represi terhadap perempuan dan konflik berkepanjangan salah satu hambatannya. Banyak negara, isu lingkungan masih dianggap sekunder dibandingkan dengan politik kekuasaan atau pertahanan nasional.
Selain itu, dominasi pemikiran Barat dalam wacana diskursus feminisme global menjadikan ekspresi lokal ekofeminisme di Timur Tengah dianggap tidak “radikal” atau “feministik” secara standar global. Padahal, konteks lokal seyogyanya mempunyai gerakan yang otentik dengan menuntut strategi berbeda. Lebih subtil, mengakar dalam komunitas, dan terkadang terbungkus dengan narasi spiritual atau adat.
Kondisi ini menjadi pertanyaan penting, bagaimana gerakan ekofeminisme di Timur Tengah? Apakah akan tetap menjadi gerakan komunitas marjinal, atau bisa berkembang menjadi kekuatan politik dan budaya yang signifikan?
Di tengah krisis iklim global dan kekacauan geopolitik Timur Tengah, gerakan ekofeminisme memberikan cara pandang alternatif unik dan menyembuhkan. Ia tak hanya mengusung ide perlawanan, melainkan rekonsiliasi antara manusia dan alam, antara laki-laki dan perempuan, antara politik dan spiritualitas.
Misalnya, praktik dalam gerakan ekofeminisme dapat kita terapkan oleh komunitas perempuan di Lebanon yang mengembangkan pertanian organik sebagai wujud ketahanan pangan. Lalu ada perempuan Kurdi mengaitkan perjuangan ekologis dengan kebebasan politik.
Di Palestina, organisasi The Union of Agricultural Work Committees melibatkan perempuan untuk merebut kembali kedaulatan pangan dibawah pendudukan. Hal ini merupakan wujud ekofeminisme secara politis dan praksis.
Oleh karenanya, ke depan gerakan ini memerlukan penguatan jejaring antar-komunitas, dukungan kebijakan, dan pengakuan dalam wacana diskursus internasional. Sejumlah akademisi, jurnalis, maupun aktivis perlu mengangkat kisah-kisah lokal yang menjadi bukti bahwa ekofeminisme bukan sekadar teori yang bersumber dari North Global, melainkan juga berkembang di jantung dunia Islam.
Jalan Panjang Menuju Keadilan Ganda
Gerakan ekofeminisme di Timur Tengah bagian dari refleksi perjuangan ganda: mendobrak praktik patriarkti dan kapitalisme ekologis. Ia berupaya hadir dalam kehidupan nyata sehari-sehari perempuan dalam menjaga kehidupan di tengah krisis. Ia bersumber dari visi besar: membangun dunia yang berkeadilan, lestari dan setara.
Oleh karenanya, bukan soal apakah gerakan ini penting, melainkan bagaimana dapat memperkuatnya. Untuk menjawab Quo Vadis Ekofeminisme di Timur Tengah adalah sejauh mana perempuan di Timur Tengah menyuarakan dan pemangku kebijakan dan masyarakat pada umumnya mendengar suara perempuan, menghargai pengetahuan lokal, dan memperjuangkan keadilan ekologis sebagai bagian integral dalam Hak Asasi Manusia. []