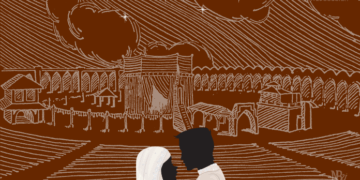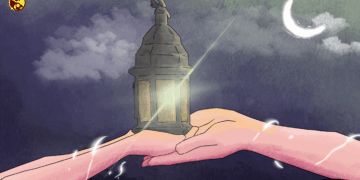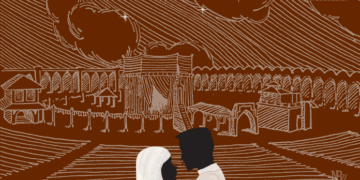Mubadalah.id – Baru-baru ini, di beranda TikTok saya muncul sebuah video yang memperlihatkan seorang perempuan menceritakan pengalaman kekerasan seksual yang ia alami saat menunaikan ibadah umrah. Dengan suara bergetar dan air mata yang tak tertahan, ia menjelaskan bagaimana seorang laki-laki dengan sengaja menempelkan kemaluannya. Bahkan memegang bagian tubuhnya selama beberapa waktu.
Dalam video tersebut, korban juga menyebut bahwa kejadian itu terjadi ketika ia tengah beribadah dan berusaha mencium Hajar Aswad. Alih-alih mendapatkan dukungan dan empati, jamaah perempuan tersebut malah mendapatkan victim blaming atas apa yang menimpanya. Beberapa komentar bahkan menuduh bahwa yang korban alami tak lain sebuah karma dan cerminan dari apa yang korban perbuat sebelumnya.
Tidak Hanya Dialami Oleh Jemaah Indonesia, Kekerasan Seksual Juga Dialami oleh Banyak Jamaah Perempuan di Dunia
Tagar #MosqueMeToo, menjadi viral bukan tanpa sebab. Tagar tersebut menunjukkan begitu masifnya kekerasan seksual yang terjadi selama para perempuan menunaikan ibadah umroh dan haji. Gerakan ini bermula dari kesaksian Sabicha Khan, perempuan asal Pakistan, yang menceritakan pengalamannya mengalami kekerasan seksual sebanyak tiga kali saat melakukan tawaf selepas salat isya.
Berangkat dari pengakuan Sabicha Khan itu, seorang jurnalis yang juga feminis Amerika-Mesir, Mona Eltahawy ikut menggunakan tagar #MosqueMeToo untuk mendukung Sabica. Penggunaan tagar ini bukan hanya sebagai bentuk solidaritas terhadap korban. Tetapi juga bertujuan sebagai upaya membuka ruang diskusi yang lebih luas dan objektif mengenai kekerasan seksual di rumah ibadah
Selain melalui media sosial, berbagai media massa internasional dan lokal turut memberitakan fenomena serupa. Laporan BBC, misalnya, memuat kesaksian tiga jamaah perempuan asal Indonesia yang berani mengungkap pengalaman kekerasan seksual yang mereka dan orang terdekatnya alami di tanah suci. Namun, masih banyak korban lainnya yang memilih diam karena takut disalahkan.
Ironi ini berkelindan dengan budaya victim blaming yang masih kuat mengintai para penyintas kekerasan seksual. Alih-alih mendapatkan dukungan dari publik maupun otoritas keagamaan, korban kerap tertuduh sebagai penyebab atas penderitaannya sendiri. Hal ini tak lain sebuah pandangan yang lahir dari keyakinan keliru tentang karma dan sebab-akibat dalam pengalaman hidup.
Kekerasan Seksual bukan Kejadian Sebab-Akibat!
Tempat suci Mekkah kerap kita kaitkan dengan keyakinan tentang adanya cerminan dari perbuatan seseorang selama hidupnya. Misalnya, ketika seseorang berperilaku buruk semasa hidup, diyakini akan mengalami kesulitan saat menunaikan ibadah haji atau umrah. Sebaliknya, mereka yang berbuat baik dipercaya akan mendapatkan kemudahan dalam setiap langkahnya di tanah suci.
Jika kepercayaan ini kita telisik dalam kejadian yang korban kekerasan seksual alami, tentu tidak dapat kita benarkan. Merujuk pada penjelasan Imam Al-Ghazali, hubungan antara sebab dan akibat tidak bersifat niscaya, melainkan terbentuk karena kebiasaan.
Dengan demikian, kesulitan yang seseorang alami saat beribadah di Mekkah tidak selalu berkaitan dengan moralitas atau perbuatannya di masa lalu. Bisa saja hal itu terjadi semata karena kebiasaan atau kondisi yang menyertainya. Hal sebaliknya pun demikian. Oleh sebab itu, dalam menyikapi kejadian kekerasan seksual yang jemaah perempuan alami tersebut kita tidak boleh menilainya melalui kacamata sebab-akibat atau karma.
Mengacu pada penjelasan Michel Foucault dalam The History of Sexuality, kekerasan seksual dapat terjadi sebab ada ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban. Penjelasan ini secara tegas menolak pandangan yang mengaitkan kekerasan seksual dengan pakaian atau perilaku korban.
Jika kita telusuri lebih jauh, korban kekerasan di tanah suci justru telah memenuhi standar kesopanan dan berbusana tertutup sebagai bagian dari niat beribadah. Ia juga hadir dengan tujuan yang jelas, yakni melaksanakan ibadah, bukan melakukan aktivitas lain.
Karena itu, anggapan bahwa kekerasan seksual yang korban alami merupakan akibat dari karma atau perilaku masa lalu adalah keliru dan tidak berdasar. Kekerasan seksual tersebut terjadi bukan karena kesalahan korban. Melainkan akibat adanya ketimpangan relasi kuasa antara jemaah perempuan dan pelaku yang dengan keji justru mencederai kesucian Mekkah.
Menciptakan Ruang Aman dalam di Rumah Ibadah
Bagaimana agar kita bisa menciptakan ruang aman di rumah ibadah bukan hanya menciptakan suasana yang mendukung kekhusyukan spiritual? Bagaimana juga kita bisa menjamin rasa aman, setara, dan bebas dari kekerasan bagi setiap orang yang beribadah. Kita perlu mendorong upaya ruang aman dalam beribadah dengan mengembalikan makna ibadah yang bukan hanya tercermin melalui tempat melainkan juga tercermin dalam perilaku umat di dalamnya.
Adapun lima hal yang dapat kita lakukan, tidak terbatas pada laki-laki namun juga perempuan sekaligus berbagai pihak untuk dapat menciptakan ruang aman dalam beribadah.
Pertama, mengakui bahwa kekerasan dapat terjadi di ruang keagamaan, sekecil apapun peluangnya. Pengakuan ini penting untuk menghentikan penyangkalan dan membuka ruang bagi korban agar dapat bersuara tanpa takut disalahkan.
Rumah ibadah seringkali kita pandang suci sehingga setiap bentuk kekerasan kita anggap mustahil terjadi di dalamnya. Padahal justru pandangan inilah yang kerap membuat pelaku merasa aman untuk bertindak dan korban semakin termarjinalkan.
Kedua, perlu adanya mekanisme perlindungan dan pelaporan yang jelas dan berperspektif korban. Pengurus rumah ibadah atau lembaga keagamaan dan otoritas pemerintah serta agen ibadah umroh dah haji dapat menyediakan jalur pengaduan yang aman. Misalnya dengan menunjuk petugas perempuan dan laki-laki yang terlatih menangani kasus kekerasan berbasis gender.
Mekanisme ini juga harus menjamin kerahasiaan identitas korban serta memberikan tindak lanjut yang nyata, bukan sekadar nasihat moral dan penyelesaian secara kekeluargaan. Hal ini tentu akan memberikan rasa aman yang jelas serta sanksi yang tegas bagi para pelaku nantinya. Sehingga semua pihak mampu mendapatkan pengalaman ibadah yang aman dan menihilkan kekerasan yang mampu terjadi selama ibadah berlangsung.
Ketiga, membangun ruang aman juga berarti melakukan pendidikan dan sosialisasi tentang kesetaraan gender serta etika interaksi di ruang ibadah. Para tokoh agama telah banyak memberikan penjelasan. Namun penegasan akan nilai-nilai penghormatan terhadap tubuh, batas pribadi, dan hak setiap individu sebaiknya semakin kita tingkatkan.
Seperti meneladani Nabi Muhammad Saw yang selalu menghargai setiap individu, termasuk perempuan sebagai makhluk yang setara. Dengan demikian, jamaah tidak hanya belajar tentang ibadah ritual, tetapi juga tentang tanggung jawab sosial dan moral terhadap sesama.
Keempat, tokoh agama perlu mengambil posisi tegas dalam menolak segala bentuk kekerasan seksual dan tidak menjadi aktor yang menormalisasi kekerasan seksual yang korban alami saat beribadah.
Posisi untuk berpihak pada korban akan menjadi teladan moral sekaligus pesan kuat bahwa agama tidak pernah membenarkan penindasan. Apalagi di ruang yang kita klaim suci. Para tokoh agama perlu menunjukkan sikap tegas dalam menolak segala bentuk kekerasan seksual, tidak hanya melalui ucapan, tetapi juga melalui tindakan nyata sebagai teladan bagi umat.
Terakhir, penciptaan ruang aman adalah proses kolektif. Jamaah, pengurus, otoritas keagamaan pemerintah, dan agen Umroh dan Haji perlu bekerja sama membangun budaya saling menjaga, saling percaya, dan saling mendengarkan. Hanya dengan cara itu, tempat ibadah benar-benar dapat menjadi ruang yang tidak hanya suci secara spiritual, tetapi juga aman dari segala bentuk kekerasan. []