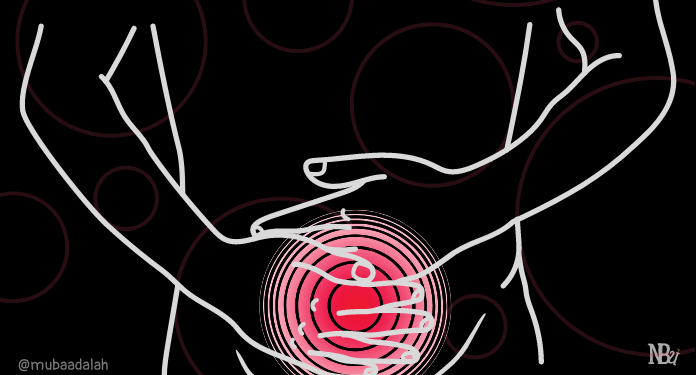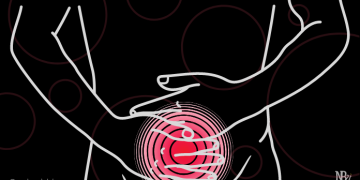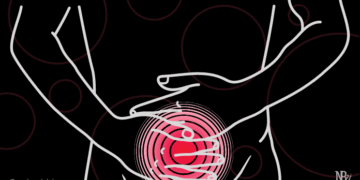Mubadalah.id – Beberapa bulan lalu, kami bersama rombongan Ngalap Berkah dari kalangan remaja-remaja desa, berziarah ke makan para wali dan orang-orang saleh yang ada di tanah Lombok, NTB. Di salah satu makam yang kami yakini paling keramat dan paling banyak peziarah, terdapat sebuah tulisan yang cukup mencengangkan. Pada tembok bagian luar makam tersebut, tepat di dekat pintu masuk, tertulis “Mohon Maaf Perempuan Haid Dilarang Masuk!!!”.
Saya yang baru kali pertama mendatangi tempat itu lagi setelah sekitar 13 tahun lalu, merasa sangat aneh. Terutama setelah lebih banyak mengkaji isu-isu perempuan. Dalam hati bergumam, ‘Ternyata di tanah kelahiran saya masih banyak sekali yang perlu terbenahi’.
Dampak dari pemandangan itu, kekhusyukan tawasul dan doa akhirnya sedikit memudar. Tidak bisa hilang tulisan itu dari benak saya. Tertancap sangat kuat dan banyak memunculkan “tanda tanya”. Sebelum kami teliti lebih jauh, sampai detik ini kami berkesimpulan, tidak sedikit masyarakat kami yang tidak ramah perempuan haid. Insya Allah beberapa waktu ke depan, kami akan terjun mencari informasi lebih lanjut.
Alhasil, tulisan itu mendorong saya menulis artikel ini. Hal pertama kali muncul adalah mengapa perempuan haid mendapat diskriminasi fasilitas spiritual di kancah sosial mereka? Apakah karena Al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 222 yang salah pemahaman, sehingga ada anggapan perempuan haid itu jorok?
Atau karena menghormati makam para wali Allah?, atau mungkin karena perempuan haid dianggap tidak lebih mulia dari “yang suci”? Tiga pertanyaan ini adalah hal yang paling mendasar sesuai dengan kondisi masyarakat yang saya lihat. Sehingga mungkin tepat bila kita memulai dari tiga ruang ini.
Tafsir al-Adza dalam Surah al-Baqarah Ayat 222
Allah subhanahu wa ta’ala berfirman dalam al-Baqarah ayat 222;
ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهنّ حتى يطهرن فإذا تطهرن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين
Artinya, “Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, ‘itu adalah sesuatu yang kotor’. Karena itu, jauhilah istri pada waktu haid; dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, gaulilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri.”
Posisi term al-adza dalam ayat di atas ini sebagai tafsir atas term al-mahidh sebelumnya yang mengandung tiga makna. Pertama, bermakna damul haidh (darah haid), kendati makna ini bukanlah yang dimaksud dalam ayat tersebut. Kedua, bermakna makanul haidh (tempat keluarnya haid), dan ketiga, bermakna zamanul haidh (masa haid). Dua makna terakhir adalah yang menjadi sorotan para ulama dan melahirkan dua konsekuensi hukum yang berbeda.
Lafal al-adza, walau secara etimologi berarti penyakit atau kotoran, namun secara konsekuensi hukum menjadi sebagai perlambang sebuah larangan (al-hadhzar). Artinya, karena itu penyakit, maka harus dijauhi. Sehubungan dengan ini, Syekh Muhammad Mutawalli as-Sya’rawi dalam Fiqh al-Mar’ah al-Muslimah (hal. 26) membuka sebuah pertanyaan yang menarik. Ia menulis;
ولكن هل دم الحيض أذى للرجال أم للنساء؟
Artinya, “Tetapi, apakah darah haid itu penyakit bagi laki-laki, atau perempuan?.”
Diskriminasi terhadap Perempuan Haid
Mufasir kenamaan Mesir itu menerangkan bahwa haid merupakan penyakit baik bagi laki-laki maupun perempuan. Itu artinya, darah haid dapat menjadi penyakit hanya dalam kondisi tertentu, terlihat dari satu sudut pandang saja (haitsiyyah makhshushah).
Yaitu, hanya dalam konteks berhubungan badan (iltiqa’ul khitanaini). Oleh karenanya, sangat tidak tepat bila kita sikapi sebagai sesuatu yang menjijikkan. Bagai langit dan bumi, jika larangan mendekati perempuan haid dalam kondisi tertentu itu, akan melahirkan kesimpulan bahwa mereka jorok dan menjijikan, di mana pun selama masa haidnya. Lagi pula, haid adalah tabiat, bukan aib.
Kalau saja tidak ada faktor lain yang mendorong munculnya sikap diskriminasi perempuan haid, sudah barang pasti merupakan akibat dari kesalahan memahami surah al-Baqarah ayat 222 di atas.
Baik, sekarang kita akan berasumsi bahwa faktornya adalah memuliakan makam para wali dan orang-orang saleh? Artinya, mereka paham dengan benar ayat di atas. Tetapi, kali ini adalah tentang adab kepada orang-orang suci itu. Sehingga para perempuan haid terlarang masuk. Jika memang demikian, sebelum merespon asumsi tersebut, penting kita tahu apa saja yang terlarang bagi orang haid.
Menelisik Lebih Dalam tentang Perempuan Haid
Seringkas yang saya baca, terutama kaitannya dengan tempat, hukum fikih kita hanya melarang perempuan haid masuk masjid-dengan catatan, ada kemungkinan mengotori (at-talwits)-,berdiam diri dan mondar mandir di sana. Adapun tempat-tempat lain seperti madrasah, musala, majelis taklim, makam dan seterusnya, terbuka pintu selebar mungkin. Sekali lagi, ini menurut fikih. Lalu, bagaimana menurut kacamata adab?
Secara lebih spesifik, jika kita melarang perempuan haid masuk makam para wali, tawasul dan zikir di sana atas nama adab, maka kita sedang menyatakan bahwa mereka tidak menghormati orang-orang saleh yang dikebumikan di sana. Jelas, sebab ini atas nama adab. Bagaimana mungkin sesuatu yang dianggap tidak beradab, tetapi masih dalam lingkar at-takrim wa at-ta’dhzim (memuliakan)?
Jika demikian, mengapa mereka masih boleh belajar, masuk madrasah, majelis taklim, dan berzikir? Jika masih konsisten dengan “atas nama adab”, seharusnya mereka juga tidak boleh belajar, masuk madrasah dan seterusnya. Mengingat, itu bagian dari memuliakan ilmu. Apa yang lebih mulia daripada ilmu di dunia ini? Tetapi, nyatanya tidak.
Mereka mendapat dorongan agar terus belajar dan bersekolah. Itu artinya agama tidak pernah sedikit pun mendiskriminasi perempuan haid dengan tidak memberi fasilitas belajar dan berzikir. Bahkan, agama tetap mensuport mereka agar tetap memperkokoh benteng intelektual dan spiritual. Alhasil, keliru jika mengatasnamakan adab.
Perempuan Haid Bisa Lebih Mulia dari “yang Suci”
Secara umam, syariat kita memiliki dua corak hukum yang sama-sama besar; pertama, larangan, kedua, perintah. Baik larangan maupun perintah, jika berhasil mengejawantahkan tujuan besar keduanya tetap tersebut sebagai ketaatan. Saat saya mendapat perintah berjalan dan saya melakukannya, jelas sebuah ketaatan (imtitsal al-awamir). Begitupun sebaliknya, saat saya terlarang berjalan dan saya tidak melakukannya, maka juga disebut taat (ijtinabu an-nawahi).
Jadi, jika perempuan mendapat perintah salat atau puasa dan mereka melakukannya, mereka adalah perempuan yang taat. Jika mereka terlarang salat atau puasa saat haid dan mereka meninggalkannya, mereka juga perempuan taat. Maka dari itu, bila kita nilai secara umum, manakah yang lebih berpeluang untuk tetap taat?
Apakah mereka yang tidak haid dengan salat dan puasanya, atau mereka yang haid dengan cara tidak salat dan puasa? Tampaknya, nyaris tidak pernah kita temukan perempuan yang sengaja salat dan puasa sementara mereka tengah haid.
Terakhir, mengutip penggalan Hadist riwayat Abu Hurairah dalam Shahih al-Bukhari (hadits ke-7288) yang berbunyi;
فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم
Artinya, “Jika aku melarang kalian, maka jauhilah!, dan jika aku memerintah, lakukanlah semampunya.”
Dari teks hadist ini, kita bisa menangkap bahwa atensi syariat terhadap larangan, lebih besar daripada perintah. Terbukti dengan redaksi “mastatha’tum” dalam rangkaian diksi tentang perintah.
Akhirul kalam, jangan pernah mendiskriminasi perempuan haid dalam ruang apapun. Selain karena itu tabiat, mereka bisa jadi lebih mulia daripada kita. Wallahu a’lam bisshawab. []