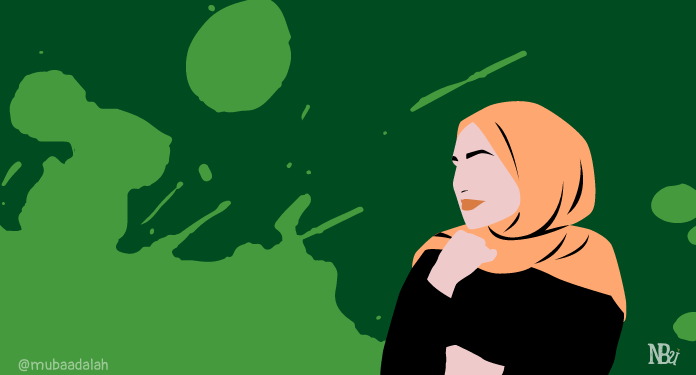“Kamu takut nggak sih hidup sendirian sampai tua?”
Atau, pertanyaannya dibalik.
Kamu siap nggak sih hidup dengan seseorang kalau kamu belum bisa hidup dengan dirimu sendiri?
Mubadalah.id – Ada kalanya saat kita sedang duduk diam, tiba-tiba muncul pertanyaan di kepala: “Kenapa ya, aku harus menikah? Karena cinta? Atau karena takut sendirian? Karena desakan keluarga? Atau, karena semua orang melakukannya?”
Di antara gegap gempita pernikahan yang dipamerkan di media sosial, seringkali terselip rasa takut yang jarang kita bicarakan. Takut tidak menikah, dicap gagal, dan takut kesepian. Tapi, apakah benar hidup tanpa nikah dan sendiri itu lebih menyeramkan dari hidup yang kehilangan jati diri?
Hmmmm… Mari kita pelan-pelan telaah.
Dalam masyarakat kita, menikah seakan jadi “ritual suci” yang tak boleh terlewatkan. Tapi, kalau kita tarik nafas dan jujur pada diri sendiri, benarkah semua orang harus menikah? Al-Qur’an sendiri tidak pernah menyuruh semua manusia untuk menikah, lho. Yang ditekankan justru adalah kemampuan dan kesiapan:
“Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.” (QS. An-Nur: 33)
Lihat? Menjaga diri, menjaga martabat, dan menunggu kesiapan adalah hal yang diutamakan. Artinya, hidup hidup tanpa nikah dan sendiri itu bukan dosa. Bukan kutukan. Ia bisa jadi bentuk ketaatan, bentuk pencarian diri, bahkan bentuk ibadah yang sepi namun dalam.
Kita sering diajari bahwa menikah akan membuat hidup lebih lengkap. Tapi bagaimana jika justru kita menikah karena kita belum lengkap? Maka pernikahan itu bisa jadi tempat pelarian, bukan pertemuan dua insan yang utuh.
Seorang sufi perempuan, Rabiah al-Adawiyah, pernah berkata:
“Cintaku kepada-Mu tidak karena surga, dan ibadahku bukan karena takut neraka. Aku hanya ingin dekat, karena Engkau adalah tujuan.”
Yang seringkali keliru bukanlah soal pernikahannya, tapi alasan kenapa seseorang melangkah ke sana sejak awal. Tentu saja, menikah tetaplah sebuah perbuatan terpuji dan mulia. Ia adalah ikhtiar menyatukan dua jiwa dalam ikatan yang terberkahi. Tapi, niat yang sering terselimuti kabut harapan romantis, tanpa sadar menyingkirkan kesadaran tentang tanggung jawab yang menyertainya.
Sedangkan, pernikahan bukanlah panggung pesta abadi untuk dua hati yang mabuk rindu, melainkan ladang tempat dua manusia belajar menanam sabar, menyiram pengertian, dan memanen keberanian untuk tetap tinggal, bahkan saat pelukan terasa jauh.
Sayangnya, manusia kerap lupa: menikah bukan soal menemukan bahagia, tapi menciptakan bahagia. Dari hal-hal yang tidak selalu indah, tidak selalu mudah, tapi selalu butuh niat yang benar sejak mula.
Lalu kita, seringkali mendekati pasangan bukan karena keutuhan, tapi karena ketakutan. Kita takut tidur sendiri. Takut menghadapi masalah sendiri. Takut mendengar suara hati sendiri. Padahal, siapa pun yang hidup terlalu bergantung pada orang lain, cepat atau lambat akan merasa hampa. Karena yang seharusnya kita bangun adalah kemandirian spiritual, emosional, dan eksistensial.
Socrates bilang, “Kenalilah dirimu sendiri.” Tapi di zaman sekarang, agaknya kita lebih sibuk mengenali algoritma media sosial daripada mengenali isi hati.
Kita takut sendiri bukan karena sendirinya yang menakutkan, tapi karena kita tak tahu harus ngapain saat sendiri. Kita tak bisa menikmati keheningan, karena di situ kita harus berhadapan dengan isi pikiran sendiri. Maka kita cari pelarian: entah itu lewat pasangan, keramaian, atau bahkan pernikahan yang terburu-buru. Benar?
Pertanyaannya: mau sampai kapan?
Kalau kamu single, coba deh jawab pertanyaan ini:
Apa kamu ingin menikah karena benar-benar ingin berbagi hidup? Atau karena takut dibilang “gagal jadi perempuan/laki-laki”?
Ketika kamu hidup tanpa nikah, bangun besok pagi dan tak ada siapa-siapa di sampingmu, apakah kamu tetap bisa bahagia dan merasa utuh?
Kalau belum bisa jawab, mungkin belum saatnya menikah. Dan itu… tidak apa-apa. Serius, nggak papa. Bahkan, itu bisa jadi tanda kedewasaan.
Disclaimer: tulisan ini bukan kampanye anti menikah yaa. Intinya, bukan pernikahan yang menakutkan, tapi ketika kita menggantungkan hidup sepenuhnya pada kehadiran orang lain. Pernikahan itu bukan jawaban atas kekosongan batin, melainkan ekspresi dari kebulatan hati.
Yang menyeramkan adalah:
ketika kita takut hidup tanpa pasangan,
Dan ketika kita tidak punya identitas tanpa status pernikahan,
ketika kita tidak tahu siapa kita kalau tidak jadi “istrinya siapa” atau “suaminya siapa.”
Sebelum bicara soal dua orang yang menyatu, mari bicara tentang satu jiwa yang utuh. Kita bisa belajar dari tokoh-tokoh hebat yang tidak buru-buru menikah, atau bahkan memilih untuk tidak menikah, demi misi hidup yang lebih besar.
Maryam a.s., misalnya. Seorang perempuan suci yang disebut langsung dalam Al-Qur’an. Beliau tidak dikenal karena pernikahannya, tapi karena integritas dan pengabdiannya.
“Dan Maryam, putri Imran, yang menjaga kehormatannya, maka Kami tiupkan ke dalam (tubuhnya) ruh dari Kami, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitab-Nya, dan dia termasuk orang-orang yang taat.” (QS. At-Tahrim: 12)
Maryam tidak menikah. Tapi lihat, ia bukan hanya kita hormati, tapi terabadikan sebagai teladan perempuan.
Kalau kamu bahagia sendiri, punya mimpi yang sedang kamu bangun, punya komunitas yang mendukung, dan kamu menikmati proses mengenal diri, itu bukan kegagalan. Itu justru pencapaian.
Maka, mari ubah narasinya:
Bukan “kapan nikah?”, tapi “apa kamu sudah bahagia dengan hidupmu sekarang?”
Bukan “takut nggak laku?”, tapi “apa kamu sudah mencintai dirimu sendiri sepenuhnya?”
Karena ketika kita utuh, pernikahan akan jadi perayaan, bukan pelarian. Tapi kalau belum utuh, sendiri pun bisa jadi jalan suci menemukan diri, kok.
Jadi, tak perlu buru-buru menikah demi membungkam dunia. Dunia toh tak akan pernah benar-benar diam. Lebih baik berdamai dengan keheningan hati sendiri. Karena dari situlah, suara Tuhan sering kali terdengar paling jelas. []