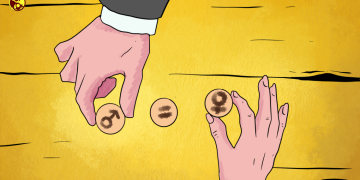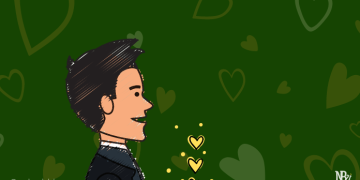Mubadalah.id – Isu mengenai busana perempuan muslimah selalu saja menarik perhatian publik. Terutama di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam ini. Ya, bisa dibilang isu tentang jilbab selalu menarik untuk didiskusikan. Termasuk dalam hal ini membicarakan batas aurat perempuan muslimah. Lagi-lagi, busana perempuan, ya.
Entah mengapa, perhatian publik terhadap berbusana perempuan tak pernah lekang oleh waktu. Sedangkan yang substansial mengenai hak-haknya sebagai manusia kerap diabaikan. Semisal nih, hak atas ruang aman, hak akses kesehatan reproduksi, dan lain-lain. Yah begitu, yang kerap terjadi berpusat pada ketubuhannya, tidak dengan kebutuhan sebagai makhluk yang memiliki biologis berbeda dari laki-laki.
Beberapa waktu lalu, timeline di akun Twitter saya ramai dengan diskusi hingga pada perdebatan sengit tetang jilbab. Oke, tidak ada yang salah dengan membuka ruang-ruang diskusi terutama di berbagai platform media sosial.
Namun, yang menjadi persoalan ialah ketika berujung pada terciptanya ujaran kebencian, saling menghina, menghujat, hingga keluar sumpah serapah. Sungguh, saat itu saya hanya bisa mengelus dada dan menahan diri agar tidak gegabah menggerakkan jempol, lalu nimbrung berkomentar. Apalagi saat itu ada juga yang sampai pada menyangkutpautkannya dengan ranah yang sifatnya sangat privasi. Ya, pastinya tidaklah etis jika ranah privat dibawa pada ranah publik.
Oh iya, salah satu hal yang membuat saya tergerak menulis hal ini ialah karena sumpek dengan beragam komentar para netizen yang tak sedikit menghujat, ketika ada seorang publik figur memutuskan melepas jilbabnya. Pastinya fenomena seperti ini tidak terjadi sekali dua kali, melainkan sangat sering terjadi. Yang ingin saya tanyakan, apa benar jilbab itu penanda atau alat ukur kesalehan seorang perempuan muslimah?
Mari kita refleksikan bersama. Sebab, sebagaimana yang kita tahu, agama tak sebatas halal-haram, surga-neraka, hitam-putih, dan lain-lainnya. Namun lebih dari itu. Ibu Nur Rofi’ah pernah menyampaikan bahwa perihal agama, sesuatu itu harus halal (diperbolehkan), toyyib (baik), dan ma’ruf (pantas).
Apa iya, muslimah yang berjilbab sudah tentu lebih mulia, saleha, dan suci dari muslimah yang tidak berjilbab? Dari pengalaman saya sebagai perempuan muslimah, tentu saja tidak demikian. Seorang muslimah yang berjilbab –entah jilbab panjang atau pendek— belum tentu lebih baik dari muslimah yang tidak berjilbab.
Yang perlu digaris bawahi, menghitung amal perbuatan seseorang bukan ranahnya manusia. Apalagi mengklaim siapa yang lebih berhak menjadi penghuni surga dan neraka. Dalam hal ini, tentu saja hanya Allah Swt. yang berhak atas itu.
Dahulu, semasa saya masih berada di pondok pesantren, saya beranggapan bahwa jilbab itu bagian dari menutup aurat yang hukumnya wajib. Hal ini tentu saja mempengaruhi cara pandang saya terhadap perempuan muslimah yang memilih untuk tidak berjilbab. Pastinya, dengan cara pandang sinis dan penuh penghakiman.
Seiring berjalannya waktu, saya menemukan beragam fakta bahwa banyak pandangan dan pendapat dari para ulama’ dan cendekiawan mengenai batas aurat perempuan. Jelasnya, menutup aurat memanglah wajib. Baik, kita kembali pada fenomena jilbab yang kerap diidentikkan dengan ukuran kesalehan maupun keimanan seorang perempuan.
Beberapa sumber yang saya dapatkan mengatakan, cerita di balik turunnya ayat Al Ahzab 59, yaitu ketika salah seorang istri Rasulullah buang hajat di luar rumah pada malam hari tanpa memakai penutup kepala. Karena disangka budak, istri beliau pun hampir menjadi korban pelecehan seksual dari laki-laki lain. Akhirnya, turunlah perintah Allah agar istri Nabi dan perempuan muslimah memakai jilbab.
Ibnu Jarir At-Thabari, guru ahli tafsir menyimpulkan ayat tersebut sebagai larangan menyerupai cara berpakaian perempuan-perempuan budak. Artinya, jika dirunut dari asbabun nuzul Al-Ahzab 59, pada dasarnya jilbab merupakan penanda status sosial. Yaitu untuk membedakan antara perempuan merdeka dan budak.
Bukan sebagai penanda perempuan muslimah dan non-muslimah, maupun keimanan seseorang. Lalu, ketika sistem perbudakan telah dihapuskan dalam ajaran Islam, apakah jilbab masih bisa dikatakan pakaian wajib bagi perempuan muslimah?
Sedangkan, menurut ulasan Prof. Quraish Shibab dalam bukunya yang berjudul “Jilbab: Pakaian Wanita Muslimah”, dijelaskan pula bahwasanya semua ulama bersepakat jikalau menutup aurat itu diwajibkan. Namun mengenai batasan aurat, para ulama dan cendekiawan pun berselisih pendapat. Di dalam buku beliau juga dijelaskan pula mengenai berbagai pendapat beserta dalil-dalil yang dikutip oleh para ulama.
Prof. Quraish juga menerangkan bahwa ada pula ulama yang berpendapat, “Yang penting itu pakaian terhormat. Berjilbab itu baik, bagus. Tapi boleh jadi, sudah melebihi apa yang dikehendaki Tuhan.”
Artinya, jilbab bukanlah satu-satunya ukuran kesalehan dan keimanan seseorang. Siapa pun itu, laki-laki maupun perempuan, ukuran kesalehan dan keimanan seseorang ialah terdapat pada kesucian hati yang dalam banyak ayat al-Qur’an maupun hadits Nabi lebih ditekankan terletak pada pikiran, cara pandang, dan hati manusia. Serta, pakaian terbaik muslim dan muslimah ialah takwa pada Allah Swt.
Selain itu, Prof. Alimatul Qibtiyah, ketika menjadi penguji skripsi saya tentang representasi perempuan Islam menyampaikan, “Semua pendapat para ulama’ dan cendekiawan tentang jilbab maupun batasan aurat perempuan itu valid.
Yang menjadi persoalan ialah ketika kita mengklaim hanya ada satu pendapat yang benar dan tidak bisa diganggu gugat. Hanya ini yang benar. Selain itu, salah bahkan sesat.”Jelasnya, setiap pendapat para ulama’ maupun cendekiawan tentu saja tak jauh dari hajat serta kondisi sosial, ekonomi, maupun politik pada saat itu.
Mengutip tulisan K.H. Husein Muhammad yang berjudul “Jilbab, Hijab dan Kesalehan” yang dipublikasikan di mubadalah.id, terdapat pandangan menarik dari Dr. Muhammad al-Habasy, direktur Pusat Kajian Islam Damaskus, Siria, yang mengatakan:
“Seorang perempuan dapat memilih pakaiannya sendiri untuk berbagai keperluan dan keadaan. Akan tetapi ia bertanggung jawab atas pilihannya itu di hadapan masyarakatnya dan di hadapan Allah. Ia punya hak sosial dengan tetap menjaga kesopanan dan kehormatan dirinya. Akan tetapi mewajibkannya untuk semua perempuan dalam segala situasi atas nama agama, sebagaimana yang berkembang di sejumlah Negara Islam dewasa ini adalah tidak realistis dan menyalahi petunjuk Nabi dan keluwesan dan keluasan fiqh Islam”. (Muhammad al-Habasy, Al-Mar’ah Baina al-Syari’ah wa al-Hayah”, Dar al-Ahbab, Damaskus, Cet. V, 2001, hlm. 67-68). Wallahu a’lam. []