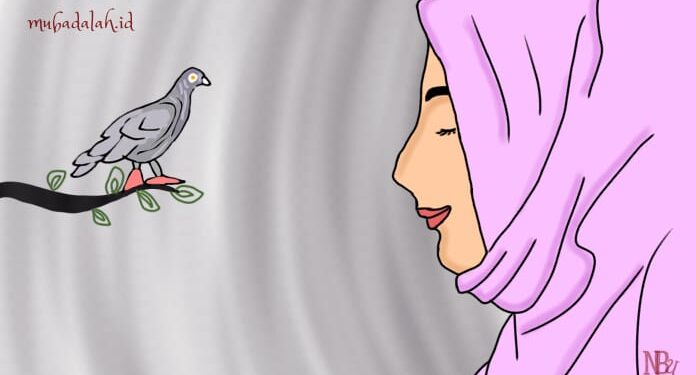Mubadalah.id – Saya ingin memulai tulisan ini dengan kata “Paraban Tuah”. Mungkin penulisan kata tersebut esok hari ada yang mengkritik, sebab ejaan yang kurang benar atau tidak pas dengan pengucapan kalimatnya. Akan tetapi, kata tersebut saya ambil dari judul cerita yang diangkat oleh Elok Teja Suminar dengan judul “Paraban Tuah”.
Tulisan Elok menceritakan kisah pengalaman perempuan-perempuan Madura atas dasar kegelisahan dan keresahan yang dialaminya sebagai bagian dari Madura itu sendiri. Pergulatan batin serta sosial masyarakat Madura menjadi keresahan penulis hingga tulisan tersebut berhasil menguras pembaca, apalagi sebagai pembaca perempuan yang terlahir dari Madura.
Fokus terhadap makna dari kata tersebut, “Paraban Tuah” merupakan istilah yang dipakai oleh masyarakat Madura untuk menyebut perempuan lajang yang belum menikah, atau dengan kata yang lebih halus dalam bahasa Indonesia, yakni “perawan tua”. Saya sempat dibuat bingung ketika sebutan ini disematkan pada perempuan Madura khususnya, mengapa tidak ada sebutan “lanceng tuah” (red: perjaka tua). Lagi-lagi ini masalah konstruk sosial. Perempuan selalu memiliki kesan tidak terlalu baik terhadap segala hal term kehidupan yang dijalaninya.
Secara umum, sebutan ini memang tidak hanya dimiliki oleh masyarakat Madura. Sebab di Indonesia sendiri, sebutan semacam ini kerap kali mengiringi perempuan yang belum menikah. Jika membaca novel yang berjudul “Genap Ganjil” karya Almira Bastari. Ada kalimat menarik yang bisa saya sampaikan pada tulisan ini dari novel tersebut bahwa kita hidup di sebuah negara, di mana anak umur 30 tahun adalah masalah besar jika belum menikah. Nyatanya kalimat itu memang benar, sangat relate dengan kondisi kita sekarang, apalagi perempuan Madura.
Perempuan Madura memang selalu memiliki problematika demikian, sebutan “paraban tuah” itu bukanlah sebuah penghargaan seperti Miss Universe dan dibanggakan oleh seluruh umat. Justru sebaliknya, sebutan itu jadi boomerang, mematikan karakter, membunuh mental, bahkan seolah-olah saya sebagai perempuan Madura merasa berdosa sebab belum memutuskan untuk menikah.
Padahal, keputusan menikah itu bukanlah yang mudah, bangunan keluarga maslahah dengan doa yang sering dipanjatkan dalam sebuah pernikahan yakni sakinah, mawaddah, warahmah itu tidak serta merta tercipta begitu saja setelah pernikahan. Pemahaman ini sangat penting untuk kita miliki. Sebab biar tidak ikut arus.
Jangan sampai kita ingin menikah hanya karena teman main kita sudah menikah, atau tetangga yang memaksa untuk menikah, lebih parahnya lagi kalau kita memutuskan untuk menikah hanya karena tidak ada alasan lain untuk melanjutkan hidup selain menikah. Tolong, ini dihindari.
Jika dalam novel Ganjil-Genap tersebut mempermasalahkan umur 30 tahun. Beda lagi di Madura, jarang sekali perempuan Madura umur 30 tahun belum menikah. Jangankan 30 tahun, 25 tahun saja sudah dianggap “Paraban Tuah”. Lulus SMP saja sudah menikah, bahkan lulus SD-pun ada yang sudah menikah. Mungkin kita bisa berpikir dan menulis panduan hidup bagi anak yang mengurus anak.
Mengemas Konstruk Pemikiran Soal “Paraban Tuah”
Jika dulu kita selalu tidak percaya diri dengan sebutan “Paraban Tuah” yang disematkan oleh masyarakat kepada kita sebagai perempuan yang belum menikah. Maka hari ini, sudah saatnya untuk percaya diri dengan sebutan demikian. Alih-alih apakah ini sebuah ajakan hanya untuk mempertegar diri dari omongan tetangga? Nyatanya tidak demikian.
Kita selama ini meyakini sesuatu, membenarkan sesuatu berdasar dari kesepakatan sosial yang dipahami oleh kebanyakan orang. Istilah “Paraban Tuah” ini selalu identik dengan perempuan yang tidak laku, tidak ada laki-laki yang berniat menikahi, atau pandangan tidak sehat lainnya.
Bagaimana kalau ternyata kita sebagai perempuan Madura hari ini yang mendapat sebutan ini, sedang mempersiapkan diri secara lahir batin untuk membangun rumah tangga? Bagaimana kalau ternyata sedang fokus menyelesaikan pendidikan? Bagaimana kalau ternyata sedang fokus terhadap pencapaian karir di masa depan dengan niat agar di masa depan keluarga yang dibangun terhindari dari masalah perekonomian, pemikiran yang tidak dewasa dan hal lain.
Tentu pilihan untuk berpikir semacam ini adalah bentuk kebebasan kita sebagai perempuan Madura. Saya kira, sejalan dengan pendidikan, pengalaman hidup perempuan, kita akan memaknai sebutan apapun sebagai sebuah pembelajaran hidup untuk belajar, khususnya dari kegagalan pernikahan.
Perempuan Madura punya pilihan untuk melakukan apapun sesuai keinginannya. Yang terpenting adalah bagaimana secara kolektif membangun kesadaran masyarakat bahwa beban pernikahan tidaklah disematkan kepada perempuan semata, lalu seolah-olah menjadi dosa dan beban moral ketika ada perempuan yang masih memilih melajang. []