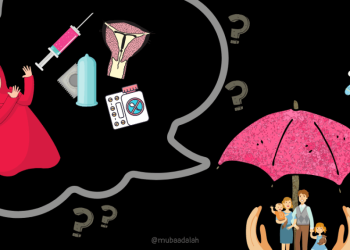Mubadalah.id – Beberapa hari lalu seorang teman memberi saya masukan untuk menulis sebuah topik tulisan sebagai upaya kampanye yang dianggapnya penting. Kemudian ia mengirimi sebuah link youtube untuk saya tonton, ya, video itu bisa jadi insight saya ketika hendak menulis tentang problematika yang menimpa perempuan. Tapi mengenyahkan rasa mager adalah hal yang amat sulit, apalagi nulis bukan hal remeh-temeh bagi manusia macam saya yang pemalas.
Dan akhirnya nasib link video itu tak kunjung saya klik dan dibiarkan tertimbun begitu saja oleh pesan-pesan lainnya, dengan begitu tentu saya tidak tau video apa sebetulnya yang teman saya kirimi itu. Tetapi kemudian saya penasaran juga dengan video yang sudah tertimbun pesan lainnya di whatshapp. Sial, saya merinding setelah menonton video yang teman saya kirimi.
Kendati demikian, video itu bukan tentang hantu yang membuat merinding, tentu bukan sama sekali, lebih dari itu ada perasaan getir di hati saya. Tubuh-tubuh kurus itu terkurung jeruji besi, sedangkan rantai besi mengikat kaki-kakinya, tak ada alas yang menghangatkan tubuh kering mereka, hanya selembar baju yang terpakai dengan penuh lusuh yang mugkin beberapa bulan tak diganti atau bahkan telah beberapa tahun, entahlah.
Memang tak semua dirantai, tetapi semua dari mereka dikurung jeruji besi dan hidup bertumpuk-tumpuk di satu tempat yang jauh dari kata layak. Mereka diperlakukan sangat tidak manusiawi karena dianggap tidak memiliki kesadaran sebagai manusia. Kalaupun memang mereka tidak memiliki kesadaran seperti manusia normal, apakah pantas merampas hak kemanusiaan seorang manusia? Bukankah ini sebuah penyiksaan?
Itulah yang dirasakan oleh ribuan penyandang disabilitas mental yang ditempatkan di berbagai panti sosial di beberapa wilayah di Indonesia. Tindakan-tindakan peyiksaan semacam itu dianggap wajar hanya karena mereka bukan manusia yang ‘dianggap’ normal, ada hak-hak mereka yang tidak didapatkan. Betul, mereka memiliki hak hidup layak sebagai manusia, dipenuhi kebutuhannya, termasuk perlidungan dari berbagai perlakuan tidak manusiawi.
Bayangkan mereka hidup di dalam panti rehabilitas berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun sampai waktu yang tidak ditentukan. Banyak dari mereka yang diputus akses untuk berkomunikasi dengan keluarga, hingga akhirnya baik penyintas maupun keluarga kehilangan kabar, ini kemudian yang membuat mereka tinggal sampai waktu tak ditentukan dengan perlakuan yang amat tidak manusiawi.
Tak jarang perempuan penyintas psikososial di panti rehabilitas mendapatkan pelecehan bahkan kekerasan seksual di sana. Bukan hanya oleh sesama penyintas yang laki-laki tetapi ada kasus di mana dokterlah yang melakukan kekejian itu.
“Dokter memegang payudara saya” ujar seorang perempuan penyintas dalam video yang saya tonton.
Seketika saya membayangkan nasib mereka itu, mendapatkan dua kali lipat perlakuan buruk dari situasi tidak manusiawi. Kita mengetahui betul perempuan memiliki kerentanan mendapatkan kekerasan termasuk kekerasan seksual, apalagi ketika mereka dianggap tidak memiliki kesadaran normal seperti orang lain. Di ranah-ranah yang nampak aman dari kekerasan seksual seperti rumah, sekolah, kampus pun tidak ada yang bisa menjamin bebas kekerasan seksual, apalagi di panti-panti rehabilitas yang keamanannya masih diragukan.
Kita pun perlu tau, berdasarkan laporan pemantauan Komnas Perempuan 2019 yang bertajuk “Hukuman Tanpa Kejahatan; Dimensi Penyiksaan dan Daur Kekerasan terhadap Perempuan dengan Disabilitas Psikososial di Lokasi Serupa Tahanan (RSJ dan Pusat Rehabilitasi)”.
Yakni, sebab-sebab yang melatarbelakangi bahkan memperparah Perempuan dengan Disabilitas Psikososial (PdDP) tak lepas dari dimensi kekerasan berbasis gender. Di antaranya adalah kekerasan seksual, kekerasan dalam pacaran, KDRT, domestifikasi perempuan dan pencerabutan otoritas diri, kekerasan fisik dan penganiayaan, kekerasan psikologis, eksploitasi seksual dan lainnya.
Tidak dapat saya bayangkan jika seorang PdDP ternyata korban dari kekerasan seksual, korban dari KDRT, korban dari eksploitasi seksual, sehingga mereka menjadi disabilitas psikososial. Dan ketika mereka di panti rehabilitas malah mendapatkan hal yang serupa, mereka dilecehkan dan sebagainya. Seketika saya bergidik ngeri, ini nampak seperti lingkaran setan bagi perempuan disabilitas psikososial.
Hal itu diperparah dengan penyiksaan yang diapatkan atas nama perawatan. Praktik Electro Convulsive Therapy (ECT) atau terapi kejut listrik, pengekangan dengan rantai besi, perampasan kebebasan dengan sel isolasi, kekerasan fisik dan sebagainya.
Apa yang mereka PdDP alami kerap luput dari perhatian kita, padahal begitu banyak pelanggaran Hak Asasi Manusia yang mereka rasakan. Dan hidup dalam kegetiran itu tidak lebih baik dari neraka itu sendiri.
Sudah saya bilang di awal, tulisan ini adalah permintaan kawan saya yang awalnya saya tolak. Tetapi setelah melihat video (teman-teman bisa tonton video-nya di link ini https://www.youtube.com/watch?v=iwnSGoo4XHE&t=2) yang dia beri, hasrat untuk menuliskannya pun tumbuh.
Bertepatan saat tanggal 26 Juni sebagai Hari Anti Penyiksaan Internasional. Dan sampai saat ini, panti-panti rehabilitasi psikososial masih menjadi tempat terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia, perampasan kebebasan, dan perlakuan yang tidak mannusiawi.
Oleh karenanya, penting bagi kita ikut mengkampanyekan Hari Anti Penyiksakan Internasional. Sekaligus ikut mendorong Indonesia untuk segera meratifikasi Optional Protocol Convention Against Torture (OPCAT)—instrumen hukum internasional tentang pencegahan segala bentuk penyiksaan— yang juga sedang dikawal lima lembaga yaitu Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, LPSK dan Ombudsman. Kendati kita sudah memiliki UU No 5 Tahun 98 dan juga sudah meratifikasi CEDAW. OPCAT dirasa perlu sebagai instrumen hukum internasioal yang hari ini sangat dibutuhkan oleh kita semua. []