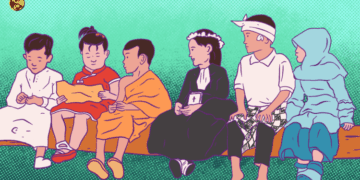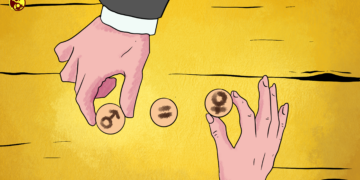Mubadalah.id – Ada pemandangan yang tidak biasa ketika beberapa pekan silam, siang itu ketika saya melintas di depan vihara Budhi Asih Jatibarang Indramayu. Banyak orang berkerumun, dan berbondong-bondong menyaksikan puluhan Bhikkhu dari berbagai negara yang tengah melakukan perjalanan Thudong dari Thailand-Borobudur (Indonesia).
Berdasarkan berita yang saya baca, perjalanan Thudong ini diikuti oleh setidaknya 30 bhikkhu yang mereka mulai pada 23 Maret 2023. Start perjalanan dari Nakhon Si Thammarat, Thailand. Perjalanan melalui rute empat negara yaitu Thailand, Malaysia, Singapura dan Indonesia. Di Indonesia sendiri akan melalui rute Batam, Jakarta, Cirebon, Semarang, Magelang dan Borobudur.
Lalu ingatan saya melintas ke momentum bedah buku “Yang Muda Merawat Bangsa”, di mana salah satu narasumbernya adalah seorang Bhikkuni Julia Surya. Sementara dalam rombongan pejalan Thudong itu, semuanya berjenis kelamin laki-laki. Saya jadi penasaran, bagaimana konsepsi relasi gender dalam agama Budha.
Budha tak Pernah Membedakan Status Sosial
Berikut saya temukan catatan dari beberapa sumber. Sebagaimana yang Ardi Yansyah tuliskan dalam artikel “Relasi Gender dalam Agama Budha”, di laman Kompas.id. Semenjak Buddha muncul di dunia dan menyebarkan Dhammanya, dia tak pernah membedakan status sosial masyarakat.
Peran perempuan dalam agama Buddha sering kali dianggap remeh bahkan sepele. Tetapi di sisi lain, perempuan juga dapat berperan besar dan memberi sumbangan kemanusiaan yang tak terkira.
Panannda susila dalam “Nasehat Sang Buddha Kepada Para Istri” mengungkapkan bahwa sang Buddha sering menggunakan istilah “matugama” yang berarti “ibu rakyat” atau “perhimpunan kaum ibu”. Hal ini menunjukkan sebagai gambaran betapa besarnya peranan perempuan. Selain itu, penghargaan yang tinggi Sang Buddha terhadap kaum perempuan.
Di Indonesia sendiri peran perempuan Buddha ditunjukkan dengan berdirinya Sangha Perempuan Indonesia. Sangha ini di bawah naungan Sangha Agung Indonesia. Tugas mereka sebagai Bhikkuni sama dengan Bhikku, mereka mengurus sendiri berdirinya vihara, cetiya, maupun pembinaan baik perempuan maupun laki-laki.
Demikian pula pentahbisan para pendeta perempuan yang membantu dalam pekerjaan untuk umat, para upasika, samaneri maupun pengelolaan Sangha perempuan.
Dalam berbagai vihara, para pendeta perempuan sebagai pembantu para bhikku dan bikhhuni memberi pembinaan kepada umat baik laki-laki maupun perempuan. Demikian pula dalam memberikan upacara perkawinan, kematian, tidak ada perbedaan dengan pendeta laki-laki, karena membutuhkan kerjasama yang sebaik-baiknya untuk umat.
Perkawinan Berasaskan Monogami
Pada tahun 70-an Sangha Agung Indonesia memberlakukan hukum waris serta membuat peraturan tata cara perkawinan yang mereka sebut hukum perkawinan. Pengesahan Peraturan ini pada 1 Januari 1977. Semua umat Buddhayana yang berlindung di bawah Sangha Agung Indonesia, mereka harapkan mentaati peraturan tersebut. Perkawinan berasaskan monogami. Harta benda dalam perkawinan adalah hak bersama.
Apabila bercerai, kelangsungan hidup dan pendidikan anak harus diperhatikan sehingga pembagiannya adalah: 1/3 untuk suami, 1/3 untuk istri, 1/3 untuk anak. Anak laki-laki atau perempuan mempunyai hak yang sama.
Wali tidak ada perbedaan laki-laki ataupun perempuan, semua dapat menjadi wali bagi anak, asal masih ada hubungan kekeluargaan. Peraturan-peraturan sesudahnya mereka atur dan dimusyawarahkan dengan Dewan Pandita yang ditunjuk Sangha, dan tidak terbatasi laki-laki ataupun perempuan.
Mengenal Prajapati Gautami
Jika kita tarik lebih mundur lagi, sebenarnya peran perempuan sudah ada sejak sang Buddha masih hidup. Ini menyiratkan bagaimana relasi gender dalam agama Budha. Salah satu tokoh yang mewarnai sejarah Buddha ialah Prajapati Gautami, ibu dari Sidarta Gautama. Ketika sang Buddha mendermakan ajarannya bahwa dunia ini ialah fana, maka Prajapati bertekad untuk mengabdikan dirinya kepada Dharma, ia memohon kepada Buddha agar bisa ditahbiskan menjadi bhikkkuni.
Lalu dia mengajak 500 perempuan untuk menghadap Sang Buddha. Tetapi Sang Buddha menolak dengan alasan bahwa tidak ada tempat buat mereka. Prajapati dan 500 orang lainnya tidak menyerah, mereka memohon kepada Buddha untuk mentahbis mereka. Sesudah diuraikan peraturan Vinaya dan semua bersedia mengikutinya.
Selesai mengucapkan, pentahbisan Gautami sebagai Bhikkuni yang pertama. Kemudian menyusul kelima ratus pengikutnya. Dengan demikian terbentuklah Sangha Bikkhuni, organisasi perempuan yang demokratis pertama di kalangan umat Buddha. Ketua terpilih dari mereka yang mahir dalam Dharma, bukan karena kedudukan atau asalnya, karena ajaran Buddha, martabat manusia ditentukan oleh perbuatannya.
Dalam Therigata, sastra Buddha kuno tercatat para Bhikkuni yang dapat menjadi teladan, dan diberi penghargaan pada 73 Their (yang sudah 10 tahun menjadi Bhikkuni). Di mana mereka berhasil mencapai titian tinggi tersebut. Pada zaman Buddha sudah banyak Bhikkuni yang mencapai tingkat tinggi dalam kesucian. Hal ini tertera dalam kitab Bhikkuni Samyutu bagian Samyutu Nikaya dan Apadana.
Bhikkuni dan Capaian Kehidupan Spiritual
Dengan terbukanya kehidupan suci untuk mencapai kehidupan spiritual yang tinggi bagi perempuan, kedudukan perempuan di masyarakat juga menjadi berubah. Perempuan tidak lagi tertindas sebagai objek pemuas keduniawian dan sekarang timbul pilihan baru dalam kehidupannya untuk mencapai kesempurnaan, sebagai perempuan terhormat.
Berdirinya perkumpulan Bhikkuni oleh Prajapati sebagai motivator, diteruskan putri Sanghamitta anak raja Asokawardana yang menyebarkan Dharma ke Srilanka pada abad ketiga sebelum masehi. Kemudian mereka teruskan ke Cina dan sekitarnya.
Kini terdapat sekitar 12.000 Bhikkuni di Korea dan 13.000 di Taiwan. Di Indonesia sejak abad kedelapan Masehi telah pula terdapat peninggalan para Bhikkuni. Menurut Prof. Moh. Yamin, Candi Sewu merupakan ashram para Bhikkuni.
Aturan untuk Para Bhikkuni
8 Garu Dhamma yang merupakan 8 aturan keras untuk para bhikkuni hasil dari perumusan kitab suci konsili buddhis pertama. Aturan ini sangat diskriminatif dan menyudutkan perempuan yang juga menempuh jalan suci. Ini dinilai menjadi salah satu alat yang mereka gunakan untuk menghancurkan Sangha Bhikkuni. Kultur patriarkis di India pada masa itu kembali merangsek masuk dalam perkembangan Buddhadharma.
Ini juga berlandaskan alibi perumpamaan ladang (sangha laki-laki) telah dimasuki wabah (sangha perempuan). Karenanya harus dibuat bendungan. Bendungan yang dimaksud itu adalah 8 Garu Dhamma. Di sini jelas perempuan mereka anggap sebagai wabah bagi ladang, dan dengan begitu peraturan ini mereka buat untuk menghancurkan Sangha bhikkuni.
Ada pula penilaian bahwa peraturan keras itu mereka buat justru untuk melindungi kaum perempuan dan institusi sangha itu sendiri. Khususnya melindungi vinaya (peraturan bagi bhikhu) mengenai berpantangan hubungan kelamin yang merupakan peraturan yang bersifat fundamental.
Ada kekhawatiran perempuan terkena dampaknya jika memasuki institusi-institusi kebiaraan. Pernyataan kekawatiran terhadap rusaknya hidup ke-sangha-an karena masuknya perempuan tersebut jelas sangat tendensius dan bersifat misoginis (benci perempuan). Memposisikan perempuan sebagai makhluk kelas kedua (second sex), dalam urusan timbulnya Hasrat seksual lelaki.
Perbedaan Mazhab
Perbedaan mazhab besar ajaran Buddha, antara Theravada dan Mahayana juga memperdebatkan posisi perempuan untuk menjalankan kehidupan suci sebagai sangha. Meskipun tidak termasuk dalam kelompok yang menggunakan kekerasan. Apa yang berkembang di aliran Theravada yang mengklaim diri sebagai aliran ortodoks fundamental itu juga memiliki kaitan dengan masalah emansipasi perempuan. Penolakan Sangha bhikkuni paling kencang dari kelompok ini.
Alasan aliran ortodok-fundamental (re:Theravada) itu adalah bahwa Sangha bhikkuni yang telah berdiri sejak masa Buddha telah terputus sejak zaman Sanghamitta, putri Raja Asoka (269-232 SM). Di mana ia yang mendirikan Sangha Bhikkuni di Srilanka pada abad ke-3 masa.
Pada masa itu, Sanghamitta dan sekelompok bhikkuni melakukan upacara pentahbisan penuh terhadap 500 calon biarawati. Orde Sangha Bhikkuni ini terus berlanjut terus di sana sampai abad ke-12, hingga kemudian terputus sama sekali. Kini mereka nyatakan bahwa tradisi menghidupkan kembali Sangha bhikkuni tersebut adalah sesuatu yang tidak mungkin.
Mengenal Tradisi Sangha Bhikkuni
Tradisi Sangha bhikkuni di Srilanka ini kemudian berlanjut dan berkembang di Tiongkok, namun tumbuh di dalam aliran Mahayana, dan terus tumbuh subur hingga dewasa ini.
Jadi, berbeda dengan aliran Theravada yang menganggap diri fundamental murni. Dalam aliran Mahayana yang lebih progresif dan liberal, perempuan mendapat kesempatan yang sama dengan laki-laki di dalam menempuh cara hidup kebhikkhuan dalam biksuni. Meski beberapa cara hidup dan peraturan kebhikkuan dalam biksuni Mahayana ini telah berbeda dari Sangha bhikkuni.
Masalah ini berlanjut sampai ke perkembangan agama Buddha di Indonesia. Lembaga Anagarini Indonesia berupaya kembali menghidupkan Sangha bhikkuni di Indonesia. Lembaga ini merupakan gerakan perempuan di lingkungan aliran Theravada. Mereka memperjuangkan terbukanya kembali Sangha bhikkuni yang menjadi sarana kehidupan suci bagi kaum perempuan.
Kesepakatan bersama aliran Buddha fundamental itu keluar setelah datangnya surat dari Sri Jayawardhhapura Kotte Sri Kalyani Samagridharma dari Srilanka tertanggal 24 agustus 2000. Surat ditujukan kepada Sangha Theravada Indonesia pada saat itu.
Surat yang bertandatangan General Secretary, Ven. Vimalaratana itu menginformasikan tidak adanya anggota dari Sangha Sabha di Srilanka yang menyelenggarakan dan mengakui pembentukan Sangha bhikkuni apa pun di Srilanka, yang jelas-jelas tidak sesuai dengan tradisi Theravada.
Sikap fundamental ini sesuatu yang terkesan diskriminatif terhadap perempuan dalam situasi sekarang. Di mana gerakan feminisme yang memperjuangkan kesetaraan gender begitu gencar. Selain itu mengkhianati semangat ajaran Buddha atau bahkan Buddha Gautama. Di mana pada masanya mempersilakan umat membuka pejalan kesucian bagi perempuan atau Sangha bhikkuni.
Mungkin atas alasan di atas itu juga, kita tidak menemukan Bhikkuni dalam rombongan pejalan Thudong. []