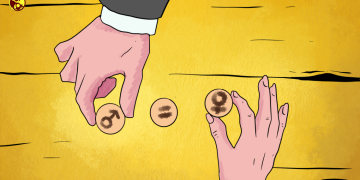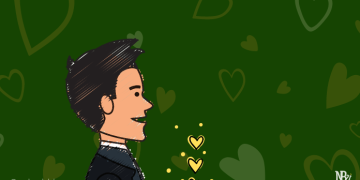Mubadalah.id – Jika kau melihat puluhan orang berkonvoi di jalanan sembari menyerukan sebuah nama partai dengan baju berwarna biru, maka itu adalah para juru kampanye dari keanggotaan partaiku. Atau jika kau menemukan gambar wajah pada beberapa baliho besar di jalanan, maka salah satu di antaranya pasti ada wajahku.
Meski masih beberapa bulan lagi sebelum akhirnya aku resmi menjadi peserta yang sudah bisa menyampaikan visi dan misiku kepada masyarakat luas, keadaan justru bukan disibukkan oleh persiapannya, melainkan hatiku, yang sejak sebulan lalu ingin pulang, ingin bertemu ibu.
Pria dewasa sepertiku, dalam pandangan orang, terlebih dengan karir bagus dalam bidang politik dan keluarga bahagia merupakan anugerah namun bagiku itu tak lain hanya sebuah titipan lantaran ada yang melangitkan doa di balik semua kesuksesanku. Meski dianggap tegas dan berwibawa, nyatanya aku adalah anak dan seorang putra yang masih meringkuk dalam belas kasih tangan ibuku.
Ingatan-ingatan Tentang Ibu
Ingatan tentang ibuku yang paling membekas adalah saat usiaku 6 tahun, ketika aku baru saja pulang dari sekolah dasar.
“Dzikri, nak, makan dulu.” Segera kulempar mobil-mobilanku ke atas kasur lantai yang membentang di depan ruang tv lalu menghambur ke ibu. Ketika tangannya memasukkan suap demi suap nasi ke mulutku, terdengar suara pintu terbuka dan tampaklah sosok bapak dari baliknya. Aku segera menghambur, memeluk bapak yang kemudian mengangkatku tinggi-tinggi.
“Sudah pulang sekolah jagoan Bapak?”
Seusai makan aku melanjutkan bermain, ditemani bapak yang tengah menonton berita di televisi. Mata bapak fokus ke layar sementara tangannya asyik bermain remot. Ketika kuperhatikan, kusadari sesuatu bahwa tangan bapakku cukup besar padahal tubuhnya kurus. Apakah lantaran bapak bekerja sebagai tukang bangunan?
“Tangan Bapak, kok, besar sekali, ya?”
Bapak hanya menengok sekilas dan tersenyum, lalu kembali melanjutkan menonton berita.
“Tangan Dzikri juga kalau sudah besar akan sama besarnya dengan tangan Bapak,” sahut ibu dari balik tirai dapur sembari membawa kopi untuk bapak.
Pertanyaan berikutnya muncul dalam benakku, mengapa tangan ibu kecil sementara tangan bapak besar. Sebuah pertanyaan sepele yang diajukan oleh seorang anak kelas 1 SD. Tapi rupanya pertanyaanku menarik bagi bapak sehingga bapak ikut menimpali,
“Meski tangan Ibu kecil, tapi tangan Ibu itu kuat.” Aku tak mengerti.
“Ya, Dzikri. Tangan Ibu kuat menggendong Dzikri, mengasuh Dzikri, memasak buat Bapak dan Dzikri, juga kuat berlama-lama mengangkat tangan untuk berdoa,” lanjut bapak.
“Benarkah?” tanyaku mencari kejelasan. Ibu tersenyum, “Benar, dong. Dzikri mau bukti? Sini panco sama Ibu!”
Merasa tertantang, aku mendekat ke arah ibu dan menyiapkan kuda-kuda pada tangan kananku untuk bersiap berpanco. Ketika akhirnya tangan kami saling mengikat, kami kerahkan masing-masing kekuatan untuk saling menggilas. Aku sangat percaya dengan kekuatanku karena tanganku hampir sama besarnya dengan tangan ibu.
Aku tertawa-tawa meski kemudian kalah beradu panco dengan ibu.
Adu Panco dan Politik
“Permainan politik seperti adu panco, mulanya sama-sama saling mengikat tapi di sana ada niat terselubung, yakni ambisi untuk menggilas yang lain!”
Salah seorang rekanku berkelakar demikian di tengah-tengah makan siang seusai rapat untuk rencana kampanye mendatang. Aku tak begitu tertarik mendengarnya terlebih membahas politik, yang padahal merupakan bagian dariku. Bahkan mungkin politik itu merupakan diriku.
Sejatinya bukanlah pilihanku untuk masuk dalam jajaran anggota dewan ini. Semuanya tak lain dan tak bukan merupakan kehendak dari mertuaku yang ingin aku melanjutkan karirnya di bidang politik. Saat itu aku memang terbilang pecundang, namun akhirnya kuiyakan juga dan kini berdirilah aku di antara orang-orang yang katanya memiliki peran dalam pergerakan dan perubahan bangsa.
Orang-orang yang katanya, merupakan wakil rakyat untuk menyambung lidah dan otak rakyat menuju perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik entah itu dalam pendidikan, ekonomi, maupun lowongan pekerjaan.
Sesekali hadir saat rapat, bayangan ibuku, yang tengah duduk di beranda sambil menjahit pakaian-pakaianku yang bolong entah itu celana di bagian depan atau kemeja di bagian ketiak. Sesekali kuperhatikan ibu saat menyapu halaman depan sehingga rumah kami menjadi padang tanpa gugur dedaunan, atau saat sedang mengepel lantai, memasak, dan menguras bak.
Kuyakini kalimat bapak, bahwa tangan ibu, meskipun kecil tapi sangat kuat. Namun aku ingin menambahi, bahwa tidak hanya tangannya, tetapi seluruh tubuh ibu itu kuat. Karena kadang pula kulihat ibu dalam keadaan tertatih, atau pun sedang sakit, tetap membantu bapak yang akan bersiap-siap untuk bekerja atau menyambutnya di kala lembur.
Perihal Ibu dan Keluargaku
“Sekarang, mah, Dzikri sudah sukses, ya?
Wajahnya muncul di media sosial. Kemarin lihat di hape Wardah, banyak orang yang mendukung Dzikri. Ibu sangat bangga,” puji ibu saat aku berkesempatan pulang ke rumah.
“Berkat doa Ibu.”
Kucium tangan ibu berkali-kali, telapak tangan hingga punggung tangannya. Tangan yang di dalamnya terkandung azimat dari diijabahnya doa. Aku tak ingin melewatkan doa keselamatan dari ibuku untuk pemilu nanti. Aku sempatkan pulang, karena aku tahu bulan-bulan berikutnya akan sangat sulit untuk menemui Ibu.
“Kenapa kau tidak meminta restu Ibumu dari telepon saja, Mas? Jauh, lho kalau kau harus pulang,” ujar istriku ketika kami baru sampai di rumah sehabis menjenguk Ibu.
“Meminta restu Ibu dengan menemuinya adalah sebuah etika, Rin,” balasku.
“Mas, kau, kan sudah ada aku. Aku kan juga sering mendoakan kamu. Apalagi kau, kan tahu kalau doa istrimu ini merupakan akar dari menjulangnya karir suami,” rajuknya.
“Sherin, dalam keadaan apapun, tunjangan doa ibu itu lebih utama,” jawabku lembut sembari menatap dan memegang pundaknya.
“Masalahnya, kalau kau harus pulang, jauh dan akan buang-buang waktu, Mas. Lagipula Ibumu juga ada yang merawat. Adikmu Wardah dan suaminya, kan ada di rumah. Aku ini hanya khawatir kalau kamu lama di rumah nanti akan ada beberapa rapat yang kau tinggal. Aku ini bosen, lho, ditanya sama Papahku terus soal kamu!”
Belum kuceritakan pada Sherin perihal ibuku yang mengidap penyakit jantung. Kudengar dari adikku bahwa belakangan ibu sudah tidak kuat lagi berdiri dan hanya terduduk lemah di kursi roda. Aku maklum jika Sherin begitu berlebihan menanggapi soal diriku yang kalau ada apa-apa harus meminta restu atau doa ibu terlebih dahulu.
Aku tak bercerita karena akan menjadi beban pikiran bagi Sherin, antara mertua yang sakit dan masa depan karirku. Terlebih sekarang putra pertama kami tengah menyiapkan ujian untuk masuk universitas ternama dan putri kedua tengah belajar mati-matian agar masuk SMA unggulan.
Doa-doa Ibu
“Sebab aku dididik oleh keduanya, yang saling bersepakat bahwa tangan ibu itu kuat. Terlebih kuat untuk berdoa. Dari situ aku yakin, bahwa semua yang aku dapat tak lebih dan tak kurang merupakan hasil dari doa ibuku, meski tak pernah kutahu apakah beliau ingin aku terjun ke politik atau tidak,” ucapku pada suatu kesempatan.
“Ya, semua orang melihat, kau seperti anak mami yang masih menetek di puting Ibumu!” balas temanku.
“Ternyata, keberhasilan karirmu bukan ditunjang mertua atau prestasimu, tapi lewat jalur langit! Hahahaaa…,” kelakar yang lain. Mengundang tawa rekan-rekan sekantor.
Aku tak menggubris karena aku tahu bahwa itu hanya gurauan belaka. Aku yakin semua orang pun sudah paham tentang tabiatku. Karena bagiku ibu adalah sejarah, terutama pada hari-hari berikutnya setelah adu panco aku menyaksikan kegigihan ibuku dalam beribadah dan berdoa.
Sering, saat berdoa kulihat ibu menggerakkan badannya ke depan dan belakang yang ternyata adalah permohonan mendalam dan permintaan dengan sangat kepada Tuhan. Dari sana, aku tekadkan diriku pula untuk rajin beribadah seperti ibu.
Kadang di kegelapan malam aku juga menyaksikan di ruang sembahyang, ibu tengah salat dengan mukenah putih terusannya. Dapat kuliah juga perut buncitnya yang saat itu tengah mengandung adikku, Wardah.
“Ibu, kenapa salat malam-malam begini?” tanyaku setelah ibu selesai berdoa.
“Ibu salat tahajud, nak,” jawabnya lembut.
“Apa itu?”
“Salat malam. Salat sunah tambahan yang dianjurkan.”
“Memangnya yang lima tidak cukup, Bu?”
“Cukup. Cukup sekali. Ibu itu lagi mengajukan sesuatu kepada Tuhan.” Ibu meraih kepalaku dan mengusapnya pelan.
“Mengajukan apa?”
“Biar besok Bapak lancar kerjanya,” pungkasnya sambil tersenyum hangat.
Kematian Bapak
Aku tak begitu mengerti dan tidak begitu tertarik jika sudah membahas pekerjaan bapak. Aku hanya tahu bahwa bapak seorang buruh bangunan, dan dalam beberapa proyek bapak sering menjadi mandornya.
Sebuah ketidakpedulian yang akhirnya aku sesali. Sebab tak pernah kusangka jika keesokan harinya, kudengar kabar bahwa bapakku meninggal dengan tiba-tiba.
“Menabrak tiang listrik, Bu,” terang seorang rekan bapak. Terbata-bata menjelaskan.
“Mulanya ada kejadian aneh,” seseorang menimpali. “Pak Hasbi berkata bahwa kepalanya pusing. Lalu sebelum menaiki motor untuk ke tempat konstruksi beliau sempat batuk dan saya lihat batuknya berdarah.”
“Innalillaaah. Mas Hasbi tidak punya riwayat penyakit, Pak…” Ibu terisak sampai tersungkur di tanah. Aku menghiba dan teriris melihatnya.
Semuanya terjadi begitu sangat cepat. Mulai dari pemakaman Bapak, kepedihan dan kesengsaraan ibu, hingga lahirnya adikku, Wardah.
Samar-samar kuingat bahwa saat itu bapak tengah menggarap proyek pembangunan sebuah masjid di wilayah yang akan menjadi taman pusat kota. Dengar-dengar, salah seorang menentang agar pembangunan masjid harus dihentikan karena akan dibangun gedung lain, namun dengan kukuh bapak tetap melanjutkannya.
“Ini wilayah strategis. Selain digunakan untuk hiburan, sekalian juga dimanfaatkan untuk beribadah. Di tengah-tengah rekreasi sebagian orang pastinya butuh salat. Ini juga yang dikehendaki kepala desa dan warga desa di sini,” jelas bapak pada seorang petugas.
“Bapak, tanah wakaf itu masih menjadi sengketa. Sebaiknya dibatalkan saja. Lagipula ini bukan hak milik bapak!” hardik orang asing tersebut.
“Tapi saya bertanggung jawab atas pembangunan ini.”
Masa-masa Kesengsaraan
Setelah kepergian bapak kusaksikan ibu pergi kesana-kemari menemui rekan bapak. Sesekali ibu menemui penanggungjawab proyek, entah untuk apa. Dalam keadaan mengandung begitu tentu aku tak tega. Sampai pada satu kesempatan aku mengajukan diri menemani ibu menemui Lurah Desa yang ikut andil dalam kesepakatan pembangunan masjid tersebut.
“Lokasinya jauh dari pemukiman warga, Bu. Tapi masih ikut wilayah pedukuhan ini,” terang Pak Lurah menjelaskan hal-ihwal proyek tersebut.
“Iya, Pak. Tapi, benarkah, suami saya…” ucapan ibu terputus. Rautnya terlihat menahan gejolak hebat di dadanya yang kemudian merambat ke wajah hingga memerah,
“Apa Bapak tahu…“ perlahan ibu mulai sesenggukan. Pak Lurah yang merasa iba menyodorkan air putih. Ibu menolak air itu dengan sopan, fokus menatap Pak Lurah,
“Apa Bapak pernah melihat kejanggalan atau merasa curiga, kalau suami saya diracun?” pungkasnya akhirnya. Membuat Pak Lurah terperanjat.
“Astaghfirullah, Bu. Jangan bicara begitu. Kita manusia tidak tahu.”
Masa-masa Ketabahan
Aku yang ikut mendengarnya dari luar pun sangat terkejut. Tapi untuk bocah ingusan sepertiku pembicaraan keduanya merupakan hal yang asing dan tidak kumengerti. Entah kemudian keduanya membicarakan apa, yang jelas lama sekali. Lurah Desa yang bijaksana dan bertanggungjawab itu seperti menenangkan dan menasihati ibu.
Tapi yang jelas setelahnya ibu tak lagi menemui rekan kerja atau orang yang terlibat proyek dengan bapak. Belakangan justru beliau lebih sering mengikuti pengajian atau berkunjung ke kiai kampung di desa kami.
Setelahnya kuperhatikan ibu berusaha melupakan kejadian itu dan menguburnya dalam-dalam. Hingga akupun ikut hanyut dalam keadaan melupakan kejadian itu. Seakan-akan semuanya tak pernah terjadi. Kematian bapakku seperti terempas angin begitu saja. Membekas dalam hati tapi tak begitu terekam jelas dalam ingatan.
Tapi, aku akan dengan sangat lantang meneriakkan bahwa bapakku seorang pemberani dan ibuku adalah sosok yang kuat. Aku tak paham kaidah bahasa perempuan kuat, tapi dalam diri ibuku aku bisa membuktikannya. Seorang ibu dengan kelembutan kasih dan doa dari tangannya, yang mengandung azimat nan makbul, bisa merawatku dan adikku seorang diri, hingga kami bisa sampai pada kehidupan sekarang.
Benang Merah Takdir
Mobil berjalan pelan membawaku ke tempat kampanye. Ketika sampai dan kuperhatikan sekilas, aku merasa mengenal tempat ini. Sebuah tanah lapang dengan plang bertuliskan ‘Pusaka Indah’.
“Ini tanah sengketa, Pak. Bapak ingat kesepakatan yang dibicarakan saat rapat kemarin, bukan? Bahwa Bapak harus memihak pembangunannya.
Selain itu Bapak harus memberi pengaruh kepada rakyat supaya mau menerapkan program pemberdayaan masyarakat dengan dibangunnya pusat perbelanjaan di taman kota, serta sebuah kafe yang nantinya akan merekrut artis-artis lokal sebagai bagian dari promosi dan menarik minat pelanggan untuk datang. Itu yang diinginkan atasan terhadap tanah ini. Akan ada keuntungan pada pemilu nanti jika proyek ini berjalan.”
Tak begitu kuperhatikan ucapan wakilku sebab aku berfokus pada beberapa paku bumi yang teronggok di ujung lahan. Beberapa batu bata telah pecah berkeping-keping mengelilinginya, juga keramik-keramik yang sebagian masih utuh, sebagian telah menjadi serpihan.
“Tunggu, sebenarnya proyek siapa ini?” tanyaku. Mas Rudi mendekat dan membisikkan jawabannya dengan pelan di telingaku,
“Ini salah satu proyek anggota residen yang akan naik pangkat jika salah satu partai presiden yang diusungnya menang, Pak. Kalau presiden yang diusung itu menang, mertua Bapak akan ikut naik pangkat juga. Jika itu terjadi, maka karir Bapak di partaipun tak jauh bedanya, akan sama-sama gemilang.”
Aku terdiam. Mencoba mencerna kalimat Mas Rudi.
“Mas Rudi, tadinya tanah ini akan digunakan untuk apa?” tanyaku tegas. Menuntut jawaban cepat.
“Sebuah masjid.”
Aku terhenyak. Seketika pikiranku menyeruak ke mana-mana. Aku merajut semua ingatan tentang kematian bapak. Mengapa semuanya tersimpul menjadi benang merah yang menyesakkan? Lalu menggulir menjadi segumpal penyesalan, mengapa dulu aku begitu tak peduli pada kematian bapak?
Dan saat itu hal yang sangat ingin kulakukan adalah segera menghubungi rumah. Meminta adikku, Wardah, untuk menanyakan pada ibu tempat bapak kecelakaan dulu.
“Wilayah Pusaka Indah, Mas,” jawab Wardah di ujung telepon.
Pulang ke Pangkuan Ibu
Tanpa ambil tempo aku segera melangkah cepat meninggalkan tempat proyekan tersebut. Menimbulkan tanda tanya di wajah Mas Rudi dan anggota lain. Mereka memanggil-manggil namaku namun tak kupedulikan dan terus berjalan menuju parkiran, berniat pulang ke rumah ibu. Soal papah mertua yang pastinya akan marah dan Sherin yang tentu panik akan kuurus nanti.
Dalam perjalanan aku meyakini satu hal, bahwa semua yang terjadi padaku pasti ada kaitannya dengan firasat ibu, yang kemudian beliau curahkan pada keheningan malam. Seketika saja air mata menetes di pipiku. Mengaburkan pandanganku saat menyetir.
“Ibu, maafkan Dzikri,” ucapku penuh dan sungguh sembari bersimpuh. Tangisan saat di mobil tadi masih berlanjut hingga tangan ibu basah oleh air mataku.
Ibu merasa heran mengapa aku menangis. Tapi beliau tak banyak bertanya dan justru mengelus kepalaku, tersenyum hangat,
“Kenapa minta maaf? Seharusnya ibu yang minta maaf, tidak bisa memberi kesempatan pada Dzikri untuk menang panco, karena tangan ibu sudah tidak lagi kuat beradu.”
Ah, ibu, sampai matipun aku rela kehilangan semuanya asalkan tidak kehilangan ibu.”
Selamat Hari Ibu. []