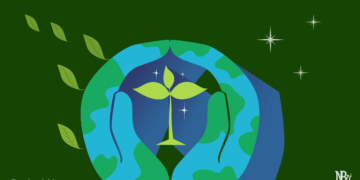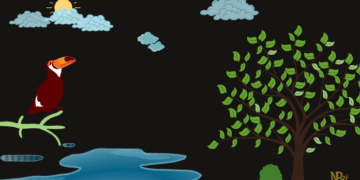Mubadalah.id – Bayangkan sebuah surga. Laut biru jernih, hutan perawan, dan gunung-gemunung yang menyentuh langit. Surga itu nyata, dan namanya Papua Barat Daya. Tapi kini, di tengah kecantikan itu, suara mesin tambang mulai menggerus ketenangan. Aroma logam berat menggantikan bau laut. Di balik janji “transisi energi bersih”, sebuah paradoks lahir. Menyelamatkan planet dengan cara menghancurkan salah satu kawasan ekologis terpenting di dunia.
Papua Barat Daya adalah rumah bagi Raja Ampat, kawasan konservasi laut kelas dunia yang menyimpan 75 persen spesies karang dunia. Tapi justru di jantung kawasan strategis ini, tiga perusahaan tambang PT Gag Nikel, PT Anugerah Surya Pratama, dan PT Mulia Raymond Perkasa mendapat izin untuk mengeksplorasi dan menambang nikel.
Luas konsesi pertambangan yang pemerintah berikan mencapai lebih dari 20.000 hektar. Sebagian di antaranya berada di kawasan hutan lindung dan konservasi. Bahkan, dua dari perusahaan itu disebut belum merampungkan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), yang sejatinya menjadi syarat mutlak untuk operasi di kawasan sensitif.
Pemerintah daerah berdalih, tambang ini untuk membuka lapangan kerja dan mengangkat kesejahteraan warga. Tapi apakah kesejahteraan bisa terbangun di atas reruntuhan hutan dan kehancuran laut? Apakah rakyat Papua ingin jadi buruh tambang di tanah Papua yang selama ini mereka jaga sebagai bagian dari identitas, spiritualitas, dan kehidupan?
Kasus Tambang Membawa Malapetaka
Yang lebih menyakitkan, suara masyarakat adat mendapat tudingan sebagai “penghambat pembangunan”. Gubernur Papua Barat Daya menyebut penolakan warga sebagai “disinformasi.” Bahkan menyebut video-video kerusakan lingkungan sebagai hoaks. Padahal, masyarakat adat Kawe dan Betew telah dengan tegas menyatakan penolakan terhadap eksploitasi wilayah mereka.
Mereka khawatir tambang akan menghancurkan laut, mengusir ikan, dan menghancurkan hutan keramat yang mereka jaga turun-temurun. Kekhawatiran yang sangat beralasan. Tak sedikit pula masyarakat adat yang menyuarakan kekhawatiran. Bahwa mereka hanya akan menerima “remah-remah” dari hasil tambang, sementara kerusakan akan mereka tanggung selama-lamanya.
Dalam banyak kasus, tambang justru membawa malapetaka. Di berbagai wilayah Indonesia dari Sulawesi hingga Kalimantan adalah bekas tambang mereka tinggalkan sebagai danau maut, hutan gundul, dan konflik sosial. Di tanah Papua, dampak sosial jauh lebih kompleks. Pembangunan tambang kerap berbarengan dengan masuknya pekerja dari luar daerah.
Ini menciptakan ketegangan demografis, kompetisi sumber daya, bahkan bisa menyulut konflik horizontal. Pengalaman pahit Freeport di Mimika yang menyebabkan pencemaran tailing di sungai-sungai dan ketimpangan sosial-ekonomi ekstrem masih membekas di ingatan publik. Masyarakat adat menjadi penonton di tanah sendiri.
Kita tidak sedang menolak industrialisasi atau transisi energi. Tapi jika transisi itu harus mengorbankan satu dari sedikit wilayah konservasi terbaik di dunia, maka itu bukan kemajuan. Melainkan kemunduran dengan kemasan futuristik.
Pengelolaan Laut Berbasis Komunitas
Tambang nikel memang kita butuhkan untuk baterai mobil listrik, tapi jika untuk membuat satu mobil listrik harus menebang satu hutan, menghancurkan satu pulau, dan mengusir satu komunitas adat, itu bukan solusi. Tapi itu adalah kejahatan atas nama teknologi.
Papua bukan halaman belakang republik. Ia adalah bagian sah dari Indonesia yang semestinya mendapat perlakuan adil. Bukan sekadar kita tambang lantas kita tinggalkan. Jika memang ingin meningkatkan kesejahteraan warga, kenapa tidak memperkuat sektor yang telah terbukti berkelanjutan dan melibatkan masyarakat, seperti ekowisata berbasis masyarakat adat?
Raja Ampat sudah membuktikan diri sebagai salah satu model sukses pengelolaan laut berbasis komunitas. Pendapatan dari sektor ini nyata, berjangka panjang, dan merata. Pada 2022, sektor pariwisata Raja Ampat menghasilkan lebih dari Rp100 miliar. Sebagian besar langsung masuk ke kantong masyarakat adat lewat sistem pengelolaan kampung wisata. Tapi mengapa justru yang terdorong adalah sektor tambang yang secara alamiah menguras sumber daya dan meninggalkan dampak permanen?
Konstitusi menjamin hak masyarakat adat atas wilayahnya. UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mensyaratkan AMDAL sebagai syarat wajib. Prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) telah menjadi standar internasional yang diakui Indonesia. Tapi semuanya bisa dilangkahi hanya karena satu hal: investasi.
Siapa Sebenarnya yang Diuntungkan?
Apakah negara begitu lemah menghadapi tekanan investor? Mengapa suara masyarakat lebih sering terpatahkan daripada terdengar? Lalu, mengapa kawasan konservasi bisa longgar hanya karena nikel dianggap “strategis”? Mengapa Pasal 37 UU Cipta Kerja, yang memperlonggar izin tambang bahkan di wilayah konservasi, bisa lolos tanpa perlawanan? Siapa sebenarnya yang diuntungkan?
Pemerintah daerah berencana membangun kawasan industri nikel terpadu di Sorong. Akan ada smelter, pelabuhan, bahkan mungkin PLTU untuk memasok energi. Tapi mari jujur: pengalaman kita dengan kawasan industri berbasis tambang tidak pernah baik. Lihat Morowali, lihat Weda Bay, lihat Konawe. Ada lapangan kerja, tapi banyak yang bukan untuk warga lokal. Ada pertumbuhan ekonomi, tapi juga kerusakan permanen. Dan, yang paling pasti: ada ketimpangan.
Lantas, apakah Raja Ampat dan pulau-pulau kecil di sekitarnya harus kita ubah menjadi pusat industri? Padahal dalam RPJMN 2020–2024, justru menetapkan kawasan ini sebagai wilayah konservasi prioritas nasional. Apakah rencana jangka panjang pembangunan hanya akan terkalahkan oleh satu-dua izin perusahaan tambang?.
Ini bukan soal romantisme alam atau nostalgia akan masa lalu. Ini soal pilihan masa depan. Di tengah krisis iklim, kerusakan lingkungan, dan krisis pangan global, menjaga kawasan seperti Raja Ampat bukanlah kemewahan, melainkan keharusan. Dunia memang membutuhkan nikel, tapi bukan dengan mengorbankan tempat seperti Papua Barat Daya. Kita masih bisa memilih cara yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada mereka yang paling terdampak.
Jangan jadikan transisi energi sebagai topeng kolonialisme baru. Jangan ulangi sejarah ketika tanah adat mereka ambil atas nama pembangunan. Kali ini, biarlah Papua menentukan nasibnya sendiri, bukan ditentukan oleh kepentingan di Jakarta, Beijing, atau New York. []