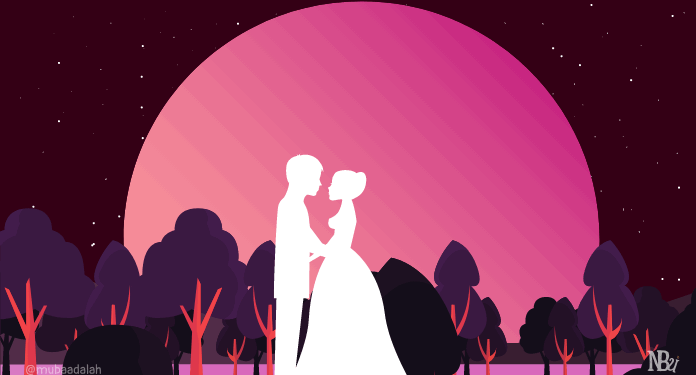Mubadalah.id – Pernikahan menjadi ibadah paling panjang yang manusia, utamanya muslim, jalankan. Berdasar alasan itu, konsep wedding dream yang mencakup tema, dekorasi, suasana, dan sebagainya ialah cita-cita para pasangan pengantin yang mesti tersiap-rancangkan dengan matang. Tiap orang memiliki standar berbeda ihwal pemilihan nomor sepatu, apalagi soal impian pernikahan sekaligus resepsinya.
Tiap mempelai berhak memilih pernikahannya terkonsep dengan: sederhana, sedang-sedang saja, atau mewah. Asalkan pilihan terbarengi kemampuan, sederhana karena memilih menabung uangnya, sedang-sedang saja menyesuaikan tabungan, atau mewah sebab siap secara materi. Yang agak gawat ialah mengonsep pernikahan mengikuti tren tetapi abai akan topangan finansialnya.
Seorang kawan takjub manakala hadir di pernikahan kawan kami yang lain. Ia enteng berseloroh, “Wah, dekorasinya mewah, ya. Ini berapa, ya, harganya? Pasti mahal. Saya bisa tidak, ya, menikah seperti ini?” Di tengah gemuruh musik penyambutan pengantin, saya menghela napas pendek dan tak ingin berpanjang-panjang menanggapinya.
Obsesi Sesaat
Di kesempatan berbeda, saya baru berani membetot kawan saya tadi soal omongannya di helatan pernikahan kawan kami tempo hari itu. Setelah menjawab panjang, ia rupanya terobsesi dekorasi dan kemewahan pernikahan kawan kami yang kemarin.
Saya pikir keinginan seseorang meniru atau mengadopsi suatu hal—apapun itu—untuk ia lakukan kelak di masa depan adalah hal lumrah. Namun, konteks ini, konsep pernikahan, bukan perkara enteng yang main-main. Saya takut kawan saya ini hanya ingin membungkam egoismenya saja semata, sementara ia tak memerhatikan finansial yang ia miliki.
Saya katakan padanya, wajar jika kawan kami yang menikah kemarin itu pernikahannya mewah dan menakjubkan, karena ia telah menyiapkan semuanya dengan matang seturut pertimbangannya. Finansial, dukungan keluarga, dan lainnya.
Sementara, kawan saya ini, takutnya hanya termakan obsesi sesaat. Tren membetot keakuannya dalam menangkap poros-poros hasad semata. Ada pertise yang ingin ia beri makan agar tak kalah dari orang lain. “Kalau dia bisa, masa saya tidak bisa?” itu mungkin egoisitas yang ia usung pada waktu itu. Dan, hal ini sukar terjadi pada seseorang yang kerap mengabsen sikap introspeksi dirinya.
Tolok Ukur Sosial
Perkara pernikahan adalah pilihan kedua mempelai dan keluarganya. Kalau merasa cukup hanya menikah di KUA kemudian merayakannya sederhana mengundang kerabat dan tetangga sekitar, maka itu tak jadi soal. Atau karena momentum sekali seumur hidup (bagi yang memang menghendaki demikian) merayakannya dengan “agak” mewah itu pun lagi-lagi tak masalah. Pernikahan dan perayaannya adalah soal persepsi dan kemampuan masing-masing.
Kita boleh saja menepi dari segala standar sosial yang mengharuskan begini-begitu jikalau itu tak sejalan dengan visi atau keluar dari wedding dream kita. Tak bisa dipungkiri juga, misalnya, banyak kasus demi merayakan pesta pernikahan sesuai standar sampai harus meminjam uang. Catatan saja, kalau itu dalam batas normal serta mempelai dan keluarga kuasa, sebagai seseorang yang tak berhak menghakimi dan mencampuri urusannya, bagi saya, sah-sah saja.
Hari-hari di penghujung Juli kemarin, saya mendapati pelbagai postingan mengenai pasangan yang menikah sederhana di KUA. Satu postingan menegaskan lewat takarir, “Menikah tak perlu mewah, yang penting sah dan bisa jadi keluarga yang berkah.” Tentu pelbagai postingan itu memiliki tujuan baik lewat normalisasi pernikahan sederhana sesuai kemampuan mempelainya.
Akan tetapi, karena informasi itu terlempar ke dinding media sosial, ia lantas mempunyai kredensi lain, yang berbanding lurus sekaligus yang bertolak-belakang. Kredensi yang bertolak, postingan ini dianggap mengglorifikasi nikah sederhana sehingga berkesimpulan seakan kesan menikah dan perayaaan mewah (tidak sederhana) adalah keliru.
Bagi mereka yang kontra atas glorfikasi “nikah sederhana” tentu memiliki alasan juga. Bahkan seorang warganet mengatakan, “Tidak usah merasa paling hemat dan paling financial planner hanya gara-gara tidak buang uang buat resepsi.” Adalah lumrah bahwa satu hal (apapun) jika ia dilemparkan ke lautan publik nyata atau maya bakal mendapat beragam reaksi. Dan itu tak bisa tersangkal daro si empunya hal itu, sebab itu di luar kuasanya.
Kesan Paradoks
Pada 2022, tatkala saya magang kuliah di sebuah balai nikah (KUA), ada semacam stereotipe negatif bagi mereka yang menikah di KUA. Selain karena memang berasal dari keluarga tak mampu, sebab menikah di KUA gratis, ialah karena salah satu mempelai mengalami kehamilan tidak diinginkan alias KTD.
Jadi masyarakat sana punya siasat, agar volume malu tak surplus, jalannya menikahkan pasangan di KUA. Biar pegawai KUA saja yang tahu, begitu yang pernah saya dengar-saksikan.
Walau bagaimanapun kita tak bisa menggenaralisir semua yang menikah di KUA adalah pasangan yang telah—mohon maaf—kebobolan lebih dulu. Ada pula mempelai yang memang berniat ingin menikah dengan sederhana.
Bagi mereka yang demikian, tidak perlu pula berkesimpulan terhadap mereka yang menikah agak atau mewah adalah sebentuk “penghamburan” uang. Justru porsi dan takaran seseorang dalam hal menentu konsep pernikahan dan perayaannya adalah wujud kemampuannya.
Tiap orang punya jalan dan cara berbeda dalam menjelmakan impian-impiannya. Dari hal kecil sampai hal besar. Pasti berbeda. Format pernikahan dan segala perayaannya tak bisa mendapat pembakuan sepihak dan labelisasi benar atau salah. Yang sederhana benar, yang mewah tidak karena menghambur-hambur.
Tidak demikian membaca persoalannya. Sebab dalam urusan ukuran sepatu saja berbeda, apalagi mimpi. Mari wujudkan pernikahan dan perayaannya sesuai batas kemampuan masing-masing. Wedding dream kamu dan saya beda, Kawan. Jangan disamakan, ya! []