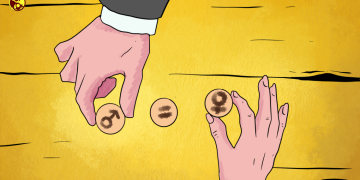Mubadalah.id – Banyaknya konflik lingkungan pengalaman perempuan menjadi testimoni bukti yang tak bisa terabaikan. Perempuan bukan hanya kelompok yang terdampak, tetapi juga menjadi aktor utama dalam menghadapi, merespons, dan merawat lingkungan hidup. Keserakahan manusia dalam menjarah alam yang semakin tidak kenal batas adalah kerja- kerja patriarki. Begitu menurut teroi ekofeminisme.
Ekofeminisme melihat bahwa relasi antara manusia dan alam selama ini terbangun di atas struktur kekuasaan yang hierarkis. Ada kesamaan atara penindasan yang tubuh perempuan alami dengan penindasan terhadap alam. Keduanya berasal dari proyek lanjutan koloniasme yang hierarkis dan brutal.
Namun, dalam kenyataan sehari-hari, perempuan justru berperan sentral dalam menjaga relasi yang langsung dengan alam. Dalam banyak aktivitas, perempuan menjadi pengelola air, penjaga benih, pelindung hutan, dan perawat keseharian ekologis.
Keterhubungan yang mendalam antara tubuh perempuan dan tubuh bumi bukan hanya simbolik, tetapi juga nyata secara kehidupan sehari- hari. Pengalaman perempuan dalam menghadapi krisis lingkungan kerap membawa dimensi yang lebih holistik dan berorientasi pada keberlanjutan hidup bersama.
Wadon Wadas
Menurut Dewi Candraningrum menyampaikan dalam buku ekofeminis bahwa proyek pembangunan skala besar sering kali mengabaikan dimensi ekologis dan sosial yang terjaga oleh perempuan. Namun, perempuan sebagai pihak yang merasakan paling kehilangan,juga menjadi garda terdepan dalam mempertahankan ruang hidup.
Seperti contoh suara perempuan Wadon Wadas menjadi pengalaman perempuan yang ruang hidupnya terampas. Penolakan mereka terhadap aktivitas pertambangan semen bukan sekadar penolakan terhadap eksploitasi tanah. Tetapi juga bentuk perlawanan terhadap model pembangunan yang memisahkan manusia dari alam.
Aksi mereka menanam kaki di semen menunjukkan bahwa tubuh mereka adalah bagian dari tanah itu sendiri. Bukan objek yang terpisah, melainkan ruh yang terikat secara mendalam dengan bumi.
Mama Aleta Baun
Hal serupa tampak dalam perjuangan Mama Aleta Baun di Mollo, Nusa Tenggara Timur. Dalam menghadapi ancaman pertambangan marmer yang merusak pegunungan sakral di wilayahnya, Mama Aleta memimpin aksi damai bersama ratusan perempuan adat. Mereka menenun di lokasi tambang sebagai bentuk protes tanpa kekerasan yang menolak perusakan tanah leluhur.
Aksi ini bukan hanya simbol perlawanan terhadap kerusakan ekologis, tetapi juga bentuk perawatan terhadap nilai-nilai kehidupan yang terjaga turun-temurun oleh perempuan Mollo. Mereka tidak hanya mempertahankan ruang hidup, tetapi juga merawat pengetahuan ekologis dan hubungan spiritual dengan alam yang selama ini menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas dan kehidupan komunitas mereka.
Ekofeminisme melihat bahwa krisis lingkungan tidak dapat terpisahkan dari bentuk-bentuk kekerasan lainnya, termasuk kekerasan berbasis gender. Ketika alam kita rusak, tubuh perempuan ikut terdampak secara langsung.
Lalu, ketika sungai tercemar atau hutan ditebang, perempuan harus menempuh jarak lebih jauh untuk mencari air atau sumber pangan. Ketika tanah dirampas, perempuan kehilangan ruang hidup yang bukan sekadar sumber ekonomi, tetapi juga identitas kultural dan spiritual. Kekerasan ekologis dan kekerasan terhadap perempuan saling terhubung dalam sistem yang menormalisasi dominasi dan eksploitasi.
Ekofeminisme; Relasi Manusia dan Alam
Tidak hanya itu perempuan juga menjadi bagian ibu bumi yang menghadirkan praktik-praktik perawatan yang menjadi alternatif dari aktifitas eksploitasi yang sangat srakah. Ekofeminisme mendorong kita untuk membayangkan ulang relasi antara manusia dan alam. Bukan relasi yang menempatkan alam sebagai objek, melainkan relasi timbal balik yang etis, berakar pada kepedulian dan keberlanjutan.
Perempuan, dengan pengalaman dan relasinya yang dekat dengan alam, menghadirkan nilai-nilai yang selama ini terpinggirkan dalam kebijakan pembangunan, nilai-nilai keberlanjutan, tanggung jawab antargenerasi, dan penghargaan terhadap kehidupan non-manusia.
Dalam konteks kebijakan publik, pendekatan ekofeminisme membuka ruang untuk memperhatikan suara perempuan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut lingkungan hidup. Model pembangunan yang mengabaikan partisipasi perempuan cenderung menghasilkan kebijakan yang timpang dan rentan menimbulkan krisis. Dengan memperkuat peran perempuan sebagai subjek ekologis, kita tidak hanya menata ulang pembangunan, tetapi juga membuka jalan menuju bentuk keadilan ekologis yang lebih menyeluruh.
Perempuan dan Bumi Saling Terkait
Melalui ekofeminisme, kita diajak untuk melihat kembali siapa yang menjaga kehidupan sehari-hari dan siapa yang sering kali terabaikan dalam wacana besar pembangunan.
Pengalaman perempuan dalam menjaga tanah, air, dan udara bukan romantisasi peran tradisional, melainkan bentuk pengetahuan dan praktik hidup yang relevan dalam menghadapi krisis iklim dan sosial hari ini. Dalam tubuh perempuan dan tubuh bumi yang saling terkait, tersimpan potensi besar untuk membangun dunia yang lebih adil dan berkelanjutan.
Berupaya memanfaatkan potensi perempuan untuk memicu revolusi ekologis bukan karena perempuan lebih dekat dengan alam secara kodrati, tetapi karena pengalaman hidup mereka kerap menempatkan mereka di garis depan dari dampak krisis lingkungan.
Dari pengetahuan lokal yang diwariskan turun-temurun hingga aksi kolektif mempertahankan ruang hidup, perempuan menawarkan perspektif yang berakar pada keberlanjutan, kepedulian, dan keadilan. Dalam dunia yang dikuasai logika eksploitasi dan dominasi, ekofeminisme menghadirkan kemungkinan perubahan yang lahir dari kerja-kerja perawatan, solidaritas, dan keberanian melawan sistem yang melukai baik tubuh perempuan maupun bumi ini. []