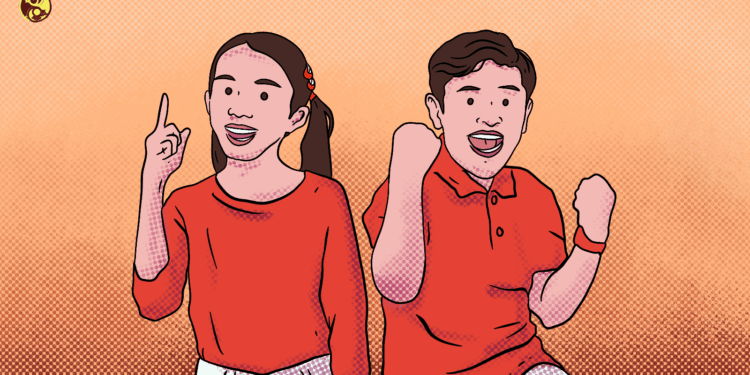Mubadalah.id – Dalam banyak keluarga, sejak bayi membuka mata, identitas gender sudah terkunci dengan dua warna. Biru untuk anak laki-laki, merah muda untuk perempuan. Mainan, pakaian, bahkan cara memanggil pun teratur sedemikian rupa agar sesuai dengan konstruksi “yang seharusnya”. Anak laki-laki kita ajari untuk kuat dan tegas, anak perempuan kita ajari untuk lembut dan patuh.
Namun, apakah dunia memang sesederhana itu?
Dalam kerangka mubadalah, relasi antara laki-laki dan perempuan tidak bisa kita bangun di atas dikotomi yang kaku. Jika kita ingin membangun masyarakat yang adil dan setara, maka harus mulai dengan mendidik anak-anak dengan kesadaran gender yang membebaskan—bukan mengekang.
Gender adalah Konstruksi, Bukan Takdir
Seringkali kita lupa bahwa banyak hal yang kita anggap sebagai “kodrat” perempuan atau laki-laki, sebenarnya hanyalah konstruksi sosial. Tidak ada yang secara biologis mengatakan bahwa perempuan lebih cocok memasak, atau laki-laki harus memimpin. Itu semua adalah warisan budaya yang bisa—dan harus—kita kaji ulang.
Anak laki-laki yang menangis bukanlah lemah. Anak perempuan yang berani bukanlah “tomboy”. Justru, ketika kita membiarkan anak mengekspresikan diri tanpa takut dilabeli, kita sedang memberi ruang untuk mereka tumbuh menjadi manusia yang utuh.
Bahasa: Alat Kecil yang Berdampak Besar
Kita sering tak sadar, bahasa adalah alat kekerasan paling halus dalam membentuk persepsi gender. Ungkapan seperti “jangan kayak cewek dong!” atau “kamu perempuan, masa mau kerja kasar?” Menyisipkan pesan bahwa feminitas adalah kelemahan dan maskulinitas adalah keunggulan.
Di sinilah pentingnya kesadaran orang tua, guru, dan masyarakat. Mengubah cara kita berbicara kepada anak adalah langkah awal untuk menciptakan ruang aman bagi mereka tumbuh tanpa merasa harus “menjadi sesuatu” demi diterima.
Peran Agama: Membangun atau Membelenggu?
Agama seringkali menjadi legitimasi untuk membenarkan ketimpangan gender. Padahal, Islam yang rahmatan lil ‘alamin tidak pernah menghendaki ketidakadilan. Dalam banyak riwayat, Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang sangat sadar gender. Beliau memuji kepemimpinan perempuan, membantu pekerjaan rumah, dan menghormati perbedaan.
Dalam kerangka tafsir mubadalah, setiap teks agama yang tampak bias gender harus kita baca ulang dengan mempertimbangkan konteks, tujuan keadilan, dan kesalingan relasi. Maka, mendidik anak laki-laki untuk menghormati perempuan bukan hanya ajaran etika, tapi juga bagian dari spiritualitas.
Mendidik Anak Laki-laki: Bebaskan dari Tekanan Maskulinitas
Seringkali pembicaraan tentang gender hanya berfokus pada pembelaan terhadap perempuan. Padahal, anak laki-laki juga menjadi korban dari sistem patriarki yang menekan. Mereka terlarang untuk menangis, dituntut untuk sukses, tidak boleh lemah, dan harus “jantan”.
Padahal, jantan bukan berarti keras. Tangguh tidak berarti menekan perasaan. Kita harus memberi ruang bagi anak laki-laki untuk menjadi lembut tanpa rasa malu, untuk peduli tanpa kita anggap lemah, dan untuk menjadi manusia—bukan mesin performa.
Mendidik Anak Perempuan: Lebih dari Sekadar Menjaga Diri
Sementara itu anak perempuan sering terbebani beban moral yang jauh lebih berat. Harus menjaga tubuh, menjaga nama baik, menjaga harga diri keluarga. Mereka penting kita ajarkan bahwa anak perempuan juga boleh bermimpi tinggi, bicara lantang, dan menuntut perlakuan setara.
Kesucian perempuan bukan satu-satunya ukuran nilai mereka. Mereka punya hak untuk belajar, memimpin, dan menentukan arah hidup. Peran kita sebagai pendidik adalah memastikan bahwa anak perempuan tidak tumbuh dengan rasa takut, tapi dengan rasa percaya diri dan harga diri.
Menjadi Orang Tua yang Sadar Gender
Orang tua bukan sekadar penyedia makan dan pakaian, tapi arsitek pertama dari cara anak melihat dunia. Jika kita ingin dunia yang lebih adil gender, kita harus mulai dari rumah: dari cara kita bersikap, berbicara, dan mencontohkan relasi setara.
Mendidik dengan kesadaran gender bukan berarti menghapus perbedaan, tapi menghargai keberagaman. Bukan menciptakan anak yang “netral”, tapi anak yang berani menjadi dirinya sendiri—tanpa takut kita kotak-kotakkan.
Dan bukankah itu inti dari keadilan? []