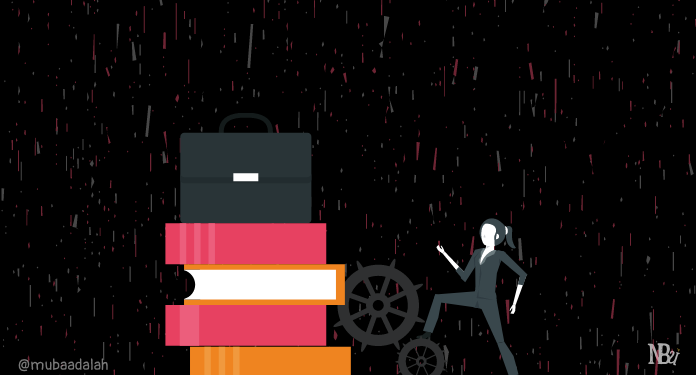“Buku memang untuk melawan, tapi bukan berarti sebagai alasan untuk menjerat seseorang.”
Mubadalah.id – Belakangan ini kasus penyitaan buku oleh aparat kepolisian kembali dilakukan mulai dari kasus Dalpedro (seorang aktivis, pengacara dan peneliti) yang menjadi tersangka terduga melakukan penghasutan terkait aksi demonstrasi Agustus kemarin.
Kemudian, polisi menyita 11 buku dari massa aksi demonstrasi yang berujung ricuh di Surabaya dan Sidoarjo. Hingga yang terbaru, Polisi telah menangkap seorang pelajar SMA di Kediri yang juga seorang penulis karena terduga terlibat dalam kerusuhan. Polisi tidak hanya menangkap mereka tapi juga menjadikan buku-buku mereka sebagai barang bukti.
Beberapa buku tersebut polisi hubungkan dengan peristiwa kerusuhan saat demo berlangsung pada Agustus lalu termasuk di berbagai wilayah salah satunya di Jawa Timur. Buku buku yang menjadi barang bukti antara lain: Anarkisme karya Emma Goldman, Kisah Para Diktator karya Jules Archer, Karl Marx karya Franz Magnis, Apa Itu Anarkisme Komunisme karya Alexander Berkman, dan ada juga buku karya Pramoedya Ananta Toer.
Buku yang menjadi simbol ilmu pengetahuan, kebebasan berpikir serta alat untuk membebaskan, memerdekakan dan pintu menuju peradaban. Tapi, buku kini dijadikan alat untuk menjerat seseorang. Hal ini tak hanya mengkriminalisasi individu melainkan memperlihatkan wajah negara yang takut pada pengetahuan.
Sejarah Singkat Buku dan Represi
Penyitaan dan pelarangan buku bukan merupakan hal baru di Indonesia, melainkan sudah terjadi sejak masa penjajahan, orde lama serta orde baru. Pada masa penjajahan masa kolonial, Belanda melarang bacaan yang mereka anggap membangkitkan semangat perlawanan.
Kemudian pada masa orde lama, pemerintah justru melakukan sensor terhadap buku dengan alasan mencegah masuknya paham-paham asing yang bisa mengganggu jalannya revolusi Indonesia yang baru saja merdeka. Sementara, pada masa orde baru era Soeharto, pelarangan buku beserta dengan pemusnahan seluruh karya penulis bahkan penangkapan beberapa penulis.
Berdasarkan fakta sejarah, berbagai buku terlarang terbit tidak saja hanya karena isinya, tetapi sudut pandang politis penulis atau penerbit buku dan pengaruhnya terhadap pembaca. Buku-buku yang terlarang tersebut berbau komunisme, pemikiran kiri, hingga kritik terhadap rezim. Dalih yang terpakai adanya pelarangan buku ialah untuk menjaga stabilitas negara.
Pasca reformasi, masyarakat mulai leluasa untuk mengakses bacaan yang dulu tersembunyi. Buku-buku Pramoedya Ananta Toer yang sempat terlarang kemudian cetak ulang. Buku berbau kiri pun bisa lebih mudah kita temukan. Namun pada kenyatannya, represi belum benar-benar hilang. Aparat masih melakukan razia serta penyitaan buku. Buku bertema Papua, sejarah 1965, atau Marxisme kerap tersita dengan alasan membahayakan NKRI.
Dengan begitu, bisa kita simpulkan kalau buku seringkali terposisikan sebagai ancaman terhadap negara. Selain itu anggapan terjadi potensi menanamkan ideologi berbahaya, bukan sebagai sumber ilmu pengetahuan. Dari kolonial hingga reformasi polanya sama membungkam pengetahuan ialah cara yang tepat untuk menjaga stabilitas.
Bukti sebagai Barang Bukti: Logika yang dipertanyakan
Ketika negara menjadikan buku sebagai bukti menjerat seseorang, sebenarnya kita berhadapan dengan logika yang problematis. Buku yang kita percaya sebagai medium pengetahuan, gagasan, mendorong terbukanya ruang diskusi, serta menciptakan imajinasi, bukanlah suatu hal yang jahat. Bukan pula sebagai alat kejahatan fisik seperti senjata. Menyita buku menandakan kalau membaca di negeri ini serupa dengan melakukan kekerasan.
Penggunaan buku secara hukum sebagai barang bukti biasanya berkaitan dengan adanya penghasutan serta penyebaran kebencian. Yang menjadi kebingungan kita, aparat dalam menentukan buku dianggap berbahaya tersebut bagaimana sih? Tidak ada kriteria yang benar-benar jelas. Jangan-jangan karena isi dalam suatu buku yang tak sesuai dengan pandangan penguasa sehingga buku dianggap sebuah ancaman?
Terlepas dari itu semua, ini sebuah ironi. Buku yang seharusnya jadi jembatan kita memahami kompleksitas realitas justru menjadi bukti kejahatan. Sebuah buku mau se-kontroversialpun, buku adalah representasi dari sebuah gagasan bukan tindakan.
Tak ada kaitannya buku dengan tindakan seseorang melakukan kekerasan. Memenjarakan seseorang hanya karena ia baca buku anarkisme misalnya, tentu sangat lucu sekali. Bukan berarti seseorang baca buku anarkisme akan menjadi anarkis. Sama seperti baca buku detektif nggak akan membuat seseorang tersebut menjadi seorang detektif.
Penyitaan buku ini menunjukkan adanya kontradiksi, negara yang seharusnya mendorong budaya literasi justru menempatkan buku seolah musuh. Alih-alih membangun masyarakat yang kritis lewat literasi, negara malah memidanakan seseorang dengan buku sebagai barang bukti yang justru melanggengkan kebodohan serta ketakutan akan pengetahuan.
Dampak Penyitaan Buku Terhadap Literasi
Penyitaan buku akan menimbulkan efek domino terhadap masyarakat luas. Ada tiga lapis dampak yang dapat kita rasakan, di antaranya:
Pertama, rasa takut di kalangan pembaca. Penyitaan buku akan menciptakan ketakutan. Masyarakat akan ragu untuk membeli, membaca, atau bahkan menyebutkan judul-judul buku tertentu.
Jika aktivitas membaca yang tadinya jadi kegiatan untuk menghilangkan penat, menumbuhkan rasa ingin tahu, serta menciptakan ruang diskusi malah membahayakan dan berujung dikriminalisasi. Akhirnya yang terjadi adalah menurunnya budaya literasi, masyarakat tak lagi dapat menunjukkan kebebasan berekspresi, masyarakat sulit berpikir kritis dan mudah terprovokasi.
Kedua, penyempitan ruang intelektual. Pemidanaan seseorang karena buku ini menyebabkan Buku sebagai sumber rujukan penting bagi peneliti, mahasiswa, aktivis serta jurnalis, ya mereka akan kehilangan referensi untuk membangun argumen. Dan jika buku sejarah dan politik yang tidak sesuai dengan penguasa dicap sebagai ancaman, akan menyempitkan ruang diskusi dengan pembahasan yang serupa.
Ketiga, ketakutan di ekosistem penerbitan. Industri perbukuan, mulai dari penerbit, penulis, hingga toko buku turut terkena imbas. Siapa yang berani menerbitkan karya kritis kalau sewaktu-waktu bisa diburu serta tersita aparat?
Penerbit tentu akan memilih karya yang aman, penulis mengurungkan diri untuk menulis karya yang kritis dan toko buku menghindari stok bacaan yang akan memicu masalah. Pada akhirnya, ekosistem literasi kehilangan keberanian untuk menampilkan berbagai macam gagasan.
Ketika buku menjadi barang bukti pemidanaan berarti menandakan bahwa denyut literasi juga terpaksa berhenti, dan ketika negara takut akan pengetahuan, itu telah membuktikan kalau sebenarnya ia sedang menghancurkan masa depan bangsanya sendiri. []