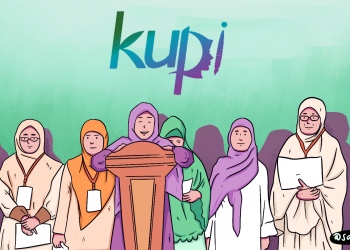Mubadalah.id – Kemarin, di sebuah desa di Lombok Timur, berlangsung sebuah pernikahan anak. Pihak KUA sebenarnya sudah menolak untuk terlibat. Mereka bahkan memberikan penjelasan agar pernikahan bisa ditunda, mulai dari soal dampak, hak, hingga kewajiban yang belum siap ditanggung oleh anak-anak.
Namun, pernikahan itu tetap dilaksanakan. Yang menjadi petugas justru tokoh agama setempat yang bersedia memimpin jalannya akad. Pertanyaannya kemudian, “Mengapa masih ada tokoh agama yang mau terlibat, padahal mereka memiliki posisi moral untuk menolak?”
Alasan Keterlibatan Sebagian Tokoh Agama dalam Pernikahan Anak
Keterlibatan sebagian tokoh agama dalam kasus pernikahan anak tentu tidak lahir begitu saja. Ada sejumlah alasan yang membuat mereka masih mau terlibat, baik karena dorongan keyakinan, tekanan sosial, maupun cara pandang budaya yang sudah mengakar.
Adanya kesalahan logika “lebih baik menikah daripada zina” hingga kini menjadikan pernikahan anak sebagai pilihan yang paling aman meskipun usia mereka belum matang.
Selain itu, sebagai bagian dari masyarakat, tokoh agama tidak bisa lepas dari tradisi. Saat sebuah keluarga besar sudah bulat memutuskan untuk menikahkan anak, tokoh agama biasanya diminta hadir sebagai saksi atau petugas.
Menolak bisa dianggap menentang keputusan keluarga, bahkan terkadang bisa menimbulkan konflik sosial. Dan ketika menerima, seringkali mereka memandang tugasnya sebatas memastikan syarat dan rukun nikah terpenuhi. Pertimbangan soal kesiapan usia, hak anak, atau dampak jangka panjang seringkali tidak masuk dalam cara pandang ini.
Ada sebuah alasan yang terdengar cukup ekstrem, namun nyata di lapangan. Meskipun aturan perkawinan di Indonesia sudah jelas mengatur tentang usia minimal 19 tahun dan adanya perlindungan anak, tidak semua tokoh agama familiar dengan aturan ini. Masih ada yang menomorduakan hukum Negara dibanding hukum agama.
Dalam situasi seperti ini, ada tokoh agama yang merasa posisinya bisa tergeser jika menolak menikahkan anak. Keluarga mempelai bisa mencari tokoh agama lain yang bersedia. Daripada dianggap tidak kooperatif atau kehilangan pengaruh, sebagian tokoh agama akhirnya memilih untuk tetap terlibat dalam pernikahan anak.
Tidak Semua, Tapi yang Sedikit Itu Berpengaruh Besar
Tentu saja, tidak semua tokoh agama bersikap permisif terhadap pernikahan anak. Banyak di antara mereka justru menjadi garda depan dalam menolak praktik ini. Mereka turut memberikan edukasi ke masyarakat, menolak menikahkan pasangan di bawah umur, bahkan aktif mendorong kesadaran hukum di tingkat desa.
Namun, kelompok kecil yang masih terlibat tetap penting untuk dibicarakan. Sebab, dalam konteks sosial seperti di Lombok Timur, suara tokoh agama memiliki bobot moral dan sosial yang sangat besar. Sekalipun jumlahnya sedikit, dukungan mereka terhadap pernikahan anak bisa memperkuat legitimasi sosial terhadap praktik ini.
Dalam arti lain, satu restu tokoh agama sering kali cukup untuk meniadakan keberatan dari pihak lain.
Ketika Tokoh Agama Menolak; Agama Itu Menyelamatkan, Bukan Sekadar Mengesahkan
Masih di wilayah Lombok Timur, ada kisah menarik tentang seorang tokoh agama yang memilih untuk tidak terlibat menikahkan pasangan muda yang belum cukup umur.
Dengan sikap tenang, ia menolak permintaan keluarga itu. Alasannya sederhana namun tegas. Ia tidak ingin melanggar aturan dan prinsip perlindungan anak. Ia menjelaskan bahwa menikahkan anak bukanlah solusi, melainkan awal dari beban baru yang belum tentu siap mereka pikul.
Penolakan tersebut sempat menimbulkan kekecewaan. Namun sikap sang tokoh meninggalkan pesan penting bahwa tugas tokoh agama bukan sekadar mengesahkan akad, tetapi juga memastikan keadilan dan keselamatan bagi mereka yang dinikahkan.
Sikap tegas semacam ini menunjukkan bahwa tokoh agama bisa menjadi penggerak perubahan sosial. Ketika mereka menggunakan otoritas moralnya untuk melindungi anak, pesan itu bergema lebih kuat daripada seribu ceramah.
Dalam masyarakat yang masih memegang erat tradisi, keberanian tokoh agama untuk berkata “tidak” justru menjadi teladan baru tentang bagaimana agama seharusnya hadir untuk menyelamatkan, bukan sekadar mengesahkan.
Refleksi; Ketika Suara Tokoh Agama Bisa Merubah Norma
Fenomena pernikahan anak yang terjadi sebagaimana di Lombok menunjukkan bahwa suara tokoh agama masih sangat berpengaruh. Ketika sebagian tokoh agama memilih untuk hadir dan menikahkan pasangan di bawah umur, masyarakat menganggap hal itu sah—baik secara agama maupun sosial.
Padahal, keputusan tersebut seringkali justru memperkuat budaya lama yang merugikan anak-anak, terutama anak perempuan.
Jika sebagian tokoh agama berani berkata “tidak” pada pernikahan anak, maka pesan moral yang lahir pun akan berbeda. Masyarakat akan belajar bahwa menolak bukan berarti melawan agama, tetapi justru bentuk tanggung jawab untuk menjaga martabat dan keselamatan anak.
Dari keberanian kecil itulah, norma baru bisa tumbuh—bahwa melindungi anak juga bagian dari ibadah dan dakwah.
Sebuah Harapan Kecil
Tulisan ini bukan untuk menuduh atau menghakimi, melainkan sebagai ruang refleksi bagi kita semua, terutama bagi tokoh agama yang punya pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat. Di tengah maraknya pernikahan anak, suara mereka bisa menjadi penentu arah, apakah masyarakat akan terus membenarkan praktik lama, atau mulai bergerak menuju perlindungan anak yang lebih manusiawi.
Harapannya, semakin banyak tokoh agama yang melihat bahwa tugas mereka bukan hanya mengesahkan pernikahan, tetapi juga menjaga nilai kemanusiaan. Sebab pada akhirnya, melindungi anak berarti menjaga masa depan umat itu sendiri. []