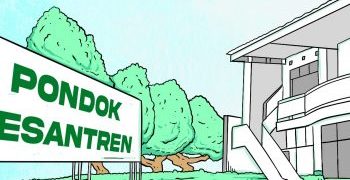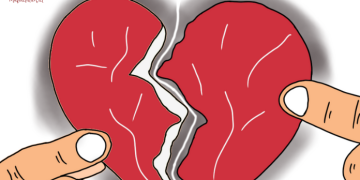Mubadalah.id – Krisis iklim menjadi salah satu topik yang diperbincangkan dalam isu-isu lingkungan, yang menyinggung sejauhmana keadilan, kekuasaan dan kemanusiaan berpihak. Dekade terakhir menunjukkan bahwa perempuan sebagai kelompok rentan terdampak perubahan iklim.
Ia berhadapan dengan persoalan keterbatasan akses terhadap sumber daya alam, meningkatnya beban sosial akibat bencana ekologis serta rendahnya representasi perempuan dalam pengambilan keputusan. Ekofemimisme hadir sebagai pendekatan kritis yang menyoroti keterkaitan antara eksploitasi alam dan subordinasi terhadap perempuan.
Jika kita tarik dalam diskursus global, perspektif ini menghadirkan ruang transformasi diplomasi iklim. Yakni diplomasi yang membawa misi keadilan, empati, dan orientasi terhadap keberlanjutan kehidupan.
Ekofeminisme dan Diplomasi Iklim: Kerangka Etis
Kemunculan ekofeminisme, hadir dari suatu kesadaran struktur patriarki dan kapitalisme eksploitasi yang memarginalkan perempuan sekaligus merusak alam semesta—sebagai “ibu” kehidupan. Sejumlah tokoh ekofeminisme, seperti Carol J. Adams, Vandana Shiva dan Maria Mies, secara umum menjelaskan bahwa cermin dari cara patriarki memperlakukan tubuh perempuan sebagai alat produksi. Bukan subjek yang mempunyai hak.
Diplomasi iklim sebagai paradigma menentang dominasi pendekatan teknokratis dan ekonomi semata, namun abai terhadap keberlangsungan dalam merawat alam semesta. Diplomasi iklim perspektif ekofeminisme mendorong negosiasi internasional agar tidak hanya fokus pada angka emisi atau investasi hijau, melainkan berpijak terhadap kerangka etik.
Misalnya, keadilan ekologis, kesetaraan gender, dan hak masyarakat adat atas tanah dan air. Prinsip ini tercermin dalam upaya negara berkembang, termasuk Indonesia dalam memperjuangkan “climate justice” di forum-forum global, seperti Conference of the Parties (COP) di bawah Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC).
Keterlibatan Indonesia dalam Struktur Global
Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, mempunyai posisi strategis dalam melaksanakan agenda diplomasi iklim. Satu sisi, Indonesia sebagai negara salah satu penghasil emisi karbon terbesar akibat deforestasi dan penggunaan lahan. Di sisi lain, Indonesia sebagai paru-paru dunia yang menyimpan 10% hutan tropis global dan 17% keanekaragaman hayati dalam planet ini.
Indonesia terlibat aktif dalam forum internasional, seperti United Nations Environment Assembly (UNEA), G20 Working Group on Energy Transition and Environment, serta COP UNFCCC. Terakhir pada agenda COP28 di Dubai, Uni Emirat Arab, tahun 2023. Sejumlah pertemuan internasional, Indonesia menegaskan komitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89% dengan upaya sendiri, dan hingga 43,20% dengan dukungan internasional pada 2030.
Pendekatan diplomasi Indonesia, kemudian perlahan bergerak untuk memperhatikan aspek sosial dan gender. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mendorong Gender Action Plan on Climate Change, memastikan keterlibatan perempuan dalam perencanaan mitigasi dan adaptasi. Langkah ini selaras dengan semangat ekofeminisme yang menempatkan perempuan sebagai penjaga pengetahuan ekologis dan agen perubahan di tingkat komunitas.
Di forum G20 Environment and Climate Sustainability Working Group, Indonesia memperjuangkan konsep “blue economy” dan “circular economy” yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya laut berkelanjutan. Hal ini penting karena lebih dari 60% penduduk Indonesia tinggal di wilayah pesisir yang rentan terhadap kenaikan permukaan air laut.
Hal ini yang menjadikan diplomasi ekofeminis menjadi relevan, tak hanya menyoal negosiasi target emisi, melainkan melindungi kehidupan komunitas perempuan pesisir, petani, dan masyarakat adat menjadi garda terdepan dalam ketahanan ekologi. Khususnya merawat alam dan keberlangsungan produktivitas pangan.
Batasan Planet dalam Sistem Pendukung Kehidupan
Sejumlah literatur ilmiah juga membahas mengenai sejauhmana keberlanjutan kehidupan di bumi ditentukan oleh apa yang disebut planetary boundaries atau batasan planet. Konsep yang diperkenalkan oleh Johan Rockström dan timnya di Stockholm Resilience Centre (2009), mengidentifikasi sembilan batas ekologis utama yang menopang kestabilan sistem bumi yang tangguh.
Jika batas-batas terlampaui, maka keseimbangan biosfer akan terganggu dan berpotensi menyebabkan keruntuhan ekosistem global. Beberapa batas utama yang melampaui ambang aman, di antaranya: perubahan iklim, integritas biosfer (kehilangan keanekaragaman hayati dan kepunahan spesies), beban aerosol atmosfer, penipisan ozon stratosfer, pengasaman laut, perubahan sistem lahan, aliran biogeokimia (siklus nitrogen dan fosfor), penggunaan air tawar global, danm pelepasan entitas baru (polusi kimia).
Sehingga kehancuran menjadi salah satu batas yang memicu efek domino pada sistem lainnya. Misalnya, deforestasi tidak hanya mengurangi keanekaragaman hayati, melainkan juga mempercepat perubahan iklim dan mengganggu siklus air. Dalam konteks ini, ekofeminisme hadir mengingatkan bahwa bumi memiliki daya dukung terbatas, seperti halnya tubuh manusia yang tidak bisa terus menerus tereksploitasi tanpa menanggung konsekuensi etis dan ekologis.
Ketahanan Pangan dan Krisis Ekologis
Salah satunya, implikasi langsung dari pelampauan batas planet adalah ancaman terhadap ketahanan pangan global. Perubahan pola curah hujan, kekeringan ekstrem, dan banjir yang sering menyebabkan gagal panen di berbagai wilayah. Di Indonesia, fenomena El Niño dan La Niña mengganggu produktivitas pertanian, sementara kenaikan suhu laut mempengaruhi hasil tangkapan ikan nelayan.
Perempuan hadir memainkan peran penting dalam merawat rantai ketahanan pangan, baik sebagai petani, nelayan, maupun pengelola pangan rumah tangga. Namun, perempuan sering kali tidak memiliki akses terhadap lahan, modal, dan teknologi adaptif. Di sinilah pendekatan ekofeminis menjadi solusi strategis dalam memperkuat posisi perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam, menghargai pengetahuan lokal tentang pertanian berkelanjutan, serta menempatkan nilai kepedulian (care) sebagai dasar ekonomi pangan.
Dalam diplomasi iklim, isu ketahanan pangan harus dibicarakan bukan hanya dalam konteks produksi, melainkan distribusi dan keadilan akses. Indonesia dalam G20 Agricultural Working Group menekankan pentingnya sistem pangan berkelanjutan yang memperhatikan kesejahteraan petani kecil, menjadi gagasan yang selaras dengan semangat ekofeminis yang menolak dominasi korporasi agribisnis atas kehidupan masyarakat.
Keterpurukan Ekologis: Melampaui Batas Eksploitasi Alam
Eksploitasi alam secara berlebihan merupakan akar dari keterpurukan ekologis yang dihadapi saat ini. Logika pertumbuhan ekonomi tanpa batas telah mengubah hutan menjadi perkebunan, sungai menjadi saluran limbah, dan laut menjadi tempat pembuangan plastik. Di balik semua ini, terdapat narasi dominan bahwa alam merupakan sumber daya, bukan relasi kehidupan.
Ekofeminisme menawarkan kritik fundamental terhadap paradigma tersebut. Ekofeminis memandang bahwa hubungan manusia dengan alam seharusnya bersifat timbal balik dan penuh empati, bukan hubungan dominasi.
Perempuan di pedesaan Indonesia, seperti petani organik di Bali, pengelola mangrove di Sulawesi, atau penjaga benih lokal di Jawa Tengah merupakan perwujudan bentuk resistensi terhadap eksploitasi alam melalui praktik keberlanjutan yang berbasis komunitas. Mereka adalah diplomat ekologis berangkat dari akar rumput.
Sayangnya, proyek ekstraktif seperti tambang nikel dan energi fosil masih mendominasi arah pembangunan nasional. Sehingga terkesan paradoks: satu sisi Indonesia aktif bicara diplomasi iklim, di sisi lain kebijakan domestiknya masih berpihak pada kepentingan kapital, yang terakumulasi oleh segelintir kelompok saja.
Sebagai penjembatan kesenjangan, kita memerlukan transformasi etika politik luar negeri, dari eco-diplomacy berbasis ekonomi menuju eco-solidarity yang berpihak pada kehidupan.
Bergerak Kearah Diplomasi Ekofeminisme Indonesia
Gagasan Diplomasi Ekofeminisme dapat kita munculkan dengan mengandung tiga prinsip utama. Pertama, pengakuan atas keterhubungan antara manusia dan alam sebagai satu kesatuan etis. Kedua, keadilan gender dalam kebijakan iklim. Ketiga, solidaritas lintas negara dan komunitas dalam hadapi krisis global.
Indonesia dapat mengadopsi prinsip dengan memperkuat diplomasi berbasis keadilan ekologis dan pemberdayaan perempuan. Melalui program Indonesia’s Forest and Climate Alliance, dapat terintegrasikan dengan inisiatif Women for Climate untuk menciptakan diplomasi yang inklusif.
Selain itu, Indonesia menjadi pelopor dalam memperjuangkan “Ekonomi Perawatan Alam” (Care Economy for Nature) di forum seperti COP dan G20—yakni ekonomi yang menempatkan keberlanjutan ekologis sebagai wujud kepedulian global.
Pentingnya keterlibatan masyarakat sipil, organisasi perempuan, dan komunitas lokal perlu kita perluas dalam proses negosiasi kebijakan iklim. Sehingga diplomasi tidak lagi dimonopoli oleh elit politik, melainkan ruang bersama untuk membangun narasi solidaritas alternatif yang menekankan diplomasi menumbuhkan kehidupan. Bukan melindungi kepentingan ekonomi yang terakumulasi kapital untuk segelintir kehidupan yang abai terhadap keberlangsungan kelestarian alam.
Sehingga ekofeminisme hadir membuka cara pandang bahwa pentingnya menyelamatkan bumi juga menyelamatkan kemanusiaan. Ekofeminisme memberikan perhatian untuk mengakhiri relasi kekuasaan yang menindas—baik terhadap perempuan maupun alam. Diplomasi iklim sebagai langkah untuk membuka peluang bagi Indonesia untuk menjadi jembatan moral dan ekologis antara negara-negara Utara maupun Selatan.
Dengan demikian, berpijak pada prinsip keadilan, empati, dan keberlanjutan, maka diplomasi Indonesia melangkah menuju arah baru. Tidak hanya bicara kepentingan nasional atas nama negara, melainkan atas nama kehidupan alam semesta beserta isinya. Pada akhirnya, bumi bukanlah milik generasi sekarang, melainkan amanah dari masa depan yang menuntut kita untuk berlaku dan bertindak dengan cinta, kesadaran, dan tanggung jawab bersama. []