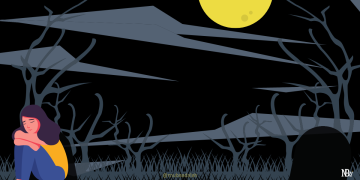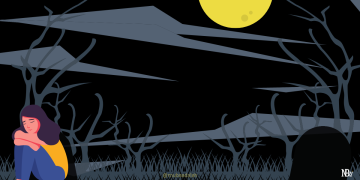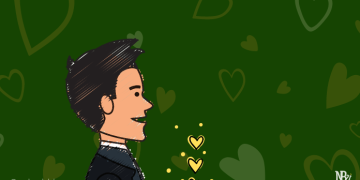Mubadalah.id – Pesantren bukan hanya lembaga pendidikan keagamaan, tetapi juga ruang sosial dan kultural yang membentuk identitas moral umat Islam di Indonesia. Dalam tradisi pesantren, hubungan antara kiai dan santri tidak sekadar berdasar pada struktur otoritas keilmuan, melainkan juga pada ikatan afektif yang dalam.
Kiai kita pandang bukan hanya sebagai guru (mu’allim), tetapi juga sebagai figur spiritual, pembimbing moral, dan simbol keteladanan hidup. Sementara santri bukan hanya murid, melainkan penerus nilai, penjaga tradisi, dan bagian dari komunitas yang hidup dalam kesadaran kolektif.
Dalam konteks inilah, muncul konsep collective pride—kebanggaan kolektif yang tumbuh dari rasa memiliki terhadap pesantren dan kiai—serta moral solidarity, yaitu kesatuan emosional dan etis yang mengikat seluruh warga pesantren dalam satu tubuh sosial.
Ketika seorang kiai disakiti atau martabat pesantren ternodai, santri ikut merasakan luka yang sama. Fenomena ini menunjukkan bahwa pesantren membangun etos afektif yang tidak hanya berakar pada intelektualitas keagamaan, tetapi juga pada empati, cinta, dan rasa tanggung jawab moral bersama.
Relasi Afektif dan Konstruksi Identitas Santri
Relasi afektif di pesantren merupakan basis pembentukan identitas moral santri. Afeksi di sini tidak hanya berarti kasih sayang dalam ranah emosional, tetapi sebuah sistem nilai yang melahirkan kesetiaan, rasa hormat, dan kepatuhan yang mendalam terhadap kiai.
Dalam kehidupan pesantren, penghormatan terhadap kiai menjadi bentuk nyata dari ta’dhim—manifestasi etika Islam yang memuliakan ilmu dan sumbernya. Santri belajar bahwa ilmu tidak dapat terpisahkan dari adab; bahwa memahami ajaran agama bukan hanya soal menguasai teks, tetapi juga meneladani perilaku guru yang mengajarkannya.
Relasi ini bersifat timbal balik. Kiai tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai figur paternal yang memelihara, menasihati, dan bahkan melindungi santrinya. Dalam interaksi sehari-hari, kiai sering menempatkan diri sebagai murabbi—pendidik yang menumbuhkan nilai-nilai spiritual sekaligus emosional. Dengan demikian, hubungan kiai dan santri terbentuk dalam kerangka afeksi yang berkelanjutan, di mana setiap tindakan, ucapan, dan ekspresi saling terhubung dalam kesadaran moral kolektif.
Dalam studi sosiologi agama, relasi seperti ini dapat kita pahami melalui konsep gemeinschaft (komunitas emosional) sebagaimana penjelasan Ferdinand Tönnies. Pesantren adalah contoh konkret dari komunitas yang hidup berdasarkan rasa kebersamaan, solidaritas moral, dan ikatan emosional yang bersifat batiniah.
Santri tidak hanya “hidup bersama” kiai, tetapi “hidup dalam” nilai-nilai yang kiai ajarkan. Maka, ketika seorang santri menyimpang dari etika pesantren atau melukai wibawa kiai, itu tidak hanya kita anggap sebagai kesalahan individu, melainkan juga pelanggaran terhadap tatanan afektif dan spiritual komunitas.
Collective Pride: Kebanggaan sebagai Energi Sosial
Kebanggaan kolektif santri—collective pride—merupakan aspek penting yang menjaga keberlanjutan nilai dan identitas pesantren. Rasa bangga menjadi santri tidak hanya berakar pada status sosial, melainkan pada kesadaran historis dan spiritual bahwa mereka bagian dari warisan keilmuan Islam Nusantara.
Identitas santri terbentuk melalui keterlibatan dalam tradisi: mengaji kitab kuning, berkhidmah kepada kiai, dan menjalani kehidupan sederhana yang sarat nilai kesabaran serta keikhlasan. Semua itu melahirkan kebanggaan moral yang terinternalisasi, bukan kesombongan simbolik.
Collective pride juga berfungsi sebagai energi sosial. Ia menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap nama baik pesantren dan kehormatan kiai. Ketika isu fitnah menyerang pesantren dan figur kiai, santri sering merespons dengan rasa sakit kolektif—karena mereka merasa bagian dari tubuh yang sama. Inilah bentuk moral solidarity, solidaritas yang berakar pada cinta dan kebersamaan spiritual.
Dalam kerangka teori Émile Durkheim, solidaritas moral tersebut dapat kita pahami sebagai bentuk mechanical solidarity, di mana kesamaan keyakinan dan nilai menghasilkan rasa kesatuan sosial yang kuat. Di pesantren, kesamaan orientasi hidup, cara berpikir, dan nilai keagamaan menumbuhkan kesadaran moral bersama. Kiai menjadi simbol nilai ideal, sementara santri menjadi representasi penerusnya. Ketika satu pihak terluka, seluruh sistem nilai ikut terguncang.
Namun demikian, kebanggaan kolektif juga dapat mengalami distorsi apabila tidak kita iringi dengan refleksi kritis. Dalam beberapa kasus, santri bisa terjebak dalam fanatisme yang menutup ruang dialog dan kritik. Oleh karena itu, penting bagi pesantren untuk terus menumbuhkan kebanggaan yang sehat. Yakni yang berakar pada ilmu, adab, dan cinta kepada kebenaran, bukan sekadar pada simbol atau loyalitas emosional semata.
Moral Solidarity: Cinta, Empati, dan Rasa Bersalah Kolektif
Solidaritas moral di pesantren tidak hanya tampak dalam bentuk kebersamaan ritual dan disiplin sosial, tetapi juga dalam dimensi afektif yang halus—yakni empati dan rasa bersalah kolektif. Ketika seorang santri melanggar norma atau membuat kiai tersakiti, muncul perasaan bersalah yang terasa bukan hanya oleh pelaku, tetapi juga oleh komunitas sekitarnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa moralitas pesantren terbangun atas kesadaran relasional. Seseorang dianggap baik bukan karena patuh secara individu, melainkan karena mampu menjaga harmoni kolektif.
Rasa bersalah kolektif ini memiliki fungsi etis yang mendalam. Ia menjaga keseimbangan antara otoritas kiai dan kebebasan santri, antara ketundukan dan tanggung jawab pribadi. Ketika kiai disakiti, santri merasa bagian dari luka itu—bukan karena keterpaksaan, tetapi karena ikatan spiritual yang telah menyatukan hati mereka. Itulah bentuk tertinggi dari moralitas afektif. Kesadaran bahwa menyakiti satu bagian komunitas berarti mengoyak seluruh jalinan cinta yang menopang kehidupan pesantren.
Lebih jauh, solidaritas moral di pesantren juga menjadi model pendidikan etika yang kontekstual. Ia mengajarkan bahwa pengetahuan harus diiringi dengan kasih sayang. Bahwa otoritas harus dijalankan dengan kebijaksanaan; dan bahwa kepatuhan sejati tidak mungkin lahir tanpa cinta. Pesantren, dalam hal ini, bukan hanya lembaga transfer ilmu, melainkan juga school of empathy. Tempat di mana afeksi, moralitas, dan spiritualitas kita pelajari dalam keseharian.
Pesantren sebagai Ruang Etika Afektif
Relasi afektif di pesantren menegaskan bahwa pendidikan moral tidak dapat terpisahkan dari pengalaman emosional dan spiritual. Collective pride dan moral solidarity santri mencerminkan bahwa pesantren bukan sekadar tempat belajar agama, tetapi ruang pembentukan jiwa dan identitas kolektif. Melukai hati kiai, dalam perspektif ini, bukan hanya tindakan personal, tetapi juga bentuk perpecahan dalam jaringan moral komunitas.
Dengan demikian, keberlanjutan pesantren bergantung pada kemampuan menjaga keseimbangan antara cinta dan kritik, antara loyalitas dan refleksi. Santri yang sejati tidak hanya bangga terhadap pesantrennya, tetapi juga mampu merawat nilai-nilai kemanusiaan dan keikhlasan yang kiai ajarkan. Sebab pada akhirnya, pesantren hidup bukan hanya karena kitab yang terbaca, tetapi karena hati yang saling terhubung dalam cinta dan solidaritas moral. []