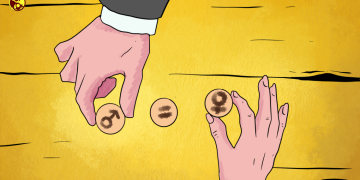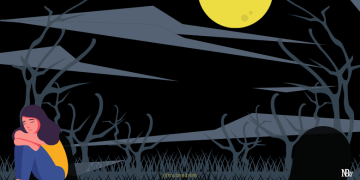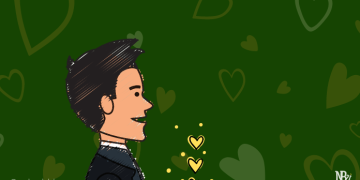Mubadalah.id – Di berbagai ruang wacana global, feminisme dalam Islam sering kali menampilkan dua arus besar yang tampak berseberangan: yang satu radikal dan menggugat secara frontal. Sementara yang lainnya lebih lembut tetapi mengakar secara teologis.
Jika kita telusuri lebih dalam, keduanya tidak sedang berhadap hadapan. Keduanya sedang menelusuri jalan yang berbeda, meliuk menemukan langkah metodisnya, dan menuju tujuan yang sama: keadilan, kesetaraan dan kemanusiaan.
Dalam konteks ini, Mona Eltahawy dan Leila Ahmed layak menjadi representasi dari dua poros penting tersebut. Di mana dalam bahasa saya sendiri akan lebih mudah menyebutnya sebagai kubu feminisme kritis dan kubu kesadaran keagamaan. Penyebutan “kubu” ini tidak berdasar kepentingan mana yang lebih baik dari satunya. Atau mana yang seharusnya lebih kita bela.
Mengapa harus Mona Eltahawy dan Leila Ahmed? Karena meski “debat” keduanya sudah berlangsung lebih dari satu dekade, saat program Melissa Harris Perry Show di channel MSNBC pada 28 April 2012, adalah tayangan ini menjadi pemantik mata kuliah di kelas Feminisme and Islam yang digawangi Prof. Sahin Achigoz. Di mana saya saat ini mengikuti kelasnya dalam program Short Course di UCR (University Of California Riverside).
Mona Eltahawy dan Feminisme Kritis: Revolusi Kesadaran
Mona Eltahawy terkenal sebagai jurnalis aktivis feminis Mesir yang lantang menyerukan “revolusi kesadaran” di dunia Arab. Menurutnya, kebebasan politik tidak akan berarti tanpa pembebasan tubuh dan pikiran perempuan dari dominasi misogini. Ia menulis dengan nada amarah: “The revolution can never be complete without a revolution in the mind without smashing the misogyny that is the real Mubarak lurking in our minds.”
Eltahawy melihat akar penindasan terhadap perempuan bukan sekadar kesalahpahaman budaya, tetapi struktur patriarkal yang terinstitusikan melalui hukum, tafsir agama, dan tradisi sosial. Ia memberi contoh bagaimana hukum di beberapa negara Arab justru melindungi pelaku kekerasan domestik. Ini bukan lagi sekadar isu moral, tetapi kegagalan sistemik. Eltahawy tidak berbicara dari menara gading. Ia berbicara dari luka dan pengalaman. Ia “berteriak” setelah kedua tangannya sempat patah akibat kekerasan polisi Mesir.
Menghadapi kritik bahwa narasinya berpotensi memperkuat stereotipe Islamofobia, Eltahawy menegaskan: “Mengakui misogini bukanlah bentuk pengkhianatan terhadap agama atau bangsa; itu adalah tindak kejujuran.” Ia menolak dikotomi antara menjadi “Muslimah baik” atau “feminis sekuler.” Baginya identitas paling mendasar adalah menjadi manusia Merdeka.
Leila Ahmed dan Kesadaran Keagamaan: Memahami Luka dari Dalam
Berbeda dengan Eltahawy, Leila Ahmed mengambil jalan reflektif penuh kehati hatian. Profesor di Harvard Divinity School ini tidak menolak kritik terhadap patriarki, tetapi menolak menjadikan Islam sebagai kambing hitam dari seluruh bentuk penindasan perempuan.
Islam sebagai ajaran spiritual justru membawa semangat kesetaraan, sementara yang menindas adalah tafsir patriarkal yang lahir dari konteks sosial dan politik tertentu. Ia mengingatkan bahwa dunia Arab bukanlah entitas tunggal. Banyak praktik yang ia anggap “Islami” berasal dari tradisi pra Islam atau budaya lokal, seperti mutilasi genital perempuan di sebagian wilayah Afrika.
Ia lebih memilih menafsir ulang teks dan sejarah Islam dari dalam. Bukan dengan amarah tetapi dengan kesabaran dan pengetahuan. Ia menolak generalisasi bahwa Islam secara inheren misoginis, karena dalam sejarahnya ia temukan banyak perempuan sufi, ilmuwan, dan pemimpin yang memainkan peran sentral peradaban Islam.
Menyatukan Dua Poros: Menuju Feminisme Sufistik
Sekilas, Eltahawy dan Ahmed tampak berada di kutub berseberangan. Padahal yang sebenarnya, Eltahawy berjuang membongkar sistem patriarki dari luar benteng. Ahmed berusaha menyembuhkan luka patriarki dari dalam ruang agama itu sendiri. Ahmed meyakini bahwa kesetaraan perempuan dapat kita temukan dalam inti spiritual Islam, bukan dari luar atau berlawanan dengannya.
Keduanya sedang menapaki jalan pembebasan, dengan bahasa dan ritme berbeda. Dalam horizon sufistik, keduanya adalah dua sisi dari satu gerak ruhani: Eltahawy sebagai jihad al nafs (melawan tiran dalam diri dan struktur), sedangkan Ahmed manifestasi tazkiyah al nafs (penyadaran spiritual). Jika kita simbolkan, yang pertama sebagai pelaku feminis dan kedua pelaku sufisme.
Feminisme sufistik meniscayakan menyatukan keduanya. Memahami bahwa perjuangan melawan patriarki dan kapitalisme tidak semata perjuangan sosial, tetapi juga perjuangan spiritual. Patriarki dalam bahasa sufistik bukan hanya sistem penindasan di luar diri, melainkan juga “nafs ammarah” dorongan dominatif kesadaran manusia yang haus kuasa dan mengobjektifikasi yang lain.
Feminisme sufistik menawarkan penggabungkan daya kritik sekaligus kelembutan spiritual, yang menggugat dengan cinta dan membebaskan dengan kesadaran. Keduanya sedang bersama sama menegaskan pesan Ibn Arabi: Tidak ada kebebasan sejati tanpa penyadaran diri, dan penyadaran tidak akan pernah lahir tanpa keberanian untuk melihat Tuhan dalam wajah yang tertindas.
Salah satu wajah tertindas adalah perempuan yang selama berabad abad terkurung oleh tafsir dan kuasa laki laki, dan sekarang menghadapi bentuk kuasa lainnya yaitu kapitalisme.
Penutup: Dari Kritik ke Kesadaran
Dialog antara Mona Eltahawy dan Leila Ahmed memberi pelajaran, bahwa feminisme Islam bukanlah monolit, melainkan mozaik pemikiran yang terus hidup dan bergerak. Feminisme kritis membuka luka agar dunia melihat ketidakadilan. Feminisme spiritual menyembuhkan luka itu agar manusia kembali utuh.
Keduanya melahirkan horizon baru; feminisme sufistik, yang tidak hanya menuntut keadilan sosial, tetapi juga menumbuhkan kesadaran ruhani. Ia memanggil perempuan (dan laki-laki) untuk keluar dari jerat dominasi. Bukan dengan membenci, melainkan dengan memahami. Sebab dalam pemahaman sejati, cinta dan kebebasan tidak lagi berseberangan, melainkan saling melengkapi.
Inilah revolusi yang sesungguhnya, bukan hanya menggulingkan sistem patriarki di luar diri, tetapi juga menaklukkan patriarki yang bersembunyi di dalam kesadaran kita sendiri.
Allah telah menyitir isyarat itu dalam kalam-nya: Dan demi jiwa serta penyempurnaan (ciptaan) nya, lalu Dia mengilhamkan kepadanya (jalan) kejahatan dan ketakwaannya, sungguh beruntung orang yang menyucikannya (jiwa itu), dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. (QS. Asy-Syams: 7-10). []