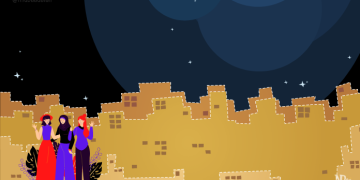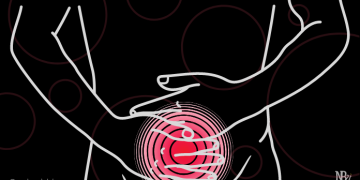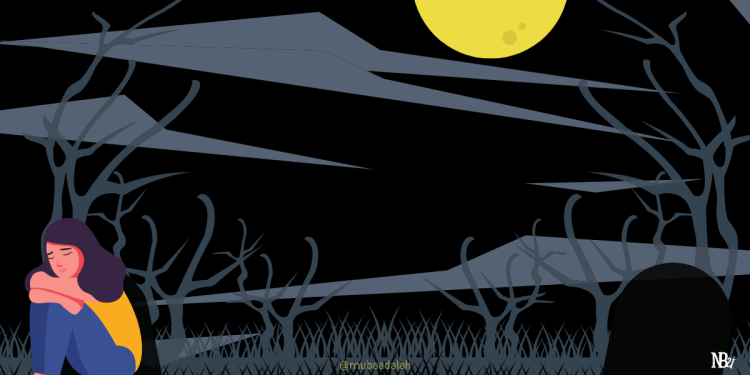Mubadalah.id – Eksotisasi kemiskinan dalam media visual bukan sekadar persoalan estetika, tetapi merupakan praktik kultural yang mengubah realitas sosial menjadi komoditas hiburan.
Dalam konteks film pangku, perempuan yang berasal dari desa atau kawasan slum kerap tergambarkan bukan sebagai individu yang memiliki kompleksitas pengalaman, melainkan sebagai figur romantik yang terbentuk melalui stereotip kemiskinan.
Narasi semacam ini tidak hanya menempatkan perempuan miskin sebagai objek visual, tetapi juga mereduksi pengalaman hidup mereka menjadi cerita sentimental yang jauh dari kenyataan sosial yang sebenarnya.
Untuk memahami bagaimana eksotisasi bekerja, penting untuk menelaah bagaimana film memproduksi gambaran kemiskinan. Bagaimana gambaran tersebut membentuk persepsi penonton terhadap perempuan dari kelas sosial rendah.
Eksotisasi kemiskinan pada perempuan slum dalam film pangku beroperasi melalui penyederhanaan karakter, latar sosial, dan konflik hidup mereka. Film sering kali menampilkan perempuan miskin sebagai sosok polos, naif, dan kurang berpendidikan. Sehingga menciptakan kesan bahwa mereka merupakan figur yang “alami” dan “murni”.
Konstruksi ini memperkuat ide romantik bahwa perempuan dari kelas bawah memiliki daya tarik tersendiri karena kesederhanaan mereka. Padahal representasi tersebut merupakan bentuk objektifikasi yang memanfaatkan kerentanan sosial sebagai komoditas visual.
Eksotisasi Kemiskinan dan Romantisasi Perempuan Slum
Dalam kerangka ini, kemiskinan tidak kita perlakukan sebagai problem sistemik, melainkan sebagai elemen dramatis yang membuat karakter tampak menarik atau patut kita kasihani. Perempuan slum sering tergambarkan sebagai pribadi yang tidak memiliki kuasa atas hidupnya, menunggu terselamatkan oleh tokoh laki-laki yang lebih mapan.
Pola ini mengukuhkan narasi patriarkis bahwa perempuan miskin selalu berada dalam posisi yang membutuhkan perlindungan dan bimbingan pihak yang lebih kuat. Akibatnya, penonton terbawa untuk melihat kemiskinan sebagai sesuatu yang eksotis. Bukan sebagai kondisi yang berkaitan dengan ketidaksetaraan ekonomi, keterbatasan akses pendidikan, atau diskriminasi gender.
Romantisasi tersebut sering kali hadir secara halus melalui dialog, pilihan kostum, hingga bagaimana kamera memperlakukan tokoh perempuan. Kekurangan yang mereka alami bukan tergambarkan sebagai tekanan sosial, melainkan sebagai “pesona tragis” yang membuat karakter lebih menarik secara emosional maupun estetis.
Model representasi seperti ini membuat perempuan slum terjebak dalam stereotip. Perempuan desa tergambarkan lembut, penurut, emosional, dan selalu siap menerima takdir buruknya tanpa perlawanan. Padahal, dalam kenyataannya, banyak perempuan dari kelas bawah menunjukkan ketangguhan, kerja keras, dan strategi bertahan hidup yang kompleks. Hal-hal yang jarang terangkat dalam Film Pangku.
Lebih jauh lagi, eksotisasi kemiskinan turut beroperasi melalui pemilihan konflik yang bersifat personal, bukan struktural. Alih-alih memperlihatkan perjuangan perempuan menghadapi sistem sosial yang tidak adil, film ini justru menitikberatkan pada plot cinta melodramatis atau kisah penderitaan yang terlalu diglorifikasi.
Kemiskinan terpotong menjadi fragmen emosional yang mudah dikonsumsi penonton, menghilangkan konteks luas tentang bagaimana ketimpangan gender dan kelas bekerja dalam kehidupan nyata.
Visualisasi Tubuh dan Ruang: Estetika yang Memperkuat Stereotip
Eksotisasi perempuan slum dalam film pangku tidak hanya muncul dalam narasi, tetapi juga dalam konstruksi visual. Kamera sering kali menyorot tubuh perempuan secara berlebihan, memusatkan perhatian pada aspek sensual. Bahkan ketika konteks cerita tidak menuntutnya.
Tubuh perempuan miskin menjadi objek yang dapat dikonsumsi secara visual, sehingga kemiskinan menjadi latar estetis yang berfungsi memperkuat daya tarik karakter tersebut.
Ruang tempat mereka tinggal, rumah reyot, pasar becek, lorong sempit, atau dapur sederhana, sering kali tergambarkan dengan cara yang menonjolkan keterpurukan. Tetapi, alih-alih mendorong pemirsa memahami kerasnya kehidupan, ruang tersebut berfungsi sebagai ornamen dramatis. Kemiskinan menjadi set yang “fotogenik” dan eksotis, bukan kondisi sosial yang menuntut refleksi.
Pendekatan visual ini menempatkan perempuan dalam posisi yang rentan. Mereka direpresentasikan sebagai subjek yang selalu terpapar tatapan kamera. Sementara ruang yang sempit dan kumuh menciptakan ilusi bahwa mereka “terlahir untuk menderita.” Sebuah narasi yang memperkuat stereotip lama tentang perempuan desa. Pasrah, patuh, tidak terdidik, dan selalu berada dalam pergumulan emosional.
Lebih jauh lagi, Film Pangku sering membangun dinamika kontras antara tokoh laki-laki dari kelas sosial lebih tinggi dengan perempuan yang hidup dalam kondisi miskin. Latar yang serba sederhana seakan mempertebal kesan bahwa tokoh perempuan adalah sosok tulus dan “alami.” Hingga kemudian menjadi alasan naratif bagi si laki-laki untuk merasa sebagai penyelamat. Visualisasi seperti ini pada akhirnya menormalisasi relasi kuasa yang timpang dan menempatkan perempuan sebagai bagian pasif dalam alur cerita.
Dampak Kultural: Normalisasi Ketimpangan dan Pengaburan Akar Masalah
Eksotisasi kemiskinan dalam Film Pangku tidak hanya berdampak pada bagaimana penonton memandang perempuan slum di layar, tetapi juga memengaruhi persepsi sosial yang lebih luas.
Ketika perempuan dari desa atau kawasan miskin terus-menerus tergambarkan sebagai sosok yang tidak berdaya, emosional, dan tergantung pada laki-laki, stereotip tersebut dapat terbawa ke kehidupan nyata. Masyarakat mungkin menginternalisasi narasi bahwa perempuan desa “memang begitu”, tanpa memahami kompleksitas hidup mereka yang sebenarnya.
Film-film yang mengeksotisasi kemiskinan juga berisiko mengaburkan akar struktural yang melahirkan ketimpangan. Dengan menjadikan kemiskinan sebagai komoditas yang menarik untuk kita nikmati, narasi film mengalihkan perhatian dari masalah mendasar. Seperti akses pendidikan yang rendah, eksploitasi tenaga kerja, minimnya perlindungan sosial, dan ketidakadilan gender. Akibatnya, penonton diajak untuk menikmati keharuan atau sensasi visual. Bukan untuk mengkritisi struktur sosial yang melanggengkan kemiskinan.
Dalam jangka panjang, representasi seperti ini dapat mempengaruhi bagaimana publik mendukung kebijakan sosial. Jika perempuan miskin terus terlihat sebagai objek yang pasif dan tidak memiliki aspirasi, maka urgensi pemberdayaan dan pendidikan dianggap kurang penting. Padahal, perempuan desa memiliki kapasitas, kreativitas, dan kekuatan yang sering tak terlihat karena media memilih menekankan sisi tragis hidup mereka.
Oleh karena itu, kita memerlukan pendekatan sinema yang lebih etis, yang berfokus pada pemberdayaan dan penggambaran karakter secara multidimensi.
Representasi perempuan slum tidak seharusnya terproduksi untuk kita konsumsi sebagai eksotika, melainkan sebagai realitas yang memerlukan pemahaman dan solidaritas. Film ini dapat menjadi medium edukatif sekaligus reflektif jika bersedia menempatkan perempuan sebagai subjek penuh, bukan sekadar simbol dramatis.
Eksotisasi kemiskinan dalam film pangku memperlihatkan bagaimana representasi perempuan slum sering kali terbentuk oleh hasrat untuk mengkomodifikasi penderitaan dan tubuh mereka. Visualisasi ini menormalkan ketimpangan gender dan kelas sekaligus mengaburkan akar masalah sosial.
Dengan mengkritisi cara film membingkai perempuan desa, kita dapat mendorong sinema yang lebih adil. Yakni menghadirkan perempuan bukan sebagai figur eksotis, melainkan sebagai aktor dengan agensi, martabat, dan kisah hidup yang layak kita hormati. []