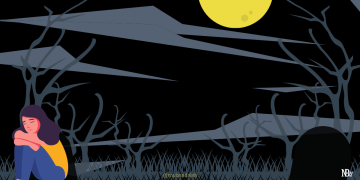Mubadalah.id – Di Desa Cikalahang, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, buah sukun melimpah ruah. Pohonnya menjulang tinggi, buahnya bergelantungan di dahan, siap dipanen. Namun, ironisnya, banyak sukun dibiarkan jatuh dan membusuk. Harganya murah jika dijual mentah, tak sebanding dengan manfaat yang ada di dalamnya.
Kisah ini menjadi perhatian kami, sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam SUPI (Sarjana Ulama Perempuan Indonesia). Di tengah libur semester, kami memutuskan untuk melakukan riset aksi di Desa Cikalahang, menggali potensi sumber daya alam yang belum dimanfaatkan secara optimal.
Di desa Cikalahang kami terbagi menjadi lima blok, dan blok 3 menjadi fokus penelitian kami. Di sana, masyarakat hidup dengan beragam profesi ada yang menjadi petani, buruh tambang, pekerja pabrik batu, hingga pekerja serabutan.
Bahkan di tengah kesibukan itu, pepohonan sukun tumbuh subur, seolah menjadi bagian dari ciri khas Blok 3 yang jarang dibicarakan.
Saat menelusuri blok 3, pemandangan sukun yang bergelantungan di dahan pohon langsung mencuri perhatian kami. Tidak hanya satu dua pohon, tapi ada sekitar 32 pohon sukun yang tersebar di blok 3 ini. Setiap musim panen, satu pohon bisa menghasilkan hingga 2 kuintal buah.
Namun, yang menjadi perhatian kami bukanlah jumlahnya, melainkan kenyataan bahwa banyak buah sukun dibiarkan jatuh dan membusuk. Bahkan ketika dijual, harganya sangat rendah, hanya Rp3.000–5.000 per kilogram.
“Kalau ada yang ngepul ya dijual, kalau nggak ya sudah, biarin,” ujar salah satu warga ketika kami wawancarai.
Padahal, jika diolah menjadi berbagai produk seperti keripik sukun, stik sukun, bolu sukun, dan lainnya, pasti lebih menguntungkan dibanding menjual mentah.
Dari 20 responden yang kami temui, hanya dua orang yang pernah mencoba mengolah sukun menjadi keripik, itupun untuk konsumsi pribadi. Sisanya memilih jalur cepat: panen, jual mentah, selesai.
Riset Aksi: Menyatu dengan Masyarakat, Menggali Potensi
Pada 23 Juli, kami memulai riset aksi langsung di Blok 3. Kami tinggal di tengah masyarakat (living), agar lebih memudahkan proses riset dan berbaur dengan warga. Kami mulai mendata siapa saja warga yang punya pohon sukun, berapa banyak pohon sukun di blok 3, hingga bagaimana pemanfaatannya.
Setelah melakukan wawancara, akhirnya kami bertemu dengan Ibu Rodiah, salah satu warga yang mengolah buah sukun menjadi keripik sukun. Kami mulai mengikuti aktivitas mengolah sukun bersama Ibu Rodiah, atau yang biasa kami sapa Mi Iyoh.
Melalui interaksi ini, kami mempelajari proses pemilihan buah, teknik pemotongan, hingga penggorengan dengan metode yang umum dilakukan masyarakat.
Dari proses inilah muncul ide, kenapa tidak mencoba membuat produk baru yang belum ada di Cikalahang? Jika keripik sukun sudah dibuat turun-temurun, maka stik sukun bisa menjadi alternatif baru yang lebih modern dan dekat dengan selera anak muda.
Stik Sukun “Mi Iyoh”: Inovasi dari Dapur Desa
Dari situ, kami mulai bekerja sama dengan Mi Iyoh untuk membuat stik sukun. Kami pun mulai merancang sebuah prototype yang kami beri nama Stik Sukun “Mi Iyoh”, kami ambil dari sapaan akrab Ibu Rodiah.
Proses pembuatan stik sukun tidaklah rumit. Kami mulai dari mengunduh sukun, membersihkan kulitnya, memotong, menggoreng, hingga mengemas. Untuk 2 kg sukun mentah, kami bisa menghasilkan 1,5 kg stik sukun dalam waktu sekitar 4 jam.
Kami mencoba membawa produk ini ke warung-warung sekitar, ke tetangga desa, dan melakukan survei kecil-kecilan di media sosial. Hasilnya mengejutkan, banyak yang penasaran, bahkan tertarik membeli.
Melihat respons positif dari warga dan beberapa konsumen awal, kami semakin yakin bahwa stik sukun bukan sekadar percobaan, tetapi dapat menjadi model usaha kecil yang relevan untuk masyarakat Blok 3.
Apalagi, selama riset berlangsung, kami menemukan bahwa buah sukun sebenarnya memiliki potensi ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan persepsi warga selama ini.
Ketika kami menunjukkan perbandingan nilai jual sukun mentah Rp 3.000–5.000/kg versus stik sukun yang bisa mencapai Rp 60.000–70.000/kg, beberapa warga mulai menunjukkan perubahan cara pandang. Mereka mulai bertanya tentang bagaimana proses pembuatannya, dan bagaimana supaya produk bisa konsisten.
Hal yang menarik adalah, perubahan semacam itu justru tidak muncul dari diskusi formal, tapi dari interaksi sederhana di dapur Mi Iyoh. Sambil menggoreng sukun, atau menunggu minyak panas, pembicaraan tentang peluang ekonomi mengalir begitu saja.
Bagiku, momen-momen kecil seperti itu yang justru paling penting dalam riset aksi, karena di situlah pengetahuan baru terasa dekat dan mungkin untuk dilakukan.
Tantangan dan Harapan
Tentu, tidak semua berjalan tanpa tantangan. Berdasarkan wawancara dengan 20 responden, beberapa hambatan utama yang kami temui antara lain:
Pertama, tidak semua warga mampu mengunduh buah sukun sendiri, sehingga harus membayar jasa orang lain. Kedua, sukun adalah buah musiman, sehingga tidak selalu tersedia sepanjang tahun.
Ketiga, akses pasar terbatas, sebagian warga bahkan menjual keripik sukun ke luar kecamatan karena minimnya pembeli lokal.
Dari situ, kami mulai memahami bahwa masalah utama bukan pada minimnya peminat, melainkan minimnya pengetahuan dan akses pasar. Sukun sudah akrab di lidah warga, khususnya sebagai keripik, tetapi inovasinya sangat terbatas. Padahal, dari sudut pandang ekonomi, sukun memiliki nilai tambah yang signifikan jika kita olah.
Membangun Ekosistem Sukun yang Berkelanjutan
Hal-hal ini menjadi catatan penting bagi kami ketika merancang prototype stik sukun. Kami ingin produk ini bukan hanya enak, tapi punya identitas, punya standar, dan bisa menjadi model yang bisa direplikasi oleh warga lain.
Karena itu, kami memilih nama “Stik Sukun Mi Iyoh”, mengangkat identitas lokal sekaligus menghormati peran penting Mi Iyoh dalam proses pendampingan.
Setelah prototype jadi, kami mulai ikut menguji jalur distribusi. Kami menitipkannya ke beberapa warung sekitar, mencoba mengukur minat konsumen, dan mengamati bagaimana respons mereka terhadap bentuk baru olahan sukun. Di warung-warung kecil dekat balai desa, stik sukun mendapat respon cukup baik.
Kami juga mengunggah produk ini ke media sosial, dan ternyata justru dari sanalah respon paling antusias muncul. Banyak yang mengaku belum pernah mencoba stik sukun, penasaran karena bentuknya yang lebih kekinian daripada keripik sukun tradisional.
Dari rangkaian uji coba tersebut, kami mulai membayangkan bagaimana jika pengembangan usaha ini berlanjut. Akhirnya, kami pun mulai memposting di media sosial, membuat akun Shopee agar memudahkan konsumen, dan kami pun menitipkannya di warung-warung hingga kantin kampus.
Akhirnya, sampai sekarang produk olahan stik sukun Mi Iyoh sudah tersedia di warung-warung dan di Shopee.
Membuka Peluang Usaha
Riset ini akhirnya memberi saya satu kesimpulan bahwa sumber daya alam tidak akan berarti apa-apa tanpa pengetahuan dan keberanian untuk memanfaatkannya.
Selama satu bulan tinggal di Cikalahang, kami menyaksikan bagaimana sebuah sukun yang selama ini dianggap biasa, bahkan sering dibiarkan membusuk, ternyata mampu membuka jalan bagi ide-ide baru dan peluang usaha.
Saya menyadari bahwa riset aksi bukan hanya tentang menemukan masalah, tetapi berusaha menjadi bagian dari proses perubahan. Stik sukun “Mi Iyoh” hanyalah langkah pertama. Yang terpenting adalah langkah itu sudah kita mulai. []