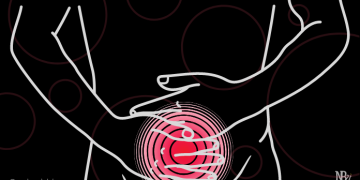Trigger warning: Artikel ini terdapat kalimat yang dapat memicu pengalaman traumatis.
Mubadalah.id – Kasus femisida terus terjadi di Indonesia. Baru-baru ini pada (31/8) terjadi kasus femisida di Surabaya, Jawa Timur. Kasus tersebut mengguncang publik karena pelaku membunuh dan memutilasi korban menjadi ratusan bagian.
Pelaku merupakan kekasih korban. Kasus ini adalah contoh bentuk femisida yang ekstrem, pembunuhan terhadap perempuan yang dilatarbelakangi oleh relasi kuasa, misogini, dan kekerasan berbasis gender.
Pelaku tidak menunjukkan penyesalan setelah membunuh dan memutilasi korban. Hal tersebut terlihat di mana pelaku tidak langsung menyerahkan diri ke polisi. Pelaku memilih untuk menyimpan potongan tubuh korban di kamar kos mereka dan sebagian lainnya ia buang di daerah Mojokerto.
Ketika polisi meringkus pelaku, ia sempat melawan dengan mengacungkan senjata tajam kepada polisi.
Pelaku mengatakan bahwa ia membunuh dan memutilasi korban karena perasaan kesal. Pelaku mengaku harus memenuhi kehidupan korban yang mewah dan sakit hati karena korban tidak membuka pintu kamar kos selama satu jam.
Membunuh korban dua kali: dari kematian fisik menuju penghakiman sosial
Narasi tunggal pengaburan femisida dari pelaku yang membuat alibi untuk pembunuhan tersebut rentan membuat korban terbunuh untuk kedua kalinya.
Pelaku membangun alibi “cinta” atau “sakit hati” karena perilaku korban. Saat menghadapi media, pelaku cenderung menunjukkan raut menyesal, hal tersebut berbanding terbalik dengan keadaan saat polisi meringkus pelaku.
Pelaku juga membangun narasi bahwa dirinya adalah “korban keadaan” dan melakukan pembunuhan tersebut karena terpaksa. Sehingga penilaian sebagian masyarakat berpihak kepadanya.
Narasi tunggal inilah yang kemudian menyebabkan masyarakat kehilangan empati kepada korban dan malah memaklumi tindakan pelaku.
Seperti pada kasus ini misalnya, masyarakat justru fokus pada kehidupan atau latar belakang korban. Masyarakat lebih memilih untuk menilai pilihan korban dan menjadi hakim moral dibandingkan berempati pada korban.
Tak hanya itu, tidak sedikit warganet yang membagikan masa lalu korban di media sosial. Penilaian yang bias ini memperkuat stigma bahwa korban “layak” jadi korban kekerasan dan pembunuhan.
Hal tersebut tentu saja menggeser akar permasalahan atau fokus utama dari femisida. Di mana perempuan rentan menjadi korban kekerasan berbasis gender hingga pada bentuk yang paling ekstrem yakni pembunuhan oleh orang terdekat.
Media Masih Sering Bias Memberitakan Femisida
Pemberitaan tentang femisida oleh media masih sering bias. Media-media online biasanya lebih mengejar pada sensasi agar viral dan mendapatkan banyak pembaca.
Masih banyak media yang memberikan sorotan pada narasi tunggal pelaku dan menguliti kehidupan pribadi korban. Hal tersebutlah yang kemudian membuat publik melupakan substansi dari femisida itu sendiri. Media sibuk mengorek masa lalu korban dibanding fokus pada akar masalah femisida.
Pemberitaan semacam itu yang akhirnya menggeser empati masyarakat. Masyarakat seharusnya fokus pada korban dan bagaimana pelaku merenggut hidup korban secara sadis daripada berempati kepada pelaku yang hadir di hadapan media dengan air mata, yang bisa saja hanya sandiwara.
Media kerap fokus pada motif pelaku dibanding menghadirkan suara dari keluarga korban. Narasi-narasi liar di media sosial membuat korban semakin jauh dari keadilan.
Keluarga korban seharusnya juga menjadi fokus utama dalam pemberitaan femisida. Jika media terus-terusan membuat narasi yang menyudutkan korban dan publik semakin mengorek masa lalu korban, bukankah keluarga korban yang akan semakin terpukul?
Pemerintah seharusnya menganggap serius kasus femisida yang kian hari kian meningkat. Media juga harus mendukung dengan memberitakan tentang substansi femisida daripada berita sensasional.
Framing Terhadap Korban Femisida Dapat Membahayakan Perempuan Lain
Jika masyarakat selalu terpaku pada bagaimana latar belakang korban dan moral korban, penilaian seperti ini tentu saja dapat membahayakan perempuan lain. Masyarakat menilai perempuan yang berperilaku tidak sesuai dengan standar norma tertentu layak menjadi korban kekerasan dan pembunuhan.
Padahal, perempuan sudah rentan menjadi korban kekerasan berbasis gender. Penilaian masyarakat akan membuat perempuan semakin tidak aman. Sistem patriarki menjadi semakin kuat dan mengontrol perempuan untuk mematuhi norma yang mereka terapkan.
Perempuan tidak boleh memilih atau mengambil keputusan yang berbeda untuk dirinya. Narasi yang menyalahkan korban atau victim blaming dapat mempengaruhi psikologi perempuan secara kolektif.
Narasi-narasi itu bisa menciptakan ketakutan, kecemasan, dan rasa tidak aman. Masyarakat patriarki mendoktrin perempuan bahwa keselamatan mereka bergantung pada perilaku atau pilihan pribadi mereka, bukan perlindungan dari kekerasan.
Hal ini juga memicu silent suffering, di mana perempuan yang mengalami kekerasan enggan untuk berbicara atau meminta bantuan karena takut dihakimi oleh masyarakat. Framing yang menyudutkan korban juga dapat digunakan untuk membenarkan pembatasan kebebasan perempuan.
Dalam kasus ini contohnya, muncul narasi yang menyalahkan gaya hidup korban dan pilihan pribadi korban yang menciptakan pembenaran bagi pelaku kekerasan. Ini secara tidak langsung membenarkan kontrol sosial atas tubuh dan kehidupan perempuan.
Fokus pada bagaimana framing negatif terhadap korban dapat merusak sistem hukum dan dukungan sosial. Stereotip dan prasangka terhadap korban membuat penegak hukum, jaksa, dan bahkan hakim cenderung bersikap bias. Hal ini dapat menyebabkan hukuman yang tidak adil bagi pelaku dan memperlambat proses keadilan bagi korban. []