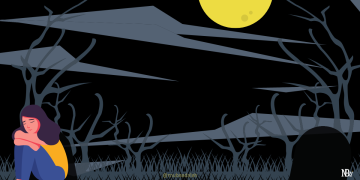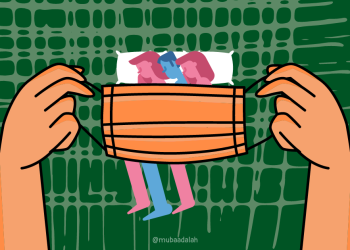Mubadalah.id – Perempuan penyandang disabilitas di budaya masyarakat kita yang patriarki selalu menjadi kelompok yang mendapat ketidakadilan. Farida (9 tahun), tetangga saya, terpaksa menghentikan sekolahnya di usia yang masih sangat muda. Hanya karena Ia tidak mampu mengerjakan tugas-tugas dan soal ujian. Sehari-hari Ia bermain dengan kerabatnya yang masih duduk di bangku sekolah dini. Karena teman-teman sebayanya tidak mampu berinteraksi dengannya.
Ketika saya mendengar kisah Farida — seorang perempuan penyandang disabilitas yang masih berusia anak-anak dan mengalami diskriminasi — pikiran saya terus terusik. Entah karena empati atau rasa iba, saya sempat berpikir bahwa Farida memerlukan belas kasih.
Bahkan, saya berencana belajar bahasa isyarat agar bisa memberikan kembali akses pendidikan untuknya. Singkatnya, saat itu saya masih memandang bahwa penyandang disabilitas adalah pihak yang memerlukan bantuan khusus.
Selama Ini Pandangan Saya Salah Soal Mereka
Saya mendapat kesempatan berharga untuk menjadi peserta Konferensi Nasional KUPI 2025 dan Workshop Kepenulisan dan Media Sosial Mubadalah yang sudah lama saya dambakan.
Dalam workshop tersebut, aaya mendapat pandangan baru terhadap “disabilitas”. Pada awalnya, saya memandang mereka sebagai pihak yang memerlukan belas kasih dan bantuan. Pandangan itu tampak wajar, tetapi kemudian saya menyadari bahwa cara pikir seperti ini sebenarnya bias.
Ia mencerminkan bentuk ableisme, yaitu cara pandang yang menilai penyandang disabilitas sebagai pihak yang harus “diperbaiki” atau “dinilai” dari keterbatasan yang mereka miliki. Pandangan semacam ini justru mengabaikan kemanusiaan dan potensi mereka sebagai individu yang setara.
Saya mendapat pandangan baru ini di hari pertama mengikuti Workshop Penulisan Media Sosial bertemakan “Perspektif Keulamaan dalam Penguatan Hak-Hak Disabilitas di Indonesia”. Salah satu rangkaian dari Konferensi Nasional KUPI 2025. Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), Yayasan Fahmina, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, dan Mubadalah.
Di hari pertama ini juga saya sempat termangu ketika baru mengetahui bahwa pada dasarnya difabel itu manusia ciptaan Allah SAW sama seperti manusia yang lain. Karena sebelumnya Saya masih mendefiniskan disabilitas itu merupakan orang yang memiliki keterbatasan fisik (cacat).
Kursi Roda Bukan Sekedar Alat Bantu
“Yang harus kamu ketahui, kursi roda itu adalah akomodasi yang layak dan menyatu dengan tubuh teman-teman difabel. Maka sebaiknya meminta ijin terlebih dahulu kepada teman-teman difabel ketika akan menyentuhnya.”, ungkap Nyai Fatimah Asri Mutmainnah atau biasa disapa Teh Aci, Anggota Komisi Nasional Disabilitas (KND).
Selama ini, saya mengira alat bantu teman-teman difabel—untuk mobilitas, penglihatan, atau pendengaran—hanya benda terpisah dari tubuh mereka. Saya berpikir alat-alat itu berdiri sendiri dan tidak menyatu dengan pemiliknya. Jika pandangan ini dibiarkan, mereka seolah tidak memiliki kendali penuh atas alat bantu tersebut.
Termasuk prostetis, alat yang menyerupai bagian tubuh yang hilang karena penyakit, trauma, atau kondisi bawaan lahir.
Penjelasan Teh Aci membuat saya memahami bahwa alat bantu bukan sekadar benda penunjang. Ia adalah bagian dari identitas dan kemandirian seseorang. Kursi roda, tongkat, alat bantu dengar, atau prostetis membantu mereka bergerak, beraktivitas, sekaligus menegaskan ruang otonomi untuk berinteraksi dengan dunia.
Saya pun tersadar, cara pandang yang menganggap alat bantu sebagai benda “asing” justru memperlebar jarak sosial antara difabel dan non-difabel. Padahal, menghormati alat bantu berarti menghormati tubuh dan martabat pemiliknya. Dari sini, saya belajar bahwa inklusivitas tidak berhenti pada empati, tetapi juga pada pengakuan terhadap kedaulatan tubuh dan pengalaman hidup penyandang disabilitas.
Bagaimana KUPI Memandang Disabilitas?
Saya menyoroti penyampaian Dr. Faqihudin Abdul Kodir, yang akrab disapa Kang Faqih. Dalam paparannya, beliau menegaskan kembali gagasan Nyai Badriyah Fayumi tentang cara KUPI memaknai hak dan pengalaman penyandang disabilitas.
Kang Faqih menjelaskan secara sederhana empat dasar cara pandang KUPI terhadap isu ini.
Pertama, karamah insaniah, yaitu bagaimana kita semua, sebagai manusia, memandang penyandang disabilitas sebagai manusia utuh dan subjek penuh dalam memberikan maupun menerima kebaikan.
Kedua, Fikih al-Murunah (fleksibilitas), yaitu fikih yang lentur dan adaptif. Hukum Islam seharusnya mampu menyesuaikan diri dengan keragaman pengalaman manusia. Prinsip ini menjadi landasan penting dalam membahas isu disabilitas.
Dalam konteks ini, Al-Ashlu huwa al-‘Azimah—berpegang pada hal yang pokok—mengingatkan kita agar tidak menetapkan hukum dari sudut pandang non-difabel, melainkan melibatkan penyandang disabilitas sebagai subjek ijtihad yang memahami kebutuhannya sendiri.
Ketiga, adaptasi teknologi (takyiif) menjelaskan pentingnya memastikan teknologi berkembang mengikuti kebutuhan penyandang disabilitas. Teknologi bukan sekadar alat bantu, tetapi bagian dari otonomi mereka untuk berdaya dan menentukan pilihan hidupnya.
Keempat, aksesibilitas sosial (tamkīn atau taqwiyah) menjadi dasar penting lain dalam cara pandang KUPI. Prinsip ini menekankan perlunya memberikan ruang dan penguatan sosial agar penyandang disabilitas benar-benar bisa berpartisipasi, berpendapat, dan menentukan arah hidupnya.
Dalam pandangan KUPI, aksesibilitas tidak hanya soal fasilitas fisik, tetapi juga tentang membangun lingkungan sosial yang menerima dan mendukung setiap individu agar dapat tumbuh serta berdaya.
Mengikuti Konferensi Nasional KUPI 2025 membuat saya menyadari bahwa penyandang disabilitas bukanlah pihak yang membutuhkan belas kasih, melainkan manusia yang memiliki otonomi, martabat, dan kekuatan sendiri.
Saya belajar untuk tidak lagi melihat teman difabel dari sisi keterbatasan, tetapi dari potensi dan kemanusiaan yang utuh. Dari kisah Farida hingga pemikiran para ulama perempuan, saya memahami bahwa keadilan dan inklusivitas bermula dari cara kita memandang sesama sebagai manusia yang setara. []